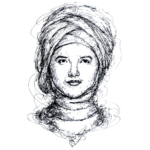Ketika mengetik kata sadis, saya langsung terngiang lagu Afgan berjudul sama. Kurang lebih salah satu kalimat liriknya seperti ini “terlalu sadis caramu, menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali…”. Cukup. Karena bila dilanjutkan, lirik lagu Afgan yang sekarang kabarnya menjalin kekasih dengan Maudy Ayunda itu tidak relevan dengan kisah Bonnie & Clyde, sepasang muda-mudi yang berprofesi sebagai perampok (termasuk beberapa pembunuhan).
Saya mengenal Bonnie & Clyde dari salah satu stasiun televisi awalnya. Kemudian selang berapa lama, saya menemukan filmnya di harddisk teman sekelas. Versi yang saya tonton adalah versi tahun 2013. Ya benar. Film ini memiliki versi yang lebih lama yaitu pada tahun 1967. Wikipedia menyebut Bonnie Parker & Clyde Barrow sebagai tokoh kriminal di tahun 1900an, tahun di mana kapal Titanic tenggelam. Penyebutan “tokoh” ini sempat membuat saya heran.
Bagaimana mungkin, seseorang yang melakukan tindak kriminal disebut sebagai “tokoh”? Padahal, berita-berita kuning di televisi atau koran sering menyebutnya dengan istilah “pelaku”. Penokohan Bonnie & Clyde ini bukan hanya terbatas frasa saja, tapi dalam dokumenternya, ketika jenazah keduanya dimakamkan, ada sekitar 50.000 orang yang melayat, entah karena senang atau sedih.
Ada beberapa kemungkinan mengapa Bonnie & Clyde disebut sebagai tokoh. Yang pertama, pada zamannya mereka adalah dua orang yang fotonya banyak disebar di media massa sebagai buron sehingga tingkat famous-nya sangat tinggi. Yang kedua, mereka dianggap ikon yang sangat berani meneruskan perampokannya, meski negara menyebut mereka sebagai public enemy yang lebih baik dimusnahkan. Yang ketiga, mereka berdua adalah trend-setter di mana jaringan kriminal diikat secara loyal melalui asmara.
Salah satu awak Sediksi, Fadrin Fadhlan Bya mengatakan munculnya istilah partner in crime berawal dari mereka. Istilah ini banyak digunakan anak gaul, yang mungkin belum mengenal sosok Bonnie & Clyde.
Saya menggarisbawahi kata partner yang disematkan pada mereka. Partner dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai rekan, mitra, dan kongsi. Artinya, pada kata ini terdapat unsur kinerja profesional. Ketika saya menonton film Bonnie & Clyde versi 2013, unsur profesional memang ada pada mereka berdua.
Namun, Sang Suhu Wikipedia mengabarkan Bonnie melakukan semua kejahatan dan kriminalitas ini karena ia jatuh hati pada Clyde, si pelanggan penjara. Bonnie rela meninggalkan ibunya, rela dimejahijaukan, rela menghadap Gubernur untuk membebaskan Clyde dari penjara, rela dijadikan buron agar ia terus bisa bersama Clyde. Sweet crime.
Oh ya, saya hampir lupa menceritakan sadisme dalam film ini. Ah, saya menulisnya dengan harapan saya tidak insomnia lagi malam ini. Bayangkan. Kematian Bonnie & Clyde disebabkan keduanya diberondong oleh 100-an peluru pistol laras panjang oleh Frank Hammer dan kawan-kawan. Frank Hammer adalah kaki tangan polisi yang berhasil menemukan dua pasang kekasih ini di dalam mobil menuju rumah saudaranya. Bonnie & Clyde meninggal seketika dalam mobil yang bersimbah darah. Mereka diadili lewat pistol. Sadis.
Saya tidak mengada-ada jika saya benar-benar insomnia setelah menonton film Bonnie & Clyde. Saya dibayangi pikiran tentang sadisme-sadisme yang terjadi. Saya tidak bisa melepaskan ingatan suara-suara pistol yang berderai di setiap adegan. Tapi selebihnya, saya terkesan setelah menyimak cerita mereka. Simpulan saya bahwa prolog dan epilog kisah asmara tidak selalu manis dan mapan, namun cerita cinta macam ini bahkan diingat oleh sebagian besar publik dan dicatat oleh sejarah. Jodoh yang ideal menurut konstruksi keluarga tidak selalu dipatuhi oleh remaja kala itu, dan mereka berani mengambil keputusan untuk menjadi diri mereka sendiri.
Poin-poin ini yang kemudian membuat industri film yang mengorbitkan cerita-cerita cinta berujung patah hati makin memberi kesan terhadap penonton. Contoh lain ada pada cerita film Titanic, ketika Rose yang dari keluarga kaya raya memilih Jack, si miskin yang hadir di tengah kemapanan keluarga. Ketidakmapanan atas nama cinta itulah yang membuat Rose mau menyerahkan apapun agar terus bersama Jack. Meski pada akhirnya, cinta mereka berakhir di laut yang beku.
Melihat adanya perspektif lain dalam menyatukan cinta, industri film Indonesia pun berlomba membuat film bergenre romantis yang berujung pada kesedihan. Ada Apa dengan Cinta misalnya, yang tidak menyatukan Rangga dan Cinta pada satu hubungan. Atau Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang kisahnya harus berakhir ketika sang kekasih meninggal di kapal, mirip Titanic.
Ketika industri film sibuk bermain seni kisah asmara yang tidak monoton pada siklus PDKT-nembak-jadian-menikah, sutradara FTV justru sebaliknya. FTV tiap siang seakan menjadi counter attack akan ketidakmapanan dalam siklus mendapatkan cinta sejati. Sehingga tidak jarang, penggemar FTV cenderung merasa bosan.
Belum lagi ditambah sutradara-sutradara film Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, 99 Cahaya di Langit Eropa dan film dengan genre cinta-religiusitas lainnya yang semakin membuat publik jenuh melihat cinta dari pandangan yang normal. Kejenuhan tersebut tidak jarang membuat cerita cinta menjadi angin lalu, tidak menarik, dan pro-kebahagiaan.
Tulisan ini tidak mengarah pada upaya untuk mempersuasi pembaca agar tidak menyukai film-film cinta dengan ending bahagia. Namun tulisan ini lebih mengajak pembaca agar menikmati cinta dengan sudut pandang berbeda. Mengapa? Karena jika kita terlalu banyak mengonsumsi film cinta bahagia, kita akan dilenakan olehnya dan dilupakan bahwa realitas kini begitu kejam membentuk cinta. Lho kok bisa? Bila cinta itu sederhana, mapan, dan bahagia, mungkin seluruh kru di Sediksi kini sudah punya pacar dan sudah menikah semuanya. Salam.