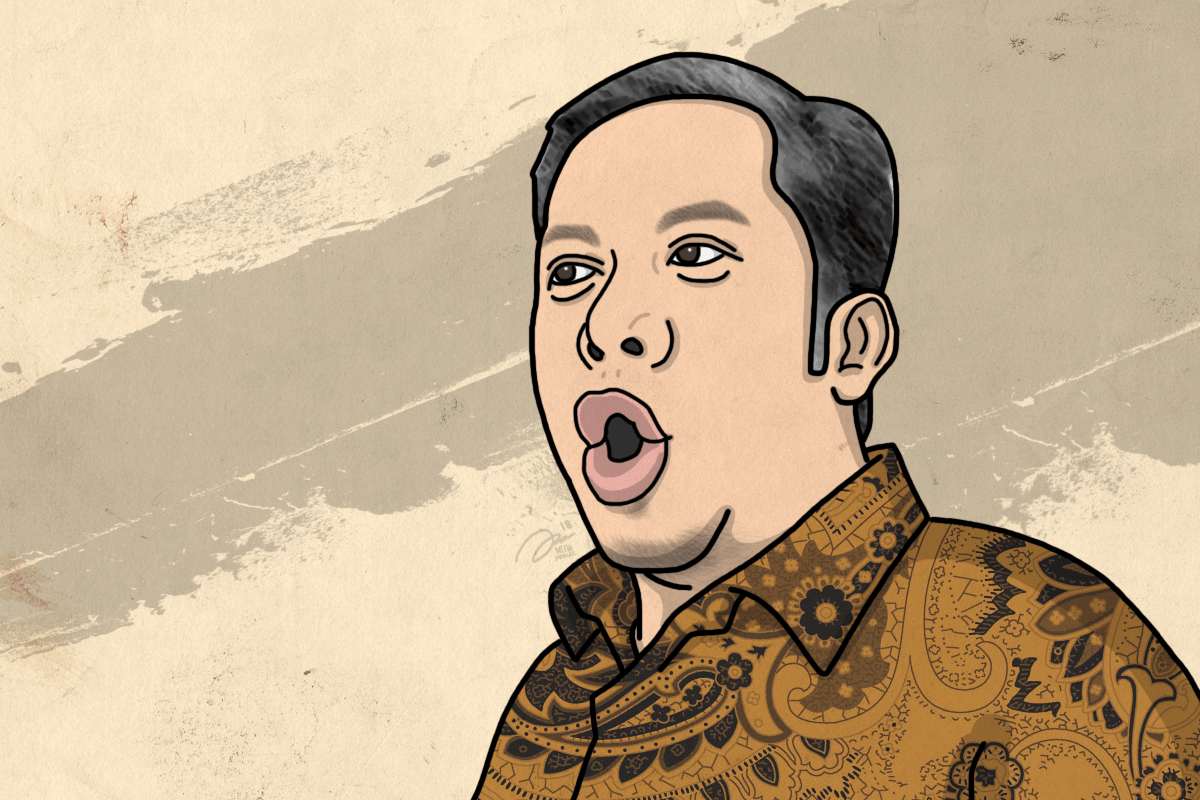Hanya beberapa menit setelah mencuit kata babu, Fahri Hamzah segera dikelilingi oleh hujatan (24/1/2017). Kata ini dianggap merendahkan dan tidak menghargai hasil jerih payah para buruh migran yang banting tulang di negeri orang. Seketika itu pula terbesit di ingatan saya tentang beberapa kata yang jika diucapkan dengan nada ofensif dapat memunculkan reaksi yang keras.
Kata baboe bersanding dengan sejumlah kata seperti koeli dan djongos telah mengalami peyorasi. Semuanya telah jeblok dengan tafsir tunggal yaitu pekerja rendahan. Jika situ ingin menjajal baku hantam dengan rekan sejawat, cobalah ucapkan ketiga kata itu dengan mata melotot, leher keluar urat, dan busa mulut yang tumpah ruah.
Pun ketiga kata itu sering diidentifikasi dengan celaan, kenestapaan, keluhan, bahkan keprihatinan. Kita bisa simak dari cerita Pramoedya Ananta Toer tentang Makhluk di Belakang Rumah. Baboe yang dirantai suasana “priyayi udik” bagi PAT kesehariannya bercorak, “Tiap minggu sekali ia kena bencana: terpeleset di sumur, paku terbenam dalam kakinya, terseterika lengan, terbalik menumbuk bangku, bahkan sekali waktu sedang duduk beristirahat di sebuah kursi rotan yang telah peot. Ia kejatuhan sepeda, kursi menjatuhi deretan piring, dan setelah itu ia kejatuhan pulung di atas kepalanya dari juragan”. Rasa frustasi ini makin menukik saat para juragan mengutuk hingga si babu berkata,” “Biar gua ditubruk kereta api!”
Kalau dalam sehari-hari, coba simak kalimat ini :
“saya ini kamu anggap teman atau baboe? Kok disuruh-suruh terus?“
Atau kalimat yang ini :
“Kamu belum mandi ya? Pantas baunya persis koeli.”
Saya dituntun rasa ingin tahu serba serbi yang melingkupi babu di masa lampau. Masa yang dipahat oleh buku PSPB sebagai jaman penjajahan Belanda. Meskipun sebenarnya banyak orang rambut pirang juga di Hindia Belanda, dari Jerman, Swedia, Prancis dkk, ya mungkin mirip dengan penglihatan “kaum terpelajar 2017” yang mengartikan kehadiran (maaf) orang mata sipit di bandara dan restoran sebagai persekongkolan bengis (TKA) Ekor Naga Tiongkok.
Persoalan perubahan baboe menjadi pembantu rumah tangga, betapa sengsaranya inlander saat era kolonial, data terkini TKI yang tetap mengirim uang ke kampungnya sembari berkelit dari cengkraman ilegal-legal, atau barangkali akun twitter Fahri Hamzah yang dibajak Ethan Hunt, saya yakin diluar sana banyak yang lebih ciamik ulasannya.
Rasa penasaran ini membuat saya terdampar di kumpulan gambar baboe yang disimpan di Geheugen van Nederland, yang kira-kira semacam portal arsip online. Pada foto hitam putih bertajuk Klein jongetje met baboe op het gras yang kira-kira berarti anak laki-laki sedang main bersama babu di rerumputan, mata saya mendelik saat melihat ada keakraban antara anak berambut pirang dengan baboe pribumi. Si balita sedang titah-titah belajar jalan, dan si baboe mengawasinya dengan sumringah.
Dari foto itu kita mungkin penasaran, ngapain itu baboe senyam-senyum ke balita bule? Ya, tugasnya kan mengasuh anak, mesti dengan senyum dong. Belum puas? Oke, sediakan mesin waktu dan adakan wawancara buat si baboe. Siap-siap situ dibikin nelan ludah akibat jawaban, “Ya gimana lagi mas, namanya kerja, yang penting halal.” Tahun, 1919 baboe loh sampai disediakan tempat persinggahan di Belanda. Nah! Ya mungkin saja kita agak sedikit mengernyitkan dahi saat melihat para baboe duduk bersimpuh dengan para Tuan dan Nyonya Bule. Paling tidak, sudah tergambar tegas garis batas mana kaum pemberi prentah dan mana kaum yang terprentah.
Setelah itu saya lanjutkan periksa salah satu penulis bernama J.H De Bussy (1909). Doi pernah ngomong, Baboe berarti kindermeid atau pengasuh anak. Menurutnya baboe itu ya salah satu jenis pekerjaan sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lain. Meneer yang satu ini sama sekali tidak menyinggung pekerjaan ini rendah, kasar, mulia, antek kolonial, apalagi halal dan haram.
Di bagian baboe, mata saya terus memperhatikan gambar balita pirang yang diselendangi oleh perempuan pribumi. Perempuan itu mengenakan kebaya dan sarung, ia memayungi kulit putih si balita agar tidak disengat sinar matahari. Kemudian, saya coba membalik halaman berikutnya, ada pekerjaan koelie yang berarti vrachtdrager atau tukang angkut-angkut, djongos yang berarti huisjongen atau anak muda (laki-laki) pelayan rumah sebutlah dalam bahasa lain pembantu atau pelayan laki-laki.
sumber foto: Geheugen van NederlandSetelah tilik-tilik beberapa poto diatas, saya tiba-tiba berpikir, bisakah melihat hubungan baboe dan balita yang digendongnya bukan sekedar hubungan kerja namun menyaru pula relasi ibu dan anak? Untung saya diselamatken catatan Frances Gouda (2009), ahli sejarah yang menuliskan bahwa baboe sepadan dengan figur ibu kandung utama. “Baboe mengajari anak-anak Belanda ini, baik perempuan dan laki-laki cara-cara memahami kehidupan alam, menghibur mereka dengan kabar angin, atau menyuguhi mereka kisah menyeramkan tentang hantu dan roh. Mereka (baboe) mungkin bercerita kepada anak-anak Eropa yang mendengarkan dengan mata terbelalak tentang kisah kuntilanak”.
Kemudian, sejak masih kecil hingga beranjak sekolah HBS setara sekolah menengah, para baboe menjadi perantara antara nilai pribumi, mulai dari mengajari permainan tradisional, menerbangkan layang-layang hingga bergaul dengan anak-anak pribumi yang lain. Namun, sayangnya para Nyonya Bule sering cemburu dengan keakraban itu dan konon mereka sangat curiga para baboe itu adalah golongan pendendam. Padahal mereka butuh baboe untuk mengajari bahasa pribumi dan menjalankan rumah tangga.
Di satu sisi, keberadaan baboe sangat diperlukan oleh keluarga Belanda. Apalagi saat angkutan perkapalan mulai sibuk di abad ke-19. Hal ini yang menyebabkan timbulnya pekerjaan zeebaboe atau baboe laoet. Baboe ini kurang lebih tugasnya mirip dengan yang “di darat”, mengasuh anak dan beberapa pekerjaan domestik seperti merapihkan pakaian Tuan dan Nyonya, namun di laut alias pada saat perjalanan di kapal. Salah satu syarat menjadi baboe laoet ialah teruji bebas mabuk laut.
Tentang ini, lagi lagi saya beruntung diselamatkan Harry Poeze (2008) yang pernah mengumpulkan salah satu tulisan dari tahun 1917 dalam buku Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Catatan itu berjudul Babu Laut ditulis oleh si X (anonim) yang bercerita tentang salah satu keluarga yang membutuhkan baboe laoet untuk merawat anaknya dalam perjalanan dari Belanda ke Hindia (Indonesia). Ini spoiler ceritanya:
“Tiga hari sebelum kami berangkat kami sadar bahwa kami memerlukan seorang babu laut untuk membantu mengurus bayi kami, umur lima bulan, babu laut yang mau ikut kami menghadapi bahaya khatulistiwa. Nasihat yang baik mahal harganya. Babu laut merupakan kalangan yang sangat tertutup, satu kasta tersendiri yang hanya sedikit memiliki hubungan dengan masyarakat Belanda. Kami bermaksud menemukan salah satu hubungan itu dan menariknya, sampai kami dapat menemukan babu laut”
Dalam tulisan ini, diceritakan pula hubungan antara baboe dan bayi sangat mesra, sedangkan hubungan antara baboe dan ibu bersifat resmi. “Kalau aku tak hati-hati, bisa dia jadi bosku”, begitu kata istri si penulis ini. Tulisan yang dimuat oleh surat kabar Indie ini diakhiri dengan satu paragraf sentimentil. Digambarkan bahwa baboe laoet akan berganti majikan dan melaut lagi. Saat itulah baboe laoet dan anak (Eropa) saling melambaikan tangan dengan berurai air mata.
Disinilah akhirnya saya paham mengapa lagu Afscheid Van Indie (Perpisahan dengan Hindia) dibuat sangat nostaljik dan sendu. Wieteke Van Dort, penyanyi kelahiran Surabaya ini mengucap perpisahan kepada Hindia, tempat kelahirannya. “Dag baboe! Dag djongos! (selamat tinggal baboe! selamat tinggal djongos!),” begitu ucapnya.
Setelah era kemerdekaan, maka semuanya berbalik, kosakata baboe, koelie, dan djongos berpindah menjadi sebutan celaan mengacu pada orang-orang yang bekerja kasar, berupah rendah, dan minim pendidikan. Kurang lebih, sama berbalik dan ironisnya dengan nasib Si Sobi berikut Si Inah dalam cerita Jongos+Babu yang harus terhempas bergonta-ganti menyesuaikan standar susila majikannya.
Pramoedya Ananta Toer lebih sadis lagi. Kosakata babu dibekap kesusilaan babu priyayi. Standar moralitas komplotan “priyayi baru” untuk memperdaya dan membikin mental babu. Walhasil, bertindak dan berfikir seperti baboe satu grup dengan kosakata minderwaardigheidscomplex, sejenis penyakit minder dan rendah diri khas bangsa yang terprentah. Tafsir ini kemudian dipilin lagi oleh orang macam Sukarno untuk mengartikan baboe, kuli, inlander sebagai simbol mentalitas manusia yang tidak merdeka dan sedikit banyak akan menjawab mengapa para TKI murka dengan Fahri Hamzah saat dicuit baboe.