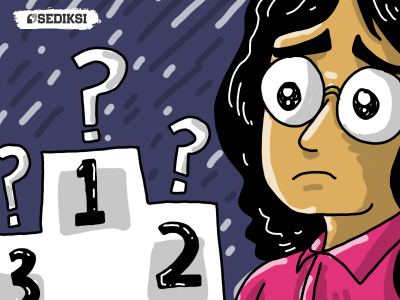Cerita perjalanan ini dibuat setelah saya baru saja menyelesaikan perjalanan dari Kota Malang menuju Surakarta alias Solo menggunakan sepeda motor. Banyak hal yang bisa saya amati dari perjalanan yang memakan waktu perjalanan total +/- 6,5 jam. Kalau ditambah mampir-mampir, total perjalanan saya jadi 28 jam.
Saya memulai perjalanan dari rumah kontrakan di kawasan utara Kabupaten Malang, Rabu, 30 Desember 2015 pukul 10.00 WIB. Saya berangkat menuju Solo melalui Karangploso, tembus ke Batu, Pujon, Ngantang, Kasembon, Pare, Kediri, Kertosono dan Nganjuk.
Ya, tujuan akhir di hari pertama adalah Nganjuk. Disana kami berdua mencoba menghubungi teman satu kontrakan lama saya yang kini tinggal di Nganjuk. Tujuan tulisan ini, bukan untuk menceritakan kisah pribadi saya selama berada di Nganjuk, melainkan apa yang saya amati selama perjalanan menuju Solo.
Cerita Perjalanan Tentang Tambangan di Nganjuk
Keinginan saya untuk menulis cerita perjalanan ini muncul saat saya sedang menaiki tambangan menuju Kertosono. Tambangan adalah istilah orang sana untuk menyebut transportasi getek yang digunakan masyarakat setempat untuk membawa pengendara sepeda motor menyeberangi sungai Brantas.
Tarif yang ditarik hanya Rp 3.000 untuk setiap sepeda motor. Jujur, tarif itu jelas terbilang murah untuk kantong mahasiswa seperti saya. Dibandingkan harus menghabiskan waktu dua kali lipat bila mengambil jalan memutar melalui Baron, tambangan adalah pilihan tepat untuk menuju Nganjuk dengan waktu yang lebih cepat.
Kesan pertama yang saya terima saat menaiki Tambangan: tradisional. Ya, entah sejak kapan Tambangan itu ada, namun saya pikir sensasinya akan selalu sama.
Menyeberang sungai Brantas dari timur ke barat, dengan arus sungai deras menuju utara, itu adalah hal yang amat mengesankan. Masyarakat setempat, cukup cerdas untuk memanfaatkan keterbatasan akses menuju Nganjuk dengan menyediakan Tambangan.
Sayangnya ada satu hal yang mengganggu pengamatan saya selama berada di atas perahu kayu itu, yakni keberadaan jembatan yang masih dalam proses pembangunan. Menurut saya, keberadaan jembatan tersebut memang efektif dan efisien. Namun, ada hal yang mengganjal melihat keberadaan pembangunan tersebut.
Pertama, keberadaan jembatan itu tentunya akan membuat nasib para pelaku usaha Tambangan menggantung. Mereka bisa saja tetap menyediakan fasilitas Tambangan untuk sepeda motor menyeberang, namun apakah penggunanya akan seramai sebelum ada jembatan? Saya kira tidak.
Namun, dengan pembangunan jembatan itu ada hal lain yang mungkin akan muncul. Ketersediaan akses menuju pusat kota Nganjuk beberapa desa di Kertosono, berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi di sana.
Saat ini, boleh saja daerah tersebut masih dipenuhi sawah-sawah. Tapi, saya berani taruhan dalam waktu 5-10 tahun ke depan, ruko-ruko akan tumbuh dengan lebat. Artinya, pola kehidupan ekonomi di daerah tersebut akan menuju kawasan industri.
Kalau Cak Nur atau Nurcholis Madjid menyebut, perubahan desa ke arah kota mampu merubah pola kehidupan Paguyuban menjadi Patembayan milik Ferdinand Toonies. Di materi-materi sosiologi-antropologi-psikologi, kehidupan Patembayan membuat individu-individu dalam sebuah masyarakat menjadi lebih individualis.
Sebuah penelitian juga menyebut kalau faktor kolektivitas individu akan berkurang seiring dengan perubahan struktur masyarakat, dari masyarakat desa menuju masyarakat kota. Dari sini, pemikiran saya agak galau, mana yang harus diutamakan, gotong royong dari sebuah fasilitas Tambangan atau pembangunan menuju daerah industri yang otomatis mengurangi kolektivitas masyarakat.
Kedua, pikiran saya terganggu ketika belum sampai satu kilometer dari Tambangan, saya melihat ada proses pembangunan Ruko. Jembatan belum jadi, tapi Ruko sudah mulai terbangun, yang benar saja? “Bagaimana nanti kalau jembatan sudah jadi” ucap saya kepada Henry saat itu.
Pembangunan Ruko ini juga membuat saya khawatir. Sebab, boleh saja akses ke desa-desa yang dilalui nanti berkembang menjadi kawasan industri, namun apakah kawasan industri itu akan dikuasai masyarakat setempat? Atau justru para pemilik modal dari luar kota yang justru lebih berhasrat untuk mendirikan pertokoan di sana? Kalau opsi kedua yang terjadi, maka habislah sudah.
Nasib masyarakat setempat sedikit banyak akan mirip dengan nasib pemilik kost-kostan di daerah Kerto-Kertoan (Mahasiswa Malang pasti tahu). Kost-kostannya kecil, lembab dan berdempet-dempetan. Berbeda dengan di bagian lainnya, seperti Watugong, Watumujur, ataupun Soekarno Hatta.
Kost-kostannya besar-besar, harganya melangit, namun yang punya orang luar Malang, bahkan ada yang luar pulau Jawa. Lagi, ini jadi pertanyaan sekaligus kekhawatiran saya terhadap masyarakat di desa-desa tersebut. Saya harap, ada orang-orang pribumi setempat yang terpelajar berniat untuk menjawab tantangan tersebut.
Terakhir, saya simpulkan cerita perjalanan ini bahwa sensasi naik Tambangan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Merasakan goyangan getek yang berlayar tak searah dengan arus sungai, membuat saya hanya tertegun diam, sambil sesekali menghisap batang rokok berinisial U.