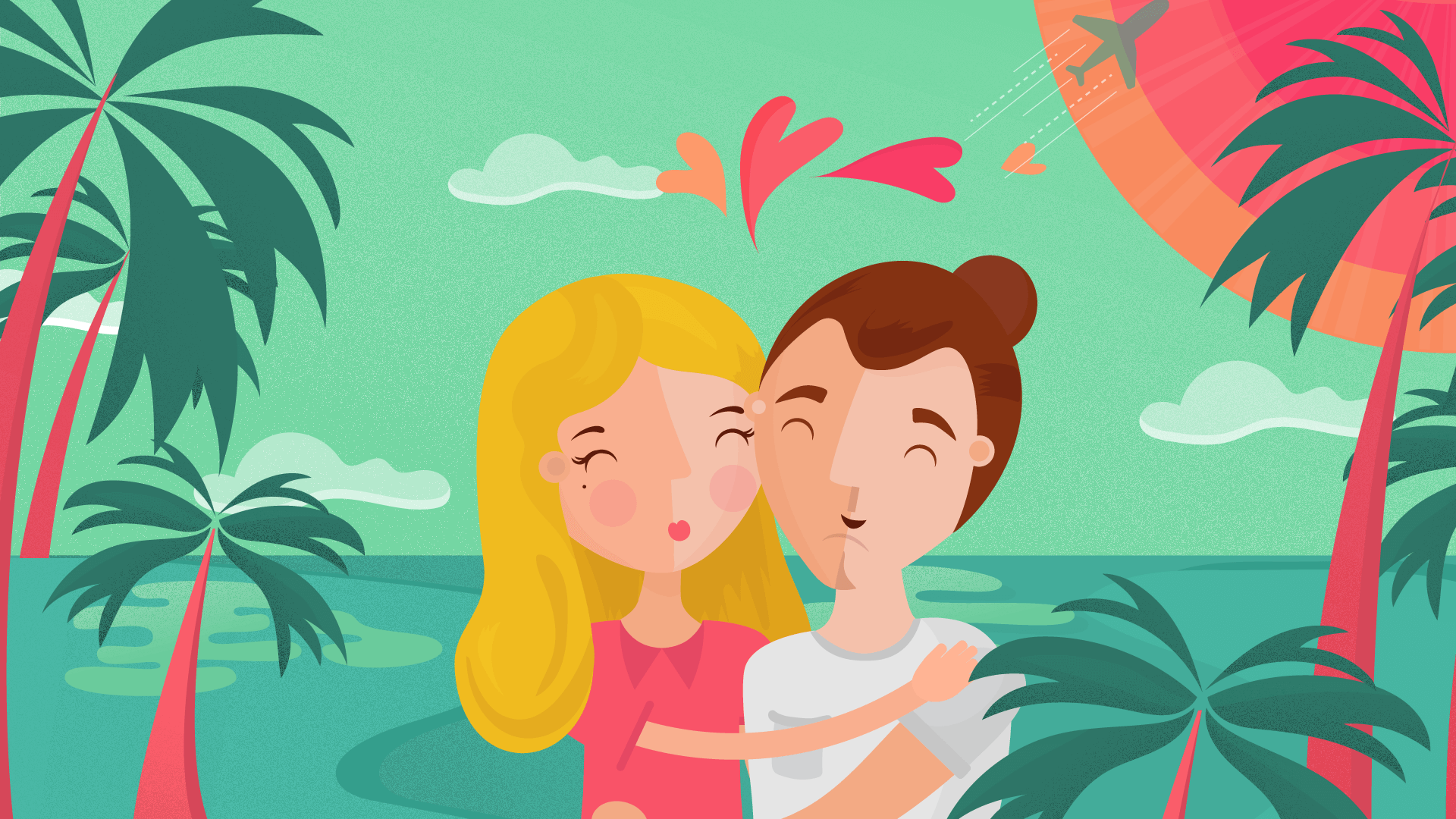Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa film dari negara miskin biasanya akan cenderung mengumbar kekayaan yang jauh dari kenyataan hidup rakyatnya. Sementara film-film dari negara kaya biasanya wajar-wajar saja, tidak terlalu mengekspos harta benda. Barangkali ini tidak lepas dari kenyataan bahwa seringkali film merupakan pelepasan fantasi liar penontonnya. Seperti fantasi seks yang terpuaskan dengan menonton film biru. Atau fantasi keagamaan yang dipuaskan dengan tayangan religi. Demikian pula dengan London Love Story.
London Love Story adalah salah satu judul film layar lebar yang terlalu banyak berfantasi. Kebetulan dua hari lalu saudara dan sepupu perempuan saya setengah memaksa mengajak menonton film itu di bioskop. Berhubung saya tidak enak hati, saya ikuti permintaan mereka. Masuk ke dalam studio bioskop ketika film sudah mulai diputar merupakan hal yang tidak saya sukai. Karena gelap, biasanya saya agak kesulitan mencari kursi. Dan malam itu saya baru masuk studio setelah film telah diputar lima menit.
Sedari masuk saya terus mengamati tiket untuk membayangkan lokasi kursi yang harus saya tuju. Dan betapa terkejutnya, sesampai di dalam studio cuma ada dua orang penonton. Bahkan sebenarya saya tidak perlu mencari tempat duduk karena bisa duduk di mana saja saya mau. Saya memang jarang nonton di bioskop karena berdasarkan kalkulasi cermat saya, menonton di laptop sendiri jauh lebih murah.
Tapi sejauh pengalaman yang sedikit itu, belum pernah saya temui jumlah penonton sesedikit itu. Bahkan sewaktu SMA saya pernah iseng dengan teman-teman menonton di bioskop tua yang memutar film-film dewasa jadul yang tiketnya hanya sekitar 5 ribu perak. Meskipun penontonnya banyak yang mesum, tapi dapat saya pastikan jumlahnya lebih banyak dibanding penonton London Love Story malam itu.
Seketika itu pula saya merasa memasuki jebakan batman. Selama satu setengah jam saya dipaksa duduk di ruangan ber-AC, tidak boleh merokok, tidak ada kopi, dan melihat film yang banyak orang tidak mau lihat.
Dan benar saja, begitu saya mencoba mengikuti film itu, adegan yang saya lihat pertama adalah sebuh mobil mewah beratap terbuka ditengah keramaian malam Kota London. Kemudian saya ketahui bahwa pengemudinya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di sana bernama Dave.
Mobil itu melaju cepat menuju sebuat diskotik. Didalam diskotik Dave bertemu beberapa rekannya sesama mahasiswa Indonesia disana. Lalu entah bagaimana, ada sesosok MILF yang berkenalan dan menari bersama. Lalu mabuk-mabukan.
Begitu saja diskotiknya dimuat dalam film, lalu Dave pulang dengan mobil mewahnya. Melewati jembatan diatas Sungai Thames yang terkenal itu, ada lagi mahasiswa Indonesia lain bernama Adelle yang hendak bunuh diri.
Dave berusaha menolong Adelle dengan mengalihkan perhatiannya melalui beberapa percakapan. Seketika itu juga saya membayangkan Dave dan Adelle pasti baru selesai menonton film Titanic. Karena adegan itu dan percakapan yang dilakukan sangat mirip dengan adegan awal perjumpaan Jack dan Rose di buritan kapal. Ketika Rose hendak bunuh diri dan diselamatkan oleh Jack.
Hanya saja adegan serupa dalam London Love Story adalah tiruan yang lebih murahan. Karena dilakoni dengan sangat buruk oleh pemain-pemainnya dan tidak ada unsur-unsur logis yang mengakibatkan di Adelle terpeleset hingga selamat di pelukan Dave. Tidak ada kelembaban udara yang memungkinkan besi menjadi licin seperti di buritan Titanic tempat Rose terpeleset.
Kekonyolan demi kekonyolan adegan, harta benda yang diekspos habis-habisan, hingga cerita cinta cengeng murahan terus bergentayangan di film ini. Memunculkan kesan yang membosankan, bisa ditebak, dan ala sinetron biasa.
Inti ceritanya sebenarnya sangat klasik jika pembaca sering menonton FTV dan sinetron. Ini adalah kisah cinta yang berputar-putar. Dave memiliki cinta lama bernama Caramel. Caramel juga masih mencintai Dave meskipun sudah lama tidak bertemu. Lalu datang Adelle yang jatuh cinta dengan Dave. Lalu ada Bima yang mencintai Caramel dan berteman dengan Adelle. Dengan adanya dua lelaki dan dua perempuan ini, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah bisa menebak akhirnya. Dave balikan dengan Caramel. Lalu Adelle dan Bima yang sama-sama patah hati menjadi semakin dekat. Selesai perkara.
Jika film ini sedemikian biasa, mudah ditebak, dan membosankan, lalu mengapa masih ada industri perfilman yang membuat film semacam ini? Padahal kisah-kisah yang serupa bisa didapati penonton di sinetron yang tayang setiap hari di stasiun televisi nasional.
Menurut pendapat saya, adalah fantasi yang dipermainkan dalam film ini. Karena jalan cerita bukan cara satu-satunya menggaet penonton. Keeksotisan kota London berlatar Big Ben, Sungai Thames, hingga Istana Buckingham memenuhi fantasi liar penonton Indonesia yang setiap hari berkutat dengan kesemerawutan kota.
Kemudian ada apartemen, mobil, dan gadget keren yang digunakan tokoh-tokoh dalam film. Seolah penonton diajak menipu diri sendiri ketika nyatanya, mahasiswa Indonesia yang sekolah diluar negeri seringkali hidup apa adanya. Karena biaya hidup dan pendidikan disana yang cukup tinggi, praktis hanya golongan mahasiswa Indonesia yang amat sangat sedikit yang mampu memenuhi gaya hidup itu.
Pernyataan Darmawan Salihin, ayahnya Mirna Salihin menyebutkan bahwa Jessica semasa studi di Australia juga sembari bekerja di Ambulance. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia Jessica termasuk anak gedongan. Sedangkan biaya hidup di Inggris jauh lebih mahal dibanding di Australia. Maka rasanya, selain anak koruptor atau mafia migas, mustahil ada mahasiswa Indonesia yang memiliki gaya hidup semewah itu di London.
Hitung-hitungan keuntungan barangkali menjadi bahan pertimbangan yang lebih diutamakan produser film ini. Karena tentunya membuat film di London menghabiskan biaya yang sangat tinggi. Untuk mengimbangi pengkeluaran akomodasi selama membuat film, bayaran untuk para pemain yang harus dikorbankan. Maka pemain-pemain yang dipakai pun memliki kemampuan akting yang alakadarnya.
Jika film adalah fragmen-fragmen kehidupan yang dikemas dalam gambar yang bergerak, maka film ini hanya berbicara tentang kehidupan yang imajiner. Namun terlepas dari itu semua, ada satu adegan yang menarik dalam film ini. Yakni ketika Bima mentraktir semua orang yang ada di antrian fast food. Dalam perspektif lain ini bisa dimaknai bahwa sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak menjadi Inlander yang menipu diri sendiri akan segala keterbatasan yang dimilikinya sekaligus mengagungkan yang lain.