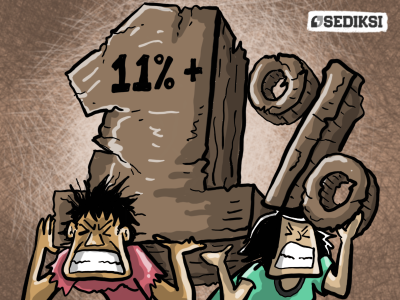Pada akhir 2020, Sediksi memuat artikel A. Arfrian yang berjudul Kami Tak Mau Jadi Petani Bukan Karena Gengsi. Sesuai judulnya, Arfrian hendak mengatakan bahwa problem mendasar dalam dunia pertanian bukan soal anak muda yang gengsi jadi petani, tapi memang negara nggak pernah peduli ama petani.
Betul, anak muda nggak mau jadi petani bukan karena takut item atau nggak keren, tapi, ya, ngertilah,jadi petani di negara yang katanya agraris ini susah.
Kalau nggak percaya, cobalah tonton film dokumenter Negeri di Bawah Kabut atau Negara, Wabah, dan Krisis Pangan. Ente bakal paham kalau kehidupan petani itu miris banget. Dari biaya tanam yang nggak murah, terancam gagal panen, hingga harga tanamannya yang murah.
Karena itu, mbok, ya, Bu Mega sama Pakde Jokowi ini kalau ngomong dilihat dulu realitasnya. Jangan asal-asalan. Di sini saya cuma ngingetin aja, ya. Hehehe.
Sama satu lagi untuk Pakde Jokowi: tolong bilangin ke Pak Prabowo untuk berhenti meneruskan proyek pembangunan infrastruktur. Sebab, petani yang acapkali jadi korbannya. Lahan mereka mesti tergusur dan tak tahu besok harus makan apa.
Pak Prabowo mending nerusin jogetnya aja, deh. Bukankah dengan kegemoyan yang bapak tampilkan dapat membuat banyak orang tertawa riang?
Nah, kembali ke analisis Arfrian soal petani, yang ia sampaikan memang nggak salah, sih. Tapi, ya, kaya ada sesuatu yang sepertinya luput dari pembahasannya tersebut.
Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan Arfrian dalam melihat persoalan petani tadi, yaitu pendekatan populis.
Gampangnya, cara pandang ini mengandaikan petani sebagai kelompok homogen, di mana mereka saling tolong-menolong dan guyub rukun untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Sehingga, problem yang mereka hadapi bukan berasal dari dalam kelompoknya sendiri, melainkan dari luar, yang berwujud pada kebrengsekan negara atau korporasi.
Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa dua hal tersebut dapat menjadi momok bagi kesejahteraan petani, ada faktor lain yang juga tak kalah penting untuk dicermati dalam melihat persoalan ini.
Nah, berangkat dari hal ini, saya akan mencoba melihat persoalan petani dari kacamata pendekatan yang lain, yaitu pendekatan kelas.
Tak Semua Petani Itu Sengsara, lho!
Berbicara soal desa, saya sebenarnya sudah muak dengan anggapan banyak orang yang acapkali meromantisirnya: bahwa desa adalah lokus yang sejahtera dan makmur.
Di sana diandaikan bahwa orang saling peduli satu sama lain dan bersedia mengulurkan tangan ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Dari situ, muncul semacam keyakinan bahwa hidup di desa lebih baik ketimbang di kota, sekalipun minim fasilitas dan teknologi.
Akan tetapi, kalian tahu nggak, sih, kalau anggapan itu sebenarnya warisan Orde Baru?
Dalam penelitiannya yang berjudul Capitalism and Agrarian Change: Class, Production and Reproduction in Indonesia, Muhtar Habibi mengatakan bahwa warisan tersebut telah berperan dalam mengaburkan realitas sosial dalam kehidupan pedesaan.
Untuk meng-counter pandangan seperti itu, Habibi pun menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan terformat ke dalam struktur sosial yang timpang, tidak homogen seperti anggapan banyak orang.
Di dalamnya dapat dijumpai kelas petani kapitalis (tuan tanah) yang memiliki lahan besar, kelas Produsen Komoditas Kecil (PKK) yang memiliki lahan kecil, dan kelas buruh tani yang tak memiliki lahan sama sekali.
Di sini, pendapatan petani kapitalis sangatlah besar, yang mana dapat digunakan untuk membeli barang-barang mewah, menyekolahkan anak mereka ke universitas ternama, dan mengakses layanan kesehatan yang memadai.
Berbanding terbalik dengan pendapatan PKK yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta pendapatan buruh tani yang sama sekali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam konteks reproduksi, petani kapitalis cenderung akan terus membeli lahan tanpa pernah peduli bila tetangganya yang buruh untuk makan saja harus kerja ngos-ngosan.
Sementara bagi kelas-kelas terbawah masyarakat pedesaan, membeli tanah tak akan pernah sedikitpun terlintas dalam bayangan mereka.
Untuk PKK, mereka mungkin dapat menambah penguasaan lahannya ketika kondisi pasar sedang baik-baiknya. Namun, ketika pasar menampakkan wajah yang predatoris, mereka beresiko jatuh menjadi buruh tani.
Pertentangan antar kelas ini terjadi dalam realitas sosial kehidupan pedesaan. Misalnya, petani kapitalis tak akan rela membiarkan buruhnya selonjoran menikmati kopi saat jam kerja.
Sementara mereka yang tenaga kerjanya dibeli akan mencoba curi-curi waktu untuk menikmati sejuknya sawah saat tuan-tuan mereka sedang tidak mengawasi.
Selain dapat membantu kita lebih memahami realitas masyarakat pedesaan atau pertanian, pendekatan kelas juga berguna untuk melihat persoalan konflik agraria yang disinggung oleh Arfrian dalam tulisannya.
Dalam penelitiannya yang berjudul Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa: Pembangunan Bandara dan Dinamika Kelas di Yogyakarta, Wida Dhelweis Yistiria menunjukkan bagaimana perbedaan posisi kelas menentukan dimensi perlawanan dan reproduksi ketika terjadi konflik agraria.
Di sini, buruh tani dan PKK adalah kelas yang paling ngotot melawan pembangunan bandara karena sawah dan tegalan adalah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Sementara petani kapitalis kebanyakan tak terlalu peduli sebab mereka akan mendapatkan ganti rugi yang besar.
Di saat sawah dan tegalan sudah tergusur, petani kapitalis akan berganti profesi menjadi juragan kos atau kontrakan, sedangkan PKK berubah posisinya menjadi buruh tani, dan beberapa dari buruh tani berubah menjadi pengangguran.
Lewat pendekatan kelas, kita akhirnya bisa memahami bahwa tak semua petani itu hidup sengsara. Hampir sulit membayangkan kehidupan seperti itu akan menimpa petani yang memiliki banyak lahan.
Dan apabila lahan mereka tergusur, kondisi penghidupannya pun kemungkinan besar tak akan banyak berubah.
Kalau Pengen Anak Muda Jadi Petani, Jalanin Reforma Agraria Dulu, Dong
Bagi siapapun pejabatnya, entah itu Bu Mega, Pakde Jokowi, Pak Prabowo, atau Opung Luhut, kalau memang niat ngajak anak muda jadi petani, ya, jalanin Reforma Agraria dulu, dong!
Eh, tapi, bukan Reforma Agraria yang tujuannya hanya untuk memperbesar dan memudahkan korporasi menguasai tanah dalam skala besar sebagaimana Pakde Jokowi lakukan, ya (Dianto Bachriadi: 2023, 74).
Yang dimaksud ialah Reforma Agraria dalam arti sejatinya, yaitu perombakan dan pengubahan pola penguasaan lahan.
Dalam hal ini, mereka yang memiliki tanah yang besar harus dibatasi dan kemudian dialihkan kepada mereka yang memiliki lahan kecil atau tak memiliki lahan sama sekali.
Lalu, mengapa program ini menjadi sangat penting? Sebab, nggak semua anak muda bapaknya itu petani kapitalis, woi!
Maksudnya, ya, gimana mau bertani kalau lahannya aja kagak ada. Mending ngonten di Youtube atau Tiktok. Apalagi beberapa konten yang menampilkan kehidupan dan keseharian pedesaan juga cukup diminati.
Baca Juga: Tidak Ada Thunda dan Samin Hari Ini
Makanya, persoalan rendahnya minat anak muda buat jadi petani itu jangan dilihat dari sekedar gengsi atau nggaknya, tapi liat juga soal akses atas kepemilikan lahan. Pada titik inilah pengimplementasian Reforma Agraria sejati dapat memainkan peran signifikan.
Lebih lanjut, program ini juga sebenarnya dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi produktivitas pertanian, lho. Sebab, ketimpangan penguasaan lahan memang minim menghasilkan produktivitas lahan yang optimal.
Oleh karena itu, melalui Reforma Agraria, anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Bahkan, mereka dapat mewujudkan perekonomian yang berdikari karena bisa memproduksi pangan sendiri tanpa bergantung pada impor.
Dan semua ini bisa terealisasai karena Reforma Agraria memang bertujuan untuk memosisikan mereka sebagai tuan dan bukan buruh di negeri sendiri.
Baca Juga: Indonesia 2045: Kuning Belum Tentu Emas