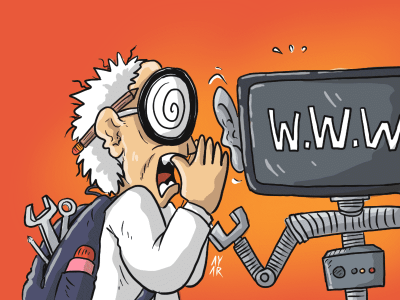Malam ini gerimis turun dan saya sedang menggarap artikel ‘Lagi anget’ untuk dipublikasi besoknya. Di tengah buntunya mencari kata kunci buat ditulis, tiba-tiba saya teringat kalau 9 Februari adalah perayaan yang kebetulan ‘diresmikan’ Pemerintah sebagai Hari Pers Nasional.
Sebelum menulis lebih panjang, (setengah memaksa) saya minta izin terlebih dahulu kepada editor untuk menuliskan ini. Saya tak yakin apakah tulisan berikut akan sesuai dengan prinsip-prinsip SEO.
Tapi setidaknya tanggung jawab artikel harian sudah saya tunaikan. Toh kalaupun ditolak, hitung saja itu sebagai hutang yang akan saya bayar di waktu lain.
Yap lanjut, beberapa waktu lalu seorang kawan menawari saya sebuah proyek optimasi website di media barunya. Karena saat itu nganggur dan tanggungan akademik juga lagi santai-santainya, saya iyakan saja tawaran tersebut dengan justifikasi yang cukup naif: “ya, itung-itung buat pemanasan skripsi, kan!”
Dalam pekerjaan menulis, sebetulnya saya tak begitu terobsesi dengan gaji atau imbalan apalah itu, kecuali dalam kondisi tertentu. Karena sepanjang pengalaman yang tak seberapa selama menjadi awak Persma, uhuk, saya berpikir menulis adalah satu upaya eksperimental saya untuk menaklukkan diri sendiri.
Bagaimana saya menantang payahnya belajar mengolah kata, merangkai kalimat terstruktur, berdarah-darah mengasahnya, semua penderitaan ini akan terus saya nikmati. Terkadang saking sukanya dengan tulisan, saya bahkan tak segan mempertaruhkan kesehatan sendiri.
Saya katakan itu pada kawan saya selepas ia menjelaskan sedikit briefing jobdesc. “Udah, urusan itu (fee dan tetek bengek) gampang nanti,” dan ia pun memahami. Obrolan berlanjut hingga bagaimana masing-masing dari kami melihat disrupsi ‘pers’ era kini. Cuok, fafifu.
Saya santai saja saat ia menyampaikan pandangannya sampai sejurus kemudian ia melontarkan pertanyaan: “kamu gapapa ta kalo misal kerjaan nulis ini bikin idealismemu luntur?”
Oh jelas, sebagai mantan awak persma yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai idealis jurnalisme Ignatius Haryanto, saya bilang saja: “bentar, tak mikir.”
Ya benar saja, siapa yang siap dengan pertanyaan-ngehe-yang-tiba-tiba ini? Akhirnya saya pastikan kembali maksud demi maksud pertanyaan dia dan mempertegas lagi luntur seperti apa.
“Di industri media sekarang, para jurnalis dituntut untuk pragmatis,” dengan penuh kehati-hatian ia menjelaskan, “nanti kamu gak akan nemuin tulisan-tulisan soal perjuangan, pergerakan, atau kritik sosial.”
Saya menghela napas sejenak kemudian reflek teringat kiprah sang perintis pers nasional asal Blora yang namanya pernah saya comot buat nge-cheat biar bisa masuk organisasi persma, Tirto Adhi Soerjo. Juragan media pada masanya yang namanya diabadikan jadi nama media besar oleh pelopor media online Sapto Anggoro.
Sambil menyiapkan jawaban yang tertata, saya berpikir mungkin untuk inilah saya menulis.
Peringatan Hari Pers yang Problematik
Ada satu cerita menarik tentang tentang Hari Pers Nasional ini. Suatu hari pada 9 Februari, saya masih mengisi posisi jaringan eksternal di sebuah LPM saat salah satu anggota kami berinisiatif membuat postingan sosial media untuk memperingati perayaan tersebut.
Dari malamnya draft sudah disiapkan dengan cepat, rapi, dan tanpa koordinasi. Saya merasa kecolongan, namun postingan sudah terlanjur terpublikasi. Saya memintanya sebagai admin untuk take down unggahan terkait.
Pada awalnya, saya sebetulnya tak pernah mengerti alasan penolakan terhadap peringatan tersebut. Hanya sesekali membaca sebuah artikel bahwa apa yang diperingati sebagai Hari Pers selama ini cukup problematik.
Dalam artikel tersebut dituliskan, ide memperingati tanggal 9 Februari sebagai peringatan hari besar Pers di Indonesia sudah lama diusulkan sejak tahun 1978. Tepatnya saat kongres ke-16 Persatuan Wartawan Indonesia yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat.
PWI sendiri saat itu dipimpin oleh Harmoko. Ya, kamu gak salah dengar, seorang wartawan veteran pemimpin redaksi Pos Kota yang kelak menjabat sebagai Menteri Penerangan era Orde Baru.
Sudah kenyang kita mendengar berita pembredelan media pada masa itu; pembungkaman, penghilangan jurnalis yang kontra orba, atau pelintiran tentang harmoko hari-hari omong kosong. Puncaknya era reformasi, Menteri Penerangan akhirnya dibubarkan oleh Presiden Gus Dur.
Lalu, apa yang salah dengan peringatan hari Pers bertepatan dengan hari lahir PWI? Penetapan hari Pers nasional diresmikan lewat Keppres Nomor 5 Tahun 1985 pada masa pemerintahan Soeharto yang saat itu mengusung sistem sentralisasi total.
Setiap organisasi diatur menurut ‘wadah tunggal’, dari setiap profesi hanya diakui satu wadah organisasi resmi. Buruh hanya boleh SPSI, dokter harus ikut IDI, guru PGRI, dan lain-lain. Dengan begitu, setiap kelompok masyarakat akan mudah untuk dikontrol dan dibuat tunduk pada Pemerintahan.
Masalahnya pasca Soeharto tumbang, PWI bukan lagi satu-satunya organisasi yang mewadahi para jurnalis. Namun tak ada upaya mengoreksi dari pihak Pemerintah. Bahkan untuk sekadar menanyakan: apa betul kita butuh Hari Pers Nasional?
Pada prinsipnya, jurnalisme nasional, asing, ataupun lokal, semuanya melebur jadi universal. Yang membedakan hanyalah segmentasi konten.
Lagian kalau mau ngomongin nasional, PWI bukanlah organisasi pertama pers yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, pada masa kolonial, Mas Marco Kartodikromo, juga berasal dari Blora, sudah membentuk Inlandsche Journalisten Bond (IJB) pada tahun 1914.
Jadi, jika Hari Pers Nasional diusulkan berdasar pada hari lahir satu organisasi saja, maka setiap wadah wartawan hendaknya punya lebarannya masing-masing. Tanpa perlu menjilat anggaran Negara.
Karena Hari Pers Nasional yang sekarang ini dibuat dan disahkan pada masa Orde Baru, maka gausah heran kalau karakternya… Duh.
Saya capek. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan salah satu berita seorang wartawan yang selama ini diketahui ternyata bagian dari BIN diangkat jadi Kapolsek di daerah Blora, lagi. Dan konon, wartawan yang bertugas sebagai kontributor di TVRI wilayah Pati tersebut juga anggota PWI.
Ya, saya sentimen sama PWI. Belum lagi kalau ingat pernyataan mantan ketua PWI pusat dua periode yang juga pernah mencalonkan diri pada pemilihan Bupati Tulungagung, Margiono, bahwa wartawan harus tunduk sama pemilik media. Kalau gak mau ya bikin media sendiri aja.
Jurnalisme tak lain merupakan sistem yang ditelurkan masyarakat untuk memasok berita. Itulah mengapa kita patut peduli pada karakter berita serta produk jurnalisme yang kita dapatkan. Mereka memengaruhi hidup, pikiran, dan budaya kita.
Saya katakan ini sekaligus menjawab pertanyaan kawan tadi menyoal idealisme pers yang luntur. Menulis artikel lintas topik dengan ketentuan ramah pembaca menurut kalkulasi mesin bukanlah sesuatu yang melunturkan idealisme.
Menurut saya, justru di situ tantangannya. Meminjam ungkapan Albert Camus, “itulah kebebasan, saat kau tidak diberi kebebasan.”
Saat menuliskan berita soal gosip adalah kebosanan, berita olahraga yang menjemukan, barangkali di situlah kreatifitas jurnalis sedang diuji. Mengungkap trivia menarik pada artikel yang kurang nyambung seperti wisata? Atau menyempilkan quote tokoh perjuangan pada berita otomotif? Hmm, terdengar revolusioner.
Sejauh ini, saya masih meyakini bahwa mungkin yang dimaksud dengan ‘idealisme luntur’ itu adalah saat seorang jurnalis tak punya karakter tulisan dan tunduk pada apa yang disebut Tirto sebagai ‘yang memrentah’.
Jadi ya, begitulah. Selamat, oh tidak, saya tidak mengakui Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari. Selamat dilantik jadi Kapolsek Iptu Umbaran, uwow!
Baca Juga: Kasak-Kusuk Media Online di Malang