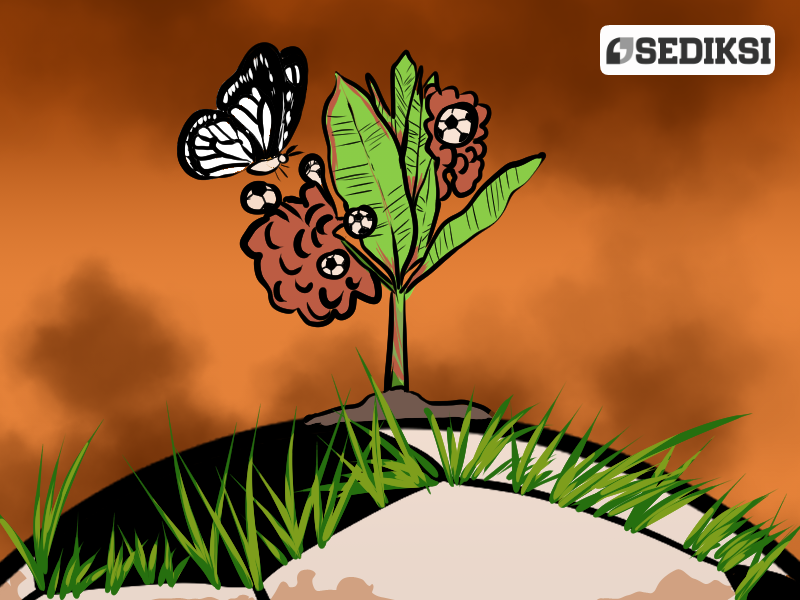Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika sepak bola di Indonesia diramaikan dengan munculnya berbagai klub sepak bola alternatif. Berbagai klub tersebut bergerak di akar rumput dan dikelola oleh para suporter.
Fenomena ini bukan hanya menjadi suatu gebrakan baru, melainkan juga menjadi sebuah pertanda sekaligus respon. Tanda-tanda itu barangkali bisa kita lihat melalui bagaimana situasi global sepak bola arus utama di Indonesia bergulir.
Lalu, apa yang membuat kehadiran klub-klub alternatif tersebut menjadi penting?
Membangun Budaya Tandingan
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh FREEDOM: Anarchist Media, Publishing, and Bookshop, Gabriel Kuhn, seorang penulis, anarkis, dan mantan pesepakbola semi-profesional asal Austria pernah mengatakan bahwa sebagai cabang olahraga rakyat, sepak bola menemukan kekuatannya ketika saling terhubung dengan kekuatan massa dan kolektivitas.
Baginya, kedua hal itu bisa membuat sepak bola menjadi lebih terjangkau sekaligus bisa membuatnya menjadi medium dalam mengakomodir berbagai kepentingan rakyat—termasuk sebagai medium dalam membangun budaya perlawanan.
“Jika Anda fokus pada peran sepak bola sebagai permainan massa, maka hal itu dapat berfungsi sebagai media untuk menantang penguasa,” ucap Kuhn.
Namun, sebagai cabang olahraga yang sangat populer, sepak bola sangat rentan ditunggangi oleh banyak pihak (dan kepentingan)—termasuk oleh para pemodal yang membuat olahraga ini bukan lagi sebatas olahraga rakyat, melainkan sebagai kepentingan bisnis.
Pada titik ini, sepak bola menjadi sangat politis sebab keberadaannya bergantung pada siapa yang berkuasa dan mengendalikannya, juga untuk kepentingan apa ia digunakan.
Seperti yang pernah terjadi di Inggris. Pada 2005, sekelompok fans Manchester United memutuskan untuk membentuk sebuah klub bernama FC United of Manchester.
Klub tersebut dibentuk sebagai aksi protes terhadap pengelolaan Manchester United pasca diambil alih oleh Malcolm Glazer, bohir asal Amerika Serikat yang secara sah membeli saham MU dengan cara berhutang.
Lantaran latar belakang Glazer sebagai pebisnis alih-alih seseorang yang memang mencintai sepak bola, ia memilih cara-cara yang paling busuk dalam usahanya membayar hutang. Salah satunya dengan membebankan biaya tersebut kepada para suporter. Caranya: menaikan harga tiket pertandingan.
Pada tahap yang paling ekstrim, keputusan Glazer itu mencerminkan bahwa klub tidak lagi memandang suporter semata-mata sebagai pendukung, melainkan sebagai konsumen yang bisa setiap saat diperas uangnya dengan menjual mitos-mitos loyalitas.
Kondisi itulah yang kemudian membuat sebagian fans kecewa, dan pada gilirannya membentuk FC United of Manchester sebagai klub tandingan dari Manchester United.
Di Indonesia, kondisi sepak bola nasional masih mencerminkan sepak bola tarkam alih-alih sepak bola industri. Saya melihat ada beberapa faktor yang mendasarinya, mulai dari pengelolaan sampai infrastruktur, dari paradigma hingga ekosistem.
Kita bisa dengan mudah melihat carut-marutnya pengelolaan sepak bola nasional di bawah naungan PSSI.
Tapi, meski begitu, gelombang industrialisasi bisa saja muncul tiba-tiba seiring dengan kepentingan pasar yang harus cermat melihat celah dalam memperluas keuntungan.
Kondisinya barangkali masih abu-abu. Tapi setidaknya, ada gejala-gejala yang bisa dilihat sebagai prasyarat, seperti harga tiket yang kian mahal, munculnya berbagai peraturan yang mengekang kebebasan suporter, persekongkolan antara pemodal dengan manajemen klub, dan upaya penundukan suporter melalui berbagai cara yang dilakukan oleh para elit.
Dampaknya bisa diprediksi: upaya-upaya itu bisa membentuk iklim sepakbola di Indonesia menjadi sangat ramah bagi kepentingan industri, dan pada saat yang sama, mendepolitisasi suporter dan menjauhkannya dari ide-ide kritis soal sepak bola.
Akhirnya, tidak sedikit orang merasa muak dengan kebijakan federasi terkait dengan pengelolaan sepak bola nasional. Kondisi demikianlah yang kemudian mendorong sekelompok suporter membentuk klub sepak bola alternatif.
Baca Juga: Saya Memilih Jadi Suporter yang Biasa Saja
Setidaknya, hingga saat ini, berbagai klub alternatif tersebut bermunculan di berbagai daerah, seperti misalnya Riverside Forest FC dari Bandung, Tribun Kultur FC dan Port City Wanderers dari Jakarta, Rainfall FC dari Bogor, Urbanside FC dari Bekasi, dan baru-baru ini, Kaliburg FC hadir dari Purbalingga serta Fortress VB dari Tangerang.
Dari data yang saya baca, setidaknya ada kesamaan motif yang melatarbelakangi terbentuknya berbagai klub tersebut. Sebagian besar merasa muak dengan pengelolaan sepak bola oleh federasi dan sebagian yang lain merasa harga menonton pertandingan kian mahal dan sulit dijangkau.
Selebihnya, klub tersebut dibentuk sebagai siasat untuk merespon berbagai isu—seringkali isu sosial—yang ada di selingkaran mereka. Dari sini, harapan baru tentang sepak bola mulai dibangun kembali.
Melalui klub alternatif, para suporter—yang dalam struktur merupakan pemilik klub—dapat menjadikan agenda-agenda klub sebagai wadah dalam bereksperimen.
Sebagaimana alternatif, berbagai klub tersebut bisa menjadi ruang untuk menjalankan ide dan gagasan yang mereka punya, mengkampanyekan nilai-nilai yang dipercaya, dan menciptakan lingkungan yang inklusif.
Dengan begitu, saya kira klub alternatif bisa menjadi sebuah medium dalam membangun budaya tandingan, atau setidak-tidaknya, mengembalikan lagi wacana kritis dalam obrolan soal sepak bola.
Dan pada saat yang sama, ia menjadi bentuk penolakan para suporter atas tindakan yang sifatnya menjinakkan dan menundukkan, sekaligus upaya merebut kontrol dan mengorganisir diri dari sepak bola arus utama yang kian tergerus gejala-gejala industrialisasi.
Memang, agak sulit membayangkan ide-ide revolusioner dilakukan lewat agenda-agenda klub sepak bola. Tapi, upaya mengorganisir diri dengan membentuk klub alternatif, bagi saya, merupakan langkah awal untuk menciptakan kembali ruang di mana wacana dibicarakan, gagasan diproduksi, dan pertemanan dijalin.
Di tengah carut-marut pengelolaan sepak bola arus utama oleh PSSI, saya menaruh harapan besar pada geliat sepakbola alternatif di akar rumput.
Karena alasan itulah, bagaimanapun bentuknya, inisiasi kecil semacam ini memang perlu diapresiasi, dan kalau tidak berlebihan, juga patut dirayakan.
Tumbuhlah Serupa Gulma, Tapi Mulailah Dengan Mengoreksi Diri
Meski kita seringkali punya bayangan yang ideal tentang harapan, tapi kenyataannya jelas tak sesederhana itu.
Saya senang bahwa ada banyak orang yang punya kesadaran dan semangat yang sama untuk menyiasati keresahan terhadap kondisi sepak bola di Indonesia saat ini. Membentuk klub alternatif adalah salah satu caranya.
Namun, berbagai klub alternatif yang bermunculan tidak lantas membuat situasi berubah sepenuhnya. Pasalnya, mereka muncul secara simultan, namun belum terorganisir dengan baik.
Klub alternatif yang ada saat ini masih berfokus pada dirinya masing-masing alih-alih membentuk satu kekuatan yang bisa melawan status quo. Kondisi inilah yang kemudian membuat klub-klub tersebut belum bisa berbuat banyak.
Dalam gerakan yang membutuhkan basis massa, berjalan sendiri-sendiri justru tidak akan membuat kita kemana-mana. Pondasi yang dibangun rentan untuk tidak bertahan lama.
Kesadaran soal ini barangkali alpa dalam narasi pengorganisiran klub sepak bola alternatif, sehingga banyaknya klub yang muncul tidak berarti membentuk suatu kekuatan tertentu.
Baca Juga: Jangan-Jangan Naturalisasi Hanya Ilusi
Pada titik inilah, klub sepak bola alternatif mesti bebenah. Orang-orang yang punya akses dalam pengelolaannya harus sadar betapa pentingnya berjejaring dengan banyak kelompok, baik itu sesama klub alternatif maupun kelompok-kelompok lain di luar kancah sepak bola.
Cara-cara ini penting dilakukan setidaknya untuk membangun jaringan, memperbaiki ekosistem gerakan klub alternatif, sekaligus juga menciptakan ruang yang inklusif.
Sebab, apabila mereka hanya fokus pada dirinya masing-masing, saya khawatir kondisi itu akan mengantarkan kita pada persoalan lama: masing-masing klub akan menciptakan identitas, citra, dan fanatisme semu, yang dibela berlebihan dengan sikap yang tak berdasar.
Hal-hal demikian justru akan mengantarkan kita pada kehancuran berikutnya. Ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman atas kehadiran klub alternatif dibangun.
Saat ini, ada banyak jargon dan narasi yang dibentuk, tapi nyaris tidak diiringi dengan pemahaman kritis tentang mengapa perlu membangun klub alternatif.
Pemahaman itu mesti diletakan pada kerangka dalam membangun budaya tandingan. Tanpa pemahaman seperti itu, kita rentan terjebak pada situasi mengambang: menganggap agenda klub alternatif sebatas agenda fun football belaka; atau menyuarakan berbagai persoalan tapi berjarak dengan isunya; atau kita tidak tau kepada siapa kita berhak marah.
Karena itulah, klub alternatif mesti memiliki imajinasi yang luas sekaligus politis. Ini setidaknya untuk membentuk suatu agenda yang relevan dengan nilai-nilai alternatif, serta juga untuk mengakumulasi kemarahan kita kepada siapa saja yang membuat kebahagiaan kita atas sepak bola tak lagi sama dan hancur lebur.
Tanpa itu, sulit untuk tidak mengatakan bahwa geliat klub sepak bola alternatif hanya sebatas jargon belaka.