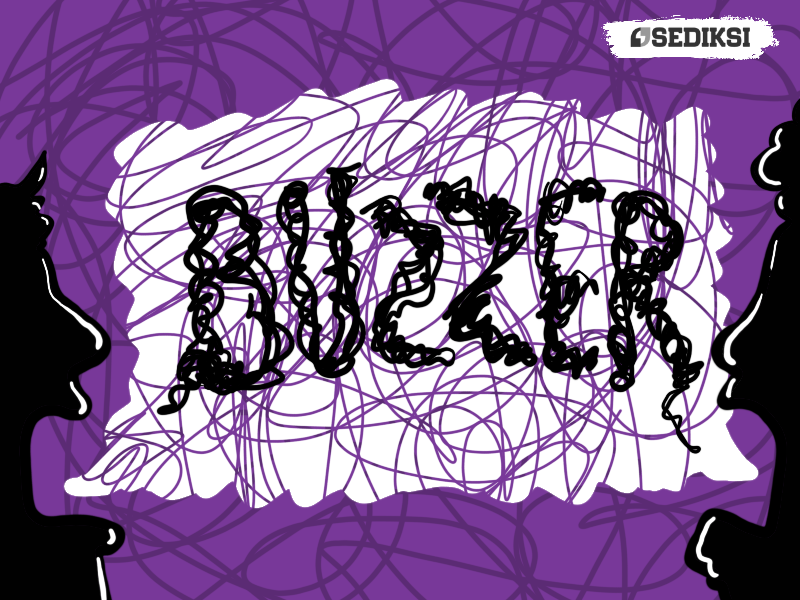Selama mengikuti diskusi seputar politik, ada satu hal yang terkadang bikin saya frustasi dan memutuskan akhirnya menyerah, yakni dituduh sebagai seorang buzzer. Beneran deh! Mood diskusi dan harga diri seketika anjlok kalau sudah terkena tuduhan ini.
Persoalannya bukan pada saya memang buzzer atau tidak—kalau kalian penasaran, saya beneran bukan buzzer, suer!—tapi pada tuduhan itu yang dewasa ini kesannya cukup hina. Benar-benar sudah kayak tuduhan kepada maling, perampok, bahkan mirip-mirip seperti teroris.
Apesnya lagi, sekali saja terkena tuduhan buzzer, maka sekuat apapun pendapat saya atau Anda (yang tertuduh), tetap saja akan tampak buruk bagi si penuduh.
Makin saya melawan dengan data dan fakta, malah makin melekat pula tuduhan itu. Ujung-ujungnya, diskusi pun jadi tak sehat. Dan saya mau tak mau harus menyerah ketimbang tuduhan buzzer makin membabi buta.
Jika kebetulan Anda pernah mengalami hal serupa, entah di media sosial ataupun di warung kopi, maka tenang saja, saya sangat paham perasaan Anda.
Rasanya pasti nggak enak, gelisah, getir, dan jelas merasa amat sangat terhina. Berbagai macam bacaan Anda tentang politik pasti seperti tak ada gunanya kalau sudah terkena cap “buzzer”.
Tapi, tenang saja. Di sini, saya akan mengajak Anda untuk membela diri. Saya coba jelaskan mengapa orang-orang yang sering menuduh itu sebenarnya sedang terjebak dalam silang sengkarut istilah buzzer.
Mulanya, Tujuan Adanya Buzzer Itu Mulia
Jika kita lihat lewat kamus Oxford Dictionaries, makna buzzer ini bisa dimengerti sebagai an electrical device that produces a sound as a signal. Atau Jika disederhanakan lagi, buzzer ialah dengungan bunyi yang berfungsi untuk memberikan sebuah tanda.
Di banyak penelitian soal fenomena buzzer di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), hasilnya juga mengemukakan hal yang hampir senada.
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada mulanya buzzer di Indonesia ini, tepatnya pada tahun 2012, dipakai untuk kebutuhan promosi suatu produk.
Jika pernah mendengar istilah dalam dunia marketing seperti word of mouth alias dari mulut ke mulut, itu sebenarnya bagian dari identitas buzzer.
Tujuannya pun jelas, yaitu untuk memberitahu sebuah produk; untuk membuat orang yang awalnya tidak tahu lalu menjadi tahu.
Baca Juga: Apakah Kita Harus Percaya Pada Pakar?
Beberapa literatur terkait juga menyebut buzzer ini terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, buzzer yang basisnya komersial alias dibayar oleh suatu perusahaan.
Kedua, buzzer organik atau khalayak yang secara sukarela mempromosikan suatu produk karena telah mendapat kepuasan.
Di Indonesia sendiri, buzzer jenis pertama biasanya dari kalangan orang-orang yang punya jaringan luas macam influencer.
Sementara buzzer jenis kedua dari orang-orang biasa seperti kita-kita ini, seperti saya dan Anda yang sedang baca! Xixixi… Orang-orang yang tak punya jaringan luas, tapi punya kepedulian untuk menyebarkan suatu produk karena dirasa berkualitas.
Nah, profesi buzzer pada tahun 2014 silam, khususnya yang berbayar, mulai digunakan di Indonesia untuk kepentingan politik. Meski demikian, tujuan adanya buzzer dalam konteks politikini sebenarnya tetap mulia.
Sebab, ia secara teoretis berfungsi untuk memberitahukan produk politik kepada rakyat yang dirasa belum mendapat pengertian gamblang.
Di Media Sosial, Fungsi Buzzer Tampak Buram
Sayangnya, seiring masifnya penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi, fungsi buzzer menjadi berubah, terutama saat situasi politik lagi panas-panasnya.
Entah itu buzzer bayaran maupun organik, keduanya sering kali justru memperkeruh pembahasan politik di media sosial.
Kita bisa lihat sendiri betapa media sosial menyediakan kebebasan yang cukup radikal kepada penggunanya. Media sosial tak punya batasan-batasan layaknya di jurnalistik dalam penyebaran informasi.
Sehingga, siapapun penggunanya, dia pasti punya kebebasan untuk memproduksi konten, sekalipun tanpa akurasi informasi yang kuat.
Ditambah lagi, dalam situasi politik, selalu tidak lepas dengan fenomena polarisasi. Misalnya pemilu 2024 kemarin, kita tahu sendiri betapa panas dan peliknya ruang publik di media sosial.
Baik netizen pendukung Anies, Prabowo, maupun Ganjar, sebagian dari mereka sama-sama militan dalam membela paslon dukungannya.
Sebenarnya, perihal militansi mereka dalam membela tidak begitu masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka saling membela paslon dukungannya dengan cara yang tidak diskursif dan cenderung kill the messenger.
Bahkan, sepanjang saya mengamatinya, beberapa netizen tanpa ragu memanipulasi informasi demi citra paslon dukungannya tampak sempurna.
Sialnya lagi, mereka yang kepalang nyaman mengonsumsi informasi secara mentah; yang tak tahan untuk memverifikasi sebelum menelan, kerap kali termakan oleh produk politik yang manipulatif tersebut.
Akhirnya, fungsi buzzer pun tampak buram. Ia tidak lagi jelas dilihat sebagai subjek yang memberitahu produk-produk politik yang berkualitas.
Ia justru cenderung dikenal sebagai subjek yang memberi informasi sensasional demi kepentingan komersil ataupun eksistensinya di media sosial. Itulah kenapa, istilah buzzer terkesan buruk, hina, dan mirip-mirip seperti teroris.
Musuh Kita adalah Pesannya, Bukan Orangnya
Jika kita tarik lebih luas lagi, istilah buzzer ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai fitrahnya manusia. Maksudnya, ketika kita punya informasi, gagasan, atau pemikiran yang dirasa berkualitas dan ingin membicarakannya pada orang lain maka kita sangat mungkin menjadi seorang buzzer.
Dalam konteks media sosial pun sama. Saat kita memposting atau membagikan suatu postingan yang dirasa baik, seketika itu juga kita bisa disebut sebagai buzzer dari postingan itu sendiri.
Jadi, buzzer seyogianya hanyalah istilah lain daripada orang atau netizen yang aktif bersosialisasi. Hanya saja, istilah itu lebih jamak diperuntukkan pada dunia marketing.
“Tapi, Bwang… buzzer ini, kan, sering kali memberi informasi yang buruk serta hoaks?”
Yep, betul, saya juga sepakat. Tapi, yang patut kita musuhi bukanlah orang atau profesinya sebagai buzzer. Melainkan informasi yang ada dalam pesan si buzzer itu.
Ya, seperti petuah yang sering kita dengar, bahwa diskusi itu lihat lah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan.
Jadi, kalau kedepannya ada diskusi-diskusi politik lagi, kemudian Anda tidak sepakat dengan paslon tersebut lalu dianggap buzzer, maka tak usah merasa terhina. Mending iyain aja. Kan, lakon menang keriiii…he he, sekian terima gaji!!