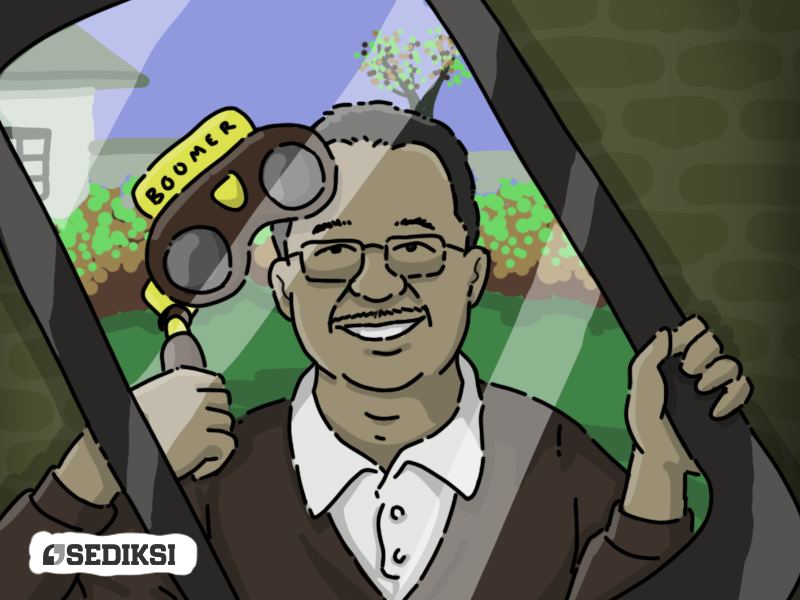Baru jalan separo durasi, rasa sebal sudah menjalar di sekujur diri saya. Bagaimana tidak, video Rhenald Kasali yang membahas Gen Z sangat kebak stigma dan analisis yang timpang.
Mana judulnya clickbait banget pula. Isinya menyoal Gen Z yang disebutnya serba instan dan tidak mau rugi (saya wegah melampirkan pranala kontennya, enak banget dia dapat adsense dari konten yang pincang itu).
Masalahnya, bukan hanya satu konten itu saja di mana Rhenald menyoal anak muda, khususnya Gen Z. Guru besar populer ini banyak memproduksi narasi seputar kaum muda dengan sebutan generasi stroberi, cerdas tapi rapuh, hingga full-time children.
Usai mengonsumsinya, saya yang sangat jarang komen ini akhirnya tergerak untuk menulis di komentar konten dia dan berniat menulis topik ini secara spesifik.
Baca Juga: Ketika Gen Z Jadi Bahan Bully Generasi Sepuh
Overgeneralisasi dan Kebak Stigma
Walau sudah geram sedari awal, tapi konten-konten dia saya tuntaskan hingga detik terakhir. Titik berat narasi Rhenald di konten itu sarat logika pasar. Langgam narasi dari sosok yang sangat business-oriented.
Misal, ia mengkritik Gen Z yang kurang daya juangnya dan mudah pindah kerja. Ini kemudian diikuti dengan tuduhannya kepada Gen Z yang tidak bertanya soal “bagaimana, ya, agar saya jadi karyawan teladan?”; “bagaimana agar karier saya bagus supaya saya bisa betah bekerja dan tambah baik di sana?”
Sepintas, pertanyaan itu bermuatan optimisme dan sarat nilai motivasional. Hanya saja, ia luput mengulik persoalan yang lebih kompleks, lebih dalam.
Ia seperti menutup mata pada sisi gelap dunia kerja dengan kapitalisme tanpa rem hari ini. Jadi, pertanyaan sugestif-individual seperti yang Rhenald sampaikan itu, pada level tertentu, bisa mendongkrak semangat kerja individu.
Namun, di level berbeda, justru mengabaikan masalah struktural dan “kejahatan korporasi” yang eksploitatif serta tidak memberi jaminan sosial yang semestinya diberi perhatian lebih.
Tapi, silakan maklum saja. Rhenald ini guru besar ilmu manajemen bisnis. Wajar kalau logikanya terkooptasi pasar dan sangat bias kelas.
Ia didikte, baik secara sadar atau tidak, oleh logika pasar di mana korporasi ingin selalu karyawannya (dalam hal ini Gen Z) agar manut dan menjaga kesehatan ‘metabolisme’ keuangan perusahaan.
Ia tidak menggali kajian generasi muda secara lebih pepak, terutama dari kacamata sosio-antropologis. Tak heran kalau dia asal comot riset, asal petik testimoni yang cuma secuil, lantas gebyah-uyah (overgeneralize), seolah semua Gen Z itu seperti yang dia pahami.
Satu contohnya, Rhenald menceritakan testimoni dari generasi senior yang punya karyawan Gen Z. Ia mengeluhkan alasan Gen Z yang izin gak kerja “hanya” karena kucingnya sedang sakit.
Tamsil kecil tersebut, kendati riil, sama sekali tidak layak dipakai untuk menggeneralisasi. Ini jelas-jelas falasi, cacat nalar, jenis hasty generalization (silakan cari sendiri, sob). Seolah Gen Z semuanya se-sembrono itu. Seakan mereka tidak punya integritas di dunia kerja. Sangat layak kena semprot: your eyes!
Sarat Nada Defektologi
Ada satu hal lagi yang sulit diabaikan dari Rhenald Kasali, yaitu nada narasinya. Mungkin ini subjektif, tetapi belum tentu salah.
Ada kesan kalau Rhenald ini sejenis boomer yang sangat berbakat untuk sambat terhadap generasi muda, alih-alih punya kesediaan untuk mendengar sambatan dari mereka (Gen Z).
Narasi timpang darinya itu yang bikin makin menyesatkan. Ia lebih sering memakai logika deduktif (top-down), suka cherry-picking data dari testimoni doang, dan bias kelas pula.
Saya curiga dia belum pernah baca liputan serial dari Project Multatuli berjudul Underpriviledged Gen Z. Isinya tentang hal-ihwal Gen Z yang kurang beruntung, suram, miskin, nebeng WiFi, kerja kasar, dan potret getir, tetapi tidak pernah ditampilkan media mainstream.
Rhenald Kasali juga terjebak pada narasi norak tentang “defektologi kepemudaan”. Sebuah pandangan yang menilai “selalu ada yang salah dan cacat” dengan anak muda (Suzanne Naafs & Ben White, 2012).
Pola begini menunjukkan suatu sikap yang kurang kritis dan menaruh bobot lebih ke sikap kepemerintahan (governmentality), alih-alih kesediaan untuk meneliti kerentanan dan aspirasi riil dari suara anak muda itu sendiri. Lihat, khas boomer elite yang nyebelin, bukan?
Ia lupa kalau masih banyak di luar sana Gen Z yang pontang-panting hanya demi hidup. Masalah struktural hari ini pun bukannya mereda, justru makin menggila. Ya itu dosa-dosa generasi tua, dong!
Wong siapa yang lahir duluan, yang justru menetaskan regulasi yang tidak berpihak pada generasi hari ini. Lingkungan dirusak. Kerja makin sulit (BPS: 15,6 juta peluang kerja formal 2009-2014 menjadi hanya 2 juta pada 2019-2024). Properti dimonopoli hingga harga meroket.
Betapa apesnya Gen Z yang lahir di negera korup bernama Endonesu ini: Juara 2 ketidakjujuran akademik versi peneliti Republik Ceko, Vit Machacek & Martin Srholec, dan Juara 2 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN.
Pesan untuk Boomers Tukang Sambat
Bagi para pencela/penyinyir Gen Z secara umum, termasuk juga Rhenald Kasali, tolong dipahami. Kerja ilmiah itu bukan cuma top down dari buku, terus dicocok-cocokin ke realitas.
Tapi, ambil data, riset dulu, baru tangkap polanya, benarkah Gen Z semuanya seperti yang dirimu sampaikan?
Toh, di sini, banyak yang ngepel di restoran pagi-pagi, gaji kecil, tahunan bekerja dan belum resign juga. Ada juga yang merintis usaha kreatif berlapar-lapar dulu.
Guru besar bidang manajemen bisnis ini asal njeplak. Baca buku sak thil, langsung gebyah uyah. Jika pun benar ia membaca riset-riset di jurnal, itu tidak lantas menjustifikasi stigma terhadap generasi Z yang kadung ia lemparkan.
Dan sekalipun dia guru besar cum influencer, tidak lantas membuat apa pun yang keluar dari mulutnya itu sahih dan benar.
Ada namanya argumentum ad verecundiam (atau ab auctoritate), kesesatan berpikir yang membuat orang terkecoh hanya karena pihak yang menyampaikan itu punya otoritas (wewenang atau marwah).
Lagi pula, dalam ilmu, selalu ada falsifikasi: bahwa setiap hal bisa salah. Setiap sesuatu bisa dipersoalkan.
Itu sebabnya, perlu penyeimbang narasi. Fungsinya untuk menangkal konten-konten yang terlalu menyudutkan dan mencacatkan anak muda—yang padahal adalah juga korban dari problem yang lebih kompleks (bukan berarti victim mentality, ya).
Penting juga menyodorkan gambaran yang lebih komprehensif. Tidak cuma satu sisi, apalagi dari testimoni secuil.
Gini, kok, ya, banyak yang percaya dan nggak mengkritisinya? Orang Endonesu memang gampang silau pada embel-embel, sematan-sematan gelar wa pangkat, padahal isinya kopong.
Orang kita, seperti ketus Mochtar Lubis puluhan tahun silam, sangat munafik, feodal, percaya takhayul, dan malas berpikir, termasuk juga guru besarnya. Asal comot saja analisis dari luar, padahal bisa saja populasi riset itu sangat tidak klop jika diterapkan ke konteks Indonesia.
Saran untuk orang seperti Rhenald: bapak, sih, mainnya kurang jauh. Berkutat di Jabodetabek doang, itu pun di kawasan elite.
Sesekali main lah ke gang-gang kecil, di pelosok desa, melihat realitas di sekitar. Masak gubes influencer kalah sama kreator konten travelling?
Pesan Untuk Gen Z
Anak-anak muda harus menolak berkompromi pada penyesatan publik. Semestinya, orang yang punya corong sebesar Rhenald kudunya mengamati secara lebih kritis dan mengambil angle yang berbeda, yang mungkin jarang diliput media-media bahkan luput dari analisis akademik di jurnal-jurnal internasional.
Bagi Gen Z, tetaplah melawan. Biarkan orang lain menyebut dirimu kutu loncat. Ludahi mereka. Toh, bukan mereka yang menyusui dan membesarkanmu sedari kecil.
Kalian punya hak untuk membuat keputusan hidup, selama tidak merepotkan orang lain dan tidak membuat orang tua kewalahan.
Jika memang banyak yang mengeluh Gen Z sekarang lemot-lemot dan kurang daya juang, jawab saja: “ya, itulah produk kalian, wahai orang-orang tua!”
Wajarlah, wong kelakuan kalian kaum tua sangat destruktif. Batubara digenjot, ekonomi mbrosot. Kita jadi warga negara terbesar dalam hal konsumsi mikroplastik, jadi, ya, wajar kalo mager, lemes, dan loyo. Lha, nutrisinya dari plastik!
Oke, iya, iya. “Daya juang tanpa berharap hasil” sebagai etos hidup memang bagus. Tapi, stoplah bersikap munafik!
Akui saja, banyak di antara kami-kami ini yang masih di strata sosial yang “bingung milih antara beli bensin untuk pergi keluar menjalin networking atau beli makan.” Gimana bisa berjuang tanpa berharap hasil, njir.
Terakhir, jangan mudah kagum sama orang, meskipun guru besar. Pakai otakmu sendiri agar kita semua terhindar dari sindiran Nietzsche: “terkadang orang-orang tidak ingin mendengar kebenaran, karena mereka tidak ingin ilusi mereka rusak.”
Apalagi kalau melibatkan psikologi fandom, makin rumit. Lebih sulit meyakinkan seorang penggemar kalau dirinya ditipu, ketimbang meyakinkan dia kalau di kamarku ada ular berkepala asu.