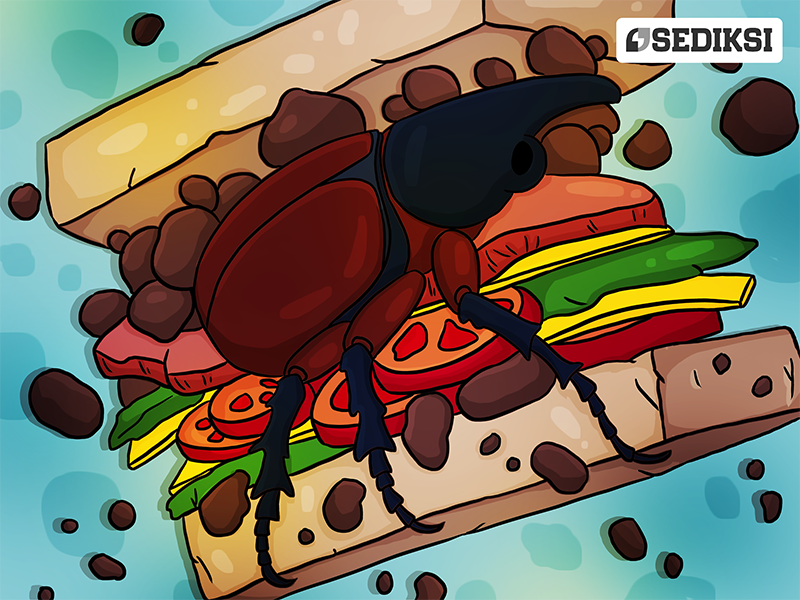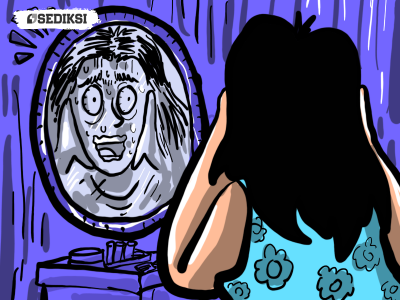“As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he found himself transformed in his bed into a gigantic insect.”
Franz Kafka berhasil menyihirku dengan kalimat pembuka ini, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Eka Kurniawan pada buku jagoannya Cantik Itu Luka.
Keduanya memiliki cara yang menarik untuk membuat pembaca merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi di dalam cerita mereka.
Benar juga yang dikatakan Kafka soal membaca, “I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we’re reading doesn’t wake us up with a blow to the head, what are we reading for?”
Baca Juga: 5 Novel yang Wajib Kamu Baca Sebelum Wisuda
The Metamorphosis adalah salah satu buku yang meninggalkan bekas begitu kuat untukku. Tidak hanya dari kisahnya yang tragis dan meninggalkan kesan absurd setelah membacanya, tapi juga dari bagaimana Kafka merepresentasikan keresahan yang terasa begitu dekat dengan generasi-generasi setelahnya.
Sehingga, bagiku, karya yang pertama kali dipublikasikan pada 1915 ini merupakan salah satu buku timeless, atau tak lekang oleh waktu.
Kalau ada yang bilang yang kubaca ini hanyalah karangan fiksi belaka dan tak mampu menyakiti segores pun, aku berani menyentilnya hingga ke gurun Sahara.
Nyatanya, karya Kafka sangat menyayat hati dan membuatku berpikir kembali tentang value diri sebagai seorang manusia.
Baca Juga: Ketika Gen Z Jadi Bahan Bully Generasi Sepuh
Si Tulang Punggung, Gregor Samsa
The Metamorphosis bercerita tentang seorang pemuda bernama Gregor Samsa yang suatu hari terbangun dengan wujud seekor serangga besar, Dung Beetle (ada juga beberapa versi yang mengatakan sebagai kecoa).
Gregor adalah seorang salesman yang bekerja dengan mengejar target harian. Hidupnya dipenuhi dengan rutinitas yang sangat pelik, ditambah ia harus menanggung hidup para anggota keluarganya.
Ayahnya sudah pensiun dan meninggalkan hutang, sementara adiknya senang bermain musik dan ingin sekali pergi ke sekolah musik.
Banyak tuntutan yang menumpuk di pundak Gregor. Sebagai anak laki-laki pertama, tentu saja ia merasa sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Prioritas utamanya adalah melunasi hutang ayahnya dan menabung agar adik perempuannya yang manis bisa belajar di sekolah musik.
Sejak ayahnya pensiun, Gregor bekerja super giat tanpa istirahat yang cukup. Kehidupannya bahkan diatur oleh jadwal kereta pagi.
Ketika Gregor suatu hari terbangun sebagai seekor serangga, hal pertama yang dikhawatirkannya adalah pekerjaan dan jadwal kereta pagi. Gila, sinting, pikirku.
Orang gila mana yang masih sempat memperdulikan jadwal kereta pagi dan pekerjaannya ketika dirinya tiba-tiba berubah menjadi serangga?!
Meskipun demikian, bentuk kekhawatiran Gregor ini juga membuatku termenung. Mungkin, tanpa sadar, kekhawatiran semacam ini sering kali dialami oleh para generasi sandwich.
Generasi sandwich, generasi roti lapis, atau generasi terhimpit, adalah sekumpulan orang dewasa muda yang memiliki tanggungan akan generasi di atas dan di bawah mereka.
Dalam kasus Gregor, generasi atas adalah orang tuanya dan generasi di bawahnya adalah adiknya. Kesehariannya dipenuhi oleh lelahnya bekerja. Motivasinya hanya demi keluarga dan cita-citanya dikesampingkan.
Gregor adalah karakter fiksi yang terasa begitu nyata. Aku yakin ada banyak di antara generasi sandwich yang cukup relate dengan perasaan Gregor.
Baca Juga: Perempuan dan Hantu Keberdayaan
Beban Moral dan Perasaan yang Diabaikan
Ada banyak sekali hal tersirat di kisah Gregor yang, tentu saja, akan terasa berbeda pada setiap pembacanya. Bagiku personal, perubahan Gregor menjadi seekor serangga merepresentasikan kelelahan yang panjang akibat bekerja tanpa cuti bertahun-tahun.
Dalam wujud serangga, Gregor juga digambarkan mengalami perubahan drastis pada selera makannya. Ia tidak lagi bisa menerima makanan segar dan akan memuntahkannya. Gregor hanya bisa makan makanan sisa.
Selain mengalami perubahan pada tubuhnya, “diri” Gregor juga berubah. Hal inilah yang membawa perjalanan cerita menjadi semakin menarik.
Gregor diperlakukan berbeda dari sebelumnya. Ia merasa keluarganya jijik bahkan hanya untuk melihat dirinya saja. Ia dianggap menjadi aib keluarga. Perubahan ini pula yang membuat Gregor merasa terasingkan, terkucilkan, dan tersingkirkan.
Diam-diam, aku pun ikut bertanya dalam hati. Apa mungkin jika tulang punggung keluarga mengalami hal serupa—perubahan sangat drastis yang membuatnya jadi kurang produktif—keluarga akan tetap memperlakukan dengan sama? Apakah keluarga masih mau menerima diri kita sebagaimana adanya?
Ada beban moral yang Gregor rasakan ketika ia menjadi tidak produktif. Ia merasa bertanggung jawab dengan terhambatnya perekonomian keluarga karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk kembali bekerja.
Pergolakan batin yang dirasakan Gregor sangat bisa dimengerti, terlebih untuk mereka yang menjadi ‘pemain andalan’ dalam keluarga.
Perasaan berkecamuk yang dialami Gregor ini memang sangat membingungkan. Ia diasingkan dan menerima perlakuan tidak manusiawi, namun di sisi lain ada rasa tanggung jawab yang tak kunjung usai.
Gregor, alih-alih menyalahkan keluarganya karena telah menjadi beban—yang mungkin terdengar sangat jahat dan akan menimbulkan rasa bersalah lain di dalam dirinya—, malah menuntut dirinya untuk berusaha lebih keras.
Sebagai anak yang paling diandalkan, ia masih merasa harus bisa membuat keluarganya hidup dengan nyaman. Ia amat menyayangi keluarganya dan merasa harus berhati besar melunasi hutang ayahnya, menyekolahkan adiknya, dan menghidupi keluarganya dengan layak.
Aku yakin, persoalan seperti ini sangat familiar di banyak tempat, apalagi di negara-negara berkembang. Tekanan-tekanan yang membuat generasi sandwich rentan stres dan cenderung mudah kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukainya. Dan tanpa disadari, orang-orang sekitar sering kali mengabaikan perasaan-perasaan lelah mereka.
Baca Juga: Merayakan Hal-hal yang Tak Mudah
Krisis Identitas
Batas akhir perjuangan Gregor Samsa terasa memilukan, penuh tragedi, dan akan meninggalkan bekas yang absurd. Kondisi yang dialaminya serta kesehatannya yang semakin memburuk mengarahkannya pada depresi.
Gregor telah bertahan sejauh yang ia bisa, namun keluarganya tetap tidak bisa menerima dirinya.
“I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.”
Krisis Identitas, dalam prosesnya, pasti akan terasa sulit. Mengenali diri sendiri bukanlah perkara mudah, terlebih membuat orang lain mengerti diri kita.
Begitulah yang dirasakan Gregor. Banyaknya tekanan yang menuntut perkara ini itu membuatnya rongseng. Hanya sedikit waktu yang ia miliki untuk mengenali dirinya.
Pada akhirnya, Gregor kalah dalam pertarungan. Ia mati dalam kesepian dan terasingkan. Aku harap tidak ada lagi Gregor Samsa lain di luar sana.