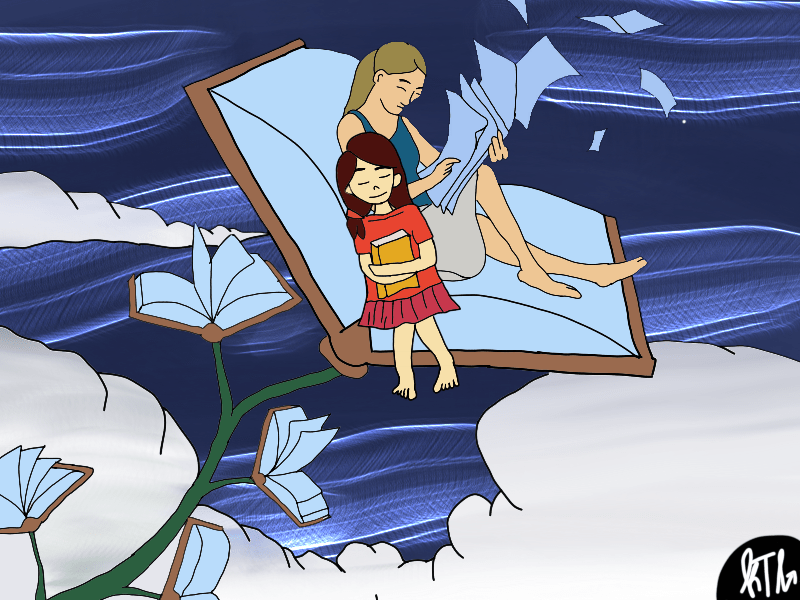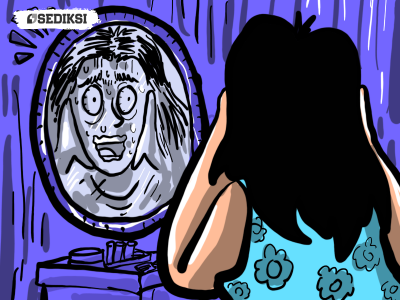“Pernah pada suatu masa, kita para manusia berbicara dalam bahasa yang sama, dalam kata yang semakna. Sampai pada akhirnya ada seorang raja manusia, Namrod, terlampau jumawa membangun sebuah menara yang hendak melampaui kerajaan langit. Tuhan murka. Manusia dikutuk untuk berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda agar saling tidak memahami, berseteru, tercerai-berai, dan saling berperang.”
Begitulah kira-kira cerita dari seorang bapak kepada anaknya sekian ribu tahun lalu, tatkala sang anak bertanya “kenapa para pedagang di pasar berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda?”.
Si anak percaya, pertanda rasa penasarannya terjawab. Gaya bercerita si bapak yang berapi-api berhasil membuatnya begitu saja percaya, bahkan takjub. Tak mau kalah, ia menceritakan ulang kepada teman-teman bermainnya, tetangga-tetangganya, kucing peliharaannya, hingga kekasihnya, dengan berusaha melampaui semangat sang bapak.
Sampai kelak sang anak berkeluarga, semangat berceritanya tak kunjung padam. Ia pun mewariskan kisah, sekaligus semangat bercerita, kepada anak-cucunya sebagai dongeng penjaga moral di malam sebelum mata terlelap. Dari mulut ke mulut, malam ke malam, kesombongan Raja Namrod menjadi abadi sebagai dongeng yang saat ini kita kenal dengan “Menara Babilonia” atau “Tower of Babel”. Sebuah legenda yang terdengar lebih apik saat kembali dikisahkan oleh kitab suci dan khotbah pada banyak agama.
Sebuah dongeng tidak butuh fakta dan data yang valid layaknya berita. Alih-alif faktual, masuk akal saja tak seberapa penting. Seabsudr apapun alur serta latar ceritanya, kemampuan bercerita dan memenuhi rasa penasaran seperti yang diwariskan oleh si bapak kepada anaknya, memang kekuatan ter-magis dari sebuah dongeng.
Dalam cerita Sangkuriang yang menjadi legenda Gunung Tangkuban Perah, misalnya. Terus mengundang pertanyaan yang membuat saya kerap tak habis pikir. Bagaimana bisa gunung berbentuk sampan telungkup itu dikaitkan dengan fetish-fetish aneh semacam perempuan cantik yang menikahi anjing atau anak yang ingin menikahi ibunya sendiri?
Siapapun yang pertama kali menciptakan dongeng tentang Sangkuriang pastilah orang yang kelewat kreatif dan nyeleneh, yang kebetulan punya pengaruh besar ke banyak orang. Sekalipun berangkat dari keisengan semata, setidaknya orang-orang percaya bahwa kisah konyol soal asal-usul gunung berasal dari praktek zoofilia dan incest.
Kisah semacam itu mungkin dipercaya karena sebagai makhluk sosial, sejatinya kita adalah hewan cerdas yang suka bercerita dan suka mendengar kisah-kisah menarik. Semenjak bocah, manusia memandang dunia dengan rasa penasaran terhadap hal-hal yang bagi mereka menarik atau tidak mereka ketahui. Rasa tertarik akan hal-hal yang tidak kita ketahui inilah yang sejatinya mendorong manusia untuk melakukan petualangan, penjelajahan, perenungan, sampai pada eksperimen yang menjadi tonggak pengetahuan dan kemajuan sains.
Bayangkan jika seandainya nenek moyang kita -para pelaut paling awal nan pemberani yang penasaran akan apa yang ada di ujung lautan- merasa takut dan urung membikin rakit sederhana? Bayangkan juga jika nenek moyang kita -yang beberapa di antaranya adalah orang-orang yang hobi begadang sendirian sambil bengong memandangi langit- takut menghitung pergerakan bintang dan lebih percaya bahwa konstelasi bintang hanyalah jelmaan para dewa?
Maka, peradaban akan jalan di tempat. Kita tidak akan mengenal betapa luasnya kosmik -bagaimana ruang dan waktu bekerja- sehingga dengan pongahnya akan terus menganggap bahwa semesta hanya berpusat pada manusia. Sebagaimana dongeng yang terus-menerus dihembuskan soal para dewa, pahlawan, dan kisah-kisah langit lainnya.
Meskipun begitu, pada awalnya dongeng-dongeng yang lahir merupakan upaya manusia untuk menjelaskan segala hal yang tidak kita mengerti. Seiring berjalannya waktu, upaya-upaya itu menjelma menjadi lebih metodis. Ia menjelma ke dalam bentuk jurnal ilmiah, hasil riset, buku, serta debat-debat dalam ruang seminar sains. Walaupun dalam perkembangannya, dongeng, -dalam hal ini karya fiksi- acapkali dianggap lebih rendah ketimbang sains, namun keduanya memiliki motif yang sama: upaya untuk memahami ketidaktahuan kita.
Maka, jika sekiranya kamu adalah lulusan astronomi atau biologi, atau pekerjaanmu berkaitan dengan farmasi atau statistik, tetaplah mendongeng. Jika suatu saat kamu bosan meninabobokan anak atau ponakanmu dengan cerita Cinderella atau Si Kancil dari buku cerita yang sudah buluk, tidak ada salahnya bercerita soal bagaimana para nelayan membaca rasi bintang. Atau ceritakanlah soal betapa menakjubkannya angka sembilan dalam perkalian atau soal bagaimana cerdasnya Eratosthenes mengukur lingkar bumi dengan hanya bermodalkan dua bilah tongkat.
Sebab ketertarikan kita pada dongeng, pada kisah tentang sosok-sosok luar biasa, pada fenomena-fenomena ajaib akan selalu sama. Hanya saja, dengan mengambil bentuk yang berbeda. Hari ini, kita mendengarkan dongeng lewat film-film superhero di layar lebar, yang meskipun tak masuk akal, kita tetap menggemarinya. Kita mengenal cerita soal pemikir-pemikir lampau di ruang-ruang kelas filasafat. Kita juga dibisikkan kisah-kisah ajaib tentang tetangga-tetangga kita sendiri -yang katanya punya ilmu kebal atau selingkuhannya belasan- di sela hingar-bingarnya warung kopi. Nyatanya kita menikmatinya.
Alasannya sederhana. Karena evolusi telah menjadikan kita untuk menikmati dan menyenangi proses mengumpulkan dan memahami infromasi. Menurut Carl Sagan, mereka yang memahami memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Akibatnya anak-anak manusia yang lahir memiliki kesukaan yang tinggi terhadap proses belajar dan mencari tahu. Seperti bayi kuda yang bisa langsung berlari beberapa menit setelah dilahirkan atau bayi penyu yang secara instingtif berlomba ke arah pantai, manusia diberi anugerah untuk belajar. Nahasnya, sering kali kita menghentikan proses belajar dan memahami itu saat dewasa, saat kita merasa cukup tahu dan risikonya kita menjadi makhluk yang bebal dan menyebalkan.
Pada akhirnya, kegemaran kita akan dongeng adalah tesis awal sebagai manusia untuk belajar dalam menundukkan rasa angkuh -sebagaimana raja Namrod yang kepongahannya diperingatkan oleh Tuhan melalui bahasa. Saya pikir ketika Namrod membangun menara untuk mencoba melampaui langit, ia tidak salah. Sebab itu adalah naluri manusia untuk mengetahui dan menyingkap apa yang ada di balik langit, tirai yang selama ini membatasi hal-hal yang tidak mampu kita jangkau. Akhir kata, selamat Hari Dongeng Sedunia, bagi yang merayakan.