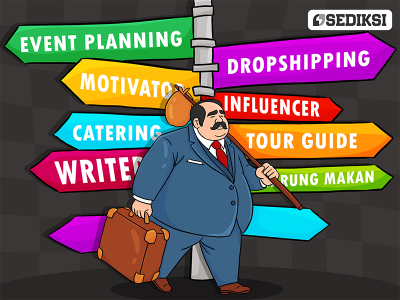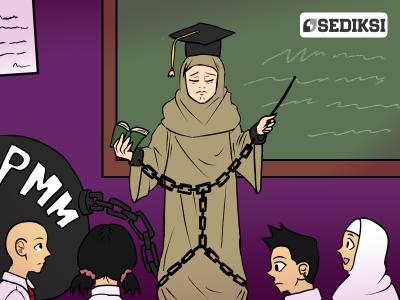Bumi dan langit adalah sepasang kekasih. Tidak jelas kapan menikahnya, sepasang ini telah melahirkan banyak anak. Anaknya tidak hanya manusia, tapi juga binatang dan tumbuhan. Sungguh luar biasa pasangan ini. Membuat pasangan seperti Romeo dan Juliet, hanya tampak bagaikan kerupuk yang mengkerut di dalam kuah Soto Lamongan.
Di antara mereka terbentang jarak yang jauh, ribuan kilometer, menurut para ahli. Tapi mereka tidak LDR, karena memang begitulah adanya. Mereka tidak mengenal jarak, karena jarak itu sendiri milik mereka. Mereka bersentuhan setiap saat melalui petir, angin, atau hujan. Tergantung mood. Mereka terus membina asmara. Dan layaknya pasangan kekasih, mereka menghadirkan banyak kisah.
Ada kisah-kisah tentang pertengkaran disertai amarah, yang terwujud dalam petir atau hujan badai. Ada kisah tentang kasih dalam gerimis yang syahdu. Kadang ada juga canda dalam sepoi angin yang menyejukkan. Dan kisah asmara ini telah hidup jauh sebelum ada manusia yang bisa bercerita atau dinosaurus yang bisa mengaum.
Di antara bumi dan langit, muncullah kita-kita, makhluk-makhluk ingusan kemarin sore yang diyakini sebagai manusia. Yups, konon bumi adalah ibu dari segala ibu. Langit adalah bapak dari segala bapak. Menurut kitab-kitab suci yang jarang saya baca, manusia tercipta dari tanah atau abu, yang secara kimiawi adalah unsur-unsur yang terkandung dalam bumi. Sedangkan sepanjang hidupnya, manusia menghirup udara yang merupakan salah satu lapisan langit.
Sedari awal, manusia berada dalam perawatan bumi dan langit. Keduanya mengajarkan banyak hal pada manusia. Awalnya tidak bisa bicara, kemudian menciptakan nada-nada untuk berkomunikasi menirukan suara-suara alam yang dikenal dengan bahasa. Awalnya tidak mampu mencatat, hingga menemukan sandi bernama huruf. Awalnya hanya mampu berburu binatang hingga dapat menanam sendiri kebutuhannya.
Demikianlah manusia menciptakan kebudayaan sebagaimana bentang alamnya, sebagaimana bumi dan langit mengajarkannya. Sebagai bagian dari upaya balas budi terhadap langit dan bumi, manusia merumuskan serangkaian kode luar biasa rumit melebihi algoritma dengan perhitungan cermat yang disusun dari generasi ke generasi. Kodenya berbunyi, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.
Kode tersebut bukan sembarang kode. Diyakini dengan mengucapkannya, manusia-manusia yang takabur dan lupa daratan dapat kembali membumi dan percaya bahwa di atas langit masih ada langit. Namun tidak bagi buaya darat atau lintah darat yang memang habitatnya ada di bumi dan tidak mungkin melangit.
Tapi celaka bagi orang-orang yang gengsinya selangit. Susah bagi mereka untuk kembali membumi dengan kode ini. Mereka hanya tahu barang-barang yang mahalnya selangit. Karena kode ini muncul di zaman pra-gadget yang tidak memungkinkan orang adu gengsi pake duit.
Nah, itulah masalahnya. Sekarang adalah eranya gengsi selangit, di mana orang-orang menggantungkan kaki di udara. Tidak mau menginjak bumi, takut kotor. Lalu dimana kepalanya kalau kaki di udara? Entahlah, mungkin di dengkul…
Bagaimana tidak, di mana-mana jakartanisasi, malu akan asal-usulnya. Gaya bahasa, kebiasaan, dan segala yang berbau Jakarta dianggap sebagai wujud modern. Jakarta dianggap lebih maju, lebih baik, dan lebih segalanya dari daerah. Sedangkan segala sesuatu yang mengandung unsur lokalitas dianggap udik, kampungan, tertinggal, atau terbelakang. Jakarta adalah yang utama, daerah figurannya. Demikianlah yang barangkali ada di benak anak gaul kekinian, para cabe dan terong berikut senior-seniornya.
Generasi gadget, cabe, dan terong tidak lagi percaya ajaran-ajaran bapak-ibunya. Bahkan bapak-ibunya juga mulai lupa ajaran moyangnya. Sedangkan moyangnya sering sulit membedakan mana ajaran leluhur, mana ajaran kumpeni. Mereka melupakan asalnya sebagaimana langit dan bumi pernah mengajarkannya. Jadilah mereka manusia-manusia lupa daratan dan kehilangan arah. Karena ingatannya hanya sebatas apa yang dikatakan televisi.
Anak presiden pelopor ‘revolusi mental’ pun juga tak kalah lupa daratannya. Dia mambuat gerai Martabak Kota Barat di Kota Solo yang masyarakatnya menyebut ‘martabak manis’ sebagai terang bulan. Jadi, kalau orang setempat memesan martabak, di situ mereka akan bertanya, “loh, mana martabaknya?” Alih-alih martabak, yang mereka dapat adalah terang bulan. Merasa dirugikan dan ditipu mentah-mentah, si pembeli bisa menuntut penjual dengan pasal penipuan UU ITE karena iklannya ada di sosmed. Dan berhubung yang jual adalah anak presiden, penjual bisa menuntut balik dengan penistaan simbol negara. Waduh, dowo critane…
Tapi begitulah. Di Indonesia martabak manis dan terang bulan adalah makanan yang sama. Bedanya, martabak manis adalah penyebutan untuk di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Sedangkan wilayah lain Indonesia menyebutkan dengan istilah terang bulan. Si anak presiden lupa daratan, lupa di mana dia berada. Yang penting terang bulan (atau martabak menurutnya) dagangannya bisa kelihatan gaul. Karena gaul itu menjual bung. Nama terang bulan kan gak gaul, terlalu udik, bernuansa kampung.
Yah, barangkali memang masyarakat Solo yang juga turut takabur dengan maraknya mall dan hotel di sana. Jadi mereka ikut-ikutan menyebut terang bulan sebagai martabak. Soalnya, ada semacam aturan tidak tertulis di mall-mall itu. Pengunjungnya harus gaul. Harus bertutur kata sesuai adat istiadat pusat perbelanjaan. Tidak boleh terlihat kampungan, di mall manapun anda berada. Karena sebenarnya, mall adalah markas besar kelompok persaudaraan cabe dan terong. Anda tidak akan diusiir jika kelihatan kampungan, hanya seisi mall akan memandang anda dengan tatapan aneh yang pada akhirnya mendorong anda untuk angkat kaki dari sana.
Ya jadi mungkin wajar, di Solo yang makin banyak mall itu, tuntutan untuk mentransformasi diri menjadi lebih besar. Seperti memaksa dirinya yang biasa mengucap “ndlogog” menjadi “anjing”.
Dan seperti nasib terang bulan, makian lokal sudah mulai tergusur dengan yang gaul dan kadang kebarat-baratan. Makian gaul apalagi meniru hollywood yang dipaksakan tidak dapat melegakan hati sebagaimana makian lokal.