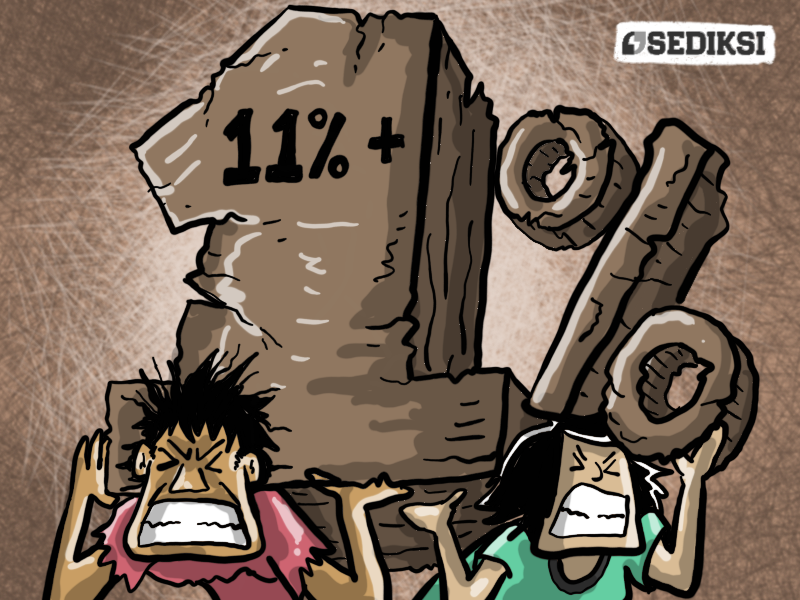Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kemungkinan akan tetap naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Beberapa pernyataan pemerintah kepada publik belakangan semakin memperkuat sinyal ini.
Kenaikan ini sendiri memang sudah tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 tetang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, di tengah kondisi ekonomi saat ini, apakah menjadi ke-bijak-an yang tepat untuk tetap menaikkan tarif PPN?
Seperti yang diketahui, daya beli masyarakat tengah menurun, ditandai dengan deflasi beruntun sejak Mei 2024 hingga September 2024 yang dominan dipengaruhi demand side.
Berdasarkan S&P Global, PMI Manufaktur yang mencerminkan aktivitas industri terus mengalami kontraksi selama empat bulan beruntun. Belum lagi, banyak terjadi PHK selama tahun 2024 ini.
Saya paham betul bahwa kapasitas fiskal pemerintah sedang berada dalam kondisi yang sulit, yang salah satu faktor utamanya adalah pandemi Covid-19.
RAPBN 2025 mencatatkan keseimbangan primer negatif di saat utang jatuh tempo mencapai rekor tertinggi hingga Rp800 triliun.
Belum lagi, dalam kondisi kapasitas fiskal yang sempit, terdapat pemerintahan baru yang tentunya telah merencanakan berbagai program yang membutuhkan biaya tak sedikit. Misalnya, program makan bergizi gratis yang tahun depan direncanakan akan mendapat alokasi Rp71 triliun.
Tak ayal, pemerintah harus mencari skema untuk memperluas kapasitas fiskal dengan meningkatkan penerimaan pajak. Apalagi, menurut pernyataan Sri Mulyani, tax ratio Indonesia masih tercatat rendah, berada di level 10,02% dari PDB.
Baca Juga: (Nyaris) Tiada Harapan Dari Merah Putih
Lebih Besar dari Kelihatannya
Kita perlu memahami bahwa kenaikan tarif dari 11% ke 12% implikasinya tidak sereduktif “hanya naik 1%”. Kita perlu mengulas lebih jauh seberapa besar efek multipliernya.
PPN sendiri sederhananya adalah pajak konsumsi—pajak yang dibebankan kepada konsumen atau pembeli pada setiap pembelian barang/jasa tertentu.
Akan tetapi, tidak semua barang/jasa dikenai PPN. Terdapat juga daftar barang/jasa yang mendapat pengecualian dari PPN.
PPN sendiri dikenakan pada setiap transaksi jual/beli pada level apapun apabila penjualnya merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Misalnya, ketika suatu barang dijual dari produsen ke distributor, PPN sudah dikenakan apabila produsen merupakan PKP.
Kemudian ketika distributor menjual kepada retailer, dikenakan PPN lagi apabila distributor merupakan PKP. PPN akan terus dikenakan hingga ke konsumen akhir. Namun, pada dasarnya, yang menanggung semua beban PPN ini adalah konsumen akhir.
Oleh karena itu, PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena konsumen lah yang secara tidak langsung menanggung semua PPN yang terjadi dalam rantai tersebut.
Ilustrasi berikut mungkin akan memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hal ini.
Produsen menjual ke distributor:
- Harga pokok produksi=Rp10.000
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 10%=Rp11.000
- PPN 11%=Rp1.210
- Harga jual setelah PPN= Rp12.210
- PPN sebesar Rp1.210 yang dipungut produsen ini harus disetor ke negara.
Distributor kemudian menjual ke retailer:
- Harga beli= Rp12.210
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 10%= Rp13.431
- PPN 11%= Rp1.477
- Harga jual setelah PPN= Rp14.908
- PPN yang dipungut distributor perlu disetor ke negara, tetapi karena sebelumnya distributor telah membayar PPN sebesar Rp1.210 ke produsen, distributor hanya perlu menyetor selisihnya yaitu Rp1.477 dikurangi dengan Rp1.210.
Retailer kemudian menjual ke konsumen akhir:
- Harga beli= Rp14.908
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 10%= Rp16.399
- PPN 11%= Rp1.803
- Harga jual setelah PPN= Rp18.201
- PPN yang disetor adalah selisih antara yang dipungut sebesar Rp1.803 dengan yang telah dibayar ke distributor sebesar Rp1.477
Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa pada akhirnya seluruh PPN ditanggung oleh konsumen akhir. Distributor dan retailer memang membayar PPN pada saat membeli barang. Tetapi, PPN tersebut pada akhirnya dapat dikreditkan dan hanya perlu menyetor selisihnya dari PPN yang dipungut saat menjual.
Rantai tersebut sangat perlu dipahami untuk nantinya dapat menaksir dampak dari kenaikan PPN. Apalagi, sebagai konsumen akhir, jarang sekali kita membeli barang langsung ke produsen kan? Kita beli sabun, misalnya, pasti ke toko atau supermarket, tidak langsung ke pabriknya.
Jadi, sangat penting untuk memahami skema ini agar dapat melihat bahwa kenaikan tarif dari 11% menjadi 12% tidak sesederhana harga barang hanya naik 1%.
Mari kita simulasikan ilustrasi di atas kembali tetapi dengan PPN 12%.
Produsen menjual ke distributor:
- Harga pokok produksi=Rp10.000
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 10%=Rp11.000
- PPN 12%=Rp1.320
- Harga jual setelah PPN= Rp12.320
Distributor kemudian menjual ke retailer:
- Harga beli= Rp12.320
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 10%= Rp13.522
- PPN 12%= Rp1.626
- Harga jual setelah PPN= Rp15.178
Retailer kemudian menjual ke konsumen akhir:
- Harga beli= Rp15.178
- Harga jual sebelum PPN dengan profit margin 20%= Rp16.695
- PPN 11%= Rp2.003
- Harga jual setelah PPN= Rp18.698
Kita bisa bandingkan, harga jual ke konsumen akhir dengan PPN 11% adalah Rp18.201, sementara dengan PPN 12% menjadi Rp18.698. Terjadi kenaikan harga sebesar Rp497 atau sekitar 2,73%!
Di situ, presentase kenaikan harga melebihi 1%, dan apabila menengok presentase kenaikan PPN, tentu lebih besar. Konsumen akhir dengan tarif 11% membayar PPN sebesar Rp1.803, kemudian dengan tarif 12% menjadi Rp2.003. Artinya, terdapat kenaikan sebesar 11,09% sendiri.
Simulasi di atas bahkan masih menggunakan asumsi yang sangat sederhana. Belum memasukkan penyesuaian margin, belum menambahkan perubahan harga pokok produksi, belum lagi bila rantai dari produsen ke konsumen akhir semakin panjang, dan sebagainya.
Sebagai contoh, Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Ardiman Pribadi, mengatakan bahwa ketika PPN dikenakan 11%, pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir sebenarnya mencapai 19,8%. Sementara, bila dinaikkan menjadi 12%, beban konsumen akhir akan menjadi 21,6%.
Beban yang begitu besar melebihi tarif PPN sebagaimana dimaksud Ardiman dapat dipahami sebagai compounding effect yang terjadi dalam rantai distribusi seperti yang diilustrasikan di atas.
Kenaikan PPN akan terakumulasi secara bertingkat hingga ke harga konsumen akhir. Belum lagi, dalam industri tekstil, rantai ini bisa sangat kompleks. Bahkan, dalam rantai distribusi bahan baku produksinya sendiri bisa jadi sudah melalui beberapa level. Jika sudah demikian, bahan baku produksi tentunya akan mengalami peningkatan.
Solusi Problematik
Dari pemaparan di atas, bisa dilihat bahwa dampak kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% jauh lebih besar dari “hanya 1%”. Kita bisa bayangkan bagaimana daya beli masyarakat akan terdampak.
Memang, ada barang/jasa yang dikecualikan dari PPN seperti beras, gula pasir, garam, dan daging. Namun, siapa masyarakat yang tidak membeli sabun, tisu, pakaian, ataupun alat tulis?
Selain itu, masih banyak barang/jasa lainnya yang dikenai PPN yang masuk ke dalam keranjang konsumsi masyarakat pada kelas manapun.
Sehingga, kita juga tidak bisa abai bahwa kenaikan PPN dapat berdampak secara tidak langsung pada kenaikan harga barang-barang yang dikecualikan dari PPN.
Ongkos produksi beras pasti akan mengalami kenaikan sehingga harga beras akan ikut naik. Misalnya, biaya transportasi untuk distribusi logistik pasti akan naik karena termasuk objek PPN.
Pupuk, pestisida, dan alat pertanian juga dikenakan PPN. Belum lagi, dengan naiknya biaya hidup, pedagang beras tentu terdorong untuk menaikkan harga guna memenuhi kebutuhan.
Selain konsumen, pengusaha juga akan terdampak. Dengan naiknya harga barang dan turunnya daya beli masyarakat, pendapatan dapat menurun. Maka tak mengherankan jika banyak pengusaha yang juga melayangkan protes terhadap kenaikan ini.
Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana untuk mendatangi Kemenkeu guna meminta penundaan kenaikan. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) bahkan tak hanya meminta untuk ditunda, melainkan juga dibatalkan.
Sejauh ini, kita harusnya sudah bisa melihat bahwa menaikkan tarif PPN tidak berpihak kepada masyarakat banyak, terutama kelas menengah ke bawah. PPN merupakan proportional tax, yang mana dikenakan kepada semua masyarakat pada tarif yang sama.
Beda halnya dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat progresif. Sederhananya, hanya kelompok yang mendapatkan penghasilan di atas jumlah tertentu yang membayar PPh, sementara seorang pengangguran pun harus ikut membayar PPN.
Inilah mengapa tak sedikit ekonom yang menganggap bahwa PPN merupakan regressive tax karena membebani kelompok masyarakat miskin lebih banyak daripada yang kaya.
Toh, penggunaan pajak sendiri masih belum mencerminkan redistribusi yang adil. Contoh sederhana, kenaikan PPN ini tak dapat dipungkiri merupakan bagian dari skema agar program makan bergizi gratis dapat dieksekusi.
Pertanyaannya, semua orang membayar PPN, tapi apakah semua merasakan manfaat dari makan bergizi gratis? Bagaimana dengan orang-orang miskin yang menanggung beban ini, sementara anaknya dalam kondisi putus sekolah sehingga tidak ikut merasakan program ini?
Alih-alih menaikkan PPN, banyak solusi lain yang sebenarnya dapat dilakukan pemerintah. Banyak ekonom memprediksi kenaikan tarif PPN akan meningkatkan penerimaan negara sekitar Rp75 triliun.
Namun, apabila negara berpihak kepada rakyat dan tidak tunduk pada oligarki, mengapa tidak kenakan pajak kekayaan saja? Berdasarkan penghitungan CELIOS (2024), pengenaan pajak kekayaan sebesar 2% terhadap 50 orang terkaya di Indonesia saja sudah memiliki potensi penerimaan hingga Rp81 triliun.
Atau benahi saja sistem perpajakan sehingga mengurangi jumlah pengemplang pajak, terutama dari kalangan atas. Buat kebijakan yang meminimalisir penghindaran pajak dengan skema transfer pricing, misalnya.
Aneh rasanya, pajak yang harusnya menjadi alat bagi negara untuk redistribusi pendapatan dan mengupayakan keadilan dari sistem kapitalisme, justru lebih membebani para proletar. Sementara untuk orang-orang kaya, pajak diampuni, diberi amnesti, diberikan tax holiday, dan sebagainya.
Memang benar, keadilan sosial bagi mereka yang bergelimang harta.
Sila kelima tidak berlaku bagi penghuni dasar piramida.
Baca Juga: Indonesia 2045: Kuning Belum Tentu Emas