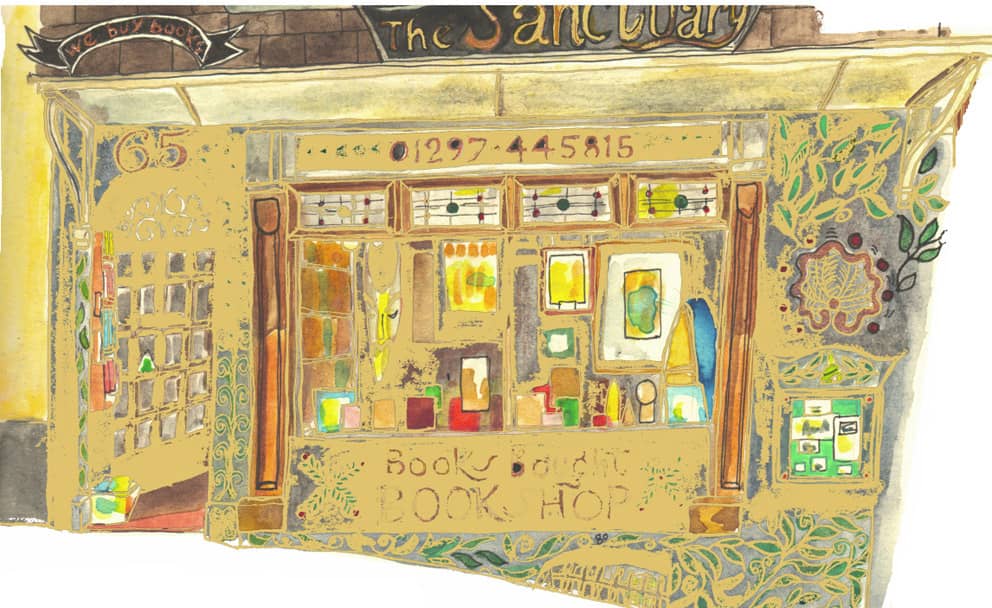“Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi” Tan Malaka, Madilog.
Toko buku bagi Tan Malaka adalah hal yang utama. Toko buku adalah penyuplai ilmu pengetahuan sekaligus penjaga peradaban masyarakat agar tetap waras. Dalam masa pelarian politiknya, mengunjungi toko buku merupakan hal yang wajib bagi seorang Tan. Bahkan ia rela menghabiskan gajinya yang tidak seberapa hanya untuk membeli buku. Saya sudah bisa membayangkan betapa kurus dan tidak fashionable-nya seorang Tan Malaka.
Datuk Tan adalah orang yang gila buku. Ia tahu bukunya pasti akan disita oleh aparat setempat atau terpaksa ditinggalkan agar tidak menghambat mobilitasnya selama masa pelariannya dari satu negara ke negara lain. Tapi itu tidak menyurutkan semangatnya menjadi individu yang intelek. Ia selalu berburu buku dan membentuk pustakanya kembali di setiap negara yang ia kunjungi.
Dalam masa pelariannya, tak hanya sambil berburu dan membentuk pustaka. Ia juga membuat sebuah kitab babon pertama yang ditujukan kepada manusia Indonesia agar bisa berpikir logis yang diberi judul, Materialisme Dialektika Logika: Madilog. Tan membuat buku Madilog dengan cita-cita membebaskan rakyat yang pada masa itu masih terbelenggu dengan budaya logika mistika.
Logika yang mengkultuskan hal-hal takhayul dan berbau gaib. Budaya yang menurut Tan menjadi sebab ketrtinggalannya sebuah bangsa. Bagi Tan kemerdekaan tak akan dapat diraih jika kemerdekaan berpikir belum dicapai.
Baca Juga: 5 Aplikasi Membuat Cover Buku yang Populer
***
Hampir 70 tahun semenjak kematian Tan Malaka, logika mistika yang begitu dibenci Tan Malaka tak sepenuhnya hilang. Logika itu juga ikut berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kini logika itu berbungkus dengan macam-macam jubah dan yang paling umum sekarang memakai jubah agama. Laku boleh saja alim tapi pemikiran sesungguhnya masih primitif.
Lestarinya logika mistika juga tak bisa dilepaskan andil dari toko buku. Lihat saja display jaringan Toko buku terbesar di negara ini, tak perlulah disebutkan nama tokonya Gramedia. Insya Allah kita akan mudah menemui buku-buku populer bercap “best seller” yang indikatornya entah didapat dari mana terpampang jelas dan bisa bertahan berbulan-bulan.
Apapun tren bukunya, buku jenis ini pasti akan selalu ada terpampang di display utama “toko buku terbesar” itu dan merupakan buku-buku paling laris. Misalnya buku-buku motivasi memperkaya diri, sedekah mendatangkan rezeki, kiat sukses jadi PNS, psikotes masuk BUMN, Cara agar dapat disenangi bos atau agar suami tidak selingkuh.
Judulnya mungkin beda, tapi garis besarnya pasti tak jauh-jauh amat dari tema how to do something. Buku-buku tadi lebih mirip manual book untuk mengoperasikan sebuah manusia tanpa otak untuk mengerjakan sesuatu, ditambah dengan sedikit bumbu agama.
Seakan jika tak mengikuti satu poin dari buku itu kita gagal menjadi manusia. Buku sampah yang membuat orang menjadi seragam dan malas berpikir.
Parahnya masyarakat kita seakan dibuat tak punya pilihan toko buku, walaupun sebenarnya ada tapi pilihannya sangat sedikit. Pasalnya ”toko buku terbesar itu” mempunyai jaringan toko di mana-mana, dan mempunyai beberapa lini penerbitan, dan juga mbak-mbak pelayan toko yang gak kalah cakep dengan mbak kasir Indomaret.
Penerbit-penerbit buku indie pun tak bisa seratus persen merdeka dari cengkraman monopoli toko buku itu. Harus diakui, mereka terorganisasi lebih baik dan punya jaringan toko buku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, hal yang tak bisa dilakukan oleh penerbit-penerbit buku indie.
Namun di balik segala kuasa dan daya yang dimiliki oleh ”toko buku terbesar itu”, toko buku ini juga menyimpan kelucuan. Toko buku ini terlalu takut dengan ormas yang sedang magang jadi Tuhan. Buku-buku tertentu dilarang masuk ”toko buku terbesar itu” hanya karena buku itu ditulis oleh seorang yang tak bertuhan atau sampul bukunya bergambar palu arit.
Tak ada guna juga bayar security dan punya tim legal perusahaan kalau melindungi buku jualannya aja gak bisa. Ironis memang. Pemberangusan buku-buku bermutu justru dimulai dari toko buku itu sendiri dan ”toko buku terbesar itu” melanggengkan budaya logika mistika yang sangat-sangat ditentang Tan Malaka.
Hal itulah yang membuat saya malas membeli di jaringan “toko buku besar” itu. Harga-harganya terlalu mahal. Baru baca judul-judul buku koleksinya dan lihat sampulnya saja sudah pengen garuk mata.
Saya lebih memilih untuk berbelanja buku di kios-kios buku alternatif atau toko buku online. Judul-judul bukunya lebih beragam, harga lebih murah, masih bisa nawar lagi, dan penjual bukunya bisa diajak diskusi.
Seharusnya toko buku bisa menjadi filter pertama bagi pembaca untuk mendapatkan buku bermutu. Penjual buku sudah selayaknya mengerti apa yang dijualnya. Menjadi penjual buku lebih dari sekadar menjual beli kertas.
Penjual buku juga adalah bagian dari kerja kebudayaan, kerja literasi . sama seperti penulis, penerjemah, penyunting, dan penerbit buku. Penjual buku juga harus membaca dan jeli melihat buku-buku yang baru terbit, apakah layak dipasarkan atau tidak.
***
Pada tahun 1942, Tan kembali ke Jakarta dari pengasingannya selama 20 tahun. Demi keperluan penulisan buku Madilognya, Tan Malaka mengunjungi toko-toko buku di Jakarta. Namun ia kaget tak satu pun ia mendapati toko-toko buku di Jakarta yang menjual buku-buku tentang logika berpikir.
Keadaan yang tak jauh berbeda dengan era sekarang. Seandainya Datuk Tan Malaka hidup lagi di era millenial dan melihat keadaan toko buku yang sekarang mungkin ia kecewa sambil mengelus-ngelus dada Awkarin.
Mungkin saja Datuk Tan Malaka akan membuat lagi buku Madilog yang direvisi biar lebih kekinian, ketika tahu masih ada doktor lulusan luar negeri yang masih percaya dengan pria yang bisa menggandakan uang tanpa keringat dan air mata.
Semakin utopis saja cita-citamu, Datuk!