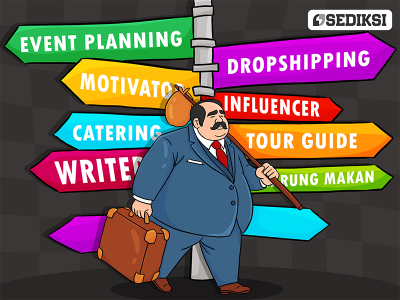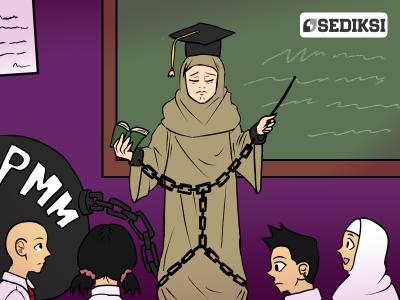Sudah sebulan lebih pasca email keramat mendarat di kotak surat bahwa saya dinyatakan tidak lulus tes beasiswa LPDP, beasiswa Kementrian Keuangan yang sedang ngehits di kalangan fresh graduate itu. Sementara itu, kondisi saya masih cukup memprihatinkan: luntang luntung pengangguran nggak jelas. Kemudian muncul celetukan dari ibu di suatu malam ketika saya masih senden-senden ria di sofa manja depan televisi, “Ini lho, di WA nya ibuk ada pengumuman tes CPNS, ikut gih, sopo eruh nasib…..”
Ibu yang dahulu tidak suka keypad HP querti, sekarang jarinya terlihat sangat fasih sekali menari di atas touch screen gejetnya. Sepintas saya lirik broadcast-an yang sudah saya tahu dari grup WA sejagat raya, kemudian saya melengos kembali menyimak acara Sule di Net TV dengan hilang mood tertawa ngakak yang biasa berkumandang di ruang tengah. Kemudian saya menerawang, bulan Oktober tahun ini adalah jatuh tempo setahun gelar sarjana yang bertengger menganggur tanpa pencapaian finansial yang kongkrit, bagi saya ini semacam sign war jika tidak mau terus-terusan dipecundangi oleh keadaan.
Terkadang mendamaikan idealisme dengan realita yang ada tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi saya sadar penuh, bahwa saya bukanlah si jenius Nietzsche yang dapat mengubah tragedi menjadi komedi, saya adalah anak perempuan biasa yang hidup di tengah arus peradaban modern dengan kiblat kesempurnaan mbak Dian Sastro dalam berbagai hal: seperti karir, asmara dan mamah muda. Tapi toh kisah hidup mbak Dian yang terlampau populer sebagai berhala bagi kaum penghayal bukanlah suatu pencerahan untuk menjawab masalah saya: krisis multidimensi pasca mahasiswa yang penuh dengan beragam sindiran.
Memang benar, sebagian besar gelora idealisme anak muda melalui proses semasa pergerakan mahasiswa tidak serta merta membuat saya memasukkan lamaran ke beberapa lowongan website jobstreet. Ada semacam dilema: antara mengabdi pada corong kapitalis—yang dulu sering kali diramalkan sebagai akhir idealisme para kawula—dengan suatu kondisi realistis sebagai anak muda yang sudah mentas sekolah di perguruan tinggi, tapi beli deodoran saja masih minta duit orang tua.
Iya, persoalan kerja-mengerjai ini tidak lebih dari masalah gengsi. Lebih jauh lagi, sebenarnya ini bukan hanya tentang komisi yang didapatkan dari pekerjaan itu sendiri, mendapatkan pekerjaan mungkin akan lebih dekat dengan persoalan pencapaian dan harga diri, dimana pekerjaan diletakkan sebagai simbol status sosial yang menunjukkan derajat hidup seseorang. Hingga akhirnya kemenangan berada di pihak yang pasti, definisi bekerja itu sendiri menyempit menjadi suatu profesi yang identik dengan ritme teratur seperti ngantor dan punya posisi serta job deskripsi yang jelas. Padahal kan ngantor nggak harus di kantor.
Saya kemudian makin ciut tatkala mendengar teman-teman seangkatan sudah pada mapan jadi staf HRD dengan gaji lebih dari UMR. Seolah-olah saya sia-sia belaka menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) sekaligus aktivis pers mahasiswa yang ternyata tidak dibarengi dengan konsekuensi praktis mendapatkan pekerjaan selepas gelar wisuda. Lalu bagaimana nasib anak gadis ibu ini yang masak saja jarang, mencuci baju pun enggan (soalnya ada mesin cuci, hehe)? Tentu saja kemudian saya merenung panjang, berulang kali setelah shalat saya dengung-dengungkan doa: minta dipertemukan dengan keberuntungan dan minta diarahkan agar saya tahu harus berbuat apa. Atau paling tidak ada naskah saya yang dimuat di suatu tempat, hanya sebagai pengingat bahwa saya masih bisa berpikir dan menulis.
Tidak dipungkiri kondisi yang sedemikian sangatlah berpotensi membuat diri semakin tertekan, mengingat belum ada kabar berbalas dari timbunan email lamaran pekerjaan yang setiap detik dinanti-nantikan. Belum lagi ada suara-suara yang bikin lemas telinga dan perasaan, semisal: obrolan membanding-bandingkan dengan anak tetangga yang sudah mulai mencicil rumah, nasehat untuk tidak berpacaran dengan pujangga, saran untuk menikah dengan pengusaha, coba masukan lamaran ke perusahaan ini, coba tes pegawai kantor itu dan ba bi bu lainnya.
Annoying itu pasti, apalagi sebagai anak muda yang selalu menghayati kegagalan sebagai suatu falsafah hidup menuju makrifat hipster keren, hal tersebut jadi semacam penolakan terhadap pendapat umum biar dikata berbeda dari yang lain. Begitulah kemudian saya yang berapi-api mendebat ibu soal tes CPNS atas nama passion dan teori hierarki aktualisasi diri Abraham Maslow yang berima-rima itu, pun akhirnya sangsi sendiri. Percakapan kami berakhir dengan ucapan ibu santai “Ibu kan cuman menasehati, tinggal bilang iya saja apa susahnya sih. Ingat, anak genduk itu nanti akan jadi istri dan mengurus generasi…”
Kemudian hening dan hanya terdengar suara iklan dari televisi, tak berapa lama kemudian seorang kawan memposting tautan situs Tempo.co di salah satu grup WA: Beredar Rencana Seleksi CPNS 2016, Pemerintah: Tidak Benar.
Ternyata hoax, saya kembali leyeh-leyeh rileks lalu ganti channel ke Tukang Bubur Naik Haji.