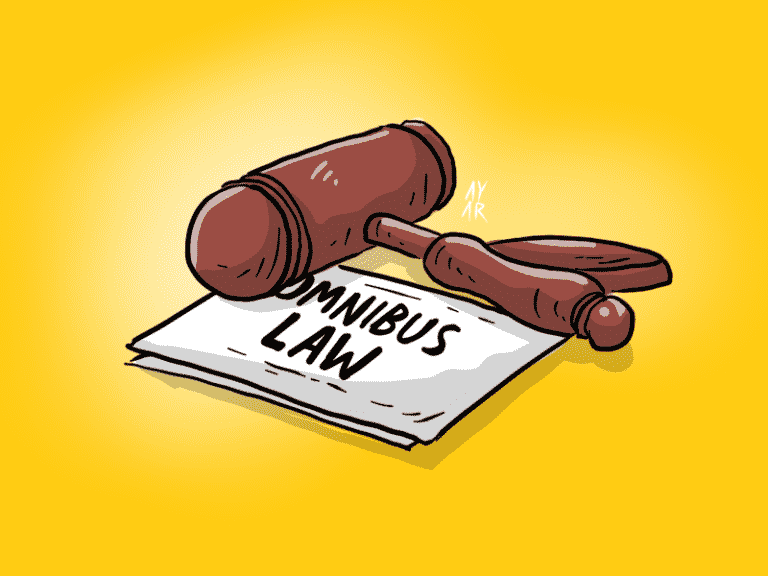Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI terus menimbulkan tanda tanya: Kenapa produk legislasi Omnibus Law ini mirip sinetron kejar tayang di televisi-televisi nasional? Ngebut. Sat-set wat-wet.
Tambah lagi ada banyak kejanggalan dari Undang-Undang (UU) Sapu Jagat ini diperbincangkan: mikrofon mati hingga banyak anggota dewan tidak menghadiri sidang paripurna pengesahan UU tersebut. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat banyak orang menaruh curiga kendati yang membela juga tidak sedikit jumlahnya. Itu bukan soal. Perbedaan pendapat adalah hal lumrah dan perlu dihargai dalam proses demokrasi.
Satu hal yang bikin banyak orang meradang adalah pembelaan merendahkan pada mereka yang memutuskan turun ke jalan: sudah baca draft-nya?
Baca Juga: K-POP dan Penolakan Terhadap UU Cipta Kerja
Narasi ini tidak hanya merendahkan, namun juga berpeluang terus-menerus direproduksi untuk melemahkan perjuangan orang-orang. Seolah mereka yang turun ke jalan tanpa membaca keseluruhan Omnibus Law sekadar ikut-ikutan atau tak tahu duduk persoalan.
Padahal, wajar belaka jika orang membaca apa yang mereka butuhkan saja. Orang-orang dengan perhatian khusus pada isu lingkungan, akan memperhatikan dengan cermat isi undang-undang yang bersinggungan dengan perhatian mereka.
Begitu pula dengan mereka yang memperhatikan persoalan ketenagakerjaan. Membaca ratusan halaman mungkin akan melelahkan dan orang-orang akan cenderung memilih bagian yang sesuai dengan kepentingannya.
Lagipula, memangnya orang-orang yang hobi melempar argumen tersebut, apa juga sudah benar-benar membaca draftnya? Atau, apa yakin para anggota dewan yang mengesahkan UU Cipta Kerja itu sudah khatam membaca draft RUU, maupun naskah akademiknya?
Omnibus Law, bagaimana pun, perlu didudukkan sesuai namanya. Ia merupakan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek dalam satu undang-undang induk. Membaca seluruh draft-nya agak mustahil ketika kita mengetahui bahwa draft yang telah disahkan bahkan bukan merupakan naskah akhir. Mengharuskan orang membaca keseluruhan draft Omnibus Law ini membuat persoalan membaca jadi rumit sekali.
Aksi massa menolak Omnibus Law, toh, bisa dibaca sebagai kumpulan masyarakat yang merasa akan dirugikan dari undang-undang ini. Mereka merupakan kumpulan orang-orang yang sama-sama gelisah nasibnya dipertaruhkan dan memiliki narasi bersama untuk memberi reaksi atas sesuatu yang akan memengaruhi kehidupan mereka.
Baca Juga: Pengen Jadi Warga Negara Swiss? Netizen Sebaiknya Pikir Ulang
Upaya mendistorsi perjuangan rakyat dengan narasi merendahkan pada situasi politik semacam ini, mirip dengan penggunaan istilah-istilah yang kerap muncul ketika terjadi kerusuhan: oknum, aktor intelektual, hingga ditunggangi.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan akan menindak secara hukum mereka-mereka yang berbuat kriminal sewaktu demonstrasi. Seolah menggiring opini publik kalau aksi massa akan selalu identik dengan pelanggaran hukum yang didalangi oleh segelintir pihak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga demikian. Ia mengklaim telah mengetahui aktor-aktor intelektual di balik penolakan Omnibus Law, sambil menyebut kalau aksi ini didalangi oleh elite dan kelompok intelektual.
Kendati demikian, baik Airlangga maupun Mahfud, tidak menyebut siapa-siapa yang dianggap sebagai dalang. Ini tuduhan yang serius dan menodai kesenian wayang.
Pernyataan bahwa selalu ada dalang dibalik protes agaknya meremehkan dan menunjukkan ketidakpercayaan pada masyarakat untuk berpikir dan menginisiasi perubahan. Muaranya adalah cara-cara negara memaksa warga menerima apa pun yang diperbuat negara, dan segala bentuk penolakan dianggap tidak alamiah.
Hari-hari ini, suara publik untuk mengawal dan mengawasi kerja lembaga negara diabaikan dan dianggap angin lalu. Yang jauh lebih buruk adalah perbedaan pendapat akan disebut sebagai narasi-narasi untuk mendelegitimasi pemerintahan.
Mengirim pesan pada orde yang tak mau mendengar ibarat mengirim pesan Whatsapp yang centang dua tapi bukan centang biru, lalu si penerima pesan sedang online, tapi tak kunjung membalas pesan. Menyebalkan.