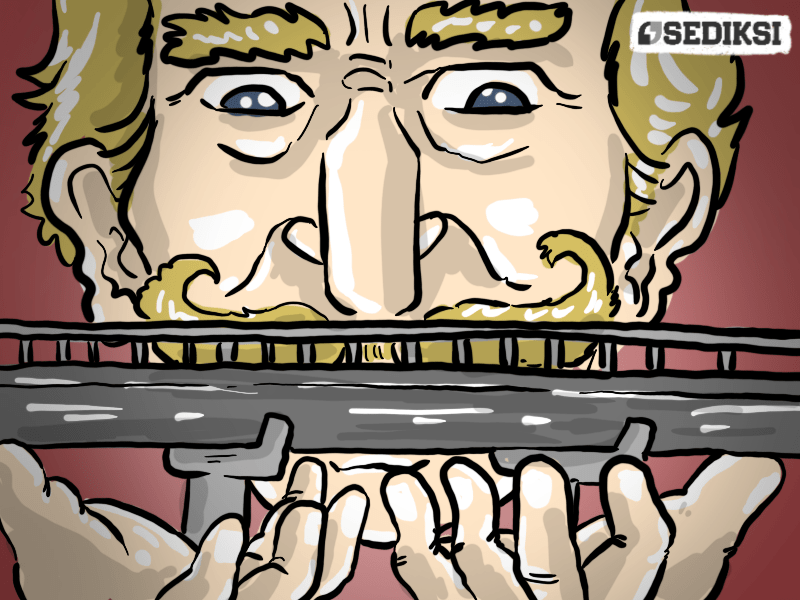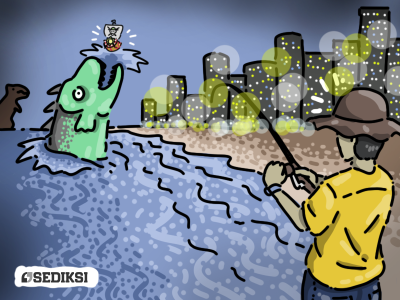Sejak adanya proyek “Napoleonik” Jalan Raya Pos Daendels (1808-1811), kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan di perkotaan tak banyak berubah. Pembangunan jalan seakan sengaja dibuat keras, lurus dan bersih pertama-tama dan utama diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang juga sekaligus simbol modernitas.
Mobil, motor, bus, dan sejumlah kendaraan beroda lain telah mendapatkan arena yang tepat. Sebuah arena yang bukan hanya mempertontonkan gaya hidup yang serba cepat dan mudah untuk dijangkau, tetapi juga berani untuk mengambil risiko dengan melakukan misi penjelajahan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
Apa yang melintas di jalanan bukan semata-mata kendaraan yang dapat membawa orang bergerak atau bepergian secara lebih cepat. Meminjam gagasan Mazrek, jalanan telah mengabstrakkan dunia dari keadaan-keadaan sosialnya untuk membuatnya tampak seperti menggantung di awang-awang.
Inilah yang merupakan bagian dari impian akhir kolonial di mana jalanan telah menjadi “bahasa modern” yang mengikat segala sesuatu dengan teknologi. Di jalanan, modernitas tidak sekadar dipertunjukkan, melainkan dibentuk sebagai sebuah optimisme yang tak jarang bahkan menyingkirkan hal yang “asing”.
Dalam konteks ini, kritik atau permainan bahasa yang dikerjakan oleh Mas Marco di tahun 1920-an dapat dijadikan contoh bagaimana perlawanan terhadap bahasa teknis (vaktaal) di jalanan kolonial akhir yang “bertulang tanpa peradaban” (cultuurloos maar gewapend) adalah enak dan perlu agar tidak terbuang secara linguistik. Menarik misalnya, ketika Mas Marco membuat singkatan untuk badan atau lembaga kehormatan Belanda, Weltvaartscomissi (Komisi Kesejahteraan), dengan sebutan “W.C”.
Meski terkesan seperti “tidak punya perasaan” (rasaloos) atau “tidak punya malu” (maloeloos), permainan bahasa itu telah membuat Mas Marco dikenai tuduhan sebagai “penyebar kebencian” (haatzaai) dan dibuang di kamp interniran kolonial Belanda yang terkenal di Boven Digul, Irian Barat, hingga meninggal pada tahun 1932.
Permainan bahasa yang divonis sebagai “koyok Cino” (seperti Cina) itu telah menjadi bahasa yang mampu mengacaukan tatanan yang merupakan keharusan Kromolanda dan melintasi garis-garis rasial. Itulah mengapa bahasa yang kerap disalahpahami, bahkan disalahnamai, sebagai “Melayu Rendah, “Melayu Betawi, atau “Melayu bazaar (pasar)” itu justru dianggap mampu menggores dan meretakkan apa yang telah dipoles dan diperhalus di koloni yang sedang membangun peradaban modern.
Singkatnya, bahasa tersebut telah menjadi media perjuangan untuk melawan apa saja yang dijargonkan secara akrobatik oleh para insinyur sebagai hal atau sesuatu yang paling modern.
Flyover, atau juga Overpass, adalah warisan dari bahasa jargon kolonial yang dikembangkan di era Soekarno, dan dieksekusi di era Orde Baru secara liar. Apapun dihabisi, termasuk kawasan hijau di perkotaan, hanya untuk menghalus-muluskan jalan.
Di Jakarta misalnya, untuk membangun jalan tol Cawang-Sudirman mesti membom jalan-jalan yang sudah ada supaya menjadi super mulus. Misi modernisasi tersebut membawa slogan “BMW” (Bersih, Manusiawi, Berwibawa). Dengan salah seorang think tank di belakangnya adalah Sang Bapak Beton Indonesia, Prof. Roosseno Soerjohadikosoemo, ahli teknik Indonesia kenamaan, yang terlibat dalam setiap perancangan tata kota sejak era Soekarno.
Diksi-diksi higienis sebenarnya sudah erat dengan proyek pembangunan sejak era kolonial. Seorang ahli farmasi, H.F Tillema pada akhir abad ke-19 datang ke Hindia Belanda. Selain menjadi pemilik dari sebuah apotek besar di Semarang, Tillema juga terpilih sebagai Dewan Kota dan banyak menulis tentang jalan-jalan di tanah jajahan.
Baca Juga: Cara Mati Ketawa ala Milan Kundera
Lantaran kepercayaannya akan kemajuan sebagai kebersihan, ia pun merumuskan sebuah konsep tentang “kebersihan jalanan” (wegen-hygiene). Konsep yang didasarkan pada kebersihan apoteker yang bersifat klinis itu direkayasa untuk membuat jalanan menjadi aman dan antiseptik.
Sebab ancaman paling serius dari jalanan bukanlah kendaraan bermotor modern, tetapi adalah debu yang dapat menjadi masalah hidup dan mati. Maka, jalanan yang higienis adalah sebuah bentuk dari komunikasi modern yang diyakini mampu memperlancar segala urusan karena dapat menghindar dari berbagai macam infeksi.
Ibarat debu, virus yang tak tampak itu bukan saja merupakan gangguan besar, melainkan adalah sebuah bentuk ketakutan dengan alasan-alasan kesehatan. Ketakutan itulah yang tampaknya lebih cepat menyebar ketimbang virusnya.
Itulah mengapa segala bentuk kepanikan dengan mudah membuncah seperti dalam hal pembelian kain penutup hidung dan mulut (masker) atau cairan/gel pembersih tangan (hand sanitizer) secara berlebih-lebihan. Bahkan ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomis dengan cara menimbun dan menjualnya dengan harga tak terduga.
Hanya masalahnya, baik takut pada debu maupun takut pada virus, tampaknya sama-sama ingin “dirawat”, bahkan “disembuhkan”, dengan kata higienis. Itu artinya, cukup dengan menyiram jalanan dengan air atau mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, maka debu atau virus akan lenyap dengan sendirinya.
Sementara, ketakutan yang tak nampak itu masih tetap bersemayam dalam diri setiap orang sebagai kekuatan yang tersembunyi (the hidden force). Bukankah orang takut paling suka mengajak orang lain untuk ikut-ikutan menjadi takut?
Dalam konteks ini, menjadi penting dan mendesak untuk mengkaji ulang apa sesungguhnya ancaman yang ada di jalanan, seperti flyover? Sebagaimana tampak dari pengamatan terhadap kata higienis, bahwa tak ada debu atau virus yang lebih mengancam daripada ketakutan terpapar olehnya.
Jadi, ketakutan yang merupakan kekuatan tak tampak itulah yang telah membuat hidup kita selalu merasa terancam. Padahal ancaman yang direpresentasikan melalui debu atau virus itu hanyalah bayang-bayang dari ketakutan kita sendiri. Masuk akal jika kata higienis pun sekadar menjadi “jargon” untuk menutupi-nutupi ketakutan yang selalu membayangi itu.
Penting untuk dicatat bahwa kata higienis bukanlah sebuah “mantra” untuk menuntaskan segalanya. Sebab di masa lalu kata itu hanya menjadi mesin atau instrumen, bahkan komoditas, yang direkayasa untuk kepentingan kolonialisme. Akibatnya, meski beragam wabah seperti pes dan kolera dapat dipetakan secara kuantitatif, namun toh masalahnya tetap tak tersentuh. Dengan demikian, kata itu sekadar menjadi “akrobat otak”.
Secara tak terduga, kata dapat dimanfaatkan untuk menggores dan meretakkan apa saja yang telah dipoles dan diperhalus. Dengan kata lain, kata dapat pula dijadikan bahasa yang efektif dan operatif untuk menciptakan khalayak yang cerdas dan tajam. Tak heran, para jurnalis awal di Indonesia, seperti Mas Marco Kartodikromo, selalu dibungkam dan dikucilkan, melalui pasal haatzaai (menyebar kebencian), lantaran mampu menyingkap selimut jargon dari berbagai kata dalam bahasa kolonial modern.