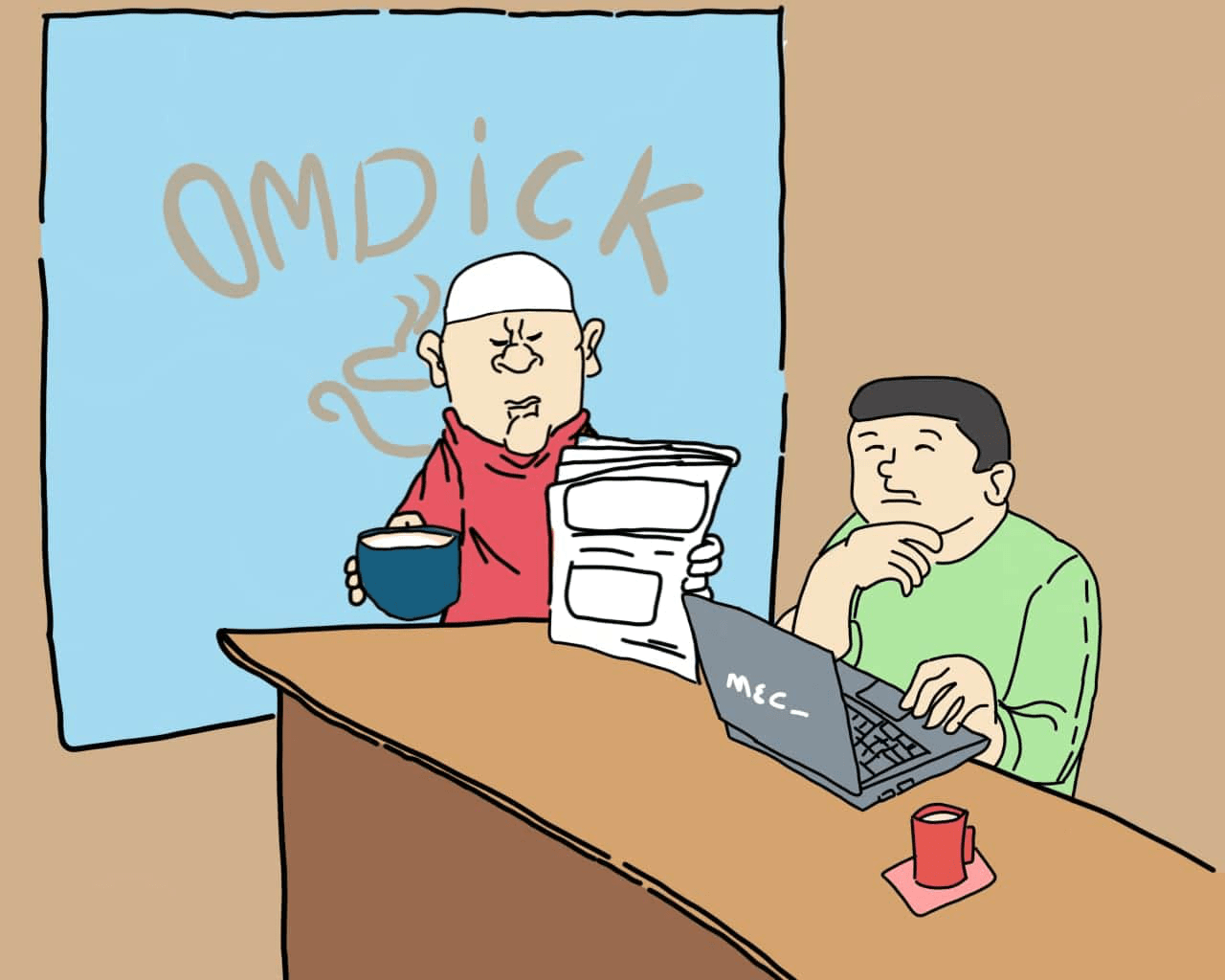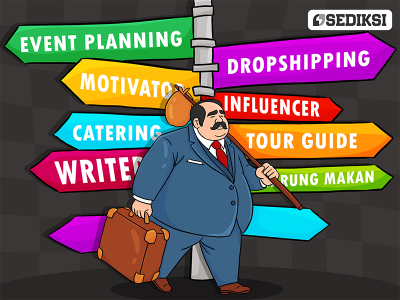Sejak berencana membangun Omah Diksi (Om Dik) di akhir tahun 2016 lalu, saya dan beberapa teman lainnya sepakat untuk menjadikan kedai kopi ini sebagai coworking space. Sebuah ruang yang bertujuan memfasilitasi sekelompok orang yang sedang mengagendakan dan mengerjakan sesuatu, seperti meeting, bekerja, pameran dan/atau workshop. Target pasarnya utama kami adalah mahasiswa. Tidak muluk-muluk, karena saat kami memutuskan membuka kedai kopi ini, mayoritas dari kami juga mahasiswa yang hidup nomaden dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya. Jadilah Om Dik, ruang kumpul sederhana. Sangat sederhana.
Fasilitas yang kami sediakan hanyalah wifi, sedikit koleksi buku, ruang privat dan whiteboard beserta spidol dan penghapusnya. Kami pikir meskipun sedikit, setidaknya fasilitas tersebut cukup lha untuk dipakai berdiskusi, rapat, mengerjakan tugas, atau agenda-agenda lain yang diinisiasi oleh personal atau kelompok.
Singkat cerita, perlahan individu dan komunitas pun berdatangan. Beberapa kali mereka menggunakan fasilitas seadanya itu untuk melakukan aktivitas yang bisa kita sebut working. Entah itu untuk kepentingan akademis, finansial, maupun aktualisasi semata.
Bagi saya, aktivitas-aktivitas semacam itu membuat Om Dik sudah patut dikatakan sebagai coworking space. Namun, tampaknya pendapat ini tak akan bisa diterima oleh kebanyakan orang. Berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan orang termasuk kru Om Dik sendiri merespon dengan sangsi apabila saya mengatakan bahwa Om Dik adalah sebuah coworking space.
Pertama, tentu karena secara fisik Om Dik tak bisa disebut sebagai coworkingspace. Om Dik yang sedikitnya sudah tiga kali berpindah tempat dan berubah tampilan, masih lebih pantas disebut sebagai kedai kopi sederhana.
Kedua, fasilitas Om Dik benar-benar sederhana, jika terlalu kasar untuk disebut “seadanya”. Tidak ada LCD Proyektor, mic, AC, jaringan internet private, serta fasilitas ‘keren’ lainnya.
Ketiga, Om Dik kurang prestisius. Datang ke Om Dik tidak bisa membuat seseorang menjadi cool begete. Gak bisa juga meningkatkan personal branding pengunjungnya.
Terakhir, perihal pandangan masyarakat terhadap coworking space. Poin ini merupakan benang merah dari poin sebelumnya. Saya kira pandangan terhadap coworking space yang lekat dengan atribut-atribut prestisius lah alasan mengapa ketiga poin sebelumnya itu tercipta.
Orang-orang jadi memangkas atribut fungsional pada sebuah ruang. Sekalipun ‘ruang’ yang dimaksud itu memiliki fungsi sama atau lebih daripada ‘ruang’ yang mengidentifikasi diri sebagai coworking space, tetap saja ‘ruang’ itu jauh dari identitas coworking space.
Kelas sosial tercipta. Coworking space jadi bergantung pada simbol-simbol tertentu: fisik, prestis, dan kadang-kadang harga pun menentukan apakah sebuah ruang dapat disebut sebagai coworking space. Paradigma yang cukup mendiskreditkan ruang-ruang lain di Kota Malang, yang selama ini memiliki fungsi kolaboratif, tapi tidak mampu memanjakan orang-orang di kelas menengah ke atas.
Media massa dan internet turut melegitimasi paradigma tersebut. Mereka kurang menjangkau ruang-ruang lain yang selama ini berfungsi menjadi ruang kolaboratif oleh berbagai pihak. Ketika melakukan pencarian di Google mengenai coworking space di Malang, beberapa ruang yang selama ini saya anggap memiliki fungsi kolaboratif ternyata tidak terjangkau dalam apa yang dianggap sebagai coworking space.
Ada Kafe Pustaka, OASE Cafe & Literacy, Petruk Warung Publik, atau Kedai Kopi Kalimetro. Sejauh pengamatan saya, kedai-kedai kopi tersebut tidak sebatas menjadi ruang untuk bersantai para pekerja dan/atau mahasiswa saja. Melainkan, juga berfungsi sebagai ruang untuk berkarya. Maka, bukan sesuatu yang muluk, bila saya juga menyebut tempat-tempat itu sebagai coworking space.
Jika ingin meninjau lebih jauh lagi, maka bisa didapati bahwa di Indonesia coworking space sudah menjamur sejak lama. Jangan-jangan, hampir setiap warung kopi di pojokan desa juga memiliki fungsi kolaboratif?
Alkisah, para kru Sediksi pernah bertempat tinggal di sebuah desa, di Utara Kabupaten Malang. Di sana terdapat sebuah warung kopi kecil. Lokasinya bersinggungan langsung dengan jalan utama yang kini menjadi jalan alternatif Malang-Singosari. Dikelola oleh sepasang suami-istri paruh baya. Komoditas yang dijual: minuman, mie instan dan makanan ringan, termasuk gorengan.
Karena warung itu merupakan warung terdekat dari kontrakan kami, maka kami jadi sering berkunjung kesana. Berbincang-bincang tentang banyak hal dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Petani, sopir, sales rokok, kolektor, hingga mbak-mbak SPG. Sesekali kami ikut bercengkerama, namun seringkali kami hanya sekadar menguping.
Kami mengamati ada kerja-kerja kolaboratif di antara mereka, para pekerja lapangan. Para sales memetakan lokasi, para petani membicarakan tentang hama tanaman dan tips-tips mengatasinya, SPG rokok berkonsultasi dengan supervisor mereka mengenai kerjaannya, hingga para sopir yang menawarkan jalan-jalan alternatif menghindari titik rawan macet kepada sopir lainnya.
Lantas, apakah warung kopi pojokan di sana bisa disebut sebagai coworking space? Merujuk pada makna coworking space secara substantif sebagai ruang kolaboratif, jawabannya adalah ‘iya’. Alasannya, sudah saya jelaskan sebelumnya.
Saya pernah mendengar atau membaca sebuah pendapat mengenai generasi yang kian hari, kian memuja simbol. Pendapat itu menjelaskan bahwa semakin kesini, orang-orang bakal lebih mudah termakan oleh simbol-simbol tertentu dalam memaknai sesuatu dan memangkas subtansinya.
Berpegang pada pendapat tersebut, tidak heran apabila seiring berjalannya waktu, makna ruang kolaboratif dari coworking space bakal terpangkas oleh simbol-simbol prestisius yang menyertainya.
Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kian hari bisnis coworking space di Indonesia kian meningkat. Hanya saja, barangkali akan lebih baik apabila perkembangan ke arah positif itu juga diimbangi dengan kesadaran bahwa coworking space di Indonesia sejauh ini sudah bukan barang baru untuk dielu-elukan.
Hal ini bertujuan semata-mata untuk menghindari kesenjangan di alam pikir masyarakat dalam memaknai sesuatu. Sehingga, tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang bersifat hirarkis. Dengan begitu, ruang kolaboratif bakal lebih mudah berkembang, terlepas dari batas-batas prestisius yang selama ini menyertainya.
Lagipula, yo mosok, sesuatu yang menciptakan kesenjangan itu bakal terus kita pertahankan?
Maaf, sekadar mengingatkan.