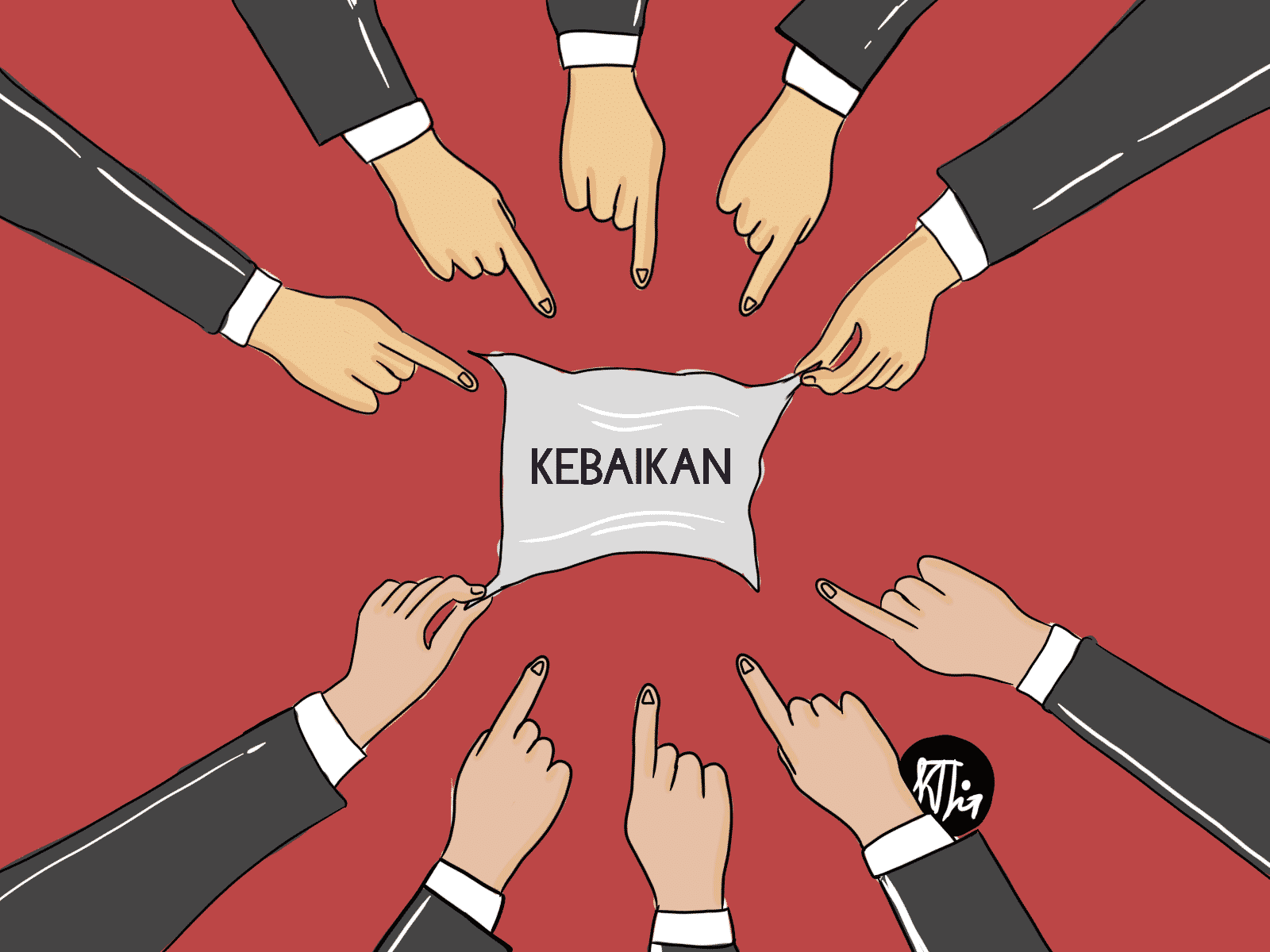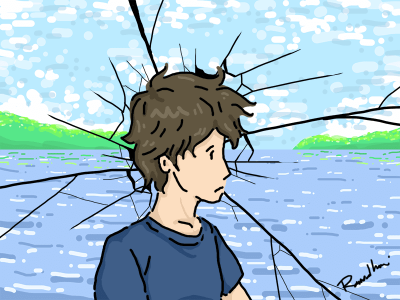Dalam ruang-ruang diskusi film, kelas-kelas sinematografi, sampai perdebatan kecil di lobi bioskop, akan selalu ada pertanyaan: bagaimana sebuah film bisa dinilai bagus? Biasanya penilaian tersebut diserahkan begitu saja pada pendapat subjektif masing-masing penonton. Penonton seperti saya misal, menganggap film yang bagus adalah film yang memberikan pengalaman dan sudut pandang yang segar. Termasuk saat saya menonton Film 12 Angry Men .
Perasaan yang ditimbulkan seusai menonton sebuah film tentu saja berbeda-beda, bisa puas, gemas, melankolis, atau justru menimbulkan perasaan gelisah disebabkan pertanyaan-pertanyaan yang belum tuntas terjawab dari film yang sudah ditonton. Ibarat guru yang rajin memberi PR menjelang pulang sekolah, salah satu film yang memberi pekerjaan rumah berupa kegelisahan itu adalah 12 Angry Men (1957) yang disutradarai oleh Sydney Lumet.
Film 12 Angry Men adalah film courtroom drama yang mengambil latar di suatu ruangan diskusi yang sempit di dalam sebuah kantor pengadilan. Kantor ini diisi oleh 12 orang pria dengan watak yang berbeda-beda. Di tengah ruangan terdapat meja panjang yang menjadi pusat kejadian-kejadian yang berlangsung di sepanjang alur cerita. Di meja inilah kedua belas pria tersebut berperan sebagai juri yang mempertimbangkan hukuman atau pembebasan terdakwa kasus pembunuhan yang baru berusia 18 tahun.
Baca Juga: The Age of Adaline: Merasakan Lelahnya Jadi Awet Muda
Meskipun film ini mengangkat tema kasus pembunuhan, kita tidak akan disuguhkan darah, aksi kekerasan, ataupun analisis lebay ala detektif SMA. Penonton justru akan diperlihatkan dialog-dialog dihamburkan ke atas meja.
Sebuah tata adegan yang jarang diadopsi oleh banyak film lain, karena film dengan satu latar tempat cenderung berisiko memiliki plot yang monoton. Tapi, tidak dengan Film 12 Angry Men. Film ini menyajikan plot dan pendalaman karakter yang sangat apik, disebabkan oleh dialog yang padat dan penuh interaksi.
Kekuatan karakter setiap tokoh bahkan membuat nama mereka tidaklah penting. Sydney Lumet nampaknya lebih memfokuskan pada eksplorasi watak-watak tiap karakter tokoh. Mulai dari cara berbicara, gestur, hingga ekspresi yang begitu hidup. Sebagaimana dalam karya seni dan sastra, film tidaklah berangkat dari kekosongan. Ia berangkat dari kolase realita di keseharian manusia.
Di film 12 Angry Men, karakter tokoh-tokoh tersebut disajikan dalam spektrum yang beragam dan saling bertolak belakang. Ada tokoh juri #1 dengan sifat ngemong, secara spontan mengorganisir tokoh-tokoh lain dan berperan menjadi moderator sepanjang diskusi. Juri #2 yang kikuk namun baik hati, juri #3 yang pemberang, juri #4 yang kaku, serius, namun rasional, juri #5 yang pendiam, juri #6 yang menjunjung tinggi etika, juri #7 yang cenderung acuh tak acuh, juri #8 yang cerdas dan penuh pertimbangan, sampai juri #12 yang suka bermain-main.
Kedua belas orang tersebut berdebat sengit di ruangan sempit sampai tak sempat memperkenalkan namanya terlebih dulu. Sedikitnya hanya dua-tiga nama saja yang selintas disebutkan. Bagaimanapun, pengosongan nama-nama ini telah berhasil menghindari stereotip negatif atas nama ras yang banyak menjadi masalah dalam sejarah panjang di Amerika Serikat. Nuansa panas dingin makin makin terasa saat para tokoh saling berbenturan secara dialogis.
Mereka harus mengambil keputusan yang menyangkut nyawa seorang anak berusia 18 tahun sebagai terdakwa pelaku pembunuhan ayahnya sendiri. Kedua belas juri ini harus mencapai suara bulat dalam mengambil keputusan bersalah atau tidaknya si anak. Jika tidak bulat, keputusan akan dipasrahkan sepenuhnya kepada hakim.
Bermula dari Perasaan Ragu
Semua bukti dan saksi yang ada, mengarah pada fakta bahwa si anaklah pelaku pembunuhan ayahnya sendiri. Hingga saat seorang juri ragu dan mempertanyakan apakah remaja itu benar-benar bersalah.
Keraguan juri #8 telah mengantarkan kita pada proses pencarian kebenaran lewat perdebatan sengit. Ini seperti ilmu filsafat, yang meski terdengar berat, hanya perlu satu proses penting yakni “meragukan” . Tidak perlu keraguan yang bentuknya besar, cukup percikan kecil akan mengantarkan seseorang pada cara berpikir yang objektif.
Selintas pertanyaan ragu di dalam benak semacam “masa sih?”, “Apa iya?”, “Kok bisa begitu?” Jika proses mengungkapkan keraguan itu tidak ada, maka tidak akan ada filsafat, dan proses pencarian serta pengetahuan akan mandeg. Sehingga, kebenaran yang dicari akan semu belaka. Toh, pada akhirnya, tanggung jawab seseorang hanyalah mencari tahu kebenaran, tapi tidak akan tahu mana yang benar.
Proses pencarian-lah yang menjadi pokok utama, saat semua orang di dalam ruangan tersebut dalam posisi tidak tahu dan asing, namun mencoba memahami kenyataan lewat rasio tanpa kesan ngoyo. Film 12 Angry Men seakan melawan premis umum bahwa kebenaran harus ditegakkan.
Film ini lebih menekankan pada pentingnya bersikap adil, objektif, dan tidak asal main klaim mana yang benar, mana yang tidak. Davis, juri #8, mengatakan, “kapanpun kau berprasangka, prasangka tersebut selalu mengaburkan kebenaran. Aku benar-benar tidak tahu kebenarannya. Malahan kupikir tidak ada yang tahu kebenarannya.”
Ucapan tersebut mengingatkan saya pada ungkapan sastrawan Seno Gumira Ajidarma (SGA). Dalam pidato kebudayaannya ia mengatakan, “kata kebenaran lebih baik tidak digunakan, dihindari, atau digunakan dengan hati-hati sekali, karena kebenaran, meskipun ada, tidak bisa diketahui.”
Argumen benar dan salah nampaknya sangat dihindari dalam film ini. Termasuk saat mayoritas juri punya asumsi yang sama bahwa si anak remaja adalah pelaku pembunuhan. Selain karena proses persidangan yang terkesan tergesa-gesa, juga catatan kriminal yang dimiliki si remaja, ada faktor kelas sosial yang melatarbelakangi pendapat mereka.
Para juri kesemuanya berasal dari kalangan kelas menengah: seorang arsitek, pemilik bengkel, guru olah raga, salesman, dan pegawai kantoran, yang sehari-harinya disibukkan dengan pekerjaan. Bagi kaum yang sehari-harinya saja penuh perjuangan sekadar hidup, kata ‘keadilan’ adalah sesuatu yang gaungnya jauh, Bung dan Nona!
Dalam film, tokoh Davis, juri #8 mencoba untuk mendiskusikan kembali bukti-bukti dan kesaksian yang ada dengan kalimat sederhana: “tidak mudah mengangkat tanganku dan mengirim si anak ke kursi listrik tanpa membicarakannya terlebih dahulu.” Ini jeda yang kemudian mengantarkan pada diskusi, hingga simulasi mulai dari alat pembunuhan, psikologi pelaku, kondisi pembunuhan, serta saksi-saksi yang terlibat. Klimaksnya terjadi adalah terjadi pertentangan. Bukan hanya antarmanusia dalam ruangan itu namun juga pertentangan batin tiap orang antara apa yang disebut prasangka melawan sikap rasional.
Film 12 Angry Men telah mengajak kita berpikir tentang sistem peradilan dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap penegakan presumption of innocence alias asas praduga tak bersalah. Saat pengadilan memberatkan si pelaku seakan-akan ia pasti bersalah. Asumsi seseorang pasti bersalah sebagai premis awal bisa saja berubah, bukan sebagai hasil akhir yang pasti.
Contohnya saat si juri #8 yang mengekspresikan keraguannya, ia juga tidak menggebu-gebu untuk mempertahankan argumen bahwa si pelaku tidak bersalah. Ia justru mengajak untuk membicarakan apakah si pelaku bersalah. Ada perbedaan mendasar antara ‘ketiadaan bukti tentang sesuatu’ dengan ‘bukti bahwa sesuatu tidak ada’. Seperti yang diungkapkan oleh juri nomor 8:
“Kita bisa saja membebaskan orang yang ternyata bersalah. Aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa tahu pasti hal itu. Tapi yang pasti, kita punya keraguan yang beralasan, dan hal itu merupakan hal yang amat berharga di sistem peradilan kita. Tidak boleh ada juri yang mengumumkan seseorang bersalah tanpa dipastikan terlebih dahulu.”
Seusai menonton film ini saya jadi bertanya-tanya:
mending mana, menghukum orang yang tidak bersalah atau melepaskan orang yang bersalah?