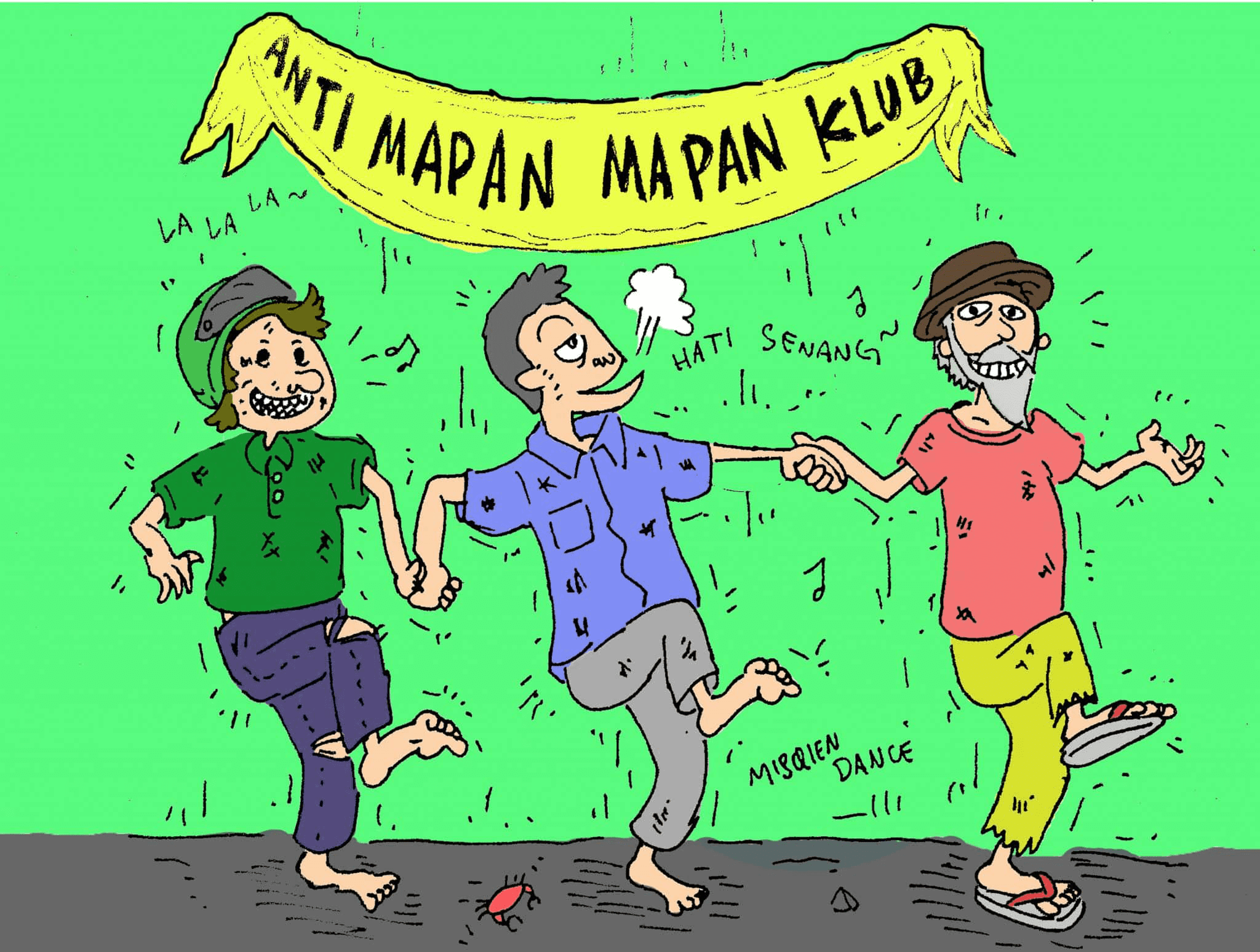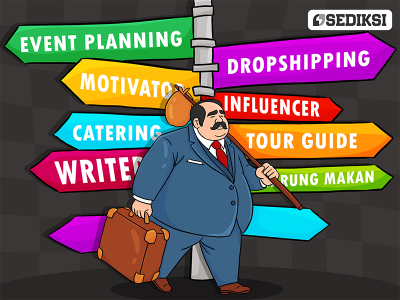Mungkin judul “Hati Senang Walaupun Tak Punya Uang” ini bakal mengundang sosialita garis keras berkomentar:
“Hellooooo, hari gini gak punya duit, mau senang dari mana? Lu olang mau kencing saja bayar 2000”.
Lalu argumen itu dibalas oleh fans berat Mimi Peri,
”Eh ketiak kambing dikasih nyawa. Ga semua itu bisa dibeli dengan duit. Contohnya cinta sejati nan suci, juga kecantikan akyu yang 17x syantiiik”.
Mencoba menengahi perdebatan nirfaedah mereka berdua, netijen garis keras pun menulis di kolom komentar,
“Duit tuh gak apa gak ada. Yang penting ada air, indomie, dan wifi.“
Sebenarnya keadaan hati saya lagi ndak senang-senang banget, saat tulisan ini saya ketik. Malah kalau boleh jujur, saya baru saja kalah berturut-turut di salah satu gim mobile yang saya mainkan di tengah-tengah merampungkan bachelor’s thesis. Tolong jangan dihujat noob bahasaku yang keminggris nih, kzl bat acutu…
“Terus kunaon sia nulis kehed?” umpat pembaca Sunda yang lagi nyasar di Malang.
Ya gak ada, iseng aja, siapa tau bisa lolos halaman enam Harian Kompas. Amiiin yra. Kalau ndak bisa ya Sediksi saja juga gak apa.
Tapi serius nih gaes, judul ini merupakan kesimpulan kecil dalam salah satu fase hidup saya yang menurut saya cukup bijak untuk dibagi. Terserah kalau mau disepakati bersama atau hanya menjadi bacaan yang mengundang orang berkomentar: opini apa ini? kembalikan beberapa menit waktuku yang berharga!
Yang jelas, baca dulu, lalu sebarkan di grup WA, hahahaha!
Ketika cebong dan kampret sibuk memperdebatkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini, apakah patut disyukuri atau malah dihujat, toh harga pertalite sudah naik. Harga nasi goreng dekat rumah saya juga naik (alasannya lpg 3 kg naik), SPP kuliah naik, gaji teman saya alhamdulillah juga naik (dikit), dan pajak usaha dan perseorangan juga naik. Tak ada yang begitu berbeda sejak masa reformasi. Walaupun memang terkadang ada beberapa sektor yang harganya turun, tapi pada akhirnya juga tetep sama: naik.
Dan itu merupakan kewajaran dalam logika perekonomian. Bahwa di dunia yang kapitalistik, nilai sebuah produk akan selalu diupayakan naik, kalau tidak bisa ya tetap. Tidak mungkin jika sebuah produk dari awal sampai nanti kiamat harganya akan tetap sama. Baik owner ataupun buruh pasti mengharapkan kenaikan. Walau kenyataannya kenaikan nilai produk atau jasa yang mereka berikan juga diikuti kenaikan kebutuhan mereka. Jadi intinya: podo ae!
Tetangga saya yang rumahnya sederhana dan bermotor Honda Astrea, dari beberapa tahun lalu sama saja kehidupannya. Ia masih menjemur nasi di depan rumahnya. Motornya tambah satu, tapi ya tetep motor keluaran lama dibeli bekas. Tetangga saya yang satunya, yang bekerja di Kalimantan, yang ketika awal pindah ke kompleks perumahan langsung membeli dua rumah dijadikan satu. Kehidupannya sepertinya tetep saja: tetep kaya. Dua mobilnya bisa dituker 200 unit motor Astrea.
Argumen klasik yang cocok dalam konteks ini mungkin: Yang kaya tetep kaya, yang miskin ya tetep miskin. Lalu apa yang membedakannya? “Derajat manusia di sisi Tuhannya, hanya karena taqwanya” jawab Bang Haji.
Lalu pembaca cum motivator akan berkomentar,”Ya itu yang membedakan usahanya, kalau dia memang rajin berusaha dan pintar melihat peluang, ia pasti bisa jadi kaya.”
Ya itu juga benar, bahkan beberapa milyarder terkaya yang namanya tercatat dalam Forbes ada yang berasal dari keluarga miskin. Saya paham itu. Tapi yang menjadi fokusnya bukan terkait pencapaian materi mereka. Lebih kepada apakah orang miskin memiliki kesempatan bahagia yang sama dengan orang kaya.
Eric Weiner menulis dalam bukunya The Geography of Bliss yang membahas perjalanannya di 10 negara untuk mencari kabahagiaan. Bahwa uang memang bisa membeli kebahagiaan, tapi hanya sampai tahap tertentu saja. Selebihnya, faktor lain yang tidak terkait dengan uang yang menentukan kebahagiaan subjektif seseorang. Hal itulah yang membuat Bhutan, sebuah negara kecil yang tak memiliki PDB sefantastis Singapura tapi memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi.
Saya berprasangka, bahwa tingkat kebahagiaan tetangga saya yang mobilnya dua ketika menyantap pizza mahal seharga ratusan ribu rupiah, bisa saja tidak jauh berbeda dengan tetangga saya yang bermotor Astrea ketika memakan lalapan ayam di pinggir jalan. Atau mungkin kasur berukuran Queen Size yang ia tiduri tidaklah membuatnya bermimpi lebih indah dari pada kasur dari kapuk yang ditiduri oleh tetangga saya yang tidak lebih kaya.
Tetangga saya yang kaya memiliki ibu yang selalu berjalan dengan kursi roda, yang tiap pagi berjemur matahari sendirian, tak bercakap dengan siapa-siapa. Sementara tetangga saya yang tidak lebih kaya, hampir tiap pagi bisa bermain dengan anaknya yang masih balita di depan rumahnya, sebelum ia mulai berangkat bekerja. Dua pemandangan yang kontras, yang berjarak tidak lebih dari 100 meter.
Lalu pesan yang bisa diambil? Tanya pembaca.
Sudah besar kok minta disimpulkan, hehe. Dari pada ngambek, nih saya kasih closing statement biar kaya motivator yang suka makan ikan sarden, Om Mario Bross. :
Sepertinya pepatah yang bilang rumput tetangga terlihat lebih hijau dari rumput sendiri seringkali tepat. Tapi coba sekali-kali kita memakan rumput kita sendiri. Siapa tau rumput tetangga itu sintesis.
Itu.
Salam Kuper.