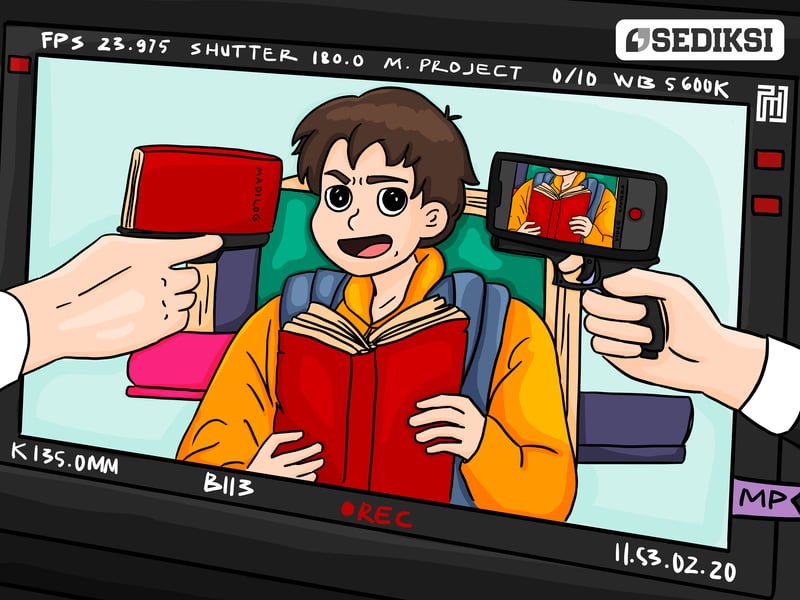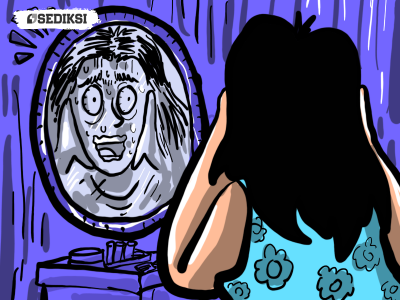Beberapa waktu lalu, para kreator konten populer berkumpul membentuk komunitas baru bernama Malaka Project. Yang terdiri dari, Ferry Irwandi, Jerome Polin, Cania Cita, Coki Pardede, Angellie Nabilla, Aurelia Viza, Fathia Izzati, Rizky Ardiprakoso, dan Dea Anugerah.
Dari nama-nama tersebut, masing-masing memiliki keunikan dan branding yang berbeda. Tentu ini menarik untuk sebuah identitas komunitas.
Bisa dibilang sebagai “teknokrat” cabang ilmu media digital. Karena mereka memang influencer yang cukup dikenal publik dengan ciri khas pikirannya.
Saya antusias, saat pertama kali mendengar kehadiran Malaka Project, dengan wacana “Menuju Masyarakat Baru”. Bingkai wacananya pun adalah melalui pendidikan. Sebuah bingkai yang sudah lama gagal diurus negara.
Selain itu, ada pengadopsian nama “Malaka”—yang kata salah satu founder-nya, diambil dari nama Bapak Republik Tan Malaka. Serta, menjadikan Madilog sebagai salah satu dasar presentasi di dalamnya.
Tentu ini sangat apik. Berbicara Tan Malaka memang tidak bisa lepas dari materialisme, dialektika, dan logika (Madilog).
Lebih lanjut membaca Madilog, materialisme sebenarnya berperan sebagai dasar pintu masuknya. Baru setelahnya materialisme itu didialektikakan (tesis-antitesis-sintesis), yang tentu saat mendialektikakan materialisme tersebut perlu dan selalu dibutuhkan logika.
Cara berpikir Madilog sendiri menurut Tan Malaka, akan membawa bangsa Indonesia (yang saat itu masih masa perjuangan kemerdekaan) ke arah pola pikir baru. Dari logika mistik ke logika materialisme.
Mengubah cara berpikir dari berbasis takhayul, pasrah, dan serba takdir-nasib menjadi lebih logis, relevan, dan berkembang.
Namun, begitu saya mengetahui program pertama Malaka Project adalah beasiswa pendidikan, seketika konsep masyarakat baru bermadilog di kepala saya runtuh tanpa sisa.
Justru karena ingin bermadilog, saya menganggap program beasiswa atas nama pendidikan itu perlu dipersoalkan. Tidak sesuai dengan semangat Tan Malaka yang revolusionis.
Tidak Ada Masyarakat Baru
Saat membicarakan pendidikan, mendengar kata beasiswa bukan lagi hal yang asing. Bahkan negara memberi jalur beasiswa sebagai upaya alternatif atas kebutuhan dan penjaminan pendidikan.
Di sektor swasta pun, beasiswa tentu juga bukan barang baru. Negeri atau swasta sama-sama memiliki motif memenuhi kebutuhan, sekaligus memberi penjaminan pendidikan pada individu-masyarakat program beasiswa.
Atas dasar itu, sebenarnya program beasiswa itu sendiri bentuk dari tesis, antitesis, atau sintesis? Kalau benar-benar ingin berdialektika, persoalan ini harus diurai terlebih dahulu. Sebab, dalam wacana pendidikan yang panjang, beasiswa rasanya hanya kumpulan tesis-tesis.
Jadi, Malaka Project sedang mendialektikakan apa? Apa sintetis dari Malaka Project terhadap pendidikan? Untuk menjawab itu tentu diperlukan antitesis terlebih dahulu. Apakah beasiswa adalah antitesis itu?
Saya pribadi tidak melihat ada antitesis terhadap pendidikan dari ide-praktik Malaka Project. Persoalan ini dapat diterima kalau kita melihat komposisi personal dalam komunitas baru tersebut.
Dari ke sembilan nama di atas, tidak ada background kreator konten pendidikan. Siapa di sana yang berjuang menyuarakan isu pendidikan nasional?
Kalau di antara mereka memang tidak ada yang fokus dan tekun di bidang pendidikan, mulai dari filosofis hingga praksisnya, bingkai pendidikan yang digelorakan rasanya perlu untuk ditinjau lebih jauh. Entah itu lewat kritik atau lewat dialektika lainnya.
Sebab, suatu hal yang dijalankan dalam pandangan yang bukan ahlinya, akan cenderung bias pada pengulangan-pengulangan langkah. Bukan pada pembaharuan dan perubahan. Apalagi sampai level Masyarakat Baru.
Saya tidak bermaksud mengatakan beasiswa Malaka Project tidak berguna apalagi salah. namun bila Malaka Project memang ingin melakukan perubahan dalam pola pikir masyarakat lewat pendidikan, sangat disarankan agar benar-benar menguasi persoalan pendidikan itu sendiri.
Jangan sampai, daya relasi-jaringan dari kesembilan founder yang begitu luas, berakhir menjadi proyek industri pendidikan berbasis konten seperti lainnya yang sudah-sudah.
Beasiswa Bukan untuk Semua
Dalam banyak catatan kritis para pemerhati pendidikan dan literatur pendukung, persoalan utama dan selalu dibahas serta diperjuangkan dalam pendidikan di Indonesia adalah memberantas ketimpangan.
Jurang ketimpangan pendidikan di Indonesia sangatlah tinggi dan terus melebar. Tidak perlu terlalu jauh membandingkan antar sekolah kota dengan daerah 3T.
Di wilayah kota satu kawasan pun, ketimpangan itu nyata sudah terjadi dan diproduksi. Bahkan antar sekolah yang letaknya berjarak tidak lebih dari 1 km, perbedaan akses, mutu, kelas, dan penunjang lainnya sudah sangat njomplang.
Dari situlah mengapa dalam konteks Indonesia, sulit sekali mengatakan bahwa pendidikan akan menyelamatkan kualitas hidup seseorang. Karena akses pendidikan bermutu itu sendiri sudah seperti barang yang memilih pembelinya. Lalu apakah beasiswa adalah jalan keluar?
Kalau diperhatikan lebih jauh, saksama, dan struktural, cara kerja beasiswa tidak berbeda dengan perebutan barang yang mensyaratkan kesiapan. Beasiswa dalam pembacaan ini lebih mirip dari turunan persoalan pendidikan itu sendiri.
Bila sekolah bermutu dan berkualitas hanya dimiliki kalangan tertentu, beasiswa juga dapat dikatakan sama saja. Dia memang disediakan untuk kalangan tertentu juga.
Sekalipun bingkainya beasiswa warga miskin, tetap saja cara kerjanya menyeleksi siapa orang miskin yang cocok dan sesuai kriteria beserta syaratnya (semisal aktif bahasa inggris, mencari pengetahuan, relasi, dan panduan lainnya).
Jadi, penentu siapa yang berhak mendapatkan beasiswa, sebenarnya bukan perkara syarat dan tata cara pendaftarannya. Melainkan pada atribut yang menempel pada individu itu sendiri (modal, materi, kesiapan, idealisme, kecerdasan, arena, dan pola pikir).
Semua itu pada akhirnya mengerucut pada gelanggang persaingan pasar bebas individu.
Bila dirangkum akan menjadi seperti ini, sekolah bermutu dan pendidikan berkualitas gagal dicapai masyarakat luas, sehingga hadirlah beasiswa untuk membantu golongan yang kalah bersaing, namun dengan cara persaingan pula.
Baca Juga: Novel Dilan dan Sobekan Potret Pendidikan
Dengan kata lain, keadaan ini juga lebih mirip “voucher promo” dari sebuah lembaga pendidikan yang jumlahnya terbatas. Silakan perebutkan itu dengan cara dan kemampuan masing-masing.
Dari sini, kita akan sama-sama melihat bahwa beasiswa tetaplah ruang kerja individualistik. Beasiswa bukan jalan keluar dari persoalan pendidikan Indonesia.
Justru, beasiswa akan berpotensi menciptakan elitisme, pengingkaran-pengingkaran nilai, dan tujuan akhir dari pendidikan. Pada titik akhirnya beasiswa tidak lebih dari harapan mistik bagi orang miskin, yang mendambakan peningkatan kualitas hidup lewat pendidikan (Dibayangkan sebagai jalan pembebasan-perubahan ternyata bukan).
Untuk mendapatkan pendidikan bermutu, rakyat sebenarnya tidak perlu bersaing secara modal, kesiapan, arena, dan nasib. Sebab, pendidikan merupakan hak dasar yang sudah seharusnya didapatkan warga negara secara berkeadilan dan rata.
Jadi, sangat disayangkan bila pada akhirnya Malaka Project dengan semangat masyarakat barunya menggunakan konsep beasiswa. Kalau mereka memaksa ingin meneruskan, maka Malaka Project akan lebih mirip kacang goreng yang dikemas dengan bungkus premium.