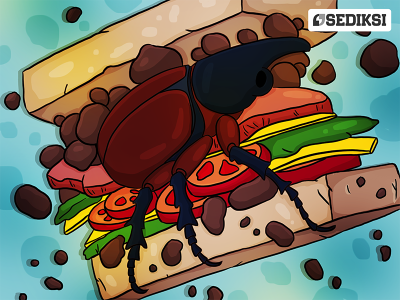Beberapa hari lalu, ketika berkunjung di sebuah kafe, teman-teman membicarakan buku yang memuat tokoh bernama Dilan. Mereka begitu asik dengan pembahasan seputar Novel Dilan.
Beragam argumen, mulai sanjungan hingga kritikan terlontar, dan saya teralienasi sebab belum membacanya. Mereka merekomendasikan agar saya membaca buku yang tengah mereka bicarakan.
Yang saya maksud ini adalah dua seri novel Dilan karya Pidi Baiq, masing-masing berjudul Dilan: dia adalah Dilanku tahun 1990; dan Dilan: dia adalah Dilanku tahun 1991. Karena saya tak memiliki buku itu, maka malam hari sepulang dari kafe itu, saya meminjam buku pertama dari manusia bernama Bayu Diktiarsa.
Sebenarnya, Bayu tergolong manusia yang paling anti-meminjamkan buku. Namun, karena yang hendak meminjam adalah saya, maka keputusannya jadi lain. Keesokan harinya, novel dilan yang terbit pertama kali pada April 2014 dengan tebal 332 halaman itu sudah rampung saya baca.
Karena penasaran tentang lanjutan kisahnya, saya mencari-cari ide agar bisa membaca buku kedua secara gratis. Sebenarnya ingin sekali memiliki buku itu dengan cara membeli, namun apa daya, kondisi keuangan saya saat itu sedang seret karena desakan tagihan SPP Progresif yang musti saya bayar agar bisa melanjutkan kuliah.
Kebetulan, saya memiliki teman bernama Denty Puspita Meilani. Perempuan kelahiran Surabaya yang baru saya kenal ketika kuliah ini diam-diam juga pecandu buku. Koleksi bukunya lebih terawat dibandingkan punya saya. Terbukti dengan sampul plastik yang melindungi setiap muka buku miliknya. “Semua buku Pidi Baiq aku punya,” ungkapnya pada suatu ketika.
Saya tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melampiaskan keinginan menyelami lanjutan kisah Dilan. Atas peran serta dan welas asih perempuan yang memiliki tatapan mata horor itu, akhirnya saya bisa membaca buku kedua. Hari itu juga kami melaksanakan prosesi serah-terima peminjaman buku berjudul Dilan: dia adalah Dilanku tahun 1991, di sebuah kos-kosan tempat ia bermukim.
Saya merasa perlu menuliskan bagaimana semua ini bermula sehingga saya mampu menikmati dua buku itu, untuk berterima kasih kepada para pihak terkait. Selain itu, sekaligus sebagai permohonan maaf kepada Mas Pidi Baiq, karena saya membaca karyanya secara gratisan, karena saya belum berkesempatan mengapresiasi ‘anak-anak rohaninya’ dengan cara membeli, sepurane Mas.
Mari kita masuk pada inti yang ingin saya sampaikan. Untuk lebih mudah memahami tulisan ini, sebaiknya kalian membaca dua buku itu terlebih dulu, agar bisa berkenalan dengan Dilan dan kehidupannya, atau menyimak resensi novel Dilan yang telah saya tulis sebelumnya di blog pribadi saya, berjudul Tentang Dilan: Asmara, Kenakalan Remaja, dan Kenangan.
Baca Juga: Jika Saya Menjadi Seorang Pustakawan
Potret Pendidikan dalam Novel Dilan
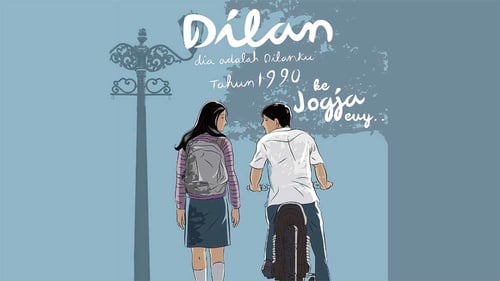
Harus saya akui, buku tersebut sukses mencongkel ingatan saya dan membawanya menuju masa lalu, masa di mana saya masih berseragam putih-kelabu. Kisah keseharian dalam novel Dilan adalah sepenggal realita yang niscaya ada pada tiap generasi ketika SMA.
Kenakalan di sekolah, jalinan asmara, dan tetek-bengek kehidupan remaja adalah sobekan potret pendidikan Indonesia yang tak bisa dipungkiri. Saya sepakat dengan Dilan, bahwa jika tidak ada siswa nakal, reuni SMA tidak akan asik.
Ini bukan berarti kenakalan siswa merupakan sebuah kewajiban yang harus ada. Seseorang yang entah siapa, pernah mengucap begini: “untuk dikenal dan selalu diingat guru, pilihannya hanya dua, menjadi paling pintar atau paling nakal.”
Lagi-lagi saya sepakat dengan kalimat tersebut. Bahkan, menurut saya, menjadi siswa yang biasa-biasa saja akan melahirkan masa depan yang juga biasa-biasa saja.
Khusus untuk fenomena kenakalan siswa, tindakan sekolah pada umumnya adalah memberi sanksi secara bertahap sesuai tingkat atau jenis kenakalannya, yang kemudian berpuncak pada pemecatan (drop out) jika kenakalan siswa itu sudah dianggap tidak bisa ditorelansi.
Kadang saya jadi bertanya-tanya, bukankah fungsi sekolah adalah mendidik agar yang bodoh menjadi tidak bodoh? Bukankah sekolah ada karena kebutuhan terhadap perangkat untuk membina yang tidak baik menjadi baik, meluruskan yang tidak benar menjadi benar, dan menata yang tanpa etika menjadi indah?
Atas pertanyaan itu kemudian muncul pemikiran di otak saya, bahwa sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu menjadikan siswa bodoh menjadi pintar, mengubah sifat tidak baik menjadi baik, dan seterusnya, dan seterusnya.
Akan tetapi, yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Sebuah sekolah dianggap sebagai sekolah baik karena ia mampu menerima lulusan-lulusan terbaik dari jenjang sebelumnya. Maka muncullah idiom-idiom sekolah favorit.
Sekolah favorit ini, dalam keseharian kita, merupakan sekolah yang paling banyak diminati siswa. Untuk masuk ke sekolah itu, harus menyingkirkan siswa-siswa lain, berdasarkan penilaian dengan indikator tertentu.
Tentu saja, dalam kasus ini, mendidik siswa yang sudah pintar agar menjadi tetap pintar adalah hal mudah. Jadi, wajar saja ketika lulusan sekolah favorit ini adalah orang-orang pintar, karena memang dari awal sudah pintar.
Sementara itu, bagi siswa-siswa yang gagal masuk ke sekolah favorit saat proses penerimaan siswa baru, harus rela memilih sekolah lain. Sekolah lain ini dianggap memiliki kualitas yang buruk – atau setidaknya lebih buruk dari sekolah favorit.
Pola pikir seperti ini seharusnya dibuang jauh-jauh. Orang tua siswa dan stakeholder terkait, mustinya berpikir ulang tentang konsep sekolah baik dan sekolah buruk. Pe-label-an sekolah baik, selayaknya diberikan pada sekolah-sekolah yang menerima siswa-siswa kurang pandai, nakal, dan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan – namun dapat mengubah siswa-siswa itu menjadi lebih baik. Bukan malah sebaliknya, seperti yang selama ini berlangsung.
Sebab, menurut saya, betapa pun seorang siswa dianggap bodoh, betapa pun siswa dianggap nakal, mereka-mereka ini tetap memiliki potensi yang harus digali. Perhatian terhadap sekolah-sekolah yang hanya menerima ‘siswa buangan’ ini harus ditingkatkan.
Menurut saya lagi, sekolah-sekolah penerima siswa pintar dan tidak nakal, pasti sudah memiliki jalan sendiri dengan dinamika dan iklim pendidikan yang berlangsung, sehingga perhatian stakeholder terkait tidak lagi menjadi hal yang perlu-perlu amat. Sementara, sekolah penerima siswa-siswa kurang pintar tentu saja perlu dibantu dalam berbagai aspek mulai infrastuktur hingga tenaga pendidik.
Perlakuan terhadap siswa yang dipandang nakal, menurut saya juga harus lebih bijaksana. Berkaca pada kasus Dilan, meskipun dia sering terlibat pertengkaran dan berurusan dengan ruang BP, sejatinya dia bertanggung jawab. Ia nakal atas kesadaran penuh dan penghitungan-penghitungan rasional mengenai sebab-akibatnya.
Baca Juga: Optimisme Harari di Tengah Pandemi
Kenakalan siswa harus dipahami sebagai proses pencarian jati diri, proses untuk menemukan perbedaan antara yang baik dan tidak baik; yang pada gilirannya berpengaruh pada pola pikir dan perubahan sikap. Orang yang sudah pernah nakal, ketika akan nakal lagi atau melihat orang lain yang baru ingin nakal, kebanyakan akan berkata sambil tertawa dalam hati:”Wah, cuma segini nakalmu? Aku sudah pernah dan nggak akan lagi.”
Jika kita peka mengamati masa silam dan hari ini, coba lihatlah bahwa sebagian besar siswa-siswa yang dulunya nakal, akan menjadi kejutan ketika momen-momen reuni, karena menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sementara siswa yang biasa-biasa saja, tetap saja menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Hidup ini asik bukan?