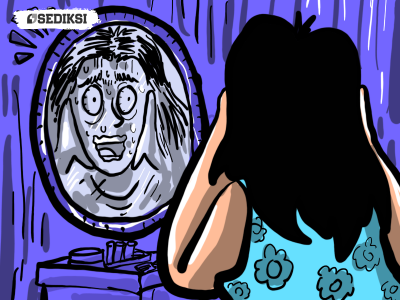Sejarah itu bersifat dinamis dan sah-sah saja untuk dipertanyakan. Tapi minimal paham bagaimana cara membaca sejarah supaya gak dicap sebagai si paling skeptis dan kontrarian!
Saya adalah seorang dengan minat tinggi terhadap topik sejarah beserta polemik yang menyertainya. Itulah kenapa saya agak terusik ketika membaca opini Mohammad Maulana Iqbal berjudul “Mempertanyakan Klaim Surabaya sebagai Kota Pahlawan”.
Ekspektasi saya saat berjumpa dengan tulisan itu awalnya tinggi. Namun, seolah dipaksa, ekspektasi tersebut perlahan turun setelah sadar bahwa opini Iqbal hanya menawarkan skeptisisme serampangan akibat kecerobohan dalam membaca sejarah.
Satu hal yang patut dipuji adalah kepiawaiannya dalam mengolah tulisan itu menjadi semacam bola liar, melalui pengarusutamaan pertanyaan ketimbang pernyataan. Strategi tersebut berhasil membuat tulisan pemuda yang mengaku “terkadang halu” ini bertahan tanpa ada upaya memproblematisasi isinya.
Padahal, setelah saya baca secara seksama, ada masalah serius dari segi sejarah pada caranya mempertanyakan identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
Oleh karena itu, dengan mencoba untuk tidak reaktif seperti bocah baru puber, melalui tulisan ini saya bermaksud menjawab kegelisahan Iqbal mengenai gelar kota pahlawan untuk Surabaya, sekaligus berbagi pengetahuan kepada publik mengenai apa yang saya tahu tentang sejarah identitas tersebut.
Dasar Legitimasi Surabaya sebagai Kota Pahlawan
Inti dari opini Iqbal adalah mempertanyakan perihal legitimasi yang menjadi dasar penyematan julukan “Kota Pahlawan”. Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap landasan hukum, beserta historisnya.
Terdapat Penetapan Pemerintah Nomor 9/Um tahun 1946 tentang penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan yang bisa dijadikan dasar hukum pemberian julukan tersebut. Karena, akar dari ketetapan itu adalah puncak rentetan peristiwa yang terjadi di Surabaya pasca kemerdekaan, dimana saat itu arek-arek Surabaya berperang mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan sekutu.
Pertempuran yang diawali pada 19 September 1945 dengan perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato (sekarang Hotel Majapahit) ini menunjukkan kepada dunia keteguhan rakyat Indonesia kala itu dalam urusan mempertahankan kemerdekaan.
Ada banyak literatur yang bisa kita baca dan pelajari untuk mengetahui detil di balik meletusnya perang revolusi kemerdekaan tersebut. Saya merasa tidak perlu menjelaskan detilnya, karena saya tidak ingin berlagak jadi si paling tahu sejarah.
Lagipula, buat apa mengulang yang sudah disampaikan oleh berbagai buku sejarah, reportase media, jurnal pendidikan, atau bahkan sebuah artikel dari jurnal arsitektur? Yang ingin saya tekankan adalah bahwa sumber-sumber tersebut disampaikan berdasarkan hasil rekonstruksi sejarah terus menerus yang semakin memperkuat penyematan gelar Kota Pahlawan pada Surabaya.
Sejarah itu dinamis, maka sah-sah saja untuk dipertanyakan. Bertahun-tahun berikutnya pun, rekonstruksi sejarah tentang peristiwa 10 November 1945 oleh para sejarawan tetap berlangsung. Paling sering berupa pelurusan mengenai detil gambaran peristiwa.
Namun, kalau sudah berkaitan dengan upaya meragukan julukan Surabaya sebagai Kota Pahlawan, ini adalah wilayah yang harus ditangani dengan hati-hati. Mengingat landasan hukum dan historis untuk penjulukan tersebut, sudah semestinya gugatan juga menunjukkan adanya upaya rekonstruksi sejarah.
Ini bukanlah tempat untuk secara sembarangan membandingkan peristiwa itu dengan rupa-rupa perang kemerdekaan lain. Atau, secara subjektif mengutip perang sebelum era pergerakan nasional berikut implikasinya terhadap perjuangan nasional yang nihil pembuktian.
Baca Juga: Salah Kaprah Nasionalisme dalam Pendidikan
Perihal Pergeseran Nilai Heroisme
Ada satu hal lagi yang mengusik saya dari tulisan Mohammad Maulana Iqbal, yakni pada bagian pergeseran nilai heroisme.
Pertama, penggunaan “konon katanya” membangun persepsi bahwa landasan sejarah penamaan Kota Surabaya itu mitos belaka. Apalagi, frasa tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya pembelokan historis pada istilah “Sura ing Baya“.
Padahal dalam sejarahnya, penamaan Kota Surabaya punya landasan historis yang kuat, yang juga dapat ditelusuri dari landasan hukumnya melalui Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1956 tentang Makna Lambang Ikan dan Buaya sebagai Simbol Kota Surabaya.
Selanjutnya, menjadikan kiprah Bonek sebagai pendukung klub Persebaya Surabaya untuk menguatkan gugatan terhadap klaim kota pahlawan itu mengada-ngada. Opini Iqbal mengesankan nilai-nilai keberanian yang tersemat dalam identitas Kota Surabaya mengalami pergeseran ke arah destruktif karena “oknum” Bonek, yang menurutnya identik dengan kerusuhan.
Bagi saya, asumsi semacam itu menunjukkan pemikiran yang kontradiktif dari si penulis. Di satu sisi, ia menyadari kalau kerusuhan yang selama ini terjadi tidak merepresentasikan Bonek sebagai kesatuan identitas. Di sisi lain, ia justru menjadikan ulah “oknum” untuk menggambarkan semangat juang arek-arek Suroboyo secara keseluruhan.
Kalau memang mau menjadikan pendukung Persebaya sebagai landasan untuk menunjukkan pergeseran nilai “Berani”, harusnya Iqbal tidak begitu saja menihilkan keberanian Bonek yang konstruktif, terutama bagi perkembangan sepak bola tanah air.
Semisal, perjuangan atas dasar penolakan klub Persebaya dan Bonek terhadap manuver politik yang dilakukan oleh federasi kala itu. Atau, aksi demonstrasi di depan stasiun televisi untuk menolak kebijakan jam tayang liga sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi, yang pada akhirnya, menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), menjadi salah satu penyebab tragedi tersebut.
Perjuangan-perjuangan di atas masih menunjukkan bahwa “keberanian” arek-arek Surabaya yang direpresentasikan Bonek masih pada tempatnya, belum bergeser seperti yang disampaikan Iqbal.
Diskursus melibatkan pertukaran ide dan gagasan. Pertanyaan sering jadi pemicu dalam sebuah diskusi dan pertukaran pemikiran. Tapi, kalau pertanyaan yang diajukan itu berisi pepesan kosong, apakah itu mampu memicu diskursus sejarah yang produktif?
Jangan-jangan, ketimbang mempertanyakan klaim kepahlawanan dalam identitas Surabaya, akan lebih berarti mempertanyakan “apakah gugatan Iqbal dalam opininya tersebut layak untuk sekadar dipertimbangkan?”
Baca Juga: Kepada Guru Bahasa: Puisi itu Membosankan!