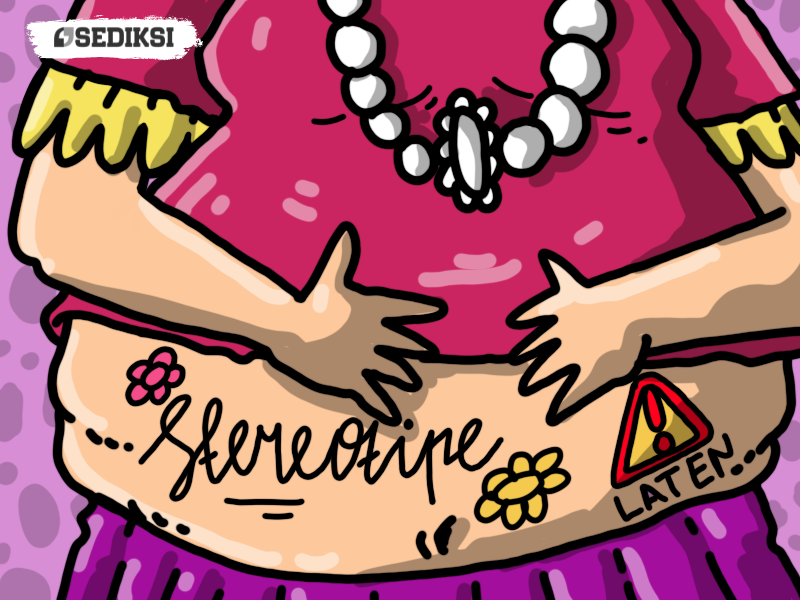Stereotipe, mau bagaimanapun bentuknya, adalah hal yang menyebalkan. Seperti yang disampaikan Helva Silvianita dalam artikel berjudul “Kenyang Makan Stereotipe Superlemot di Medan” yang dimuat Sediksi pada awal Mei lalu.
Saya sangat setuju kalau hal-hal abstrak tentang sebuah identitas kultural tak pernah cocok dijadikan landasan seperti dekret jadi-jadian untuk mendeskripsikan seseorang. Misalnya, orang bersuku Batak tak pantas disebut kasar hanya karena vokal.
Namun, dalam beberapa hal, Helva seperti ketus dan sebal atas stereotipe yang dijatuhkan kepadanya sehingga melampiaskan penyematan identitas yang aneh itu dengan cara yang tak ubahnya sama: melaksanakan stereotipe kembali.
Bahkan, Helva ingin membuat suatu identitas kultural sebuah suku dengan landasan pemikiran beberapa orang dari sebuah suku tertentu.
Misalnya seperti yang disampaikan Helva atas mamak-mamak Batak yang tak ingin menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan Jawa.
Helva menyimpulkan penolakan mamak-mamak Batak atas pernikahan beda suku dengan sebuah kalimat yang barangkali telah sering ia dengar atau terima sendiri. Tetapi, apakah dengan kalimat itu kita bisa langsung menilai suatu perkumpulan kolektif?
Baca Juga: Batak, Rantau, dan Mitos Ketidaksuburan
Segelintir Hal yang Mematahkan Stereotipe Mamak-Mamak Batak Ala Helva
Pada tulisannya, Helva sempat menyinggung terkait betapa ketatnya suku Batak dalam pemilihan pasangan. Berdasarkan pengamatannya, ia memang tidak menyamaratakan semua mamak-mamak Batak melakukan hal demikian.
Meski begitu, tetap ada yang perlu diluruskan terkait “ketat dalam pemilihan pasangan ini.” Ketat yang dimaksud Helva bukanlah semata tentang mewariskan marga.
Sebagai orang yang akan berada di masyarakat Batak hingga mati, saya melihat Helva tidak mempertimbangkan perihal historis kultural dalam melihat hal ini.
Maksudnya, sikap ngotot mamak-mamak Batak harus mendapatkan menantu orang Batak bukanlah hal sepele.
Sikap ngotot ini adalah budaya yang telah ada bahkan sebelum agama masuk ke Tanah Batak. Mengambil pasangan dari suku lain, bagi orang Batak, membuat makin panjangnya prosesi adat yang harus dilalui.
Sebab, pasangan yang tak bermarga itu wajib membeli marga terlebih dahulu. Efisiensi mengambil sesama orang Batak adalah cara yang paling aman untuk dilakukan.
Baca Juga: Agak Sulit Menjadi Laki-Laki (di) Madura
Kemudian, hal lain yang perlu dipahami dalam melihat ketatnya pemilihan pasangan ini ialah soal potensi tergerusnya pemerolehan dan pelestarian bahasa Ibu, yakni bahasa daerah. Dengan orang tua yang heterogen, pelestarian bahasa Batak akan semakin susah diturunkan.
Suka atau tidak, alasan ini mungkin terkesan memaksakan. Tetapi, coba lihat data pelestarian bahasa daerah saat ini. Disebutkan bahwa bahasa Batak menjadi salah satu yang perlu dilestarikan. Alasannya jelas: ada banyak orang Batak, tetapi penuturnya kebanyakan kalangan tua.
Lebih lanjut, mengambil pasangan yang juga harus bersuku Batak tidak melulu soal meneruskan marga. Perlu diketahui, sekalipun pasangan—dalam hal ini perempuan—bukan orang Batak, tetap saja meneruskan marga itu berjalan.
Pasalnya, orang Batak adalah masyarakat patrineal. Dari mana pun asal suku sang ibu, tetap darah ayah yang diturunkan. Artinya, pemahaman meneruskan marga itu juga merupakan kesalahan pola pikir tentang struktur kehidupan masyarakat Batak paling dasar.
Jadi, kalimat seperti, “Halah, mijak taik aja enggak penyet, kek mana pulak mau ngurus anak nanti?”, tak bisa langsung dijadikan alasan cum stereotipe jika mamak-mamak Batak tak ingin anak lelakinya menikah dengan perempuan Jawa.
Sekali lagi, Helva memang mengatakan tidak seluruh mamak-mamak Batak demikian. Akan tetapi, hanya karena mereka Batak dan mamak-mamak, kita tidak bisa begitu saja menjadikannya alasan untuk menggeneralisasi pemikiran suatu suku.
Mungkin mamak-mamak yang kebetulan bersuku Batak itu memang julid. Tetapi, bukan berarti itu alasan yang tepat untuk akhirnya menyimpulkan keengganan mamak-mamak Batak menikahkan anak lelakinya dengan perempuan Jawa.
Selanjutnya, Helva juga perlu menyadari kalau keharusan lelaki Batak menikahi perempuan Batak itu sebenarnya omong kosong belaka. Ini mungkin terdengar jarang ditemukan, tetapi di beberapa kasus, ada banyak lelaki Batak yang menikah dengan perempuan bersuku lain.
Sejumlah teman saya melakukannya, meski memang hal tersebut sangatlah sulit dilakukan. Terlebih ketika menikahi perempuan tak bersuku Batak dan tak membeli marga akan membuat anak nantinya sulit menikah.
Sebab, anak dengan latar belakang orang tua yang belum menikah secara adat akan dianggap hina, dan sang anak nantinya diharuskan membuat pesta adat untuk dirinya dan orang tuanya.
Hal melelahkan semacam itu memang bisa saja tidak dilakukan oleh sang anak. Namun, tidak dianggap dalam sebuah komunitas suku akan menjadi bola api yang harus siap dihadapi.
Selain itu, kehilangan identitas kesukuan juga berpotensi mendatangkan kepunahan sebuah suku. Kalau soal ini memang jauh, sih. Tapi, kan, siapa yang tahu?
Bahaya Kenyang Makan Stereotipe
Hal semacam keresahan Helva atas mamak-mamak Batak itu sejujurnya pernah saya rasakan. Pada tahun 2022, saya mendapatkan magang Kemensos di Nias Utara.
Kedatangan saya saat itu tidak tepat. Sebab, beberapa bulan sebelumnya ada kasus seseorang yang bermarga sama dengan saya menghina suku Nias.
Alhasil, ketika saya memperkenalkan diri, muncul stereotipe: kamu saudaranya dia (si penghina suku Nias). Mereka bahkan mengganti nama saya dengan nama si penghina itu, serta tertawa ketika mendengar marga saya.
Momen bajingan itu saya dapatkan bukan hanya dari mamak-mamak belaka. Bapak-bapak dan anak-anak muda juga demikian.
Di sini, bukan hanya mamak-mamak yang berprofesi sebagai Pekerja Rumah Tangga, mamak-mamak yang merupakan pejabat pemerintahan, seperti di kantor camat hingga kantor dinas setempat, juga melakukan hal yang sama.
Baca Juga: Kebaya: Bentuk Rasis yang Diperhalus
Tetapi kemudian, apakah pantas jika suku yang meledek saya habis-habisan itu saya sebut rasis? Tentu tidak.
Pemikiran segelintir orang yang kebetulan bersuku yang sama tak bisa menjadi alat mutlak untuk membuat identitas baru terhadap suku itu.
Alasannya, kadang kala sebuah pemikiran bisa diyakini banyak individu, tetapi alasan itu tak mendorong keyakinan berpikir kolektif bisa disamaratakan.
Nah, terakhir, ngomong-ngomong soal “kenyang”, banyak riset kesehatan yang menyebutkan untuk tidak makan hingga “kenyang”, terlebih lagi hingga kekenyangan. Tak hanya secara ilmiah, menurut teologi juga demikian.
Bahkan ada sebuah candaan di Medan yang berhubungan dengan kenyang. Orang-orang Medan selalu mengatakan begini: “tebodoh kalo dah kenyang ko kan.” Artinya, “jadi bodoh kau kalau sudah kenyang.”
Begitulah. Semoga kita nggak sering-sering kenyang.