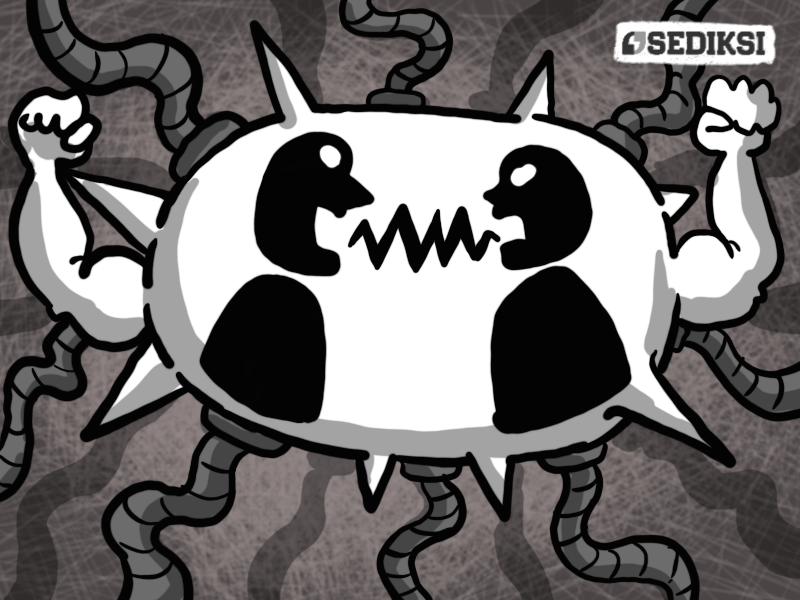Debat ihwal kekayaan Bahasa Indonesia kembali memanas untuk kesekian kali. Teranyar, seorang kreator konten bernama Indah G menyebut Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang miskin.
Ia merujuk pada kosakata Bahasa Indonesia yang katanya berjumlah jauh lebih sedikit ketimbang bahasa lain di dunia, semisal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Perbandingan yang keliru, tentu.
Pernyataan ini memang cuma memberi contoh kecil perihal penutur Bahasa Indonesia yang tidak cakap. Lebih banyak atau lebih sedikit adalah satu hal. Sedangkan lebih kaya atau lebih miskin adalah hal lain.
Ruang publik sendiri sudah sering diwarnai oleh wacana tentang kekayaan Bahasa Indonesia. Misalnya, kita sering mendengar ajakan untuk mencari dan menggunakan padanan bagi istilah-istilah asing.
Memang sah-sah saja (bahkan pada titik tertentu, perlu!) memasifkan penggunaan padanan itu. Apalagi guna menyangkal pernyataan kalau Bahasa Indonesia itu miskin hanya karena kosakatanya lebih sedikit dibanding bahasa lainnya di dunia ini.
Semisal kita menjumpai sebuah istilah asing yang belum punya padanan sekalipun, saat itu pula kita bisa buatkan padanannya. Selesai perkara.
Akan tetapi, persoalan kekayaan bahasa bukan cuma itu, dan hal inilah yang saya hendak uraikan dalam tulisan ini.
Pemahaman kita tentang apa yang kita sebut sebagai kekayaan itu faktanya acapkali terlalu sempit. Terjebak dalam perspektif biner: hitam dan putih, alih-alih memandang bahasa sebagai medan penuh kemungkinan.
Narasi yang muncul selama ini sebatas:
“Siapa bilang Bahasa Indonesia miskin? Kita punya ‘daring’ untuk menggantikan online, ‘luring’ untuk offline, ‘pendengung’ untuk buzzer, dan seterusnya.”
“Bahasa Inggris cuma punya rice untuk segala bentuk beras, sedangkan kita punya padi, beras, nasi, dan seterusnya.”
Lantas, kenapa? Gagah-gagahan yang sungguh mubazir!
Padanan: Pengayaan dan Pemiskinan
Benar belaka bahwa Bahasa Indonesia punya banyak kosakata hanya untuk tanaman bernama latin oriza sativa. Tapi, di luar sana, orang punya teknologi mutakhir untuk mengembangkannya.
Lalu, terciptalah, misalnya, padi hybrid yang kualitasnya di atas rata-rata. Kemudian kita menyebutnya dengan bahasa kita sendiri: padi hasil kawin silang. Atau, kita langsung menyerap istilah asingnya menjadi padi hibrida.
Dari contoh di atas, kita bisa melihat bagaimana Bahasa Indonesia berkembang. Tampak jelas bagaimana perkembangan itu berkelindan dengan pengembangan teknologi yang tak ada sangkut pautnya dengan Bahasa Indonesia itu sendiri.
Contoh lainnya, dalam kajian hukum kiwari, ada yang namanya abusive constitutionalism, yakni siasat rezim picik untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang (tampak) konstitusional.
Istilah ini kemudian oleh para pemikir hukum kita ditemukan padanannya menjadi konstitusionalisme yang melecehkan, atau sebagainya.
Lagi-lagi kita menyaksikan bagaimana Bahasa Indonesia berkembang. Akademisi mungkin tak kepikiran dengan istilah itu. Tapi, setelah pemikir luar (maksudnya, yang bukan penutur Bahasa Indonesia) memperkenalkan istilah itu, Bahasa Indonesia turut berkembang karenanya.
Kembali ke soal kekayaan bahasa, dari contoh di atas, kita mungkin bisa lekas mengambil kesimpulan bahwa Bahasa Indonesia itu kaya karena kita selalu bisa menerjemahkan bahasa asing.
Namun, penerjemahan itu sendiri terjadi karena adanya perkembangan yang berlangsung di luar konteks Bahasa Indonesia itu sendiri. Sederhananya, Bahasa Indonesia tidak kaya dengan sendirinya, melainkan diperkaya oleh adanya gerak interaksi di dalam maupun di luar konteks Bahasa Indonesia.
Sayangnya, kita kerap hanya berfokus pada kekayaan, alih-alih memberi perhatian pada proses pengayaan. Tak mengherankan karena, sejauh pengamatan saya pada debat perihal kekayaan Bahasa Indonesia, rumusan masalahnya seringkali dilingkupi oleh sentimen. Entah itu sentimen nasionalisme, sentimen kewilayahan, sentimen kelas, dan seterusnya.
Orang yang berbicara dengan Bahasa Indonesia seutuhnya tampak lebih nasionalis ketimbang mereka yang bertutur dengan Bahasa Indonesia bercampur bahasa asing.
Kelompok yang bicara dalam bahasa bercampur-campur itu dilekatkan dengan borjuasi perkotaan. Orang kabupaten yang memakai dialek kota kena ejek kawan-kawan tongkrongannya, dan seterusnya.
Kenyataan sentimen ini, saya pikir, akan menyulitkan kita dalam membicarakan secara objektif perihal kekayaan serta pengayaan Bahasa Indonesia.
Baca Juga: Anomali Bahasa dan Hiperkoreksi Orang Sunda
Kegetolan mencari padanan, di satu sisi, bisa memicu pengayaan. Tapi, di sisi lain, hal ini juga bisa berdampak pada pemiskinan Bahasa Indonesia.
Ada bidang-bidang yang kita pahami bukan dengan istilah yang tumbuh dalam Bahasa Indonesia. Mempertahankan penggunaan istilah aslinya dalam bahasa asing bukan berarti mengamini bahwa Bahasa Indonesia miskin, melainkan untuk menjaga garis perkembangan pemikiran yang melahirkan istilah-istilah tersebut.
Sebaliknya, memaksakan padanan justru berpotensi memiskinkan, lagi mendistorsi pemahaman tentang hal-hal yang spesifik.
Sebagai contoh, seorang duta bahasa mungkin akan getol menyebut microphone sebagai pelantang suara. Sebuah penggunaan bahasa yang kaya bukan? Memilih menggunakan istilah semacam itu barangkali membuat Anda kelihatan “si paling Indonesia”.
Namun, pada saat bersamaan, juga bisa terdengar menggelikan. Pasalnya, microphone adalah perangkat teknologi yang spesifik, sementara yang bisa melantangkan suara bukan cuma microphone.
Oleh karena itu, tidak hanya dari padanan, kekayaan sebuah bahasa seharusnya bisa juga dilihat dari daya adaptifnya: penyerapan istilah, kombinasi, dan sebagainya.
Baca Juga: Apalah Arti Sebuah Nama Aplikasi Pemerintah?
Perihal Penggunaan yang Miskin
Ada pula anggapan bahwa yang miskin itu bukan bahasanya, melainkan penggunaan ragam kosakatanya. Hal ini bisa benar, bisa problematis.
Benar karena pada titik tertentu kita memang kurang mengeksplorasi. Problematis karena: apakah kita memang mesti menggunakannya? Atau, kapan dan di mana kita menggunakan kosakata itu?
Kemiskinan penggunaan bahasa pun dimaknai sebagai keengganan, kemalasan, atau bahkan ketidaktahuan untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, lagi-lagi, hal inipun tidak sepenuhnya kemiskinan.
Sebab, sebagai ganti dari tidak digunakannya Bahasa Indonesia (yang sudah mapan) secara optimal, barangkali orang-orang mengoptimalkan bahasa daerah, bahasa asing, dan ragam istilah yang lahir sebagai akibat dari proses kebudayaan.
Baca Juga: Uneg-uneg Guru Bahasa Jawa
Selanjutnya, terkait kemiskinan penggunaan bahasa ini, kita juga bisa mengambil lirik lagu-lagu folk indie Indonesia sebagai contoh. Betapa kayanya kosakata yang diramu dalam bait-bait lirik itu.
Bahkan, acapkali dari lirik lagu-lagu itulah kita pertama kali mengetahui ragam kosakata dalam Bahasa Indonesia. Bukan cuma kaya, ragam kosakata yang terdengar baru itu pula berimplikasi pada anggapan kita mengenai kata-kata yang indah, puitis, sastrawi, dan sebagainya.
Lalu, kenapa kita menyebutnya puitis? Apakah karena jarang kita dengar? Ataukah karena digunakan sebagai lirik lagu?
Dari sini, tampak bahwa klaim kemiskinan penggunaan bahasa bisa sangat relatif, dan subjektif. Kecenderungan seorang sastrawan untuk mengeksplorasi bahasa tentu berbeda dengan kecenderungan seorang akademikus, misalnya.
Demikianlah, dari beberapa contoh yang diutarakan di atas sedikit-banyak menunjukkan bahwa betapa mubazirnya ribut-ribut soal kekayaan bahasa yang selama ini berlangsung di ruang publik kita.
Pasalnya, kekayaan bahasa bukan semata persoalan jumlah kosakata, istilah-istilah puitis, dan sebagainya. Kekayaan bahasa adalah ketakterhinggaan kemungkinan dalam bahasa itu sendiri.
Baca Juga: Ke Mana Perginya Para Bapak?