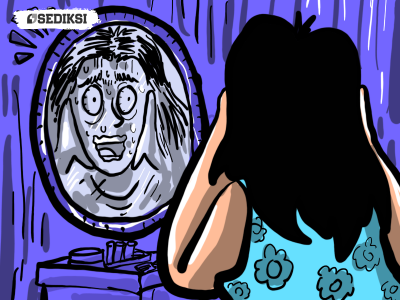Saya merasa bahwa ada keadaan di mana permintaan maaf jadi begitu menyebalkan. Hal ini saya sadari ketika akhirnya tahu bahwa meminta maaf dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan.
Ini disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang merasa berkuasa, sehingga bisa memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungannya sendiri. Sebagai contoh, ada seseorang yang sengaja meminta maaf tanpa benar-benar menyesal atau mengakui kesalahannya, hanya demi membuat dirinya merasa lebih baik dan lega.
Saya menjadi semakin sebal waktu tahu ada sebuah eksperimen yang membuktikan bahwa ternyata, meminta maaf lebih efektif daripada kompensasi finansial.
Pada tahun 2009, University of Nottingham melakukan penelitian yang membandingkan efektivitas permintaan maaf dan pemberian uang tunai bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan pengampunan dari pelanggan yang merasa kecewa
Hasilnya menunjukkan bahwa 45% pelanggan bersedia memaafkan dan melakukan transaksi lagi setelah diberikan permintaan maaf, sementara hanya 25% pelanggan yang mau melakukan bisnis setelah diberikan uang tunai sebagai bentuk kompensasi kesalahan perusahaan.
Penjelasannya sederhana. Secara psikologi, mengucapkan “maaf” merupakan hal mudah untuk dilakukan, sekaligus sulit diatasi secara rasional. Bagi sebagian pelanggan, meminta maaf adalah upaya mengakui kesalahan, mengungkapkan rasa malu, serta tanggung jawab secara bersamaan.
Penelitian tersebut merupakan kabar gembira bagi para pelaku bisnis. Mengutamakan solusi termurah dan termudah sudah menjadi ‘watak’ umum sebuah bisnis. Maka, perlukah mengeluarkan kompensasi berupa uang tunai kepada para pelanggan jika permintaan maaf terbukti lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan?
Namun hal ini bukan kabar baik bagi saya. Setelah mengalami momen hangat saat bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri selama puluhan tahun, saya jadi sangsi terhadap permohonan maaf yang pernah atau baru saja saya terima beberapa hari yang lalu.
Meminta maaf itu, sudah mudah, murah pula. Siapa saja bisa melakukannya, apalagi jika didukung tradisi bermaaf-maafan yang katanya bisa membuat manusia kembali fitrah. Barang murah, mudah didapat, namun kualitasnya belum tentu menjanjikan. Hanya karena satu atau dua permintaan maaf, rasa sakit dari masalah yang lalu tentu tidak akan selesai begitu saja.
Antara Meminta Pengampunan dan Pengakuan Terhadap Penyesalan
Permintaan maaf itu sangat sakral bagi penganut ajaran Yunani Kuno. The Apology karya Plato menyebut bahwa permintaan maaf bisa saja menjadi justice morality, pembelaan, dan bahkan pengampunan.
“Maaf” dari karya tersebut dibahasakan dengan Apology, bukan Sorry. Kedua istilah tersebut pada zamannya memiliki makna yang berbeda. Apology berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang dikatakan atau ditulis untuk membela atau membenarkan apa yang bagi orang lain dianggap salah atau apa yang mungkin dapat ditolak.
Maka The Apology karya Plato adalah sebuah catatan tentang pembelaan diri yang disampaikan dalam persidangan Socrates, bukan penjelasan tentang bagaimana filsuf tersebut mengakui kesalahannya. Nyatanya, sebelum abad ke-16, Apologi selalu merujuk pada pembelaan atau pembenaran.
“Sorry”, memiliki makna yang mengungkapkan rasa penyesalan. Keduanya berbeda, hingga di abad ke-16 William Shakespeare menjadi tersangka utama yang berhasil meleburkan makna kedua kata tersebut menjadi seperti yang saat ini kita ketahui.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna Apology dan Sorry menjadi satu dalam kata “maaf”. Maaf bisa bermakna sebagai upaya pembelaan dan pengampunan, namun juga dapat digunakan sebagai ekspresi untuk mengungkapkan penyesalan. Namun, dari apa yang telah saya lalui, maaf lebih sering terdengar sebagai ungkapan penyesalan.
Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad (SAW) menganjurkan pengikutnya untuk memberi pengampunan dan meminta pengampunan kepada orang lain sebelum kematiannya agar tidak ada Dinar atau Dihram di kehidupan setelah mati.
Muslim didorong untuk meminta maaf kepada siapa pun yang mungkin telah mereka salahkan, dan mencoba untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ini bisa melibatkan memberikan ganti rugi, menawarkan permintaan maaf yang tulus, atau sekadar menghubungi seseorang untuk menunjukkan bahwa Anda peduli.
Namun, meskipun negara Indonesia mayoritasnya muslim, sebagian dari kita bahkan tidak benar-benar mengerti kata maaf itu sendiri. Hasil ini saya dapatkan setelah berupaya menjawab rasa penasaran lewat Forum Quora, dimana menunjukkan bahwa Indonesia, bersama Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak benar-benar mengerti makna minta maaf.
Hasil tersebut sedikit lebih baik daripada Amerika yang sama sekali tidak mengenalnya. Namun, lebih buruk dibanding India yang justru karena sangat memahami maknanya, jadi jarang meminta maaf. Di sana, permintaan maaf atas kesalahan-kesalahan kecil lebih sering ditunjukkan oleh mimik wajah yang menunjukkan perasaan menyesal.
Tawaran Untuk Berhenti Meminta Maaf
Sejak kecil, kita selalu dididik untuk mengucapkan “maaf”—selain “tolong” dan “terima kasih”, demi memenuhi standar kesopanan budaya ketimuran. Hingga saking terbiasanya, kita jadi sering menyepelekan subtansi dari apa yang kita sebutkan.
Tapi saya menduga banyak dari pembaca Sediksi adalah orang dewasa yang mulai merasakan jenuh tradisi maaf-memaafkan. Bukan karena membosankan, melainkan karena mulai tersadar bahwa semua kesalahan kita maupun kesalahan orang lain terhadap kita tidak bisa termaafkan melalui momen tersebut.
Ingatlah bahwa “maaf” sudah menjadi “barang murah” yang kehilangan maknanya. Untuk itu, melalui tulisan ini saya tawarkan kepada pembaca untuk berhenti meminta maaf atau memberi maaf, jika sekadar formalitas.
Dengan begitu, kita tidak perlu bergantung pada keputusan orang lain. Selain itu, kita juga tidak perlu dipusingkan oleh pertanyaan-pertanyaan seperti, “Hmmm, apakah permintaan maaf itu diucapkan dengan tulus, ataukah diucapkan oleh orang yang ahli dalam meminta maaf?” atau “Siapa yang salah dan perlu minta maaf?”
Jika kita ambil keputusan tersebut, maka perlu kerelaan untuk melepaskan banyak hal yang telah diajarkan. Kemungkinan keputusan itu melibatkan syok, rasa sakit, dan kebingungan. Itu normal, karena yang paling penting kita dapat memberikan batasan pada beberapa ucapan yang berhak untuk disampaikan oleh orang lain maupun tidak.
Sekalipun saat ini kita belum bisa berhenti meminta maaf, itu tidak masalah. Namun, kita harus tetap ingat bahwa ada pihak yang sangat tidak tahu diri untuk meminta maaf? Ya, Negara. #dontstoptalkingsboutkanjuruhan #usuttuntastragedikanjuruhan
Baca Juga: Merayakan Hal-hal yang Tak Mudah