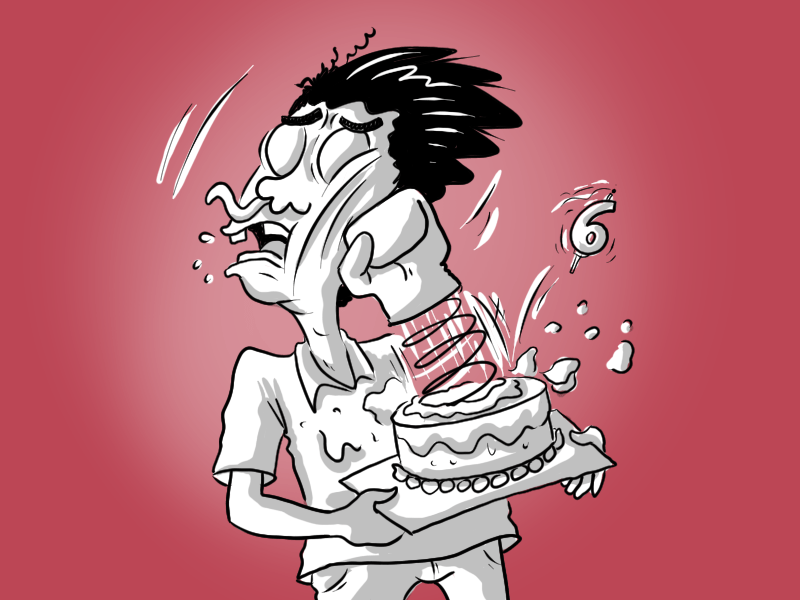Kalau saya perhatikan, rentang usia 20-30 tahun rupa-rupanya memang absurd dan nano-nano. Ada teman saya yang sudah punya karir mapan, atau berkeluarga, beranak, dan merayakan sudah punya rumah.
Di sisi lain, ada yang ngga kelar-kelar kuliah dan makan nasi kecap tiap akhir bulan, bahkan ada juga yang kalau mau keluar malam masih minta izin ortunya. Sepertinya, Tuhan memang sedang bermain dadu.
Di usia macam ini, hidup mencekoki saya bermacam-macam pelajaran. Salah satunya adalah soal kegagalan. Gagal jalan sama gebetan, gagal melamar pekerjaan, gagal dapat beasiswa, atau gagal untuk maju sidang skripsi. Rasanya tidak nyaman dan tentu saja bikin kesal.
Kalau dipikir-pikir lagi, yang membikin kesal sejatinya adalah perasaan seolah-olah diri atau ego kita ikut terlibat dalam kegagalan. Itu berdampak pada munculnya anggapan bahwa ketika usahamu gagal, maka keseluruhan dirimu juga ikut gagal, kamu tidak cukup baik, maupun kamu tidak cukup mampu.
Hal-hal macam itu bukan hanya berisiko membuat perasaan kita terluka, tetapi juga harga diri kita. Meskpiun sebenarnya ngga gitu, kan ya. Yah, seenggaknya kita belum gagal sebagai manusia, sebab masih ada peluang selama masih mau berusaha.
Saya yakin, sebenarnya kita semua tahu bahwa momen goblok, lowest point of life, kejatuhan, dan kegagalan adalah keniscayaan dalam hidup. Enggak bisa di-skip.
Seringnya, kita udah meluangkan waktu, tenaga, duit, tetapi malah berujung gagal. Cuma dapet hikmah doang.
Saya tahu ini tulisan agak klise, soalnya kalau dibaca awak redaksi sediksi, pasti bakal dikomenin, “halah, kene ki wis kakean hikmah, lur.” Tapi setidaknya harus ada yang ngomongin dan nepuk pundakmu kalau semua kegagalan itu hanyalah salah satu ruang tunggu sebelum beringsut menuju kegagalan lainnya.
Yah, meskipun harus ada banyak ruang tunggu yang harus dilalui kaya sistem birokrasi yang panjang dan ribet di negeri ini.
Ruang tunggu itu, kalau dalam fotografi ibarat ‘liminal space’, yang mengabadikan objek berupa ruang kosong. Tidak sembarang ruang kosong, namun tempat yang sebenarnya familiar. Semisal mall di malam hari yang lengang, lorong yang redup dan sepi, atau ruang tunggu tanpa orang di dalamnya.
Ruang macam itu berpeluang membuat perasaan tidak nyaman karena tidak biasa dan janggal. Ibarat ruang tunggu tadi, konsep liminal ini memberi impresi tidak nyaman dan perasaan ingin segera beranjak.




Alasannya, setidaknya ada 4. Pertama, impresi yang membuat seakan-akan kita terjebak dan tidak mampu keluar dari tempat itu. Hal ini akan memantik respon panik, perasaan sempit, terbatas, dan tidak bebas.
Kedua, suasana yang suram, gelap, dan malam hari yang membuat kita merasa tidak aman dan terancam. Ketiga, adanya sumber cahaya yang terasa kurang, remang, atau tidak alami yang membuat cemas dan asing.
Empat, tidak adanya tanda-tanda kehadiran makhluk hidup di dalam atau di sekitar objek, bahkan walaupun itu sekedar siluet atau bayangan makhluk hidup.
Keadaan demikian membuat kita merasa ditinggal sendirian dan terasing. Dari semua itu, ada perasaan bahwa tempat yang kita pikir kita kenal, ternyata menjadi asing dan kosong. Sehingga muncul ketidaktahuan dan membuat kita merasa takut dan ingin cepat-cepat pergi.
Konsep liminal ini banyak diaplikasikan ke dalam karya film maupun game. Terutama genre horor dan misteri. Misalnya dalam film “The Shining” atau dalam game-game besutan Chilla’s art.
Dalam konteks ini, serupa dengan fase tadi, liminal juga dapat dimaknai sebagai fase di mana kita tidak dimaksudkan untuk menetap. Atau ruang peralihan sementara sebelum memasuki fase selanjutnya.
Misal dalam konteks waktu, bisa juga dimaknai sebagai fase sehabis putus dan belum move on atau fase nganggur selepas resign dan hendak mencari kerja. Karena itu, wajar saja jika perasaan tidak nyaman, gagal, dan serba terbatas tidak terhindarkan.
Berada di dalam fase peralihan memang tidak nyaman. Namun ada baiknya sambil membunuh waktu kita menikmati melakukan hal-hal kecil atau sekadar melakukan refleksi sambil menerima kegagalan dan kegoblokan di masa lalu.
Dalam hal ini, mari menertawakan dan merayakan kegagalan ataupun kita sendiri. Memangnya cuma keberhasilan dan pencapaian saja yang patut dirayakan?
Di Meksiko, ada yang namanya “Dia de Los Muertos,”, festival tahunan yang digelar untuk mengenang orang-orang mati. Keluarga, kerabat maupun kolega memajang foto, pergi ke pemakaman, kemudian makan-makan untuk mengenang mereka yang telah tiada.
Acaranya meriah betul. Kesedihan akibat kehilangan orang-orang yang disayang tak melulu disikapi dengan meratap-ratap. Itu satu dari sekian contoh kalau memang kesedihan bisa dirayakan. Kenapa tidak?
Menerima perasaan bahwa usahamu gagal adalah soal upaya melepaskan ego dengan tindak-tandukmu untuk kemudian melangkah ke fase selanjutnya. Orang Jawa bilang, “nrimo.” Kalau gagal lagi? Ya, bangkit lagi. Begitu terus sampai Tuhan iba.
Bicara soal penerimaan, saya selalu salut dengan perayaan ulang tahun. Rasa-rasanya, ulang tahun adalah satu-satunya perayaan di mana kamu disyukuri, diterima, dan dirayakan hanya karena kamu lahir dan ada. Udah, titik.
Tidak seperti perayaan naik jabatan, peringatan pernikahan, atau selametan beli rumah baru. Tidak perlu ada pencapaian apa-apa, kamu diterima sebagaimana kamu adanya. Lagipula, perayaan ulang tahun adalah kesempatan untuk orang-orang terdekatmu untuk mengekspresikan betapa mereka mensyukuri eksistensimu.
Menjelang ulang tahun ke-6, Sediksi ngga bisa mengadakan lomba seperti tahun-tahun sebelumnya. Merayakan kondisi serba kekurangan, merayakan lagi ngga ada duit, atau merayakan kegagalan diri sendiri, juga sebenarnya tidak buruk-buruk amat.
Bagi beberapa orang yang saya temui di Sediksi, Sediksi adalah ruang singgah, tempat eksperimen, ruang sambat, tempat mbribik, atau bahkan ruang untuk mengaktualisasi diri tanpa perlu banyak duit. Kenyataan bahwa tulisanmu bisa diterima di sediksi, sebenarnya sudah cukup untuk merayakan betapa kamu sebenarnya ‘ada’.
Lagipula, memangnya salah kalau kita hidup apa adanya, tanpa berorientasi pada manfaat?
Maksud saya, menjalani hidup sebagai orang bermanfaat tentu sangat baik. Namun kadang, seringkali secara tidak sadar kita terlalu menuntut diri untuk menjadi “bermanfaat” dan melupakan kenikmatan-kenikmatan kecil, lalu lupa menerima diri apa adanya.
Sebagaimana kata pepatah ‘don’t measure other people’s shoe with our feet’ (jangan pernah mengukur kaki kita di sepatu orang lain), juga berlaku sebaliknya. Selain karena ‘menjadi pribadi yang bermanfaat’ itu susah, karena tolok ukurnya macam-macam.
Kita memang tidak bisa memaksakan nasib baik tiap saat. Singkatnya, life isn’t supposed to be easy. Tetapi ingat, sulit bukan berarti tidak mungkin.
Akhir kata, selamat ulang tahun Sediksi.