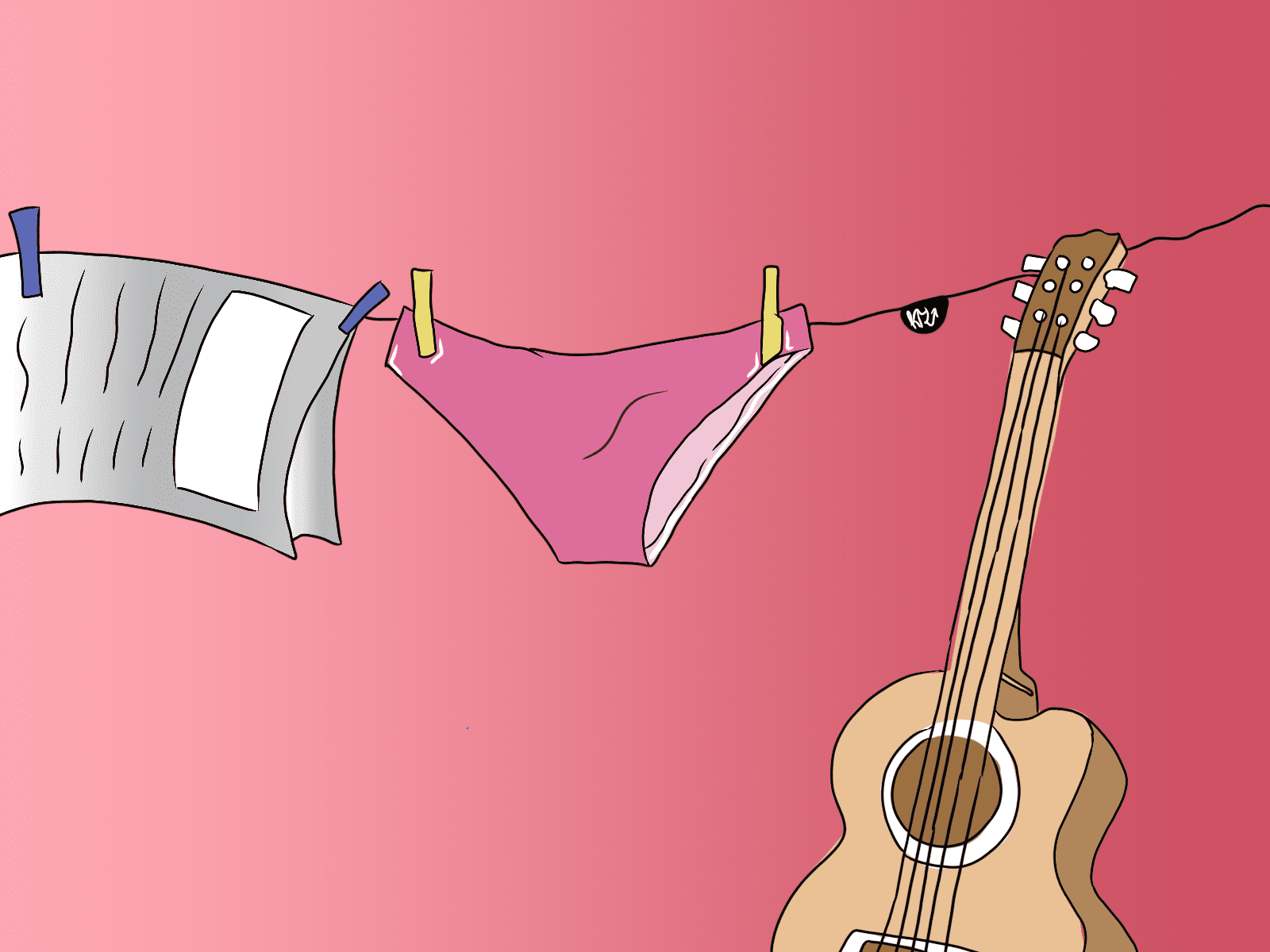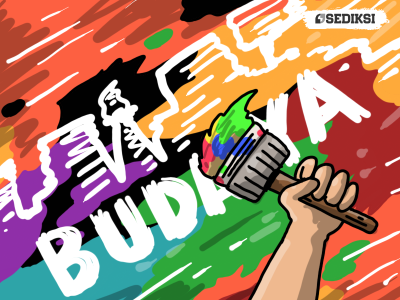Sebagai seorang awak media (yang masih hiatus beberapa saat) sekaligus penikmat musik yang baik, saya cukup mengeluhkan bagaimana kontribusi jurnalisme dalam dunia musik. Terutama beberapa tahun belakangan. Jurnalisme Musik
Saya kesal ketika banyak media hanya menayangkan berita musik yang, yaaa, begitu-begitu saja. Berita yang diangkat kebanyakan berisi chord, playlist, album terbaru, dan tentu saja skandal musisi atau seniman.
Iya, saya mengerti. Berbagai media di arus yang serba cepat ini sedang berebut tren. Ibarat kata sekelompok ayam yang berlomba-lomba memperebutkan jagung bakar. Saat jagung bakar habis, mau tidak mau ya mengais sisa-sisa jagung yang masih menempel di bonggolnya.
Kekesalan ini bertambah ketika tren tersebut justru menghilangkan mata pena dari jurnalisme itu tersendiri. Tidak ada penggalian fakta yang mengakar dan mampu menyalakan gagasan kritis dari masyarakat.
Saya berani bertaruh bahwa tren yang sedang merayap di tengah linimasa sosial media, dunia maya, dan paru – paru Google semuanya adalah wabah yang tidak pernah habis. Dalam dunia musik, kita dapati banyaknya sub-genre baru yang tidak tahu siapa orang tuanya. Alias, tidak tahu asal muasalnya.
Penyematan genre dalam musik tentu saja bukan sekadar pemanis. Genre berperan penting dalam musik. Sangat penting. Genre adalah suatu bentuk tutur musik yang diiyakan bersama sehingga menjadi pakem tertentu, meski tidak memiliki batas yang jelas. Kesalahan memahami genre, tentu saja kesalahan memahami pattern tutur musik tersebut.
Saya setuju parah dengan pendapat Taufiq Rahman, Penulis Pop Kosong Berbunyi Nyaring sekaligus Deputy Editor in Chief The Jakarta Post. Dirinya mengatakan bahwa musik seharusnya lebih dari sekadar hiburan.
Musik, mau tidak mau, memiliki cukup kekuatan untuk menggambarkan kondisi masyarakat pada masanya. Taufiq mengangkat contoh lagu Interpol berjudul Turn On The Bright Lights yang mampu membeberkan suasana teror dan ketakutan paska teror 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Mengintip isi Celana Dalam Jurnalisme Musik di Indonesia
Saya pribadi lebih suka memberikan gambaran nyinyiran mahasiswa dikemas dalam Peradaban oleh .Feast yang kadangkala dicap sebagai lagu demo paling keras bagi kalangan aktivis daun hijau.
Saya pikir, baik musik atau lagu, seharusnya mendapatkan tempat yang sama seperti ketika jurnalis mengupas habis ulah Kekeyi. Sama gemuruhnya saat memberitakan pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Saya pikir, kekayaan pengetahuan perihal musik dan lagu lebih pantas digoreng berkali-kali dibandingkan berita pencalonan Giring Nidji sebagai calon presiden 2024.
Oh, ya, saya mengerti benar. Usai saya kirimkan tulisan ini, maka para awak redaksi akan memberikan pendapat betapa naifnya penulis opini ini dengan alis mengangkat. Atau, seorang pimpinan redaksi yang barangkali pernah menjadi anak band tutup mata usai melihat tulisan ini.
Tapi mari kita bandingkan, dan mengukur kenaifan saya. Salah satu tonggak penting kemunculan musik di Indonesia digagas oleh seorang pecinta musik jaz, Harry Lim. Atas kecintaannya itulah dia menerbitkan Swing, majalah musik yang diprakasi oleh jaz Batavia Rhythm Club pada 1940 di Jakarta.
Di lain ujung, tepatnya di Malang, lahirlah Caecillia yang mulai beredar bulan Oktober 1941, diterbitkan oleh Asosiasi Kesenian HIndia Belanda. Usai Indonesia mencapai kata merdeka, perkembangan media masih terhalang akibat susahnya mendapatkan kertas. Namun, radio dan film Barat menggantikan peran hausnya masyarakat soal pengetahuan musik, yang kebanyakan datang dari Amerika.
Mari kita cermati. Masifnya raksasa pengaruh Amerika, terutama sihir Rock n Roll dan RnB yang memakan anak muda pada tahun 1956 itu melahirkan kecemasan para kritikus musik.
Andjar Asmara, dengan cermat pun mengkritik wabah tersebut. Termasuk, soal musik yang ditulisnya dalam artikel “Muziek dalam Film Indonesia” pada tahun 1940. Sementara Amir Pasaribu, menyampaikan kritknya melalui berbagai majalah, soal keterpurukan musik tradisional.
Baca Juga: 4 Faktor Penyebab Bisnis Studio Musik Gulung Tikar
Saya mencermati bahwa pada era itu, berbagai opini tersebut mendapatkan tempat yang sama dengan ulasan tren gaya hidup hippie yang sedang menjamur. Ah, tapi saya masih akan mendapati soal keraguan dari cara ulasan seperti ini.
Pasalnya, memang pada masa itu musik belum jadi batu loncatan artis buat dapat engagement. Dan, pada masa itu, masyarakat masih disibukkan dengan isu ideologi yang masif, belum lagi panasnya situasi politik. Sehingga, musik menjadi pelarian paling afdal. Sudah barang tentu opini saya bisa dipatahkan dengan perbedanyaan kondisi sosial yang begitu jauh.
Namun, mari kita menengok Diskoria dan Aktuil. Majalah yang paling millenial pada masa itu. Namun, dari banyaknya media yang bercokol usai kemerdekaan, Aktuil merupakan pemegang peran yang besar.
Aktuil punya kekuatan penyajian gaya hidup yang mampu langsung menciptakan tren (bukan mengikuti). Barangkali bukan karena Denny Sabri yang dianggap nabi, karena bisa tinggal di Eropa dan mengikuti berbagai perkembangan band Barat secara langsung.
Saya menganggap, Aktuil hanya sedang hoki. Selain karena masyarakat yang begitu antusias, terutama anak muda, namun juga karena longgarnya Orde Baru terhadap masuknya budaya Barat.
Kendati demikian, risiko Aktuil dalam menciptakan tren ini juga tetap dinyinyiri oleh sebagian kaum. Ya, pada masa itu rock dianggap dewa dari semua musik, dan semakin menenggelamkan musik Melayu. Bahkan, dikarenakan Aktuil mampu menyeimbangkan kontennya dengan baik (tidak selabil Diskoria yang kehabisan uang lantas menjual halamannya untuk konten politik secara mentah), dan memiliki opini yang kuat mengulas musik, majalah itu mampu merombak pola pikir masyarakat terhadap musik.
Contohnya saja istilah dangdut, lahir dari rahim Aktuil. Tepatnya dari tangan Billy Silabumi, redaktur Aktuil. (Saya sering membayangkan bagaimana jadinya jika Aktuil mengulas salah satu artis yang baru bisa menggoreng telur dadar).
Baca Juga: 5 Lagu Dangdut Asep Irama, Bapak Melankoli Indonesia pada Zamannya
Di luar sisi positif dan negatifnya, saya barangkali cukup memahami bahwa jurnalisme di Indonesia terus berkembang di berbagai era. Perkembangan jurnalisme musik di Indonesia tentunya belum seberapa dari yang saya kutipkan. Di balik musik yang terus berkembang inilah (entah semakin baik atau buruk), saya yakin, bahwa jurnalisme di Indonesia mampu mengemas musik secara lebih cerdas. Tidak justru hanya menyajikan nyinyiran warganet Twitter yang dicomot mentah – mentah.