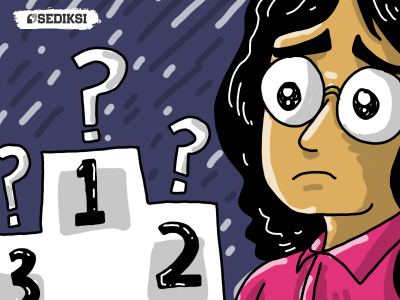Punya nggak temen yang asalnya dari Minangkabau? Atau seenggaknya mengenal seorang anak dari perantau Minang?
Kalau pernah, biar kutebak! Pasti dia laki-laki.
Tebakan saya ini tidak mengada-ada.
Ini dikarenakan garis matrilineal yang dianut oleh Suku Minangkabau. Kedudukan laki-laki tidak lebih dari abu di ateh tungku atau abu di atas tungku, yang berarti tidak memiliki pegangan kuat, ditiup atau digoyang sedikit ia akan terbang).
Hal itulah yang mendorong laki-laki Minang untuk merantau. Walaupun ada beberapa sektor lain yang bisa digarap sebagai sumber penghidupan.
Belum lagi cemoohan orang-orang yang didapat, seakan-akan pencapaian mereka lebih hebat dari Napoleon Bonaparte.
Pada dasarnya, orang-orang di Minang memang kebanyakan pencemooh. Jadi jangan heran jika bertemu dengan laki-laki Minang, yang mulutnya lebih lemas daripada kursi plastik yang dibakar. Tak jarang juga kelakarnya juga lebih tinggi daripada Burj Khalifa.
Ini jugalah yang mendorong para remaja Minangkabau untuk tidak menetap di kampung. Sekaligus menjadi ajang pembuktian.
Bolehlah dibilang idealis. Idealis kan emang cuman kata keren dari keras kepala.
Faktanya, di kampung memang tidak ada yang bisa digarap. Khususnya bagi mereka yang tidak terlahir dengan sendok emas. Mau mencari kerja juga susah.
Emang apasih perusahaan yang paling besar di sana? Pabrik semen? Jangan harap kalian bisa dapat kerja kalau tidak memiliki koneksi. Selain menggarap semen, mereka juga menggarap nepotisme.
Baca Juga: Agak Sulit Menjadi Laki-Laki (di) Madura
Yang Dirasakan Laki-laki Minang saat Merantau
Meninggalkan kampung halaman bukanlah hal yang mudah untuk pertama kali. Sebenarnya ini dirasakan oleh orang dari mana pun yang merantau sii.
Tapi yaa laki-laki Minang tuhh kayak udah pasti merantau. Bisa jadi saat merantau, mereka meninggalkan kekasihnya. Tak heran lagu-lagu Minang kebanyakan bercerita tentang long-distance relationship (LDR). Aduhh, merana betul!
Rindu makanan kaya rempah
Kebanyakan orang Minang memilih ibu kota sebagai tempat perantauan. Pada awalnya pasti sangat terkesima dengan segala kemewahan tanah rantau, sambutan gedung-gedung mewah, dan makanan yang tersentuh budaya barat.
Makanan gaya barat biasanya cenderung hambar dan memiliki satu cita rasa saja alias monoton. Sedangkan orang Minang terbiasa dengan makanan yang kaya rempah. Ini juga yang membuat saya agak-agak kurang sreg ketika di tanah perantauan. Saya kangen makanan Minang.
Tapi, terlepas dari konflik batin yang dialami perantau, ketika pertama kali menghirup napas di pulau seberang, tanah orang memang menjadi harapan untuk menjadi pembuktian diri. Banyak perantau dari Minang yang menekuni bidang niaga atau berjualan nasi padang.
Orang minang dan nasi padang
Sejarah nasi padang juga tidak jauh dari eksodus orang-orang Minangkabau pada awal tahun 1970an.
Sebenarnya di Sumatra Barat tidak ada istilah “nasi padang”. Kami lebih mengenal lapau nasi, los lambuang, atau ampera.
Hal ini tidak lepas dari imbas Pemberontakan PRRI saat itu. Masyarakat Minang banyak yang menjadi tahanan di tanah sendiri, dicurigai sebagai pemberontak, sehingga mendorong orang-orang untuk melakukan eksodus besar-besaran ke perantauan.
Alih-alih dicurigai sebagai pemberontak di tanah orang, akhirnya mereka lebih memilih memakai nama “nasi padang” dibandingkan dengan nama yang lebih umum di kampung halaman. Didukung fakta bahwa kebanyakan laki-laki Minang memang lihai dalam mengotak-atik rempah-rempah dan mengolah isi kuali.
Berbeda dengan perantau yang tidak memiliki keahlian memasak dan tidak memiliki modal banyak, sesampainya di rantau mereka pasti akan segera mencari induak samang atau orang tua angkat.
Biasanya mereka lebih memilih menjadi pekerja serabutan. Anggaplah hanya sekadar tukang basuh piring di restoran, atau menjadi kernet angkot. Tersebut semata-mata mereka lakukan untuk mengumpulkan modal terlebih dahulu sebelum memulai sebuah usaha.
Cara orang Minang survive di tanah perantauan
Mereka juga harus langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bahaya. Sesuai dengan filosofi yang dibawa dari kampung: dima bumi dipijak di situ langik dijunjuang.
Tidak heran jika para perantau terpaksa menjadi super adaptif saat di rantau. Manusia memang bakal lihai ketika keadaan terdesak. Mau tidak mau gengsi harus dibuang agar cacing di lambung tidak meronta.
Belum lagi memikirkan bekal yang kredibel untuk pulang ke kampung halaman, harga diri berada di atas kepala. Tidak masalah kepala hilang asalkan harga diri tidak diinjak.
Minimal pulang harus berpakaian branded untuk membungkam mulut para pencemooh sebab orang-orang di lapau hanya tau jika perantau sudah pulang kampung, berarti ia sudah memiliki kantong yang tebal.
Setidaknya lebih tebal dari kepedihan yang ditabung selama meninggalkan kampung halaman. Bahkan yang ada di kepala para perantau tersebut pilihannya hanya dua: mati di rantau atau pulang membawa pajero.