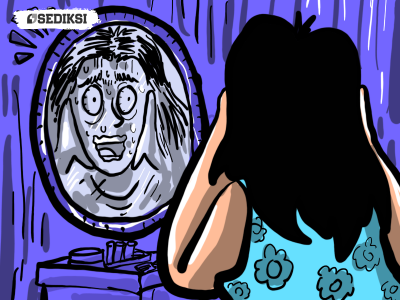Mengenang nama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sama halnya dengan memperingati tiga dunia sekaligus: politik, kemanusiaan, dan sepak bola.
Sosok Presiden RI ke-4 yang karismatik sekaligus kosmopolitan ini amat berpengaruh, terutama dalam konstelasi politik. Gus Dur adalah seorang oposan tulen dan tokoh politik yang nyentrik di masa reformasi.
Orang-orang juga mengingat Gus Dur kental dengan semangat humanis dan sikapnya yang universal dalam berperilaku. Di lain sisi, belum afdal rasanya jika penikmat Mozart ini tak dirayakan sebagai fans sepak bola ulung.
Kecintaan Gus Dur terhadap Sepak Bola
Di bidang politik, pujian dan hujatan memang sudah terlanjur merekat dan tak dapat dipisahkan dari kebesarannya selaku negarawan yang autentik. Namun yang tak kalah penting dan sering dilupakan, namanya juga melekat sebagai salah satu pecinta sepak bola sejati.
Sejak masa kecil, rasa cintanya akan si kulit bundar sudah mulai tumbuh subur. Salah satu kisahnya diceritakan secara lugas oleh Greg Barton dalam bukunya Biografi Gus Dur (2002).
Memiliki seorang ayah dengan tipikal bapak dari suku Jawa yang kerap menjaga jarak dengan anaknya, ia justru gemar mengolah bola di halaman belakang rumahnya di Jakarta dan menjadi lebih dekat dengan sang ayah, Wahid Hasyim.
Lewat sepak bola, Gus Dur membuktikan bahwa tembok pembatas yang kepalang tinggi itu mampu diruntuhkan.
Memasuki fase sekolah, Gus Dur menghabiskan sebagian besar perhatiannya untuk membaca buku dan rutin menonton matchday. Penyaluran energi dan rasa cintanya itu dapat ditegaskan melalui tulisan yang apik, cerdas, sekaligus nyeleneh.
Menulis sepak bola ibarat side hustle yang tak saja bergerak dari sifat materiel, melainkan juga nilai.
Cara Gus Dur Mendudukkan Sepak Bola dan Politik
Ada satu fenomena unik ketika Gus Dur dan salah satu “peletak batu pertama” penulisan sepak bola Indonesia, Sindhunata, berbalas argumen. Alih-alih menyambangi sebuah konferensi pers formal, Gus Dur sekali waktu menjawab kritik dalam perspektif sepak bola melalui tulisan di surat kabar.
Dalam salah satu kolomnya di Tempo berjudul “Piala Eropa: Adu Pola” (1992), Gus Dur mengamati bahwa efektivitas pola permainan tak ubahnya seperti efektivitas birokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Apabila sang juru taktik (kepala pemerintahan) lihai dalam meramu komposisi tim (masyarakat dan sumber daya), pola paling efektif sudah semestinya mampu dikembangkan.
Di rubrik yang sama dengan tajuk “Piala Dunia ’82 dan Landreform” (1982), Gus Dur juga membahas kultur sepak bola negatif (negative football) yang cenderung bertahan: meredam gedoran lawan seraya mengintai kelemahannya.
Hal ini, menurutnya, berbanding lurus dengan gagasan landreform: tunggu saja gedoran kekuatan politik yang menghendaki penataan kembali pola pemilikan dan penguasaan tanah. Sebab, nanti toh muncul titik kelemahannya.
Buah pemikiran Gus Dur di atas seolah-olah menekankan bahwa sepak bola tak mungkin dilepaskan dari politik, dan sebaliknya.
Semangat kemanusiaan ini juga sering muncul dalam sepak bola. Sebagai contoh, kampanye kemanusiaan melalui sepak bola bisa dilihat dari dua kasus yang amat dekat dengan situasi saat ini, yakni kampanye anti-invasi Rusia ke Ukraina maupun tragedi Kanjuruhan.
Krisis di Ukraina disorot oleh klub sepak bola dan tak terkecuali oleh penggemar bola di seluruh dunia. Poster bertuliskan “Peace” yang terbentang di Old Trafford, hingga La Liga yang sempat menyematkan “Stop War” di pojok layar kaca, persis berdampingan dengan papan skor.
Dekat dengan kita, tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 menimbulkan 135 korban jiwa. Tragedi ini direspon oleh khalayak sepak bola dunia. Pendukung Bayern Munchen, misalnya, membentangkan banner “More Than 100 People Killed by The Police” di ajang Liga Champions Eropa.
Keterkaitan antara sepak bola dan politik secara sah tidak dapat diceraikan usai Presiden Joko Widodo turun tangan menangani kasus Arema FC dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dewasa ini, kita juga melihat betapa simpul gerakan perempuan akhirnya melahirkan Piala Dunia Wanita FIFA, kendati beragam persoalan relasi kuasa masih melekat.
Jangan lupakan pula Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva yang mengutuk tindakan rasis terhadap penggawa timnasnya yang merumput di Santiago Bernabeu, Vinicius Junior.
Masih ingat dengan slogan “Kick politics Out of Football”? Seribu kali slogan—yang tampak naif itu—disucikan dalam beberapa tahun terakhir, seribu kali pula jargon ini menggagalkan dirinya sendiri dan menjadi tidak relevan karena tuntutan realitas.
Korupsi di tubuh FIFA? Sudah rahasia umum, Bung!
Kasus yang agak berbeda muncul jika Palestina dilibatkan dalam perbincangan. Kampanye kemanusiaan untuk Palestina dari para pendukung klub Eropa sering mendal.
Ingat saja aksi suporter yang acapkali menyerukan kampanye dukungan kepada Palestina: Celtic FC, AS Roma, Lazio, Partizan Belgrade, Red Star Belgrade, St. Pauli, dan lainnya. Alih-alih mendudukkan dalam koridor kemanusiaan yang sama, UEFA malah memberi sanksi.
Andai Gus Dur masih hidup, ia mungkin masih menulis soal politik, kemanusiaan, dan sepak bola.
Andai Gus Dur Masih Aktif Menulis Sepak Bola
Ketika masih produktif dalam menulis dalam rentang 1970-an sampai 1980-an, sepak bola diwarnai dengan persaingan antar-raksasa Eropa. Sebut saja Bayern Munchen, AC Milan, hingga Real Madrid.
Kala itu, sepak bola belum mempunyai kompleksitas sebagaimana hari ini. Hit and Run, Total Football, dan Catenaccio masih menjadi tiga patron besar dalam persepakbolaan.
Dunia berputar, dan sejumlah tim jempolan masa lalu kini sedang mengalami krisis, baik ekonomi maupun identitas.
Gus Dur pernah pernah memprediksi kemajuan sepak bola Asia dan Afrika pada pertengahan 2000-an.
Rupanya, prediksi Gus Dur mendekati kenyataan. Coba tengok beberapa bintang Liga Inggris dan Eropa berasal dari Asia dan Afrika. Mohamed Salah (Mesir/Afrika) di Liverpool, maupun Son Heung-Min (Korea Selatan/Asia) di Totttenham Hotspur.
Jika menengok urusan liga, klub Arab Saudi berkat suntikan dana besar-besaran pun bisa masuk dalam hitungan mengacu pada tingginya eksodus para super star ke negeri gurun pasir tersebut.
Dinamika zaman berubah. Pun demikian dengan sepak bola.
Pesohor lapangan hijau seperti trio Ronald Koeman, Ruud Gullit dan Frank Rijkaard dari Belanda atau Guido Buchwald serta Jurgen Klinsmann dari Jerman telah digantikan Erling Haaland di kutub yang satu dan Kylian Mbappe di seberang yang lain.
Adu strategi antara Rinus Michels, Franz Beckenbauer, dan Berti Vogts kini menjelma pertarungan otak milik Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, dan Jurgen Klopp.
Ditilik dari jejak tulisannya soal kemanusiaan, politik dan sepak bola, Gus Dur mungkin tak luput mengaitkannya.
Saya jadi membayangkan, apa yang akan ditulis Gus Dur jelang Pilpres tahun 2024 nanti. Akankah ia mengaitkannya dengan sepak bola?
Bagaimana Gus Dur menaruh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto di posisinya yang paling optimal? Siapa yang berhak mengisi pos gelandang, striker, dan penjaga gawang?
Lalu, formasi apa yang bakal dipraktikkan di masa cyber-physical system yang serbacepat ini?
Apakah skuad bernama Indonesia harus berlaga sambil memainkan Tiki-Taka dengan ball possession, body crash football yang meledak-ledak ala Skandinavia, atau Gegenpressing yang digodok oleh Ralf Rangnick? Biarlah pembaca saja yang menerka jawabannya.
Kemanusiaan adalah Fondasi Politik dan Sepak Bola
Agresi dalam sepak bola itu sudah lumrah, begitu pula dalam urusan politik. Semuanya tidak perlu ditanggapi dengan kaku. Toh, mantan Ketua PBNU itu kerap “menggoda” Presiden Soeharto dengan beraneka manuver. Karena bagaimanapun, kemanusiaan tetap wajib mengambil peran sebagai fondasi. Sudah sepatutnya ketiga unsur di atas ditanggapi dengan santai, gitu aja kok repot?
Gus Dur pernah berpesan, terkadang kita harus menerapkan kejujuran layaknya sepak bola samba ala Brasil dalam menghadapi kehidupan. Rivalitas sengit dalam sepak bola berakhir setelah 90 menit, demikian juga dalam kontestasi politik.
Berbagai label atas sederet kontroversi memang telah disematkan, tapi perjuangan dan karyanya tak akan pernah tenggelam dilahap zaman sekalipun dirinya telah meninggalkan kita lebih dari satu dekade lamanya.