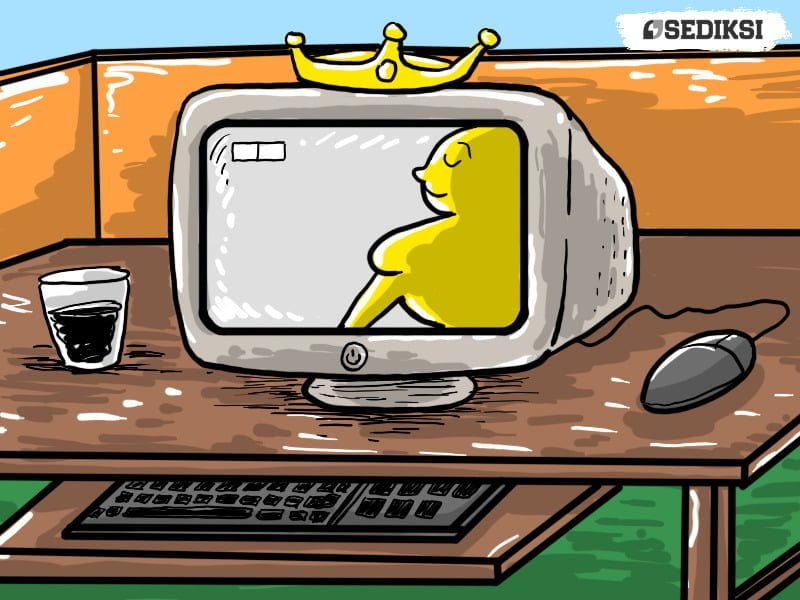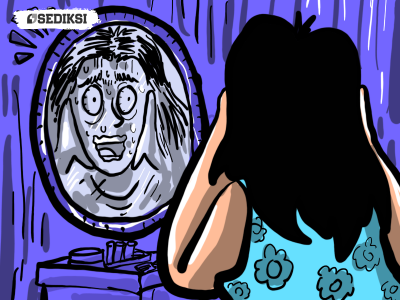Saat itu, bisnis warung internet (warnet) mulai berdenyut di nadi perkotaan. Saya masih SD dan pernah bermain ke warnet yang komputernya hanya dua biji saja. Sehingga banyak orang mengantre. Karena itu, pemilik warnet membuka bisnis es Jasjus dan gorengan, yang ternyata lebih cuan ketimbang warnet itu sendiri.
Menginjak SMP dan SMA, saya menemui bahwa warnet sudah bukan sekadar tempat untuk menikmati berselancar di internet. Tapi juga tempat untuk nongkrong, ruang untuk sendirian, tempat melipir sepulang sekolah, sampai destinasi pacaran.
Warnet menjelma menjadi tempat singgah, yang menyediakan ruang untuk berinteraksi sosial, seperti warung pada umumnya.
Lebih dari itu, bagi saya, warnet seakan menjadi ruang dengan realitas ganda. Ruang di mana interaksi sosial dan interaksi digital bertemu. Ruang di mana pembaruan teknologi masih berdampingan mesra dengan cara bersosial yang masih konvensional.
Warnet dan Manusia yang Merindukan Ruang Aman
Warnet seakan menjadi sebuah jembatan transisi kebudayaan. Buset, keren banget. Maksudnya masa peralihan soal bagaimana perilaku manusia dalam berinteraksi sosial berubah tanpa disadari. Dari yang sebelumnya serba tatap muka beralih ke interaksi yang serba online seperti sekarang ini.
Selain itu, warnet menjadi ruang privat yang menjanjikan kebebasan yang bahkan tidak ditemui di dalam rumah sendiri. Di bilik yang bahkan lebih kecil dari lubang makam itu, setiap orang bisa melakukan apapun.
Ngegame, nyari chord gitar, ngebokep, nyari teman baru di Myspace atau friendster, jatuh cinta dengan akun palsu di Facebook, sampai numpang tidur atau bahkan nangis sambil dengerin Avenged Sevenfold di Winamp huhu.
Inilah letak keunikannya. Warnet menjadi sebuah tempat yang menjanjikan kebebasan, di mana setiap orang bakalan aman-aman saja bersibuk ria dengan diri sendiri.
Bahkan, warnet juga menjadi tempat healing murah meriah buat mengobati masalah. Asmara misalnya.
Ada seorang teman saya yang biasanya rutin main di warnet. Setelah jadian ia tidak kelihatan batang hidungnya. Namun beberapa bulan kemudian saya menemukannya meringkuk seperti Smeagol di bilik paling pojok. Alhasil, sepanjang malam saya mendengarkan curhatannya sambil mengunduh film bajakan. Sementara ia curhat dan menangis sambil mengunyah pentol hasil ngutang.
Bagi banyak orang, warnet adalah ruang aman dari segala permasalahan. Tidak terbatas pada realitas sosial yang nampak saja, namun dalam realitas digital, warnet juga menjadi titik kumpul yang aman. Di media sosial, di kolom chat, atau bahkan di lobby game.
Mengantarkan Generasi ke Era Digital Lewat Warnet
Meski meniadakan batas usia dalam interaksi digital, adanya warnet ini juga menandai batas antar generasi. Terutama generasi milenial dan Gen Z.
Pembagian generasi berdasarkan tahun lahir itu sebenarnya nggak masuk akal. Anak kelahiran 98 di Amerika sono, jelas beda dengan yang lahir di kabupaten Ngawi. Baik secara paparan teknologi, budaya, maupun perilaku sosial.
Kalau pembagian generasi ini dilihat dari perspektif teknologi, maka jawabannya gampang. Yaitu generasi millennial merasakan gelombang disrupsi teknologi digital. Sementara gen Z saat lahir udah kenal sama yang namanya teknologi digital. Kalau bahasa kerennya, digital native.
Makanya, menurut saya warnet bisa menjadi tolok ukur pembatas antar generasi. Warnet menjadi semacam ruang liminal atas proses adaptasi teknologi digital ini.
Di masa saya kuliah, warnet mulai ditinggalkan pengunjungnya. Anehnya, tak ada yang protes. Semuanya mengalir begitu saja. Lalu perlahan WiFi dan smartphone mulai menggantikan kenyamanan dalam berinternet.
Para Gen Z juga banyak yang tidak menjalani masa-masa kejayaan warnet ini, dan itu tak jadi soal buat generasi milenial.
Biasanya, ketika ada perubahan teknologi, kebudayaan, dan sosial bakal menimbulkan chaos. Masih ingat betapa kencangnya gelombang penolakan ojek pangkalan saat terkena disrupsi aplikasi ojol? Atau bagaimana saat ini para pekerja kreatif mulai gelagapan menghadapi tsunami teknologi AI?
Pada masa revolusi Gutenberg dulu juga begitu. Di mana mesin cetak mulai diproduksi massal, bahkan mampu menumbangkan dogmatisme gereja, ia mampu mengubah nilai dalam masyarakat, serta merevolusi pengetahuan dan pendidikan.
Pada masa itu bahkan sekat antar generasi kian senjang. Banyak generasi tua yang menyinyiri generasi muda sebagai generasi anti sosial yang gemar menunduk membaca koran dan abai dengan lingkungan sekitarnya. Sementara generasi mudanya menuding para orang tua sebagai generasi kolot.
Tidak ada yang salah tentunya. Toh semuanya soal sudut pandang.
Setiap generasi melahirkan kebiasaan, perilaku, dan pola interaksi yang berbeda. Kita menyebutnya kebudayaan. Warnet, sebagai produk kebudayaan juga ikut serta menciptakan kebudayaan baru buat generasi selanjutnya.
Baca Juga: Tech Winter Terus, Kapan Summer-nya?
Dramaturgi Warnet dalam Tiga Babak
Warnet dalam perkembangannya mengalami modifikasi, sesuai zaman serta kebutuhan pelanggannya. Pada awalnya adalah warnet konvensional dengan segala macam aktivitas yang berhubungan dengan internet bisa dilakukan di dalamnya.
Bagi yang mengalami masa-masa awal warnet, pasti memiliki banyak kenangan di dalamnya. Kombinasi antara warnet, hujan, dan indomie kuah adalah pengejawantahan paling nyata, dan tak terbantahkan dari ayat “nikmat mana lagi yang kamu dustakan,”
Lalu masuk babak kedua, masa di mana segalanya mulai serba cepat dan akses internet sudah banyak didapatkan dari wifi dan paket data. Warnet kawin-mawin dengan tempat printing dan penjilidan.
Pada masa itu, waktu kunjung orang makin singkat. Sebatas meng-copy tugas, lalu tinggal nge-printsaja. Bahkan di beberapa tempat jasa printing, penggunaan komputer beserta internetnya malah digratiskan.
Dan babak ketiga, saat turnamen game online mulai marak. Warnet sekali lagi mengubah wajahnya. Seakan menemukan napas, warnet menjadi identik dengan aktivitas gaming. Bahkan beberapa warnet bekerja sama dengan klub e-sport. CPU spek tinggi, kursi gaming, dan kenyamanan lainnya menjadi kewajiban.
Dari fase-fase itu kita bisa melihat bagaimana kebudayaan dalam bingkai teknologi berkembang dan berubah bentuk. Misal aktivitas ngegame yang pada awalnya identik dengan hiburan semata, atau bahkan candu bagi orang kurang kerjaan, saat ini dipandang keren dan justru menjadi profesi menjanjikan.
Sekarang, warnet menjelma sebagai ruang yang lebih luwes. Seperti kafe, warkop, dan public space. Tempat yang bisa menikmati kesendirian, mencari hiburan, berkumpul bersama teman, sampai tempat merampungkan pekerjaan.
Entah bagaimana nasib warnet ke depannya. Bisa berganti, bisa juga mati. Yang pasti, kebudayaan terus bergerak dan berubah bentuknya. Namun ruhnya tetap sama, selama kebutuhan manusia juga tetap sama. Kebutuhan untuk memiliki ruang aman tentunya.