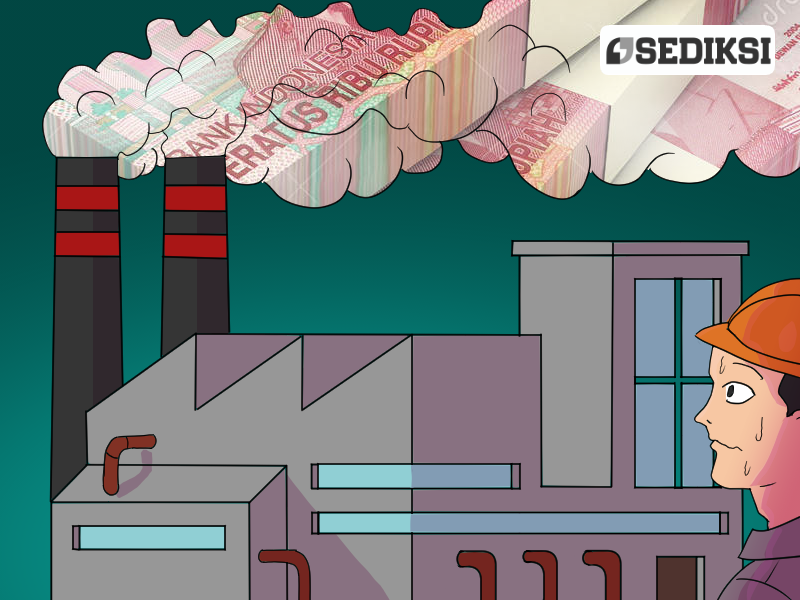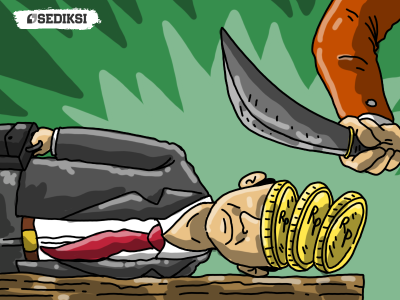Persoalan lingkungan menjadi salah satu tema utama yang diangkat pada kampanye Pemilu Capres-Cawapres 2024, di mana pajak karbon menjadi salah satu yang paling disorot di dalamnya.
Hal ini memang wajar mengingat topik seputar kelestarian lingkungan adalah sesuatu yang penting untuk dibahas oleh seluruh masyarakat dunia. Kondisi dunia yang tengah mengalami global warming mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi dan keberlangsungan alam.
Salah satu solusi yang ditawarkan terkait persoalan akibat peningkatan emisi gas rumah kaca ini adalah pajak karbon. Namun, apakah pajak karbon itu solusi yang mutakhir dan dapat dengan efektif menjawab persoalan ini?
Sekilas mengenai Pajak Karbon
Pajak karbon merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mencegah global warming. Pajak ini seakan mengikat para produsen yang melepaskan senyawa karbondioksida ke udara dalam proses produksinya.
Konsep pajak ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya saja namanya berbeda, yaitu pajak pigovian (pigovian tax). Arthur Pigou menjadi orang yang pertama kali mengemukakan konsep terkait pajak jenis ini dalam bukunya, Economics of Welfare, pada tahun 1920.
Tujuan pajak pigovian ini ialah untuk menginternalisasi biaya yang terpaksa ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses transaksi. Biaya ini dapat kita sebut juga dengan istilah “eksternalitas”.
Misalnya ada pabrik yang mengeluarkan asap hitam ke udara. Biaya yang ditanggung pabrik tersebut, selaku produsen, awalnya hanya biaya produksi saja.
Mereka tidak memperhitungkan atau membayar biaya sosial seperti kerusakan lingkungan akibat asap yang dikeluarkan. Mereka tidak bertanggung jawab padahal telah mengeluarkan eksternalitas berupa asap hitam ke udara.
Baca Juga: Indonesia 2045: Kuning Belum Tentu Emas
Harga dari kerusakan itu malah ditanggung oleh masyarakat ataupun flora dan fauna sekitar, yang bahkan banyak dari mereka tidak mengonsumsi barang yang dijual oleh pabrik itu.
Harga yang harus ditanggung ini muncul dalam bentuk biaya berobat ke rumah sakit karena gangguan pernafasan atau usaha-usaha perbaikan kerusakan lingkungan.
Oleh karenanya, pajak pigovian berusaha menginternalisasi eksternalitas yang dikeluarkan pabrik tadi. Pabrik dipaksa bertanggung jawab menanggung biaya eksternalitas yang mereka hasilkan. Hal itu dilakukan dengan cara menagih mereka untuk membayar pajak.
Nah, konsep pajak karbon itu sebenarnya kurang lebih diambil dari sini. Dengan pajak ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki serta mencegah kerusakan alam akibat tindakan ugal-ugalan pabrik tadi.
Caranya sendiri ada bermacam-macam. Bisa melalui subsidi teknologi terbarukan agar perusahaan beralih ke mesin yang ramah lingkungan, penanaman pohon di sekitaran kawasan pabrik, subsidi biaya kesehatan, dan lain-lain.
Problematika Pajak Karbon
Dalam penerapannya, terdapat sejumlah permasalahan pada pajak karbon. Pertama, kalau tarif pajak karbon dirasa terlalu rendah, perusahaan ataupun produsen bisa saja melakukan moral hazard.
Moral hazard adalah kondisi di mana suatu pihak memutuskan untuk mengambil risiko yang lebih besar karena merasa sudah ada yang akan menanggung akibatnya. Kalau bahasa non-formalnya, sih, “aji mumpung”.
Apabila tarif pajak karbon yang dikenakan masih terbilang murah, perusahaan akan berpikir, “Tidak apa-apa kita mengeluarkan banyak karbon, kan, tinggal bayar pajak aja… Paling jumlahnya nggak seberapa”. Akhirnya, tidak ada dorongan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan.
Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan utang pada bank atau semacamnya untuk meringankan beban dalam membayar pajak karbon, seperti yang ditulis Elie Appelbaum dalam penelitiannya yang berjudul “Improving the efficacy of carbon tax policies.”
Ya, berarti tarif pajaknya jangan yang rendah, dong, biar nggak disepelein sama perusahaan. Memang, dengan tarif tinggi, perusahaan kemungkinan dapat dipaksa mengurangi emisi karbonnya.
Akan tetapi, hal ini dapat memunculkan permasalahan selanjutnya, yaitu kenaikan harga barang yang dijual pabrik tersebut.
Kalau kamu nonton debat cawapres kemarin, pasti tidak asing dengan kata “greenflation”, kan? Greenflation adalah inflasi yang timbul dalam tahap pergantian dari energi tak terbarukan ke terbarukan. Inflasi akibat pajak karbon merupakan salah satu wujudnya.
Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan tingginya tarif pajak tadi seakan dilempar ke para konsumen dalam bentuk harga yang mahal.
Jadi, yang sebenarnya bayar pajak itu konsumen melalui harga barang. Lha, rugi dong? Ya jelas rugi. Apalagi kalau barang yang permintaannya inelastis seperti BBM dan gas. Mau tidak mau harus dibeli walaupun mahal karena kita butuh untuk bahan bakar kendaraan.
Tidak hanya konsumen, produsen juga dirugikan apabila kondisi permintaan di pasar elastis. Permintaan terhadap barang mereka bisa turun apabila konsumen dapat menemukan alternatif dengan barang substitusi (barang pengganti).
Selain itu, produsen yang dapat membayar biaya produksi sebelum pajak dengan harga murah terpaksa membayar biaya mahal setelah ada pajak. Akhirnya, mereka perlu mengurangi jumlah produksi karena hal itu.
Baca Juga: Pinjol ini Membunuhku: Cerita dari ITB
Pajak Karbon? Bursa Karbon? Atau Keduanya?
Di beberapa negara, pajak karbon memang dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, tak jarang juga ditemukan permasalahan dalam penerapan solusi ini untuk menangani masalah emisi gas karbon.
Sebenarnya, ada satu solusi lagi yang bisa jadi lebih efektif, yaitu bursa karbon. Solusi ini dapat menjadi alternatif dalam menangani masalah karbon karena memungkinkan pasar bebas berjalan dengan baik tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan.
Bursa karbon dapat berjalan selaras dengan motif perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa, yaitu mencari keuntungan.
Dalam bursa karbon, perusahaan memiliki surat berharga berupa izin untuk mengeluarkan karbon ke udara, namun dengan batasan yang sudah ditentukan dalam surat izin tersebut. Apabila ingin mengeluarkan karbon lebih banyak, perusahaan perlu membeli surat izin milik perusahaan lain.
Tentu, pihak yang paling diuntungkan dalam skenario seperti ini adalah perusahaan yang tidak atau sedikit mengeluarkan karbon, atau dengan kata lain memiliki surat izin yang baru terpakai sedikit.
Mereka dapat menjualnya pada perusahaan lain yang membutuhkan surat izin lebih banyak, tapi tentu saja, dengan syarat perusahaan tersebut berhasil mengurangi emisinya di bawah batas yang telah ditentukan.
Harga surat izin yang diperjual-belikan antar perusahaan ini ditentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran surat izin di pasar.
Cara main bursa karbon ini pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk mengganti mesin dan teknologinya dari yang kotor dan penuh polusi kepada teknologi ramah lingkungan. Pasalnya, komitmen untuk mengurangi emisi dapat berujung pada insentif yang menjanjikan dalam perdagangan karbon.
Selain itu, potensi pasar karbon di Indonesia juga perlu menjadi pertimbangan. Dikutip dari Tempo, negara ini diperkirakan menyumbang 75-80 persen kredit karbon dunia yang mana dapat memberikan kontribusi sebesar 150 miliar dollars bagi perekonomian negara. For your information, Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan bursa karbon sejak September 2023 lalu.
Nah, dari sini bisa dilihat bahwa solusi pajak karbon itu kadang tidak efektif. Memang, kajian perlu terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui kecocokan penerapan solusi ini di Indonesia.
Kalau cocok, ya, syukur, kalau tidak juga tidak masalah. Sebab, kita bisa mengambil alternatif lain seperti bursa karbon.
Bahkan, kedua model kebijakan itu juga sebenarnya dapat digabungkan, seperti yang dikatakan oleh Wei Li dan Zhijie Jia dalam penelitian mereka yang berjudul “Carbon tax, emission trading, or the mixed policy: which is the most effective strategy for climate change mitigation in China?”.
Mereka berpendapat bahwa kebijakan campuran (mixed policy) antara pajak serta bursa karbon dapat lebih efektif di Tiongkok.
Selain itu, dilansir dari Mongabay, negara-negara seperti Korea Selatan, Portugal, Prancis, dan Swedia juga telah mengkombinasikan model kebijakan pajak karbon dengan instrumen pasar karbon lainnya dengan pengimplementasian yang disesuaikan pada kondisi serta arah kebijakan masing-masing negara.
Baca Juga: Menyuarakan Nasib PRT di Tahun Kritis