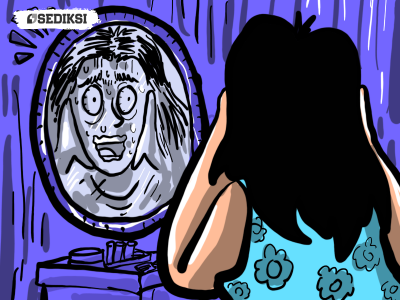Belakangan ini, quotes filsafat berseliweran di mayantara (dunia digital). Saya menanggapinya dengan antusias. “Filsafat”, ucap saya sambil berjingkrak-jingkrak dalam imajinasi, “akhirnya menarik untuk dilirik.” Betapa tidak, makhluk aneh nan belibet itu akhirnya muncul ke permukaan dan perlahan mulai disukai banyak orang.
Setidaknya animo ini menjadi opini tandingan bahwa filsafat tak harus dipelajari secara kaku. Filsafat juga bisa memotivasi dan relate dengan kehidupan sehari-hari.
Namun, semua euforia itu berhenti seketika. Setelah saya amati, ternyata masih banyak orang yang menyambut filsafat itu tanpa benar-benar memahaminya secara utuh dan cenderung terlihat seperti FOMO (Fear Out of Missing Out) belaka.
Kutipan dari para filsuf bertebaran di sana-sini. Se-fruit pemikiran mereka dicuil, di-save, dan dijadikan story oleh berbagai orang di berbagai media sosial. Oh, iyaa… tidak lupa diktum para pecinta kebijaksanaan tersebut dicantumkan di bio medsos masing-masing, contohnya:
Cogito, ergo sum (I think, therefore I am)
~ René Descartes ~
Tidak jauh beda dengan konten viral dan motivasi lainnya, konten-konten filsafat menggugah sesaat. Orang-orang berbondong-bondong untuk terlihat intelek secara spontan dan instan alias menjadi filsuf abal-abal.
Pemikiran-pemikiran filosofis disitir dan dijadikan caption untuk keren-kerenan. Tak jarang, filsafat juga jadi alat untuk mencari perhatian orang lain.
Stoikisme sebagai Contoh
Bukti bahwa filsafat tengah naik daun, sebut saja misalnya, fenomena viralnya stoikisme. Salah satu aliran filsafat Yunani klasik itu tengah marak diperbincangkan. Stoikisme digadang-gadang sebagai “alat tempur” generasi kekinian. Setidaknya ada dua alasan utama kepopulerannya di kalangan kawula muda.
Pertama, tentu saja, akibat keberadaan mayantara. Stoikisme diminati khususnya sejak Henry Manampiring (Om Piring) menulis buku Filosofi Teras.
Buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, menjadi best seller, dan didapuk sebagai book of the year oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 2019. Om Piring pun sering diundang ke sana kemari untuk membahas bukunya itu.
Para kreator konten—seperti biasa—menyesuaikan diri sesuai permintaan pasar. Mereka ikut-ikutan membahas stoikisme, entah itu secara pribadi maupun dengan mengundang sang penulis Filosofi Teras dalam kontennya. Memang, tidak semua kreator konten bersikap pragmatis, tetapi mayoritas demikian.
Alasan kedua stoikisme bisa viral tidak lain dari doktrinnya yang mudah untuk “dikunyah”. Stoikisme mengusung semboyan “filsafat sebagai laku hidup”. Ajarannya tidak jauh-jauh dari hiruk-pikuk keseharian. Dalil -isme yang satu ini men-trigger pembacanya untuk menjaga rasio dalam menyikapi segala sesuatu yang kadang-kadang kidding.
Stoikisme mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan terbebas dari emosi-emosi negatif, seperti marah, iri, dengki, dst. Caranya dengan menerapkan “dikotomi kendali” [istilah ini dipakai oleh Om Piring dalam bukunya tersebut].
Singkatnya, dikotomi kendali adalah soal pemilahan dan pengambilan sikap terhadap apa-apa yang dapat kukendalikan dan apa-apa yang tidak dapat kukendalikan.
Yang pertama sifatnya internal (different) dan tergantung pada diriku. Sementara yang terakhir itu eksternal (indifferent) dan tidak tergantung pada diriku. Umpamanya, soal agenda pilpres.
“Siapa pun yang berkuasa nanti, nggak akan menjamin aku bahagia. Ngapain harus gelisah, galau, merana dengan perdebatan para (pendukung) paslon, apalagi fanatik habis sama salah satu calon?”
Sejauh ini, semua terasa baik-baik saja. Masalah terjadi ketika doktrin stoik dipakai untuk melegitimasi sikap menyerah pada nasib, mager-mageran, pasif, dan apatis tak bertanggung jawab.
Pilpres tadi benar-benar tidak dipedulikan seolah tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kehidupannya. “Dikotomi kendali” dibaca sebagai suatu upaya untuk mengabaikan tanggung jawab bermasyarakat dan tidak peduli dengan orang lain.
“Udahlah, lupakan soal pilpres. Itu urusan orang-orang partai dan cukongnya, mending golput aja.”
Alasan Orang Salah Persepsi
Setidaknya ada 2 hal yang menjadi penyebab kesalahan mempersepsi informasi kiwari: (1) karena hanya dikutip sebagian dan/atau (2) karena tidak melihat konteks.
Dikotomi kendali adalah subdoktrin dari stoikisme. Sifatnya mendasar, tetapi tidak mewakili stoikisme secara utuh. Stoikisme masih memiliki ajaran-ajaran yang lain!
Pemahaman populer soal dikotomi kendali di atas pun belum cukup untuk menggambarkan dikotomi ini sepenuhnya. Hasil pilpres, kekayaan, kesehatan, pendidikan, omongan tetangga, dst.; semuanya itu tidak berada dalam kendali kita. Namun, semuanya itu masih bisa kita usahakan.
Salah bila dikotomi kendali disamakan dengan sikap “bodo amat” tanpa tanggung jawab. Seorang dosen filsafat STF Driyarkara, Augustinus Setyo Wibowo, menyebutkan bahwa ada hal indifferent yang layak diminati (preferred indifferent) dalam bukunya Ataraxia: Bahagia Menurut Stoikisme [hal. 171].
Benar bahwa kita harus menjaga pikiran, persepsi, ucapan, dan tindakan dalam menyikapi pilpres. Hal itu terjadi karena keempat hal tersebut sepenuhnya dapat kita kontrol.
Akan tetapi, pilpres bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Setiap keputusan, entah itu golput atau memilih salah satu calon tertentu, berpengaruh terhadap hasil pilpres.
Lagi pula, stoikisme juga memiliki doktrin “kosmopolitan” yang mengajarkan bahwa manusia adalah warga dunia. Jadi, ada keterikatan antar sesama dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional.
Dalam hal ini, pilpres tentu memiliki andil bagi kepentingan maslahat. Soal siapa yang terpilih, itu di luar kendali. Namun, kalau nanti tingkahnya nyeleneh begitu terpilih, kita pun masih bisa slepet rame-rame.
Contoh lain yang lebih dekat, misalnya, soal omongan “negatif” orang-orang terhadap kita. Boleh jadi kita tidak bisa mencegah kelakuan orang-orang semacam ini.
Meskipun begitu, pilihan untuk bersikap biasa aja atau misuh-misuh dan balas dendam (omongin balik) sebagai cara menanggapinya, sepenuhnya ada dalam kendali kita.
Ini pun perlu pemeriksaan lagi. Jangan-jangan omongan orang itu benar? Hal-hal negatif sekalipun kerap kali bisa menjadi kritik bagi si aku. Bisa jadi setelah memperbaiki diri (atau sedari awal memang aku tidak bersalah), omongan orang itu terus berdengung. Jadi, memang dasarnya beliau pengin nyinyir aja.
Kalau begitu, apakah aku secara strict mesti menjadi anti sosial? Apakah aku sama sekali tidak lagi bisa memercayai orang lain? Apakah aku harus menyindir-nyindir orang itu lewat status WA dan IG story? Kalau aku mengiyakan ketiga pertanyaan ini, itu, sih,“kekanak-kanakan yang berlindung di balik kata stoik,” namanya.
Oleh karena itu, perlu ketenangan dan kehati-hatian dalam menerapkan dikotomi kendali. Dikotomi kendali merupakan bagian kecil dalam rangka memenuhi tujuan universal stoikisme, yakni selaras dengan alam.
Selaras dengan alam berarti hidup sesuai prinsip keteraturan alam itu sendiri. Masa, iya, itu artinya mengabaikan atau menumbuhkan konflik dengan orang lain?
Baca Juga: Fenomena Maraknya Penggunaan Kata Estetik
Supaya Pengetahuan Tidak Terputus
Quotes filsafat (maupun quotes lainnya) memang bukan problema. Namun, bila dibaca setengah-setengah pasti jadi problematik.
Berapa banyak, sih, orang yang membaca paragraf asli dari sebuah quote? Quote-nya dikutip dari halaman 25. Eh, bukunya yang 250 halaman nggak dibaca sepenuhnya. Wajar saja bila kehilangan konteks soal mengapa quote itu begitu menggugah.
Oleh karenanya, supaya pengetahuan tidak terputus, ketika menemukan quotes filsafat dan tergugah, lanjutkan dengan belajar dari bukunya langsung.
Masih banyak lagi cara untuk memperdalam filsafat. Yang jelas belajar (filsafat) itu menyenangkan, meski kadang membuat kepala berasap.
Mereka yang hendak belajar filsafat perlu mencurahkan waktu dan berpikir keras demi memahami isi kepala filsuf-filsuf itu. Ya, begitulah adanya, si ibu para ilmu ini.
Baca Juga: Mlijo: Panggung Kekuasaan ala Foucault