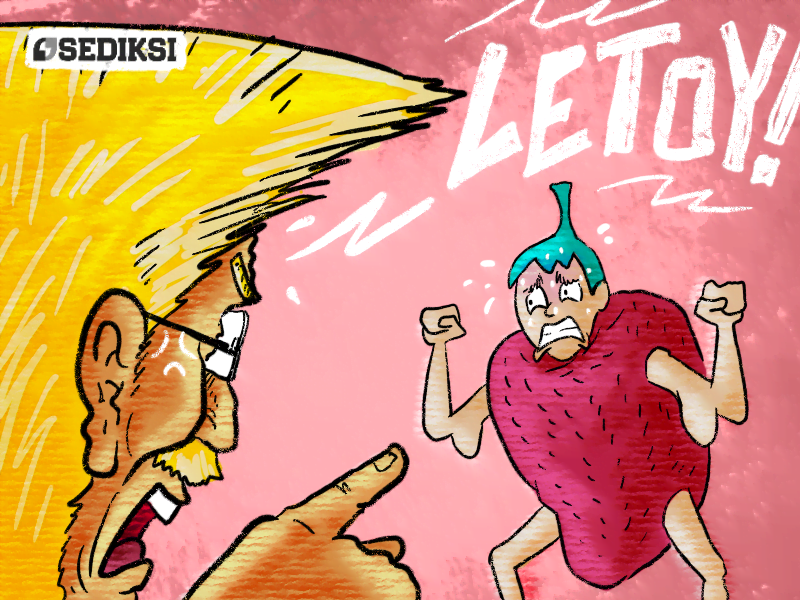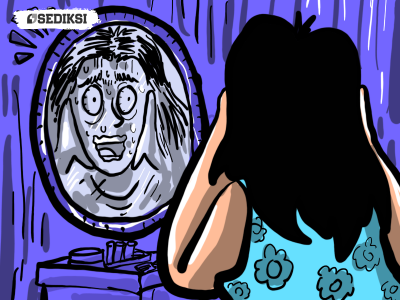Dear, temen-temen Gen Z.
Banyak orang nyebut generasi Z sebagai “Generasi Stroberi”. Sebenarnya, saya nggak ngeh apa maknanya. Setelah baca-baca di internet dengan saksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya memutuskan tidak setuju.
Sebutan generasi stroberi menunjukkan bahwa generasi Z dianggap menarik dan menggiurkan, sebagaimana stroberi. Generasi Z dianggap memiliki pemikiran yang cemerlang, kreatif, dan penuh inovasi. Wah, pasti senang ya dianggap begitu.
Jangan keburu senang dulu. Sebutan itu sebetulnya malah lebih digunakan sebagai ejekan.
Berhubung buah stroberi, ya, jadinya mudah hancur. Nggak ngerti deh kenapa label mudah hancur atau mental rapuh disematkan secara semena-mena. Apakah karena ekspresif di media sosial, baik saat senang, sedih, marah, takut, maupun kecewa?
Dalam surat ini, saya ingin mengatakan ketidaksetujuan akan stigma masyarakat bahwa generasi stroberi itu mentalnya rapuh. Nah, istilah generasi stroberi itu sering dibenturkan dan dibanding-bandingkan dalam hal mental.
Ada beberapa poin yang bisa membantah bahwa generasi stroberi itu tidak bermental lemah, rapuh, maupun mudah hancur.
Bukan Rapuh, tapi Ekspresif
Generasi Z tumbuh saat media sosial berkembang pesat, dan generasi yang aware akan kesehatan mental dibanding generasi-generasi sebelumnya yang masih denial (menyangkal) akan kesehatan mental.
Kenapa saya sebut denial?
Sebagai kelahiran 90-an alias milenial, saya masih menghadapi stigma masyarakat yang menjauhkan dari kesadaran memahami kesehatan mental. Salah satu contohnya, anggapan kalau laki-laki nggak boleh nangis.
Barangkali masih ada dari kita yang mendengar atau hidup di lingkungan dengan stigma seperti itu. Rupanya sih masih cukup banyak.
Stigma itu muncul karena laki-laki dibayangkan sebagai sosok yang kuat nan tangguh. Pantang bagi mereka untuk menangis. Nggak jarang stigma macam itu kita temui di kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, ada bocah laki-laki yang lagi lari-larian kemudian tersandung. Sebetulnya, wajar belaka kalau mereka menangis, tetapi ada orangtua yang meresponnya dengan mengulang stigma laki-laki harus kuat.
“Cup, cup, cup, udah gak usah nangis. Cowok kok nangis. Gak boleh nangis!” yang lebih parah sampai ada orang tua yang sampai melabel buruk anaknya. “Kalau kamu nangis, nanti jadi banci lho.” Parah.
Kalau dipikir-pikir secara rasional, adakah larangan agama atau pemerintah soal laki-laki tidak boleh menangis? Nggak ada kan? Kalau memang laki-laki gak boleh nangis, lalu apa tujuan Tuhan menciptakan air mata buat manusia?
Generasi sebelum-sebelumnya masih mengalami stigma tersebut, maupun stigma sejenis lainnya, yang intinya menjauhkan hak seseorang untuk memvalidasi perasaannya. Secara tidak langsung, perilaku macam ini masih abai akan pentingnya kesehatan mental.
Penyangkalan kesehatan mental terbukti dengan masih banyaknya pandangan masyarakat bahwa penyebab permasalahan mental karena kurang iman, kurang ibadah. Beberapa yang lain menyimpulkannya karena karena gangguan ghoib.
Sudah begitu, orang-orang yang datang ke psikolog atau psikiater berpeluang dianggap ‘gila’. Padahal, faktanya jelas tidak. Datang ke psikolog maupun psikiater merupakan satu dari sekian cara mengatasi gangguan psikologis ringan maupun untuk pengembangan diri.
Wahai generasi Z, bersyukurlah karena lahir di zaman sekarang. Berkat teknologi, informasi dan edukasi psikologi memungkinkan tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Memvalidasi dan mengekspresikan perasaan, sekaligus memahami bagaimana cara mencintai diri bukan sesuatu yang aneh.
Sebagian besar generasi kami dan generasi sebelumnya masih salah mengartikan bahwa itu bentuk kerapuhan, lemah, dan “bermental stroberi”.
Perlu kita tahu bahwa orang-orang itu tak terbiasa memvalidasi perasaan dan mencintai dirinya. Saking tidak terbiasanya generasi lama memvalidasi dan mengekspresikan emosi, membuat seseorang bisa merasa bangga pada hal yang sebenarnya keliru.
Misalnya, sejumlah orang generasi X merasa bangga atas hukuman fisik yang ia alami. Nggak jarang kebanggaan mereka dituangkan di komentar-komentar media sosial, terutama konten yang ngebahas kehidupan generasi Z.
“Dulu, kalau aku salah, kalau nggak dijewer ya dipukul pakai sapu. Biasa aja sih, nggak kayak anak sekarang yang kena bentak dikit udah curhat di medsos.”
Sekarang kita telaah. Apakah kekerasan fisik seperti itu dibenarkan? Atau kah sebenarnya itu memang tidak layak dilakukan, namun dianggap biasa di masa itu karena stigma yang keliru saat itu? Atau jangan-jangan sebenarnya banyak dampak negatifnya hanya saja tidak mereka validasi dan belum ada sosmed sehingga tidak terekspos?
Hayo, mikir.
Baca Juga: Yang Bisa Kita Pelajari dari Negative Self Talk Anna Sasaki dalam “When Marnie Was There”
Generasi Bukan Perlombaan
Tidak ada perlombaan mana yang jadi generasi terbaik, sebab generasi bukan perlombaan.
Mindset senior lebih baik dari junior sudah sangat biasa. Kakak tingkat merundung adik tingkat, atau senior ngospek mahasiswa baru dengan cara-cara yang bikin geleng-geleng, tapi berdalih pendidikan karakter. Basi banget!
Jadi, jangan heran generasi yang lebih tua biasanya merasa generasi mereka lebih baik. Sungguh ini hal yang kocak sekali. Asli.
Para manusia yang tumbuh di zaman sebelum sekarang sering menyebut generasi Z mudah sekali mengeluh dan rapuh. Dengan hanya sedikit kasus, orang-orang langsung menyamaratakan, kemudian menghakimi generasi Z kebanyakan drama.
Mereka menganggap kehidupan generasi Z tak seberat kondisi-kondisi mereka dulu. Mereka merasa generasi mereka lah yang kehidupannya paling berat dan generasi stroberi yang paling mudah hidupnya karena kemajuan teknologi.
Sebentar. Mereka menganggap generasi stroberi penuh keluhan, rapuh, dan penuh drama, tapi anggapan mereka bahwa generasi mereka lah yang paling berat itu bukannya malah menunjukkan drama juga?
Lha kok malah mereka yang curhat? Ehem. Drama kok teriak drama.
Lagian, apa sih untungnya membandingkan generasi ini dan generasi itu? Pemenangnya bakal jadi komisaris gitu?
Mikir!
Beda Tantangan
Setiap generasi memiliki tantangan kehidupannya masing-masing. Zamannya udah beda, bosku!
Keluhan utama generasi sebelum generasi Z umumnya karena teknologi yang dipakai sudah berbeda. Lagipula, itu bermasalah sekali. Generasi mereka juga bakal diolok oleh generasi sebelum mereka lagi.
Mau ngelacak begitu terus sampai manusia bikin api dengan batu?
Setiap generasi memiliki tantangan yang berbeda-beda. Teknologi di masa lampau memang tak secanggih sekarang. Dulu tidak ada internet, sekarang ada. Media sosial pun baru ada dua dekade terakhir. Justru, tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi lah yang aneh.
Ya, masa udah ada laptop dan printer, masih harus tetep pakai mesin tik?
Sudah ada teknologi yang namanya handpone, masih berkenankah dikau berkomunikasi lewat surat ataupun merpati pos?
Artinya, jelas. Setiap generasi memiliki permasalahan dan tantangannya tersendiri. Tentunya, perlu cara yang berbeda dalam mengatasinya. Tidak bisa disamaratakan, dan sudah waktunya berhenti mencangkokkan kenangan pada siapa pun.
Baca Juga: Efek Wajah Sinis di Masa Quarter Life Crisis
Kalian Berharga
Jadi, wahai generasi Z, jangan percayai label-label soal generasi yang mudah mengeluh, rapuh, lemah, maupun mudah hancur. Itu semua soal mindset kok.
Kalian sudah selangkah lebih maju memahami kesehatan mental. Teruslah berusaha memvalidasi setiap perasaan. Apa pun bentuk emosi itu tidak ada yang salah. Yang bisa salah adalah cara pengekspresian.
Memang dibalik buah stoberi yang cantik, menarik, dan menggiurkan, ada potensi mudah hancur. Namun, hancur di sini bukan semata karena stoberi itu sendiri. Ada peran dari luar juga.
Di tangan yang salah stroberi bisa mudah hancur dan membusuk. Sebaliknya, stroberi yang berada di tangan yang tepat, stroberi bisa lebih cantik, menarik, dan mahal.
Sadari, kalian sungguh berharga. Pilih dan temukan orang-orang yang bisa membantu agar terus bertumbuh. Bukan orang-orang yang malah membuatmu layu dan hancur.
Baca Juga: Merayakan Hal-hal yang Tak Mudah