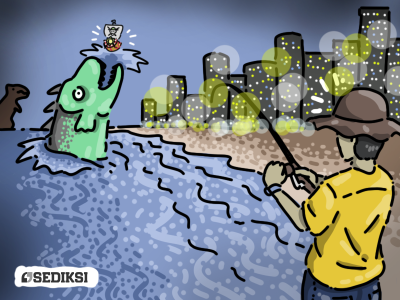Di desa, dimana kehidupan agraris tampak nyata; membuka lahan, membajak, menanam, hingga tiba saatnya memanen adalah imaji yang bersahaja nan syahdu sekaligus menghadirkan sukacita bagi para petani. Entah berasal dari desa atau tidak, sebagian dari kita mungkin akan sepakat kalau kehidupan semacam itu begitu menentramkan.
Kalau tidak, mustahil gaya hidup slow living misal, jadi sangat populer dan didambakan banyak orang. Tak sedikit orang yang bekerja keras di usia muda dengan menjadi budak korporat, sabar menabung, kemudian setelah modal dirasa cukup mereka membeli sebidang tanah di desa dan menjadi petani.
Jika kamu memimpikan hal serupa, saya tidak ingin mengusik mimpi itu. Saya hanya tertarik untuk kemudian mempelajari lebih lanjut hubungan tanah dengan manusia. Terutama para petani yang entah sampai kapan, harus mati-matian tidak hanya menggarap tanah tapi juga mempertahankannya.
Ya, ada banyak kisah pemberontakan petani di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah Pemberontakan Petani Banten 1888 atau Geger Cilegon. Sartono Kartodirdjo adalah salah seorang sejarawan yang menghabiskan banyak waktu untuk mencari pangkal gejolak pemberontakan petani yang ada di tanah air.
Menurutnya, pemerasan tenaga kerja, wabah penyakit, bencana, hingga isu agama konflik merupakan sederet isu yang melatarbelakangi terjadinya konflik tanah selama ini.
Lalu apa yang membuat para petani bangkit melawan dan berani melakukan pemberontakan? Tentu tidak lain karena hubungan petani dengan tanahnya itu sendiri.
Baca Juga: Kami Tak Mau Jadi Petani Bukan Karena Gengsi
Thunda dan Samin, Sebuah Epos Kebijaksanaan
Petani, bagi Goenawan Mohamad serupa lukisan Picasso. Ia menggambar orang-orang yang sok tahu daripada penyangga tatanan pangan itu sendiri. Sementara mereka tidak tumbuh di tepi sawah. Tidak cakap membikin saluran ledeng. Kurang tahu duduk perkara yang memicu petani melakukan pergerakan sosial.
Pergolakan sosial yang tercuplik sampai penghujung abad ke-19, bukanlah sepenuhnya pigura dari imajinasi petani yang dipahat Presiden Soekarno dalam figur Marhaen. Kata Bung Karno, petani yang jumlahnya jutaan itu adalah kelompok masyarakat bawah yang hidup miskin dan melarat, oleh sebabnya harus bersatu mendalangi revolusi.
Sartono punya pandangan berbeda, ia menilik tokoh politik dan agama menjadi awal pangkal dalam tahun-tahun “kaotik” saat itu (meminjam istilah mendiang Ben Anderson). Sesungguhnya, bukanlah petani yang menjadi dalang pemberontakan. Perlawanan berkecamuk dipantik pelbagai anasir, yang sebetulnya tidak hidup dalam periferi sawah. Sekelompok orang itu hanya peduli bagaimana tumpukan guldennya menyusut, setelah digerus kebijakan kolonial. Biarpun di baris terdepan mengarak bedil bersama petani.
Perdebatan tindak-tanduk petani dalam babad pergolakan sosial akan senantiasa terjelma. Bak jamur di musim hujan. Bermunculan banyak tafsir, mengkaji asbabun nuzul pergerakan. Mengotak-atik bangunan imajinasi yang kadung terpatri dalam alam pikir. Layaknya Koloseum, tidak bisa dipugar agar tetap monumental sepanjang masa.
Terkadang pergerakan sosial dalam imajinasi kita merujuk pada wajah-wajah anarkis. Ditambah lagi stereotip petani sebagai kriminal mengitari perjuangan dalam menjaga wilayah komunenya. Prasangka demikianlah yang meredam kebijaksanaan para pejuang agraria hari ini. Sebagaimana kita memandang kerbau yang menjadi simbol bestie petani, hewan memamah biak yang hidup berkoloni di alam liar dan berguling-guling di paya-paya.
Bukan berarti kosakata liar menjadi cerminan kerbau tidak ber kebijaksanaan. Bernard Rutley, pada tahun 1975 menceritakan kisah nyata tentang Thunda, seekor pimpinan kerbau liar Afrika yang bijaksana. Di semak-belukar Afrika, Thunda piawai mengelola kebijakan agar kelompoknya selamat dari serangan singa buas dan pemburu. Ia juga membikin ciut nyali para pemuda suku Masai yang masyhur suka berperang dan berkelahi dengan binatang liar.
Pernah sekali, Maoli coba memimpin pemuda Masai untuk memburu Thunda dan kawanannya. Pertempuran berlangsung sengit. Tapi karena kekuatan dan siasat Thunda lebih tajam, mereka lelah dan kalah. Maoli terpaksa undur diri menyisakan mayat-mayat di medan peperangan.
Apa yang dilakukan Thunda dalam mengorganisir kawanannya dari gangguan luar, bukankah kebijaksanaan? Ia tidak pernah mengusik satupun suku dan kelompok satwa lainnya. Menjunjung tinggi perdamaian dan tidak pernah menyerang lebih dulu. Sekali tanah dan kelompoknya terancam, maka tanduknya lebih tajam daripada peluru dan ujung bedil, membikin musuhnya binasa tak bernyawa.
Dari situ, kita bisa menelusur renungan tentang kebijaksanaan. Masalah petani dan kerbau. Soal Thunda dan petani, keduanya berpegang teguh pada Gemah Ripah Loh Jinawi.
Jika rantai makanan bukanlah asas hukum tertinggi dalam siklus hidup, bisa jadi Thunda mengedepankan dialog. Seperti ketika menyelinap dari singa dan suku Masai, alih-alih siap tempur, Ia dan kawanannya memilih meninggalkan semak belukar yang menjadi tempatnya beranak-pinak.
Kendati Thunda dan petani berbeda dunia, padanan imaji keduanya tak boleh dinafikan. Seperti Thunda, petani sememangnya memimpikan hidup aman, tentram, dan damai. Jauh dari hiruk-pikuk kekerasan, apalagi kekuasaan.
Walau sengketa tanah sering mengancam, meski jadi penentu kekuasaan demokratis, mereka lebih risau jika bedeng-bedeng persawahan tidak dialiri dengan baik. Bahkan ketika penggusuran tanah komunal, mereka melawan dengan guyub. Sebagaimana hikayat pemberontakan petani yang nir kekerasan melawan penjajahan Belanda pada akhir abad ke-19.
Samin Surosentiko dan warga Sedulur Sikep, dua abad silam, membangun pilar perlawanan berasaskan kedamaian dan kebijaksanaan. Melawan pemerintah kolonial tanpa bedil dan baja. Menangkal tagihan pajak dan enggan memangku titah perundang-undangan birokrasi.
Berkat aksi damai itulah, menjelma imajinasi di relung hati dan pikiran perjuangan, hingga hari ini. Menitis menjadi ajaran, dirujuk pelbagai aksi perjuangan sebagai sebuah piwulang.
Hari ini kita melihat piwulang itu bekerja. Menangkal muslihat korporat mengokupasi tanah adat milik komunal. Masih ingatkah kita sebuah komidi dokumenter “samin vs semen” yang ditonton hampir jutaan orang Indonesia dan mancanegara? Karya jurnalistik bernas, memotret perjuangan warga desa yang hidup di sepanjang pegunungan karst Kendeng, Jawa tengah.
Protes-protes dilakukan dengan kebijaksanaan, jauh dari potret anarkis dan kekerasan sebagaimana sangkaan orang-orang kebanyakan. Aksi-aksi longmarch dilakoni pelbagai unsur warga dan aktivis.
Serangan telak ditembakkan kepada pialang korporat yang bersembunyi dibalik hukum. Tak dinyana, perjuangan dimenangkan dalam meja persidangan. Akhirnya, kemenangan petani diraih sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Barangkali, Thunda dan Samin punya cara sendiri membangun imajinasinya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa tahu imajinasi Samin, jika kita tak pernah menangkar benih di atas pukul dua belas siang. Lebih paham siasat cerdik kawanan Thunda membentuk lingkar pertahanan dari serbuan pemburu, jika kita tak pernah menelusur semak-belukar.
Tampaknya orang merasa pintar menerawang imaji petani hanya dari bilik griya-griya tradisional desa wisata. Kita barangkali seperti itu?