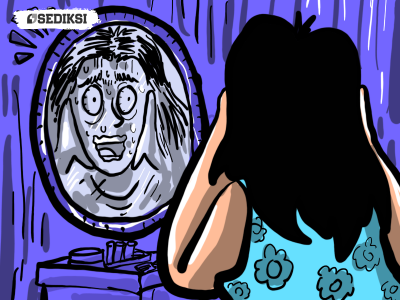Hai sobat krisis, kalau kamu pernah sebal membaca artikel-artikel di internet soal fase Quarter Life Crisis (QLC), kamu tidak sendirian. Saya pernah mengalami dan jengkel dibuatnya.
Pernyataan-pernyataan ini saya temui saat membaca artikel terkait fase Quarter Life Crisis di internet, misalnya, “kamu terlalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain”. Atau yang bernada seperti, “kamu terlalu banyak bermain sosial media”.
Artikel-artikel di internet kerap mengulas penyebabnya dengan memusatkannya pada mereka yang sedang mengalaminya. Mereka cenderung mengabaikan bahwa Quarter Life Crisis bukanlah kemauan kita dan bukan kita penyebabnya.
Sekiranya kamu sedang berada dalam fase Quarter Life Crisis, sekali lagi, kamu tidak sendirian. Beberapa momen ini kira-kira menggambarkan bagaimana keadaan memaksa orang mengalami Quarter Life Crisis.
Pemicu Momen Pelik di Fase Quarter Life Crisis
1. Fresh Graduate: “Cari kerja gampang, yang susah dapatnya bos!”
Saya cukup yakin bahwa momen ini telah dialami oleh banyak orang. Ribuan lulusan SMK yang digadang-gadang siap kerja, maupun lulusan perguruan tinggi berbondong melamar pekerjaan. Memang benar adanya bahwa selain banyak lulusan, banyak juga lowongan yang tersedia.
Tapi gimana ya, dari deretan persyaratan selalu ada syarat yang siap menjegal langkah semangat dari para fresh graduate ini: telah berpengalaman. Syarat itu agaknya bertolak belakang dengan semangat memberi kesempatan kerja bagi lulusan baru.
Bagaimanapun, syarat itu berputar-putar belaka: untuk bekerja, kita butuh pengalaman; untuk punya pengalaman, kita butuh bekerja. Perusahaan-perusahaan, yang tujuan mereka mengakumulasi kapitalnya, mau bayar orang tanpa pengalaman?
Lebih gede resikonya daripada untungnya. Merekrut pekerja siap pakai jelas lebih menguntungkan. Eh, jangan bilang kamu masih mikir kalau itu simbiosis mutualisme?!
2. Punya Kerja Sih, Tapi Gak Cukup untuk Subsisten
Tantangan lain yang kerap ditemui fresh graduate, bisa dapat kerja tapi gajinya kelewat mepet atau malah kurang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kadang sampai ada yang harus memilih: bisa makan cukup tapi tidak bisa sewa tempat tinggal, atau bisa sewa tempat tinggal tapi kurang makan.
Sayangnya banyak orang yang menganggap kondisi ini sebagai pilihan logis untuk menyelamatkan para pencari kerja dari bayang-bayang pengangguran. Padahal disebut pilihan pun tak pantas, ya mau gak mau jalani saja pekerjaan bergaji tak manusiawi ini (sambil kerja dobel di tempat lain mungkin), daripada disebut kufur nikmat kan?
Kalau masih ngotot ini pilihan logis, coba tengok kawan-kawan guru honorer yang harus masuk dan mendidik anak-anak tiap hari, tapi gaji bulanannya di bawah angka 300 ribu, deh. Gimana?
3. Punya Kerja Gaji Lumayan, Tapi Beban Kerja Berlipat Ganda
Bukan hanya Munir yang berlipat ganda, beban kerja juga punya kemungkinan yang sama. Momen ini terlihat jelas berbeda dari momen sebelumnya. Dari segi gaji ya memang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan mungkin lebih. Tapi apa bedanya kalau beban kerjanya juga meningkat berlipat ganda?
Momen ini bisa bikin orang-orang stres karena pekerjaan, atau bahkan sakit. Mengeluarkan banyak uang buat menghibur diri tampak masuk akal, tetapi nggak menyelesaikan pekerjaan.
Singkatnya, orang-orang nggak bisa kabur dari kenyataan. Itulah wujud dari syarat “Mampu bekerja di bawah tekanan” yang ada di lowongan pekerjaan yang dianggap wajar oleh banyak orang.
Pekerja kantoran maupun pekerja lepas berpeluang besar untuk mengalami momen ini. Apalagi saat work from home seperti saat ini kan? Jika kamu tak mampu lagi menyelesaikan pekerjaanmu, tak masalah bagi bos untuk memecat. Sebab ia punya banyak cadangan.
Pada akhirnya, kesimpulan dari gaji cukup bagi pekerja di level rendah – selain untuk mengganti tenaga agar dapat bekerja di hari esok, adalah untuk membeli ketenangan hidup dan kesehatan. Atau ada hal lain yang kamu rasa terbeli dari dirimu?
4. Pemaksaan Minat Belajar dan Pekerjaan
Kita bisa dengan mudah menemui anak-anak yang dipaksa untuk belajar ini itu oleh orang tuanya, atau dipaksa harus bekerja di bidang tertentu kemudian mengalami kebuntuan dan tidak terhubung dengan yang mereka jalani.
Kondisi ini biasanya terjadi karena pihak pemaksa – biasanya orang tua atau keluarga, memiliki kuasa yang lebih besar dan tidak bisa dilawan oleh pihak yang terpaksa.
Alasannya bermacam-macam: karena pihak pemaksa yang membiayai pihak terpaksa, karena orang tua tau apa yang terbaik untuk anaknya, hingga menjaga martabat keluarga di masyarakat. Layaknya bom waktu, stres yang dipendam akibat selalu menjalani hal di luar minatnya akan meledak.
5. Belum Lulus Kuliah Saat Orang Sepantaran Sudah Bekerja
Kondisi yang pedih ini hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa yang masa studinya lebih dari 4 tahun. Merasa tertinggal dan terus diperbandingkan dengan sepupu, tetangga, saudaranya tetangga, tetangganya saudaranya tetangga yang sudah bekerja.
Kuliah lebih dari 4 tahun lebih sering disebut denga kuliah lulus molor oleh banyak orang. Tapi bagaimana bisa dibilang molor, kalau proses yang dilalui setiap mahasiswa berbeda-beda, terutama saat pengerjaan tugas akhir. Apa yang menjadi standar molor dan tidak molor?
Kita tahu, bahwa kelancaran proses perkuliahan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhinya: kemampuan mahasiswa itu sendiri untuk mengelola dirinya dan memahami kompleksitas penelitiannya, tenaga pengajar dan/atau pembimbing tugas akhir, serta tenaga administrasi kampus. Satu saja dari tiga hal itu tersendat, nasib kuliah dipertaruhkan.
Setiap mahasiswa mengalami hambatannya masing-masing, Namun yang sering terjadi, para mahasiswa berstatus legenda ini langsung dicap pemalas, tanpa mau membantu masalah apa yang membuat mereka terhambat dan menjadi malas. Memang, lebih gampang nyelathu, kok.
6. Belum Nikah Atau Punya Anak Saat Orang-orang Segenerasi Telah Melaluinya
Populasi dari kelompok ini gak sedikit, lho. Begitu kerasnya ejekan dan tekanan kepada mereka, sampai-sampai kita mudah menemukan orang-orang yang mengejek dirinya sendiri sebelum diejek orang lain.
Ejekan dan tekanan itu mengaburkan berbagai penyebab yang membuat orang-orang tak kunjung menikah atau punya momongan, seolah-olah menikah dan punya anak adalah fase terakhir yang mesti dicapai dalam hidup ini. Masalah ekonomi, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, merawat anak dan lainnya seolah tak pernah ada di dunia ini.
7. Hidup di Tengah Masyarakat yang Mengabadikan Momen-momen di Atas
Momen-momen di atas adalah sedikit dari momen yang dapat memicu Quarter Life Crisis dan dapat dianggap sebagai masalah receh bagi orang lain. Namun kita tidak sedang berbicara betapa lemahnya mental orang-orang yang mengalami stres dengan berbagai pemicu.
Kita juga sedang tak berbicara soal seseorang yang terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain, pemalas, kurang usaha ataupun kurang bersyukur. Sebab ia tak akan membanding-bandingkan jika tak ada standar yang diamini.
Sekalipun kita menolak standar tersebut, kita tetap hidup di dalamnya. Mau tak mau harus diakui bahwa kondisi sosial, ekonomi dll di zaman ini memang nyata dapat menyebabkan permasalahan serius terhadap kesehatan mental seseorang.
Tragisnya, saat seseorang mengamini nilai-nilai sosial yang eksis saat ini secara buta, saat itu pula dirinya akan terjerumus dalam perputaran krisis tanpa ujung. Inilah momen inti dari pemicu fase Quarter Life Crisis.
Saat berbagai momen pemicu terus dianggap tak bermasalah dan para targetnya terus hidup di dalamnya maka krisis ini semakin lama akan menjadi wajar dialami oleh orang-orang di usia 20-30-an. Padahal, seperti gejala mental lainnya, fase Quarter Life Crisis lebih baik dicegah daripada harus mengobati.
Tapi bukannya mencegah, masyarakat kita justru sedang mengabadikannya. Misalnya lewat seminar kewirausahaan, seminar-seminar motivasi yang disampaikan oleh ‘orang sukses’, juga seminar-seminar nikah muda yang beberapa tahun terakhir sedang laku di pasar.
Para pemateri itu tak jarang mengaburkan berbagai faktor dasar yang menyebabkan seseorang bisa ‘sukses’ juga menyempitkan arti kesuksesan pada aspek finansial saja.
Jadi, untuk penyelenggara seminar-seminar motivasi atau nikah muda, daripada menyajikan materi kunci sukses yang sulit diimplementasikan dalam kehidupan nyata dan mengajak nikah muda tapi tak tau bagaimana menyelesaikan permasalahan pasca-pernikahan, sebaiknya habiskan anggaran dana untuk riset dan studi yang mendukung perubahan sosial lebih baik.
Apakah kamu juga merasakan hal yang sama di fase quarter life crisis ini? Saya bersyukur kalau kita ternyata se-frekuensi.