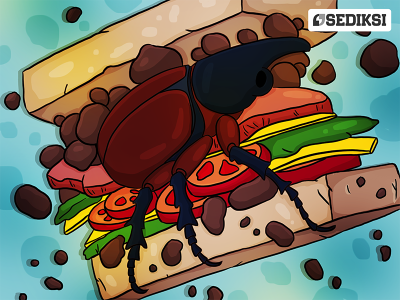Gemes tak kepalang, rasanya ketika membaca “Belajar Agama ala Nietzsche dengan Cara Menjadi Ateis” garapan Fransiskus Sardi. Langsung saja saya bilang, tulisan ini nggak jelas! Kek kenapa harus jadi ateis njir?
Saat membaca hingga akhir tulisan pun, saya masih dongkol bin heran; kok bisa filsafat Nietzsche dijadikan “kompas untuk kembali memahami agama dengan benar”, kok bisa “warta kematian Tuhan menjadi jalan pulang pada nilai substansial agama”?
Saya tak akan punya keberatan sama sekali jika pada akhirnya Bung Sardi ini secara jernih menerangkan perlunya menjadi ateis dalam belajar agama. Tapi tidak, dan itulah yang jadi masalah. Apa maksud klaimnya, coba?
Lagian, siapapun tau kalau “a-” dalam kata “ateis” berarti tanpa, dan “teis” berarti Tuhan. Secara sederhana, nalar anak SD pun bisa menebak, bahwa ateis berarti orang yang tak bertuhan. Nah loh, jadi bagaimana maksudnya belajar dan menghayati agama tapi malah dengan tidak bertuhan dan tidak beragama?
Baca Juga: Nietzsche Pun Seorang Hipster
Kengawuran yang Bikin Saya Dongkol!
Kedongkolan ini membuat saya akhirnya membaca buku Gaya Filsafat Nietzsche karya Setyo Wibowo tahun 2004. Ini demi mengerti betul apa yang terkandung di dalamnya, biar saya tak salah tuduh dan malu di kemudian hari. Barangkali saya saja yang sotoy, kan?
Pada tulisan, Bung Sardi menuliskan, “Artinya Nietzsche gila, terbelah, berkepribadian ganda, bipolar.” Kemudian, mari bandingkan dengan tulisan Romo Setyo yang menjadi rujukannya, “Nietzsche adalah gila, terbelah, split, berkepribadian ganda, dan semacamnya,” (Wibowo, 2004, hlm. 281);
Nggak ada kata “bipolar” tuh–meskipun memang beberapa orang menuduh Nietzsche bipolar siih. Terus terang, saya jadi curiga Bung Sardi ini salah memaknai bipolar sebagai sebutan yang sama untuk kepribadian ganda, sebagaimana umumnya disalahpahami ckckck.
Keberatan saya selanjutnya adalah dengan klaim “semua agama pastilah mengajarkan kebaikan”. Saya tak berniat memperdebatkan klaim barusan. Hanya saja, klaim itu terasa sangat mengganjal dan naif jika saya ingat sisa ajaran Nietzsche. Klaim tersebut sebetulnya bertentangan dengan metaetika Nietzsche, apalagi kalau Bung Sardi betulan mau konsisten pakai perspektifnya.
Baca Juga: Tidak Ada Thunda dan Samin Hari Ini
Kalau kita tengok metaetika Nietzsche, kita malah dapati bahwa, “tidak ada fenomena moral, yang ada hanya interpretasi moral atas fenomena-fenomena” (Nietzsche, 1968, bag. 258). Artinya, nilai kebaikan itu gak betulan ada. Itu cuma karangan kita.
Nilai-nilai kebaikan yang ada dalam ajaran agama, filsafat, politik, atau bahkan ateisme sekalipun muncul karena kebutuhan kita akan pegangan hidup. Pegangan itu harus dianggap pasti dan memberi arahan “kamu harus”.
Masalahnya, bagi Nietzsche, sikap manja seperti ini mencirikan kehendak diri yang cacat dan lemah. Ia bergantung pada orang lain untuk mengutuhkan dirinya, seperti bocah yang tak tau apa yang dia mau (Wibowo, 2004, hlm. 202–204).
Dalam tulisannya, Bung Sardi juga menjabarkan sikap manusia modern saat dihadapkan pada warta kematian Tuhan. Sayangnya, penjabarannya bermasalah.
Baca Juga: Cara Mati Ketawa ala Milan Kundera
Perlu saya tekankan, “ya” dan “naif” harusnya terhubung sehingga menjadi “ya-naif”. Gabungan kata ini bermaksud sikap yang meng-iya-kan kematian Tuhan secara naif.
Begitu pula “tidak-naif”: ia berarti sikap yang men-tidak-kan kematian Tuhan secara naif. Jadi, sikap ya-naif bukanlah sikap yang betulan naif dan sikap tidak-naif juga bukan sikap yang bestari. Kalau keduanya ditulis tanpa tanda hubung, nyaris pasti bikin pembaca salah paham.
Alih-alih bersikap naif, Nietzsche mendakwahkan sikap iya-sekaligus-tidak. Maksudnya adalah sikap cermat yang mengambil jarak dan berhati-hati.
Dakwah Nietzsche adalah: realitas sepatutnya diterima apa adanya, termasuk bahwa Tuhan telah mati. Tapi, jangan putus asa ataupun anarkis tanpa arah karenanya. Tetap waspadalah di antara keduanya. Jadi sebetulnya, Nietzsche ini ateis-sekaligus-anti-ateis. Semoga cukup jelas.
Daripada makin pusing, saya sudahi saja ghibahan saya tentang tulisan orang. Mending kita cari hikmahnya saja, yuk.
Beragama Ya Beragama Saja
Filsafat Nietzsche sudah terkenal susah dipahami. Sudah sewajarnya kita berhati-hati saat dihadapkan hal sulit. Kalau tak punya niat belajar yang mantep, mending belajar hal lain.
Menurut saya, mempelajari pemikiran Nietzsche secara setengah-setengah, khawatirnya, cuma bakal menimbulkan sentimen, penyembahan buta, bahkan kesesatan yang betulan. Sekali lagi, waspadalah!
Jangan salah kira pula. Saya tak bermaksud untuk melarang pembaca untuk mengkaji Nietzsche. Saya malah percaya, kalau kita bisa mengambil hikmah dari apapun.
Kalau begitu, mari berwaspada juga pada ajaran Nietzsche. Katanya, manusia modern telah membunuh Tuhan. Di era pascamodern ini, mungkin Nietzsche akan bilang kalau yang tersisa dari Tuhan hanyalah tulang belulang-Nya. Tapi kan itu tak berarti kita tak bisa menghidupkannya lagi, wong katanya pernah begitu.
Kalau kita ingat konteks warta kematian Tuhan yang dibawa si orang sinting, ini kan berlatar di Eropa. Belum tentu loh hal yang sama terjadi pula dalam sukma umat beragama di Indonesia.
Justru, barangkali Tuhan belum dan tak pernah mati. Tuhan, dalam pengertian seluas-luasnya, dapat selalu hidup dalam praktik keseharian kita yang lurus. Kita boleh saja menjadikan dugaan ini sebagai pegangan, tak peduli dalam ragam yang bagaimana. Kenapa tidak, iya kan?
Lalu bagaimana praktik yang lurus itu? Saya yakin Nietzsche juga akan menyerahkan persoalan ini pada Anda, pada pribadi yang jatuh bangun melampaui dirinya, pada pribadi yang menggelorakan nilai-nilai pribadinya.
Terakhir, biarlah saya menyitir tanggapan Romo Setyo atas Nietzsche yang bagus, ”Tetapi bukankah Tuhan-kristiani, Tuhan-metafisis tersebut masih bisa dikehendaki secara orang kuat? Dikehendaki secara kuat Tuhan seperti itu akan dihayati sebagai gerak pewahyuan yang tak pernah berhenti. Tuhan menjadi daya dorong manusia untuk senantiasa berziarah mencari-Nya tanpa pernah berpretensi bisa menangkap-Nya secara fiksatif dan antropomorfistik belaka” (Wibowo, 2004, hlm. 359).
Sudah, sudah! Pokoknya, selama toleransi dirajut ketat, beragama ya beragama saja.
Baca Juga: Agama Netizen Adalah Agama Mie Instan