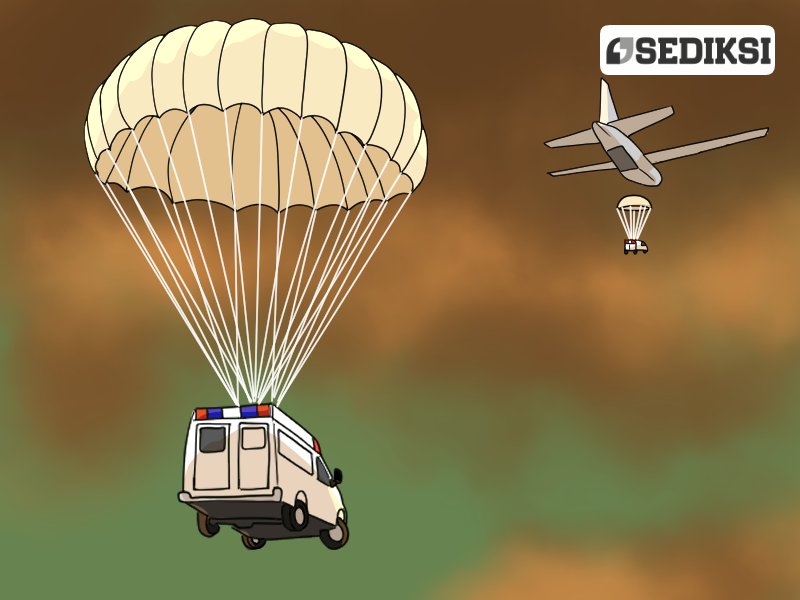Program makan siang gratis semakin ramai dibahas, apalagi setelah hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini memperlihatkan bahwa paslon pengusungnya hampir pasti akan keluar sebagai pemenang dalam Pilpres tahun ini.
Meskipun calon kuat pemimpin kita 5 tahun ke depan ini juga menyampaikan berbagai program lainnya pada masa kampanye kemarin, makan siang gratis terlihat yang paling dominan dibahas.
Padahal terdapat beberapa program lain yang sebenarnya tidak kalah megah, tidak kalah ambisius, serta tidak kalah kontroversialnya dengan makan siang gratis. Salah satunya ialah yang berkaitan dengan persoalan kesehatan nasional.
Mungkin banyak dari kita yang masih ingat dengan rencana memperbanyak fakultas kedokteran demi menambah jumlah dokter yang muncul pada debat capres terakhir.
Di situ, salah satu calon melihat bahwa akar permasalahan kesehatan di Indonesia adalah kurangnya jumlah dokter. Beliau kemudian menawarkan solusi, yaitu pembangunan ratusan fakultas kedokteran negeri baru serta rencana untuk mengirim anak-anak Indonesia belajar ilmu kedokteran ke Eropa dan Amerika
Dokter memang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam penghitungan kelayakan hidup, ketersediaan dokter per-jumlah jiwa juga dihitung.
Tapi, apa benar solusi tersebut dapat menjawab akar permasalahan kesehatan Indonesia yang sebenarnya justru lebih rumit dari sekadar ketersediaan jumlah dokter?
Biaya Pendidikan Kedokteran Masih Tinggi
WHO sendiri mencanangkan target capaian rasio sebanyak 1 dokter per 1000 jiwa. Sementara di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya terdapat 160.000 dokter, yang kebanyakan terpusat di wilayah barat Indonesia.
Guna mengejar rasio yang masih di bawah 1:1000 tersebut, pembukaan sekolah kedokteran terlihat seperti solusi yang masuk akal. Di Indonesia sendiri, sejauh ini, terdapat 90 lebih fakultas/sekolah kedokteran di seluruh universitas negeri.
Jumlah ini sudah termasuk beberapa universitas negeri yang baru saja membuka fakultas kedokteran mereka, dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).
Fakultas kedokteran universitas negeri memang menjadi pilihan populer pelajar di Indonesia, dengan asumsi biaya pendidikan yang jauh lebih murah dibanding universitas swasta. Yaa, meskipun yang namanya fakultas kedokteran mau di mana pun juga hampir pasti mahal, sih, bagi kebanyakan orang.
Belum lagi jika kita berbicara mengenai jalur masuk fakultas kedokteran yang semakin membuka kemungkinan memperbanyak kuota dari jalur mandiri. Selain UKT-nya mahal, uang pangkalnya pun tidak jarang menyentuh angka ratusan juta.
Ini juga belum mencakup kebutuhan tambahan seperti untuk praktik dan alat peraga yang tidak jarang harus ditanggung oleh peserta didik.
Selain soal biaya, ketersebaran sekolah-sekolah kedokteran milik negara ini nyatanya juga masih terpusat di Jawa saja. Ditambah lagi soal fasilitas, di mana tidak semua fakultas kedokteran negeri sudah memiliki rumah sakit pendidikan sendiri.
Berkaca dari hal-hal di atas, sang capres sendiri tidak menjelaskan lebih terperinci mengenai rencana menambah lebih banyak fakultas kedokteran ini.
Belum jelas skema seperti apa yang akan digunakan ketika membangun ratusan fakultas kedokteran baru sembari memastikan sekolah kedokteran menyediakan akses yang ramah bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
Masih Soal Akses
Salah satu hal yang dijadikan dasar rencana penambahan jumlah dokter ini sendiri ialah cerita mengenai sebuah rumah sakit di Atambua yang hanya memiliki satu dokter. Tapi, kalau dipikir-pikir, mengapa fokusnya tidak diarahkan ke persoalan akses alih-alih hanya melihat jumlah ketersedian dokter di sana.
Kita perlu memahami seberapa mudah dan murah akses ke daerah tersebut. Akses di sini tidak hanya menyangkut masalah distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan, fasilitas pendukung termasuk akses listrik agar peralatan medis dapat berfungsi, serta akses bagi pasien jika perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar.
Akses juga menyangkut keinginan sang dokter untuk ditempatkan di daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) serta soal kesejahteraan, termasuk upah para tenaga kesehatan yang mengabdikan diri di daerah tersebut.
Pentingnya Pendekatan Promotif serta Preventif
Gagasan besar ini pada dasarnya hanya berkutat pada pendekatan kuratif dan luput pada dua tahapan lain yang jauh lebih penting, yaitu promotif dan preventif.
Penentuan kebijakan kesehatan yang hanya mengambil pendekatan kuratif seharusnya menjadi solusi akhir dari alur penyelesaian permasalahan kesehatan.
Kebijakan yang harus ditempuh seharusnya meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat luas terkait pemenuhan asupan gizi dan makanan sehat, termasuk di dalamnya intervensi pemerintah dalam menjamin upah layak bagi masyarakat dan menjamin akses makanan bergizi yang terjangkau.
Kebijakan kesehatan nasional juga harus berfokus pada peningkatan kesadaran terkait pencegahan penyebaran wabah dan penyakit.
Intervensi pemerintah juga diperlukan dalam memastikan tempat tinggal masyarakat sudah memenuhi persyaratan hunian sehat, akses toilet yang layak dan bersih, hingga detail seperti regulasi pengaturan kadar gula dalam peredaran makanan di pasar.
Di sinilah seharusnya fokus pemerintah lebih diperbesar guna menjawab permasalahan kesehatan yang tidak kunjung usai. Pengalihan fokus kebijakan kepada dua pendekatan ini juga berarti bahwa jumlah dokter dan fakultas kedokteran tidak serta merta menjadi jawaban.
Baca Juga: Pinjol ini Membunuhku: Cerita dari ITB
Upaya ini juga melibatkan tenaga kesehatan lainnya yang bergerak di bidang penyuluhan dan edukasi. Terdapat ahli gizi, ahli kesehatan, epidemiolog, ahli K3, hingga bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang mampu menjawab dan ikut terlibat dalam proses ini.
Tenaga kesehatan ini, seperti bidan, juga sudah lama terlibat dalam upaya edukasi dan penyuluhan informasi kesehatan terutama pencegahan stunting di daerah-daerah terpencil.
Rasanya agak miris jika pemerintah sendiri terkesan menganaktirikan dan mengabaikan kontribusi mereka dan memberikan kredit kepada satu profesi saja.
Dengan melibatkan tenaga kesehatan sebagai promotor pola hidup sehat hingga edukator pencegahan penyakit menular, fasilitas kesehatan juga tidak akan hanya berfungsi sebagai tempat berobat, namun juga sebagai tempat edukasi dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
Optimalisasi fasilitas kesehatan ini tidak akan tercapai jika pemerintah masih berorientasi pada aspek pengobatan saja.
Peningkatan alokasi sumber daya dalam pendekatan ini sangat penting mengingat target dari perbaikan kebijakan kesehatan bukan hanya menaikkan angka harapan hidup, namun juga meningkatkan umur harapan hidup produktif (healthy life expectancy).
Indonesia masih cukup tertinggal dalam hal ini, terutama karena meningkatnya beban penyakit tidak menular yang sebenarnya dapat ditekan melalui tindakan preventif dan edukasi pola hidup sehat.
Jangan Asal-Asalan
Meskipun kurang sepakat dengan program yang berfokus pada menambah jumlah dokter ini, namun jika pada akhirnya langkah tersebut yang ditempuh pemerintah, tolong jangan asal-asalan.
Kualitas dan mutu pendidikan serta fasilitas penunjang yang dapat diakses oleh semua calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya sangat perlu diperhatikan
Regulasi juga harus dimulai dari hulu: biaya pendidikan hingga fasilitas penunjang kegiatan belajar dan praktik. Calon dokter dan tenaga kesehatan lain tidak akan dapat bertugas dengan maksimal jika harus ditempatkan di tempat tanpa akses listrik dan akses obat-obatan.
Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati juga sudah seharusnya dijadikan sebagai arah perumusan kebijakan kesehatan secara serius. Optimalisasi posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya juga penting dalam melakukan pendekatan pencegahan.
Mungkin, jargon “hilirisasi” lebih cocok digunakan untuk menjawab permasalahan menahun di Indonesia, termasuk masalah akses pelayanan kesehatan layak yang masih menjadi hutang negara kepada warganya.