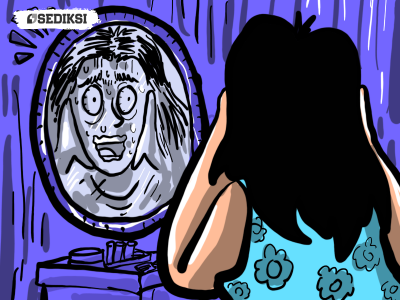Perempuan dan keberdayaan. Saat mendengar dua kata itu hal yang pertama kali terlintas di kepala saya adalah bagaimana perempuan harus bisa ini itu dengan embel-embel ‘berdaya’.
Publik begitu keras menuntut perempuan. Perempuan diharapkan bisa menjadi ahli dalam berbagai hal. Ia selalu dituntut untuk bisa menjadi sosok yang luar biasa.
Hanya karena perempuan diharapkan dapat menjadi madrasah pertama dalam keluarganya, ia pun menanggung beban harapan dari lingkungan sosial. Perempuan selalu diharapkan untuk menjadi makhluk yang sangat berdaya di dunia ini.
Tak hanya harus mampu mengasuh dan mendidik anak, perempuan juga diminta mampu memastikan pemenuhan gizi anak. Perempuan juga dituntut untuk jadi sosok yang bisa memastikan kenyamanan keluarganya.
Perempuan pula yang biasanya disalahkan jika ada hal yang tak beres dalam keluarganya. Saat anak melakukan hal yang tidak disukai lingkungan sosial, ibunyalah yang biasanya akan terlebih dulu mendapat teguran. Bahkan jika suami berselingkuh, perempuan pulalah yang seringnya dituduh serba kurang dalam menjadi pendamping.
Salah Kaprah Tentang Makna Berdaya bagi Perempuan
Keberdayaan perempuan adalah topik yang selalu menarik untuk menjadi sebuah jargon. Dalam kurun waktu lima tahun ini saja, tak terhitung berapa banyak organisasi serta instansi yang menggunakan jargon “perempuan berdaya” untuk diterapkan dalam berbagai kegiatan.
Namun, apakah semua penyelenggara kegiatan yang menggunakan tema perempuan berdaya benar-benar peduli dengan keberdayaan perempuan? Apakah jadi perempuan berdaya itu seperti wanita karier atau ibu rumah tangga sambil berkarier atau ibu rumah tangga seutuhnya?
Pertanyaan itu memang hanya sebuah retorika. Tanpa perlu kita kuliti satu demi satu, ya, pasti ada saja komunitas yang menggunakan jargon perempuan berdaya sebagai strategi marketing belaka.
Hampir setiap kegiatan dengan tema pemberdayaan perempuan sukses membuat perempuan, terlebih kaum ibu, mendekat. Ya, siapa yang tak ingin ikut menjadi perempuan berdaya? Saya yakin, perempuan masa kini pasti resah ketika ia merasa menjadi bagian dari kelompok perempuan yang kurang berdaya.
Sayangnya, dari banyaknya kegiatan tentang perempuan berdaya, yang dibahas hampir selalu tentang produktivitas, pencapaian, hingga pendapatan tambahan. Semua berujung pada pemahaman bahwa perempuan berdaya hanyalah perempuan yang berhasil melakukan upscale pada dirinya.
Intinya, perempuan berdaya berarti bisa menghasilkan uang sendiri sambil mengurus urusan domestik seperti kehidupan rumah tangga. Saya pribadi agak terganggu dengan konsep ‘keberdayaan’ seperti ini!
Memaknai Konsep Berdaya yang Keliru
Perempuan berdaya di mata publik adalah perempuan yang menghasilkan sesuatu dalam wujud terukur yang bisa terlihat dalam keterbatasannya. Hal ini pun akhirnya membuat bentuk keberdayaan perempuan tak jauh dari sesuatu yang bernilai material.
Padahal, terkadang, pengertian berdaya bagi seorang ibu hanyalah sesederhana bisa bangun dari tempat tidur lalu merawat keluarganya dengan penuh cinta. Tapi apakah hal itu mendapat apresiasi dari publik sebagai bentuk keberdayaan? Tentu saja tidak.
Jangankan apresiasi, disorot pun tidak. Keseharian seorang perempuan dalam melakukan rutinitasnya hanya akan dipandang sebelah mata sebagai hal normal, tak ada istimewanya. Perempuan dan harapan keberdayaan selalu menjadi isu yang terkadang justru membuat perempuan merasa tertekan hingga sunguh-sungguh menjadi tidak berdaya.
Saya sering mendapat cerita dari sesama perempuan tentang rasa kepayahan. Hal itu terjadi karena ia berpikir bahwa segala yang dilakukan sangat monoton dan tidak berguna. Beban itu muncul hanya karena mereka merasa belum mencapai hal-hal yang dianggap bernilai prestisius.
Padahal di era melek kesehatan mental ini, kita tahu bahwa bisa bangun, memasak, menyiapkan anak pergi ke sekolah, kembali menonton drakor favorit, membersihkan rumah, mencuci, memasak lagi, lalu melanjutkan rutinitas hingga malam dan berulang 365 kali dalam setahun bukanlah suatu kesalahan.
Maafkan kalimat saya yang kelewat panjang tadi. Tidak enak jika dibaca hanya dalam satu kali tarikan napas, bukan?
Coba bayangkan kalimat itu tadi kamu lakukan setiap hari. Terasa monoton, bukan? Wajar saja jika ada perubahan emosi yang dirasakan oleh perempuan.
Terkadang terasa sangat berat dan melelahkan apalagi di masa period, saat secara fisik perempuan mengalami ketidakstabilan hormon. Tapi siapa yang peduli? Perempuan tetap diminta mampu menjalankan segala hal yang diwajibkan untuknya dalam kondisi apa pun.
Menerima Kekurangan juga Bentuk Keberdayaan
Mematahkan stigma bahwa perempuan berdaya hanyalah perempuan yang harus punya pencapaian tidaklah mudah. Saya punya seorang teman yang belum lama ini menunjukkan bahwa ia adalah perempuan berdaya justru dengan melepaskan pendidikan S2 yang sedang dijalaninya. Ia adalah seorang penyintas bipolar.
Tesis yang menjadi syarat lulus ternyata memicu banyak lesatan trauma hingga membuatnya relaps. Tentu hal ini mengganggu keseimbangan dalam keluarga kecilnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia pun akhirnya rela melepaskan gelar S2 yang sudah di depan mata.
Peristiwa yang dialami teman saya itu membuat saya memahami bahwa kadang yang disebut berdaya itu bukanlah dengan mencapai sesuatu yang bernilai prestisius menurut publik. Bahkan, berani memilih pilihan tidak populer yang dapat menyelamatkan jiwa kita pun dapat disebut keberdayaan.
Intinya, hal yang ingin saya garis bawahi dari contoh di atas adalah berdaya juga menerima kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Toh, selama ini kita hanya ingin melihat kelebihan diri sendiri. Berdamai dengan luka dan menerimanya tak akan membuat diri kita rusak. Justru hal itu yang membuat manusia menjadi lebih berdaya, tak hanya perempuan, lelaki pun juga demikian.
Piye, sih, Berdaya Iku, Lur?
Bingung-bingung soal berdaya sesungguhnya. Pie, karepe, lur?
Kenyataannya, frasa perempuan berdaya terlanjur disenangi oleh instansi dan organisasi kemasyarakatan di sekitar kita. Dan di sinilah kita semua, terjebak dalam hantu keberdayaan perempuan yang pengertiannya tak jauh dari soal punya penghasilan sendiri.
Memang tak mudah untuk membangun konstruksi baru tentang makna keberdayaan perempuan yang terlanjur melekat. Namun, sudah saatnya pengertian keberdayaan perempuan itu dikembalikan pada hal yang lebih mendasar.
Perempuan berdaya mestinya adalah perempuan yang memiliki kebebasan penuh untuk memilih jalan hidupnya. Ia tak harus menjadi sosok pahlawan super dengan beban aneka harapan dari lingkungan sosial.
Sempitnya pemahaman lingkungan sosial terhadap konsep pemberdayaan perempuan saat ini hanya akan membuat perempuan dihantui oleh tuntutan dan harapan yang semakin tinggi. Ia diminta untuk bisa mencapai aktualisasi diri agar semakin percaya diri dan tangguh.
Bagus, sih, jika masih ada bahan bakar yang cukup dalam jiwanya. Tetapi jika perempuan sudah di titik terendah, kadang-kadang bentuk keberdayaan itu hanya sekadar berani memilih untuk mengistirahatkan tubuh dan pikirannya yang lelah. Dan jika beristirahat adalah hal terbaik yang bisa kita upayakan untuk diri kita saat ini, mengapa tidak?
Pada akhirnya, menjadi perempuan berdaya bukan berarti harus menjadi seperti apa yang lingkungan sosial mau dari perempuan. Menjadi perempuan berdaya adalah menjadi perempuan yang memiliki kekuatan dan kendali atas apa yang menjadi kehendaknya.
Bahkan jika kehendak itu berupa keinginan untuk bebas dari tuntutan produktivitas harian. Perempuan berdaya tak hanya mereka yang serba menakjubkan. Perempuan berdaya juga definisi untuk para perempuan yang mengupayakan istirahat di hari-harinya yang sangat sibuk.
Bagaimana, sudah berdaya belum kamu hari ini?