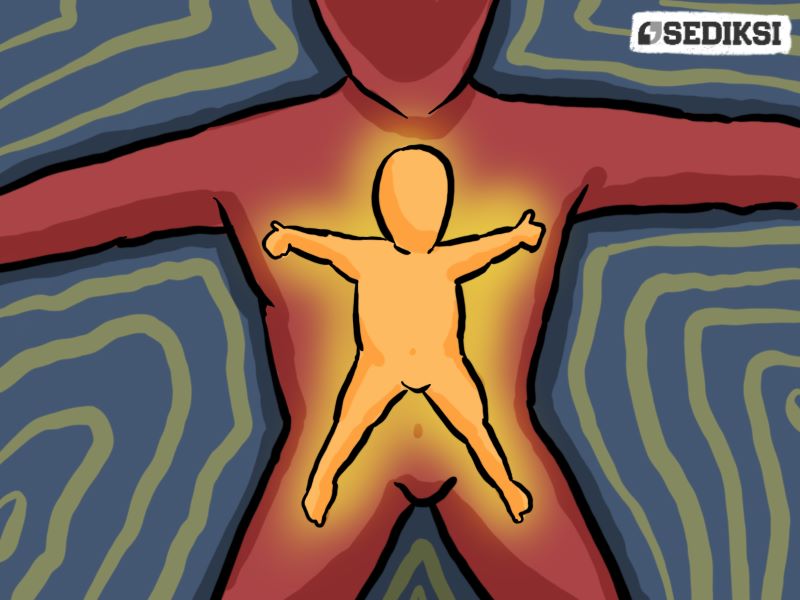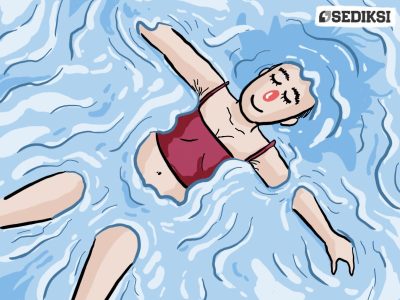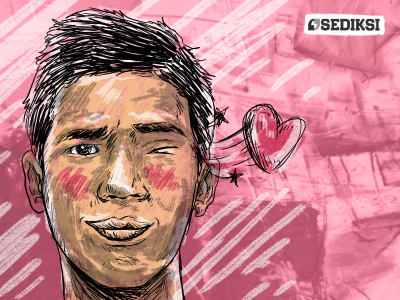Konfrontasi dengan kenangan yang tidak menyenangkan dari masa kecil bisa menjadi sangat menantang, sekaligus menyakitkan. Namun, karena sudah terlanjur berlarut, mau tidak mau aku harus siap menghadapi masa lalu yang menjadi penyebabku terjebak dalam perasaan insecure, mudah tersinggung, tak percaya diri, serta mudah merasa bersalah.
Waktu itu, aku memaksa diriku menerima realita bahwa ada pengalaman masa anak-anakku yang terluka. Tepatnya, aku mencoba berkomunikasi dengan sisi kekanak-kanakan yang biasa disebut para Gen-Z sebagai inner child.
Itu adalah proses yang sulit. Mencoba berkomunikasi dengan masa lalu traumatis yang kita miliki, bukan perkara mudah. Namun, untuk benar-benar dapat menangani luka, sudah sepatutnya kita mampu mengidentifikasi rasa sakit. Saat melakukannya, aku menangis sekeras-kerasnya, akibat menahan rasa sakit untuk waktu yang sangat lama.
Aku mulai terbiasa setelah cukup sering berkomunikasi dengan sisi kecilku. Perlahan, terjadi perubahan dalam hidupku. Bukan berarti aku sudah sembuh total, tapi setidaknya sekarang aku sudah bisa menangani lukaku dengan memberikan apa yang tidak kudapatkan semasa kecil. Diriku yang sebenarnya cuma ingin dilihat, didengar, dan disayangi.
Namun, apa yang membuat aku heran adalah bagaimana sebagian orang dengan begitu mudahnya menggunakan istilah inner child dengan salah kaprah. Menjadikan inner child sebagai tameng dalam menghadapi emosi negatif atau masalah yang mereka hadapi. Padahal, bagi mereka yang benar-benar mengalami luka batin di masa kecil, berhubungan dengan inner child bisa menjadi sangat menyulitkan.
Menurutku, ini adalah miskonsepsi tentang inner child. Orang-orang terlalu mudah mengatasnamakan inner child sebagai pembenaran atas ketidakmampuan mereka sendiri. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena mengaburkan pemahaman yang sebenarnya tentang inner child.
Inner child adalah konsep yang sangat rumit, karena melibatkan berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti emosi, perilaku, dan hubungan interpersonal. Seorang psikolog klinis, Reynitta Poerwito, menjelaskan konsep ini sebagai bagian dari diri manusia yang tetap menjadi anak-anak secara emosional dan psikologi.
Inner child terkait erat dengan pengalaman masa kanak-kanak yang memengaruhi perkembangan emosi dan perilaku kita saat dewasa. Inner child merupakan bagian dari diri kita yang masih menjadi anak secara emosional dan psikologis. Pengalaman buruk di masa kecil, baik berupa pengabaian, pemberian beban yang berlebihan, atau tuntutan yang berlebihan, bisa menyebabkan inner child terluka. Apa yang menurut kita hal biasa, bisa jadi hal yang menyakitkan bagi anak hingga membekas di ingatan hingga dewasa.
Misalnya seseorang yang memiliki kepercayaaan diri rendah, mungkin dia selalu dibandingkan oleh kedua orang tuanya semasa kecil, selalu dikritik, dan tidak pernah mendapat apresiasi atas usahanya. Contoh lain adalah ketika seseorang sulit membuat keputusan, mungkin dia selalu diatur oleh orang tuanya, tidak pernah diajak diskusi, tidak pernah ditanya, dan ketika dia membuat kesalahan dia akan dimarahi habis-habisan.
Jadi, jika seseorang mengalami suatu pengalaman buruk di masa kecil yang memengaruhi perilaku dan emosinya saat dewasa, bisa jadi dia memiliki sisi inner child yang terluka.
Masalahnya, tidak semua perasaan negatif saat dewasa itu disebabkan oleh inner child.
Ini dia permasalahan yang sering bikin greget. Ada banyak sekali orang berlindung di balik tameng inner child. Sedikit-sedikit, “menyalahkan” inner child. Padahal kenyataannya cuma tidak mampu mengendalikan emosi atau menghadapi masalah di usia dewasa. Ini sangat menjengkelkan buatku.
Inner child letaknya di masa lalu. Kalau kita tidak punya “pengalaman” yang memengaruhi tingkat emosional dan cara kita bersikap saat dewasa, maka belum tentu itu perasaan negatif kita rasakan saat dewasa disebabkan oleh luka inner child. Dan untuk mengetahui apakah inner child kita terluka, butuh proses dan peran dari profesional, bukan klaim mandiri semata.
Inner child tidak sesederhana kita yang ingin beli mainan, barang-barang lucu, boneka, atau balon, karena di masa kecil kita tidak pernah dibelikan oleh orang tua. Atau kita yang ingin sekali jalan-jalan bareng keluarga, karena kita tidak pernah melakukan itu semasa kecil. Ini sama sekali bukan inner child, ini cuma keinginan tertunda yang belum terwujud di masa kecil.
Awareness terhadap mental health satu dekade belakangan ini memang telah meningkat. Tapi, sebagaimana ‘barang’ populer lainnya, akan menjadi semakin murah dan semakin mudah disalahartikan.
Inner child adalah salah satunya. Meski populer di kalangan gen-Z, menurutku masih banyak yang belum tahu sama sekali tentang konsep ini secara pasti, sehingga terjadilah pergeseran makna. Setidaknya, ini yang saya temukan berseliweran di sosial media orang-orang. Menyebut-nyebut inner child seakan-akan hal itu patut dibanggakan.
Mengenal inner child memang baik, bahkan dianjurkan. Tapi, sejujurnya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh banyak keberanian untuk menyadari saat kecil dulu, kita tidak mendapat kasih sayang orang tua. Padahal, di sisi lain, kita tahu betul bahwa itu adalah hal utama yang menentukan masa depan anak-anak. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk akhirnya berdamai dengan itu. Makanya aku suka gusar kalau ada yang dikit-dikit bilang “inner child aku pengen boneka,” atau “inner child aku meronta-ronta.”