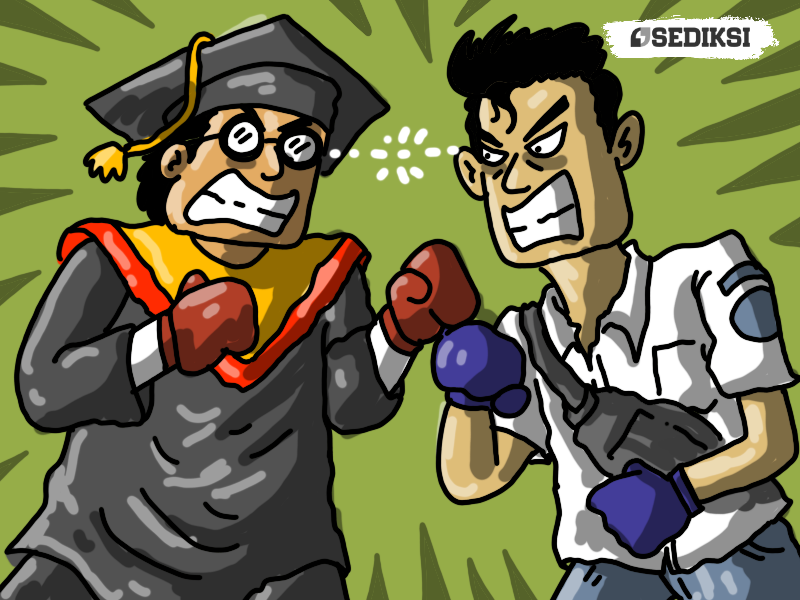Beberapa waktu lalu, salah seorang kawan saya dibuat menggerutu oleh perdebatan “sarjana vs SMA” di TikTok. Perdebatan itu sendiri muncul gara-gara ada yang salah menginterpretasikan poster mahasiswa UNSOED bertuliskan: orang miskin dilarang sarjana.
“Orang-orang lulusan SMA ini, ya, berkali-kali dibilang kuliah itu tujuannya bukan cuma cari kerja. Kalaulah bicara soal kerja, besar kemungkinan tingkatannya juga beda,” ujar kawan saya.
“Mereka bisa main TikTok pun gara-gara founder-nya kuliah. Lha, ini, kok, masih aja pamer-pamer pekerjaan sambil merendahkan para sarjana. Mbok ya minimal kalau bodoh itu jangan anti intelektualisme juga gitu, lho!”
Saya diam saja waktu mendengar kata “anti intelektualisme”. Sebab, bukan satu-dua kali saya mendengar luapan emosi serupa.
Bahkan di TikTok pun, ketika perdebatan sarjana vs SMA diinisiasi oleh kata-kata “kuliah adalah pengangguran dengan gaya,” saya juga sempat menjumpai konten dari beberapa sarjana yang narasinya seperti gerutu teman saya tadi.
Memang betul bahwa kawan-kawan lulusan SMA ini keliru. Mereka terlampau naif memandang seseorang bisa dapat kerja hanya dari tingkat pendidikannya saja. Pasalnya persoalan tersebut jelas banyak banget faktor yang mempengaruhinya.
Bisa dari individunya yang gengsi, ekspektasi keluarganya yang ndakik-ndakik, minimnya lowongan kerja yang sesuai bidang, bahkan miskinnya relasi orang dalam. Pokoknya banyak.
Tapi jangan lupa, bahwa dalam perdebatan tersebut bukan cuma lulusan SMA saja yang bisa dibilang anti intelektualisme. Kebanyakan kawan-kawan sarjana yang di TikTok pun sebenarnya juga terjebak dalam lubang yang sama.
Saya tahu ini mungkin terasa menyakitkan. Tapi, sebelum sakit hati itu bikin naik pitam, mari kita pahami dulu apa itu yang disebut anti intelektualisme.
Baca Juga: Sesat Pikir Konten Bersyukur ala TikTok
Tiga Jenis Anti Intelektualisme Menurut Richard Hofstadter
Istilah anti intelektualisme ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelum para sarjana dan lulusan SMA ribut-ribut di TikTok. Pencetusnya adalah seorang Amerika bernama Richard Hofstadter.
Dalam bukunya berjudul “Anti-intellectualism in American Life”, Pak Hofstadter membedah anti intelektualisme menjadi 3 jenis.
Pertama ialah anti rasionalitas. Pak Hofstadter bilang bahwa anti rasionalitas ini adalah penolakan terhadap pendayagunaan akal budi, yang biasanya datang dari tradisi keagamaan.
Kalau kita pernah mendengar bahwa berpikir kritis dan mendalam bikin kita jauh dari nilai-nilai agama dan Tuhan, maka itulah yang dimaksud sama beliau.
Kedua, anti elitisme. Jenis kedua ini hampir sama dengan apa yang disebut Pak Tom Nichols sebagai anti pada pakar. Hanya saja, Pak Hofstadter menambahkan bahwa anti elitisme juga berarti penolakan terhadap pemikiran yang tidak populer dan tidak memuaskan aspirasi banyak orang.
Ini biasanya terjadi ketika ada orang yang punya unpopular opinion yang sebenarnya valid, tapi malah “ditodong banyak pedang” hanya karena opininya tidak sama dengan kebanyakan orang.
Ketiga, instrumentalisme non reflektif. Dalam pengertian yang sederhana, jenis ini adalah bentuk gagasan atau pemikiran yang hanya didasarkan pada tujuan pragmatis dan bukan jangka panjang.
Contoh paling gampangnya adalah FOMO terhadap barang yang sedang viral. Kita membeli barang bukan untuk kebutuhan jangka panjang, tapi cuma untuk memuaskan rasa penasaran, bahkan gengsi semata.
Gimana? Apakah sudah nangkep kenapa saya menganggap para sarjana di TikTok itu juga terjebak anti intelektualisme? Kalau belum, mari ikuti lagi penjelasan saya.
Baca Juga: Apakah Kita Harus Percaya Pada Pakar?
Sarjana dan SMA Sama-sama Hanya Merebut Citra Sosial
Jika dilihat berdasarkan ketiga jenis anti intelektualisme tadi, tentu para sarjana di TikTok tidak terjangkit semua jenisnya. Dari konten-konten yang diunggah, setidaknya mereka itu—termasuk yang lulusan SMA juga—terjebak pada jenis anti intelektualisme yang ketiga.
Maksud saya begini. Kita ‘kan tahu sendiri bahwa tren sarjana vs SMA di TikTok itu berisi banyak konten-konten yang cenderung pamer pencapaian. Dari kalangan lulusan SMA, mereka pamer pekerjaan, uang, barang mahal, bahkan lowongan pekerjaan yang katanya untuk para sarjana.
Demikian juga para sarjana. Mereka ada yang pamer rumitnya pemahaman akademis, pemahaman tulis menulis, pengalaman praktik lapangan, pengalaman nongkrong dengan para akademikus, bahkan pamer betapa berharganya lulusan sarjana dibanding SMA di dunia pekerjaan.
“Lho, tapi ‘kan, para sarjana ini beda. Mereka lebih berkualitas pamer pencapaiannya dibandingkan lulusan SMA yang nggak ada kaitannya sama intelektualisme?”
Wo iya, tentu saja. Tapi ingat, pamer pencapaian mereka itu tampak beda karena dilihat berdasarkan logika entertainment TikTok.
Sementara jika mengacu pada logika Pak Hofstadter tadi, keduanya sebenarnya sama saja. Sama-sama terjebak pada pemikiran yang hanya didasarkan pada tujuan pragmatis, bukan jangka panjang.
Yang lulusan SMA pengin merebut citra sebagai orang yang tidak perlu intelektualisme karena sudah dapat pekerjaan dan uang. Yang lulusan sarjana pengin merebut citra sebagai orang yang tidak mau direndahkan.
Jadi jelas, antara sarjana dan SMA pada perdebatan tersebut sama-sama hanya sekadar mengejar tujuan pragmatis bernama “citra sosial”, bukan jangka panjang.
“Lho, tapi tujuan mereka ingin merebut citra ‘kan agar intelektualisme tidak lagi direndahkan; biar para lulusan SMA ini sadar bahwa intelektualisme bukan sekedar untuk meraih pekerjaan dan harta doang.”
Oke, kalau memang dengan pamer pencapaian hasil kuliah bisa membuat lulusan SMA sadar, kenapa dari dulu hingga sekarang perdebatan keduanya masih saja terus berulang?
Pertanyaan itu tak usah dijawab karena sudah jelas. Bahwa sebenarnya para sarjana di TikTok itu masih pragmatis; tendensinya masih ke arah pencitraan, bukan perubahan.
Bisakah para Sarjana Berempati pada Lulusan SMA?
Kalau saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi boleh kasih saran, maka sederhana saja: berempatilah pada para lulusan SMA. Kenapa harus berempati?
Jawabannya karena pengetahuan orang itu tidak selalu universal. Pengetahuan manusia selalu terlokalisasi alias bersumber dari posisi sosialnya masing-masing.
Karena pengetahuan manusia berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka wajar jika ada yang memandang hidup hanya soal ini dan itu. Ini bukan saya yang bilang, lho, ya. Dalam ilmu komunikasi ada teorinya, yaitu standpoint theory.
Nah, kalau kita bisa berempati pada lulusan SMA, kita mustinya paham bahwa kelakuan mereka yang seperti itu karena mereka nggak pernah merasakan nikmatnya; manfaatnya mendapat ilmu pengetahuan di perkuliahan.
Baca Juga: Monopoli Sejarah dan Penghinaan Nalar Publik
Yang pernah mereka rasakan, ya, mungkin tidak jauh-jauh dari dapat duit banyak berkat hasil kerjanya. Jadi, percuma kita yang sarjana ini malah memamerkan pencapaian hasil berkuliah. Mereka jelas peduli setan sama pandangan bahwa hidup itu juga butuh ilmu pengetahuan.
Lalu, apa yang perlu kita lakukan sebagai sarjana ataupun yang masih calon?
Tinggalkan sikap mental superior bahwa status sosial mereka lebih rendah dari kita. Mulailah membangun habit pergaulan dengan mereka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Spill-lah dikit-dikit buah dari intelektualisme kita untuk membantu masalah hidup mereka di luar dunia kerja. Dan yang paling penting, konversikan bahasa menara gading itu ke bahasa tongkrongan.
Kalau itu dilakukan, saya yakin, sedikit banyak para lulusan SMA ini akan sadar kalau ternyata kuliah juga penting untuk jangka panjang. Mereka akan sadar bahwa pemahaman intelektualisme itu memang kegunaannya tidak hanya untuk meraih pekerjaan doang.