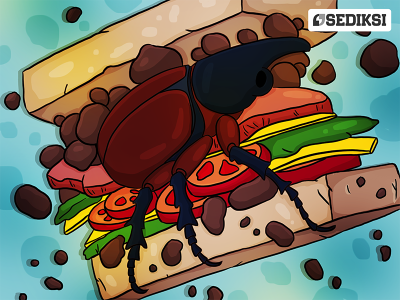Saya sempat kepikiran soal salah satu kutipan sambutan Joko Widodo, dalam sambutan pembukaan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference pada 7 Agustus lalu.
Pemilik plat kendaraan R1 itu mengatakan bahwa, di bidang keagamaan, masyarakat mulai semakin tidak religius. Survei IPSOS Global Religion tahun 2023 terhadap 19.731 orang dari 26 negara dunia menunjukkan 29 persen menyatakan agnostik dan ateis.
Kecemasan Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Dari kacamata sejarah agama, sesungguhnya ateismen dan agnostik seumuran. Entah itu ateisme yang radikal atau hanya tataran teori saja.
Dalam hal apa-pun, sesungguhnya agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Semua agama pastilah mengajarkan kebaikan.
Namun sekarang, banyak sekali orang menyalahgunakan ajaran agama untuk kejahatan dan keuntungan pribadi. Atau menggunakan agama sebagai dalih untuk perbuatan yang tidak pantas.
Sebenarnya, dengan begitu seseorang sedang menghilangkan esensi agama.
Agaknya, orang perlu belajar agama dengan cara menjadi atheis ala Nietzsche.
Hahh? Kek mana tuh?
Baca Juga: Agama Netizen Adalah Agama Mie Instan
Latar belakang religius menjadi ateis
Konon, di Rocken tanggal 15 Oktober 1844 lahir bocil dari keluarga agamais. Ayahnya, Karl Ludwig, seorang pendeta Lutheran.
Kelak, bocah dan ‘si pendeta kecil’ ini menjadi seorang yang ‘berlari siang hari di tengah keramaian mewartakan kematian Tuhan’.
Pemikirannya sangat ‘gila, radikal, kafir, ateistik’. Ia mengumandangkan ‘Tuhan Mati, “Gott ist tot” dan pembunuhnya adalah kita semua; kau dan aku’.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), demikian nama bocil ateis tersebut. Ia menyatakan dirinya tak bertuhan saat berusia 21 tahun. ‘Kritik atas teisme’ menurut Budi Hardiman, dalam buku Filsafat Modern; 2004, ‘menjadi napas dari karya-karyanya’.
Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana seorang yang berlatar belakang religius, tiba-tiba menjadi ateis.
Menurut literatur yang saya baca, kakek dan kakek buyut dari ibunda Nietszche, Franziska Oehler, berprofesi sebagai pendeta. Sungguh Nietzsche dibentuk dalam rahim religius yang tinggi.
Sayangnya ia dengan lantang menjadi proklamator pembunuh Tuhan. Naskah utuh tentang warta kematian Tuhan ada dalam “La Gaya Scienza”. Pada tanggal 25 Agustus 1900 sang pembunuh Tuhan ‘dibunuh’ oleh Tuhan. Tragis.
Manusia tanpa rasio akan menjadi gila
Dalam tafsiran Setyo Wibowo, Gaya Filsafat Nietzsche; 2017, ‘omong besar tentang kematian Tuhan Nietzsche’ dapat ditafsir dalam dua jenis.
Tafsir pertama dan paling mudah ialah mencap Nietszche sebagai pribadi yang terbelah.
Hal ini disebabkan karena di satu sisi ia terdidik secara religius, lalu frustrasi dan meninggalkan agamanya. Di sisi lain entah karena apa, ia mencari-cari Tuhan.
Artinya Nietszche gila, terbelah, berkepribadian ganda, bipolar. Ini semacam tafsir ad hominem dalam logika dasar.
Tafsir kedua yang agak intelegen berkisar di pernyataan ‘ya naif dan tidak naif’. Sederhananya, ya naif berarti kematian Tuhan diterima begitu saja. Dengan kematian Tuhan, manusia bebas, berdikari.
Jika Tuhan yang maha segalanya itu dihilangkan, kebebasan yang bablas pun bisa mekar dimana-mana.
Bahasa ilmiahnya ialah ateisme humanistik. Supaya manusia menjadi manusia, maka ia harus dibebaskan dari Tuhan. Itulah ya naif pertama.
Baca Juga: Cara Mati Ketawa ala Milan Kundera
Ya naif berikutnya ialah kematian Tuhan sebagaimana dalam tafsir pertama menitik beratkan perhatiannya pada kemanusian.
Oleh karenanya kematian Tuhan adalah kematian manusia juga. Mengapa? Rasio, subjek, rasionalitas manusia yang dihubungkan dengan Tuhan dimakamkan bersama kematian Tuhan.
Manusia tanpa rasio akan menjadi gila.
Alurnya demikian; Tuhan mati, kemanusian mati, era edan pun lahir. Ke-edan-an ini ditandai dengan anarki, hedonis, hidup tanpa orientasi.
Tuhan mati, hukum moral pun tidak lagi berperan, dan manusia jadi sebebas-bebasnya, disitulah sesungguhnya arti kematian manusia. Karenanya ya naif kedua berhubungan dengan kematian manusia.
Cukup rumit memang.
Lalu bagaimana dengan pendapat tidak naif? Ada lelucon menarik mengenai pendapat ini yang saya baca dari tafsiran Wibowo tersebut.
Pada suatu hari ada tulisan “Tuhan sudah mati, tertanda: Nietzsche”, keesokan harinya muncul tulisan “Nietzsche sudah mati, tertanda, Tuhan”.
Pendapat tidak naif ini secara gamblang menolak habis kemungkinan kematian Tuhan. Menolak habis-habisan kemungkinan bahwa Tuhan bisa mati.
Membaca Nietzsche: kompas kembali memahami agama dengan benar
Nietszche menasihati setiap pembacanya untuk menjadi diri sendiri. Ia ingin setiap orang mawas diri.
Anjurannya seperti bersikap ‘ya sekaligus tidak’. Inilah kelihaiannya, menawarkan pembacanya untuk melampauinya. Sebagai ‘manusia religius yang tersesat’ kita mesti berhati-hati menyudutkannya sebagai seorang ateis.
Sindhunata, dalam pengantar buku Gaya Filsafat Nietzsche tersebut menarasikan bahwa, ateismenya bisa menuntun manusia yang ‘sok religius’ untuk mencapai pencerahan.
Dalam hal ini, Nietzsche yang a-religius itu sesungguhnya orang yang sangat religius.
Memang tidak mudah memahami karya-karya Nietzsche secara umum, dan warta kematian Tuhan secara khusus.
Baca Juga: Sains Menunjukkan Cantik itu Tidak Relatif
Kendati demikian, Wibowo mengatakan ada cara termudah untuk memahaminya, yakni membacanya dari perspektif pengalaman personal.
Dalam satu tulisannya, ia menulis, ‘kalau kau mencerna bukuku, pasti kau tahu bagaimana mengerti diri sendiri bersamaku’.
Nah, untuk mengenalnya, kita mesti pulang pada pendirian paling tua dari filsafat Yunani, yakni Gnothi Seauton, kenali diri sendiri.
Membaca warta kematian Tuhan sejatinya menjadi jalan untuk kita memahami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari.
Benar mungkin apa yang dipercayai Heraklitos ‘anjing-anjing hanya menyalaki yang tidak mereka kenali.”
Dalam kaitannya dengan pemikiran Nietszche ialah, kenali secara benar baru berkomentar. Agar tidak naif menolak dan mengiyakan begitu saja karya Nietzsche.
Membaca Nietzsche seharusnya menjadi kompas untuk kembali memahami agama dengan benar. Warta kematian Tuhan menjadi jalan pulang pada nilai substansial agama.