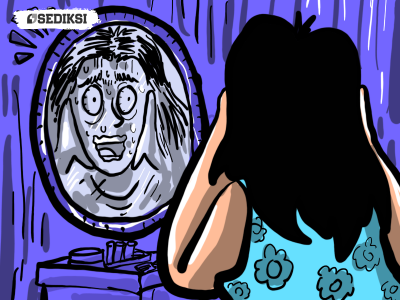Kampanye kesejahteraan ibu guna mendukung tumbuh kembang anak yang sehat jiwa raga mulai jamak terdengar. Jelas, ini penting dan perlu dilanjutkan.
Terlebih dalam masyarakat yang berpikir ibu mesti mengerahkan segala yang ia punya dan bahkan kadang harus mengorbankan pekerjaan, impian-impiannya, atau waktu berkualitas bagi dirinya sendiri.
Pasalnya, anak niscaya sulit sejahtera bila ibunya low bat fisik maupun mental. Koneksi sungguh-sungguh ibu dengan si bocah tereduksi, begitu juga dengan dirinya sendiri.
Ironisnya, ketika masyarakat punya ekspektasi tak masuk akal terhadap sosok ibu, sosok yang sama “dituntut” pula untuk bahagia demi mencukupi kebutuhan keluarganya.
Baca Juga: Perempuan dan Hantu Keberdayaan
Tuntutan Tak Masuk Akal
Sekitar empat tahun silam, seorang perawat mengunjungi saya yang waktu itu berada dalam kondisi pasca melahirkan dan kesusahan menyusui.
Ia dengan gampangnya bilang, “Ibu mesti happy supaya ASI-nya keluar banyak.” Seakan emosi bisa disetel dengan tombol on-off.
Kalimat nirempati—yang seyogianya diubah jadi pertanyaan “apa kabar, Ibu?” atau “apa yang Ibu rasakan?”—ini jadi tekanan lain bagi sang ibu yang dalam banyak kasus mungkin sudah memiliki prakondisi depresi pra melahirkan, mengalami baby blues, atau depresi pasca melahirkan.
Alih-alih menguatkan, kata harus atau mesti menjadi duri yang membuat batin ibu berdarah-darah.
Pun, demikian dengan ayah. Dalam budaya patriarkal, laki-laki juga menghadapi beragam tuntutan mencekik. Menjadi pencari nafkah, pantang menunjukkan tangis dan kerentanan, ditambah tuntutan sukses dari masyarakat yang diukur dari jabatan atau materi.
Bapak pun sebenarnya bisa mengalami depresi begitu anaknya lahir. Namun, tak banyak yang sadar, peduli, atau menindaklanjutinya. Dibanding kampanye ibu sejahtera, kampanye bapak sejahtera jauh lebih jarang terdengar. Bahkan, hampir nihil.
Saya mengangkat isu ini dari perspektif perempuan karena saya percaya bahwa relasi setara dan sejahtera berawal dari kepenuhan diri semua gender.
Kesehatan Mental adalah Hak Asasi Universal!
Kesejahteraan ayah dan ibu itu simultan. Bukankah saat bicara relasi rumah tangga it always takes two to tango?
Dan seperti halnya tema Hari Kesehatan Mental Dunia 2023, saya meyakini kesehatan mental adalah hak asasi universal yang patut diperjuangkan.
Mengupayakan kesejahteraan ibu kurang lengkap tanpa kesejahteraan bapak. Dalam pemulihan kesehatan, aspek biopsikososial perlu diperhatikan.
Ketika ibu burned out atau depresi, tentu tak cuma dia yang butuh konseling atau minum obat agar pulih. Lingkungan sosialnya pun perlu memberinya dukungan, utamanya pasangan dan keluarga inti.
Suami sehat jiwa raga adalah prasyarat kesejahteraan ibu dan anak-anaknya, tetapi tidak semua keluarga memiliki sosok begini. Dari luar, barangkali sang bapak terlihat baik-baik saja, terbilang “sukses” malah. Tetapi, bisa jadi dia diam-diam mengalami depresi atau problem yang menggerogoti jiwanya.
Apalagi laki-laki sering dituntut untuk selalu tangguh serta tidak boleh mengekspreksikan kerentanan atau menangis.
Tuntuan macam ini bisa berkontribusi terhadap angka kematian bunuh diri laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan, yang merupakan konsekuensi dari realitas toxic masculinity yang masih mengakar di masyarakat kita.
Menurut berbagai riset dari American Journal of Men’s Health, misalnya, laki-laki disebut lebih enggan datang ke psikolog/psikiater daripada perempuan.
Data WHO per 2019 secara global menyebutkan, per 100 ribu kematian akibat bunuh diri, rasio laki-laki banding perempuan berada di angka 12,6:5,7. Sementara data serupa dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2016 berada di angka 4,8:3,4.
Saat kondisi mental ibu melemah, kondisi mental suaminya sebagai caregiver bisaturut terdampak. Dari pengalaman pribadi, salah seorang laki-laki pembaca buku saya pernah curhat terkait kondisi istri yang tak stabil mental sehingga mempengaruhi sikapnya ke anak mereka serta kondisi psikisnya.
Dia bertanya, “Mbak, tahu komunitas atau support group buat bapak-bapak yang istrinya sedang bermasalah kejiwaan, nggak?”
Saya tahu sederet komunitas dan support group buat para ibu, termasuk yang bergerak di bidang kesehatan mental. Saya pun mengenal orang-orang dari beberapa support group spesifik untuk gangguan-gangguan jiwa tertentu.
Namun, yang khusus buat suami-suami caregiver,kok, tak satu pun yang muncul di kepala, ya?
Apakah ini menyiratkan terlalu kuatnya patriarki dan maskulinitas toksik untuk ditandingi oleh kesadaran dan literasi kesehatan jiwa? Ataukah ini perkara sistem lain yang menyebabkan minimnya supply and demand wadah bagi bapak-bapak bermasalah kejiwaan?
Sudah Saatnya Kesejahteraah Bapak sekaligus Ibu Digaungkan
Banyak bapak pekerja, utamanya kelas menengah ke bawah, mesti komuter berjam-jam saban weekday untuk mencari nafkah.
Dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh Lee Dong-wook di Korea Selatan yang diterbitkan oleh Journal of Transport & Health, disebutkan bahwa pekerja yang melakukan perjalanan lebih dari 1 jam ke kantornya berisiko 1,6 kali lebih tinggi mengalami depresi.
Ada juga riset-riset yang menemukan paparan polusi udara bersumbangsih terhadap peningkatan gejala depresi. Hasil-hasil temuan ini menyumbang faktor-faktor risiko gangguan depresi selain faktor genetik dan biologis, riwayat trauma, pengaruh lingkungan, dan faktor psikologis.
Sebagian faktor risiko tadi menjadi bagian rutinitas bapak-bapak ketika mencari nafkah. Namun, banyak perusahaan, sadar atau tidak tentang itu, masih membuat kebijakan yang tak fleksibel soal cara dan tempat bekerja karyawannya.
Karena atas nama produktivitas, sebagian bapak pekerja dituntut mengerahkan energi dan waktu lebih banyak di kantor, sembari sesekali bergelut dalam konflik dan tekanan di sana.
Baca Juga: Tips Jadi Bapak yang Jenaka ala Etgar Keret
Kapitalisme yang berkelindan dengan patriarki mendorong perusahaan memberi lebih sedikit kesempatan bagi bapak untuk berpartisipasi secara berimbang dengan istrinya di ranah domestik.
Pihak kantor sendiri kerap berpikir bahwa urusan rumah dan anak seharusnya sudah menjadi tanggung jawab perempuan. Alhasil, di banyak keluarga, anak minim sentuhan fisik dan emosional dari bapak, sehingga berefek pada psikisnya sampai dewasa.
Kondisi semcam ini juga pada gilirannya berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga. Bapak dan ibu sama-sama kelelahan, koneksi dan intimasi berkurang, emosi gampang tersulut, dan jadilah pertengkaran rumah tangga yang menambah level stres kedua pihak.
Kalau ada yang menonton drakor Death’s Game, pasti ingat ada dua tokoh laki-laki memilih bunuh diri lantaran tekanan ekonomi dan perkara relasi romantis yang ambyar.
Ini pun juga pernah saya alami. Ketika suatu hari berkonflik dengan suami, gejala gangguan kepribadian yang saya alami kambuh, sementara suami terdiagnosis depresi.
Sejak berumah tangga dan memiliki anak, kami sangat jarang dibantu orang tua atau kerabat masing-masing karena keluarga kami tinggal berjauhan.
Keadaan finansial tak memungkinkan untuk menyewa jasa pengasuh. Kebanyakantetangga atau teman pun tak dapat menjadi opsi support system karena mereka sibuk atau punya anak-anak kecilnya masing-masing. Dalam batin, saya mengerang, where’s our support system?
Beruntung kami memiliki literasi kesehatan mental dan akses ke psikolog/psikiater yang disokong oleh BPJS. Meskipun mengurusnya agak pelik karena mesti dioper ke rumah sakit yang jauh dari rumah dan perlu mengantre lama.
Perlu diingat bahwa tidak setiap kantor memberikan bapak pekerja toleransi untuk mengurus masalah kejiwaannya setiap waktu. Sebab, di sebagian kasus, mereka perlu berobat dan konseling intensif sehingga memangkas waktu kerja.
Maka dari itulah perlu ditekankan lagi bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga bukan perkara individual atau satu gender saja. Masalah ini juga menjadi salah satu problem dalam sistem sosial, budaya, dan ekonomi.
Isu anak sehat, ibu-bapak sejahtera, serta keluarga bahagia adalah isu publik yang melibatkan peran berbagai aktor. Tak pernah ada cerita seorang pesakitan yang sepenuhnya pulih tanpa sokongan tangan-tangan penolong.
Saya berharap, kalau besok-besok ada yang bertanya lagi seperti pembaca buku saya tadi, saya bisa lebih cepat menjawab lantaran tempat yang mewadahinya telah bermunculan.
Semoga kelak saya, pasangan, dan putra kami bisa mencicipi masa ketika lelaki tak lagi dipermalukan karena menangis atau menunjukkan kerentanan, dicemooh ketika mencari bantuan profesional, juga tak melulu diwajibkan menjadi penanggungjawab utama dalam keluarga, karena peran itu bisa diemban siapa saja atau dijalankan bergantian.