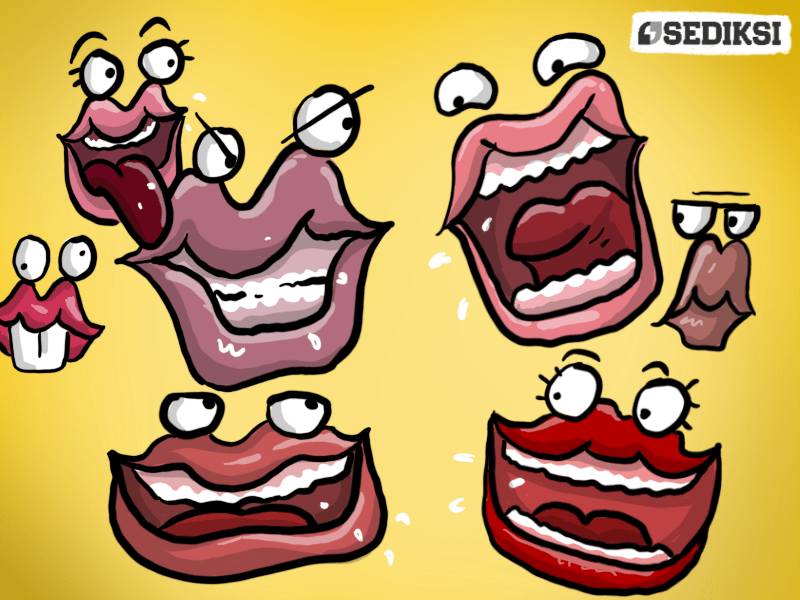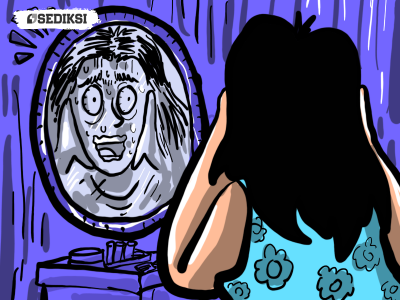Suatu ketika, saya hendak menyampaikan pendapat kepada orang tua mengenai konsep pernikahan yang saya inginkan, yakni seperti yang sempat viral di media sosial kemarin. Pernikahan tanpa resepsi dan hanya berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) saja. Namun, setelah dipikir ulang, saya lantas mengurungkan niat itu.
Sepertinya akan sia-sia menyampaikan hal tersebut. Pasalnya, sebagai seorang anak, saya merasa belum punya cukup keleluasaan menyampaikan pendapat di depan orang tua.
Saya trauma, karena beberapa kali ketika mencoba memberi pendapat, saya malah disuruh diam dan mereka berkata, “Kamu dengarkan saja. Biar kami orang tua yang urus.”
Pantang dibantah.
Apalagi, dalam tradisi keluarga saya, segala keputusan menyangkut masa depan anak ada di tangan para tetua. Misalnya urusan pernikahan. Ini merupakan momen sakral, maka keluarga wajib merayakan dengan meriah.
Padahal, pendapat mengenai konsep pernikahan low budget menurut saya jauh lebih efektif dan efisien. Hanya saja, ide tersebut mungkin masih asing di telinga mereka, sehingga peluang untuk “dikebiri” jauh lebih besar ketimbang diterima.
Tentu sebagai anak, saya tidak akan puas apabila yang disepakati adalah konsep yang malah akan menyusahkan saya nantinya.
Sepupu saya pernah bilang “Sudah, percayakan saja kepada orang tua. Karena mereka yang lebih berpengalaman,”
Apakah dengan begitu semuanya dijamin akan berjalan lancar? Saya rasa belum tentu.
Saya tahu bahwa tidak semua dari mereka punya pengalaman indah mengenai pernikahan. Sebagai pendatang baru, saya pun harus belajar dari pengalaman-pengalaman buruk mereka. Sangat penting memberikan kesempatan kepada siapa saja, termasuk saya, untuk berpendapat.
Pertimbangan seperti ini mesti dibicarakan dengan bijak, supaya dapat menghasilkan jalan keluar terbaik untuk semua pihak. Ini penting. Saya juga sudah cukup dewasa dalam berpendapat dan pasti akan mempertanggung jawabkannya di kemudian hari.
Dengan membatasi atau bahkan menolak pendapat saya, sama saja dengan membiarkan saya hidup sebagai anak yang terus menerus berlindung di balik bayang-bayang orang tua.
Saya pikir wajar saja menyampaikan ide atau gagasan di depan umum, termasuk di keluarga. Tindakan tersebut harusnya dianggap sebagai hal positif dalam melawan bentuk dominasi pemikiran yang feodal dan dogmatis. Misalnya, dalam melawan rasa takut menyampaikan pendapat pribadi, akibat “tekanan moral” yang datang dari orang tua atau anggota keluarga lain yang lebih tua.
Biasanya, anak dibilang tidak sopan saat berbicara atau membicarakan sesuatu yang dianggap melenceng. Padahal, berargumen tidak bisa disamakan dengan sopan santun. Ketika merasa terkekang, seorang anak boleh saja protes terhadap perlakuan orang tuanya. Berbeda dengan sopan santun yang adalah merupakan wujud dari penghormatan anak kepada orang tua.
Mengapa demikian? Sebab, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap orang. Siapa pun berhak menyampaikan keresahannya terhadap ketidaknyamanan yang dia rasakan.
Di dalam konteks keluarga, anak yang sering berkomunikasi dengan orang tuanya dan diberi kebebasan dalam berpendapat, berpeluang tumbuh sebagai anak yang kritis, dan teguh mempertahankan identitas pemikirannya.
Lha, gimana nggak kritis, wong si anak dibolehkan untuk speak up setiap ada sesuatu yang dirasa mengganggu akalnya kok. Karena itulah, cara ini perlu diterapkan dalam keluarga, agar anak bisa terus semangat belajar, mencari hakikat kebenaran yang dia tuju.
Selain itu, kebebasan yang diberi kepada anak juga akan membantu proses pendewasaan diri. Mereka akan terus menggali pengetahuan tentang makna kehidupan, merenungi identitas mereka yang sebenarnya.
Baca Juga: Tips Jadi Bapak yang Jenaka ala Etgar Keret
Waktu kuliah, ada satu teman saya yang terkenal cerdas di kelas. Bacaan bukunya banyak dan cara berpikirnya juga tidak konvensional. Lantas, saya penasaran bagaimana dia bisa tumbuh sebagai mahasiswa sekeren itu?
Kata dia, sebabnya sederhana. Dari kecil dia sudah terbiasa bertanya tentang apa saja kepada orang tuanya. Orang tuanya pun menyambut baik segala pertanyaan itu. “Orang tuaku malah seneng ketika aku banyak bertanya atau ngomong,” terangnya.
Yang bisa saya simpulkan adalah tentang bagaimana sikap orang tua dalam menghargai pendapat anak, apapun yang ingin dia sampaikan. Anak akan merasa lebih percaya diri karena diberi ruang untuk berekspresi. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi rahasia anatara orang tua dan anak.
Tidak akan ada hal-hal yang disembunyikan karena takut dimarahi, dihakimi, ataupun dihukum. Maka, nggak heran kalau teman saya itu bisa terlihat lebih charming dari yang lain.
Sedangkan saya? Boro-boro. Punya gebetan baru di sekolah saja, tidak berani cerita. Bisa dicecar dua hari dua malam saya.
Ketakutan semacam ini, muncul akibat membayangkan respons dari sosok orang tua yang tidak pernah mendukung pendapat anak. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan cara menolak atau mengabaikan pendapat anak, atau menunjukkan sikap tidak setuju baik secara langsung maupun tidak langsung kepada si anak.
Perlu diakui bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan si anak juga. Orang tua tentu khawatir, jika pendapat anaknya bisa saja membawa pengaruh buruk bagi lingkungan dan dirinya sendiri. Akan tetapi, orang tua juga punya pilihan untuk melakukan pendekatan emosional serta rasional kepada anak. Serta membuka ruang diskusi dengan anak, demi menemukan jalan keluar terbaik.
Orang tua mesti sadar bahwa perbedaan pendapat itu sulit dihindari. Faktor penyebabnya bisa beragam. Salah satunya, yaitu karena adanya perbedaan prinsip antara orang tua dan anak.
Kita pasti sering mendengar kalimat sakti orang tua yang sering diucapkan, seperti:
“Waktu zaman bapak dulu…” atau
“Kenapa sih, anak sekarang kok susah dibilangin?”
Mohon maaf. Bagi saya, kalimat seperti itu hanya mencerminkan ego satu generasi semata. Mereka menganggap zaman mereka lebih baik. Tanpa menyadari bahwa setiap zaman punya keunikan masing-masing.
Perbedaan zaman adalah niscaya. Kita tidak bisa membandingkan tren di era sekarang dengan tren di era orde baru dulu, misalnya. Begitu pula tren yang akan muncul dua puluh tahun lagi. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Poinnya adalah bagaimana cara orang tua menghadapi pola pikir anak yang berbeda dengannya. Memberikan kesempatan bagi anak untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang apa yang dia pikirkan, adalah langkah paling bijaksana. Sedangkan, membatasi pendapat anak, sama dengan merampas haknya sebagai manusia merdeka.
Perlu diingat bahwa, kebebasan yang diberikan jangan sampai disalah tafsirkan oleh anak. Sebagai anak, kita juga wajib mendengar dan menghargai pendapat orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Seperti kata Nelson Mandela, kebebasan bukan hanya bertujuan melepaskan rantai yang mengikat seseorang, tapi juga menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain.
Dari situ, akan hadir manfaat yang bisa diterima anak, yakni meningkatnya rasa empati dan jiwa sosial terhadap orang lain. Di samping itu juga meningkatkan kesabaran saat memahami cara pandang orang lain yang berbeda dengannya. Ini merupakan faktor utama dalam mengantisipasi konflik yang akan terjadi.
Terakhir, saya harap semoga kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bisa diterapkan oleh seluruh keluarga manapun di negara ini tanpa dihambat dengan alasan-alasan normatif lagi.
Baca Juga: Tampan Adalah Koentji. Titik!
Saya juga berharap agar pendapat tentang konsep pernikahan yang saya inginkan bisa diterima dengan senang hati oleh keluarga. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa hampir mustahil jika itu terjadi.
Saya malah tambah khawatir apabila ada pernyataan orang tua yang kira-kira bunyinya begini, “Mau dibikin gede atau sederhana itu perkara mudah. Sekarang masalahnya, pasanganmu mana?”