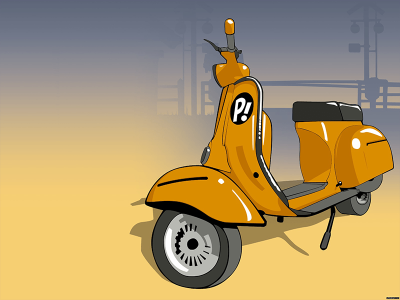Christoper Nolan adalah sutradara yang bisa membikin pengalaman nonton film serasa ujian nasional. Setidaknya bagi saya, ia berhasil menghadirkan perasaan tegang, melankolis dan mengajak penonton memeras otak, kalau perlu sampai mempertanyakan realitas dan pengin muter gasing.
Tahun ini, Nolan kembali menghadirkan ‘ujian nasional’ melalui sebuah film biografi berjudul Oppenheimer.
Seperti judulnya, Oppenheimer akan berkisah tentang Julius Robert Oppenheimer. Ia merupakan seorang fisikawan Amerika yang menjadi tokoh kunci dalam Proyek Manhattan selama Perang Dunia II. Proyek ini ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Terlibat dalam proyek ini membuat Oppenheimer kelak dikenal sebagai sosok di balik lahirnya bom nuklir yang sanggup menghancurkan satu kota dalam sekejap. Orang-orang menyebut bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki menjadi gong penutup Perang Dunia II.
Trailer film ini mulai bertebaran di artikel dan video melalui internet. Tentu saja tulisan ini tidak akan membahas trailernya. Omong-omong soal trailer Oppenheimer, ingatan saya tiba-tiba terbang ke The Wind Rises-nya Ghibli.
Dua film ini punya nuansa yang mirip. Keduanya menyuguhkan sebuah pertanyaan kepada audiens: “Bagaimana rasanya menjadi pencipta alat pencabut nyawa masal?”
Protagonis yang Bernasib Tragis
Dalam sejarah, baik Oppenheimer maupun Jiro Horikoshi (protagonis The Wind Rises dan pembuat pesawat Zero) tampaknya akan terus dikenang sebagai pelaku genosida perang. Mereka didakwa seolah mereka adalah pelakunya.
Meski tangan mereka tak berlumur darah, teknologi mereka menjelma jadi senjata pemusnah nan mematikan. Mereka turut menanggung beban moril atas tragedi yang terjadi.
Di balik itu semua, Robert Oppenheimer dan Jiro Horikoshi bisa jadi adalah korban paling awal dari ciptaannya, bahkan sebelum terjadinya tragedi. Oppenheimer menyambut kesuksesan uji nuklir dengan perasaan menyesal sambil mengutip Bhagavad Gita, “Now I am become death, the destroyer of the world.”
Horikoshi juga menyikapi uji pesawat Zero dengan sebuah mimpi buruk akan peperangan, kehancuran, dan korban berjatuhan. Ia melihat pesawat ciptaannya hancur, jatuh, dan membunuh banyak orang. Semua itu disertai perasaan ketidakmampuan mengubah masa depan buruk yang pasti akan terjadi.
Nasib membuat mereka terjebak dalam keadaan yang menuntut mereka berbuat sesuatu. Panggilan jiwa mereka sebetulnya ingin menghadirkan sesuatu untuk membawa dunia jadi lebih baik. Celaka bagi mereka saat temuan mereka justru digunakan untuk menciptakan petaka. Itu semua lebih dari cukup untuk menyebut mereka dikutuk oleh takdir.
Oppenheimer dan Horikoshi adalah ahli di bidangnya, yang rasa penasaran atas inovasi pengetahuan rupa-rupanya masihlah murni. Oppenheimer merupakan ahli fisika nuklir, sementara Horikoshi seorang insinyur pesawat terbang. Mereka berdua mempersembahkan hidupnya untuk pengetahuan.
Realita tampaknya tak begitu ramah pada orang-orang yang berprinsip kuat. Kisah mereka adalah perseteruan antara impian seorang saintis dan kutukan takdir.
Oppenheimer mesti berpacu dengan waktu sebelum Jerman membuat bom atom lebih awal. Horikoshi mesti mengejar ketertinggalan Jepang dalam pengembangan teknologi pesawat terbang. Semua itu terpaksa mereka lakukan untuk menghindari prahara yang lebih besar.
Baca Juga: Salah Beli Fantasi di London Love Story
Jika dianalisis sebagai sebuah karya, maka karakter mereka ini bisa dimasukkan sebagai tragic hero, yaitu protagonis yang berkonflik dengan realita yang membuat keputusan-keputusan yang diambil pada akhirnya mengahancurkan dirinya sendiri.
Tak peduli seberapa keras mereka menampik takdir, mereka tak kuasa mengakali takdir yang melekat. Secara lebih luas, kita mengenalnya dengan kisah ironi.
Mungkin kamu bisa saja menjadi orang baik, namun tetap gagal dan disalahkan. Toh simalakama sudah di kerongkongan.
Tema soal ironi ini sebenarnya bukan barang baru. Tengoklah kisah Hamlet yang naif dan lugu mengharuskannya menjadi korban sekaligus pelaku dalam tragedi pembunuhan keluarganya. Namun di sini lah letak keindahannya.
Dalam trailer Oppenheimer, kita dituntun melihat sudut pandang protagonis dalam menyambut kelahiran ‘senjata penghancur’ yang ia ciptakan:
“They won’t fear it until they understand it.”
“And they won’t understand it until they use it.”
Bagi Oppenheimer, manusia adalah ras naif yang bebal, destruktif, dan tak mau belajar dari kesalahannya. Karena itu, ia menyambut kesuksesan uji coba nuklir dengan perasaan pilu dan getir membayangkan apa yang manusia bisa lakukan dengan senjata pemusnah masal.
Seperti bocah nakal yang sedang bermain-main dengan pisau lipat, maka begitulah manusia ketika mendapat ‘mainan’ baru berupa senjata nuklir.
Fisika yang Menjadi Melankolis
Selama ini, sains, terutama fisika, seakan membawa kesan kaku, kering, dingin, dan jauh dari nilai kemanusiaan. Pelajaran sains identik dengan kesan ruang kelas yang menjemukan. Terkutuklah model pembelajaran ilmu eksak di negeri tercinta ini.
Kadang-kadang sains bisa menjadi begitu romantis dan puitis bahkan melampaui seni itu sendiri, terutama ketika mengangkat topik-topik soal kemanusiaan.
Hal semacam itu bisa kita temukan, misalnya, melalui Carl Sagan yang dalam buku-bukunya yang menggambarkan kosmik sebagai sesuatu yang transenden, megah, dan misterius.
Begitu juga dengan tema nuklir yang coba dinarasikan ulang melalui Oppenheimer. Umumnya, orang-orang memahami nuklir sebagai sinonim dari petaka. Media dan seni mengamplifikasinya, dan makin membuat nuklir dipotret sebagai momok menakutkan.
Nuklir tak pernah jauh dari perang, tragedi maupun nyawa yang dicabut paksa. Nuklir ibarat sangkakala penutup zaman atau kotak pandora yang jika terbuka akan menggedor pintu kiamat.
Nolan lihai menyisipkan emosi manusia, juga kerapuhan mereka, dalam film-filmnya. Oppenheimer bisa kita maknai sebagai cara yang ia gunakan untuk menawarkan perspektif baru.
Oppenheimer Menawarkan Perspektif Baru
Bagaimana jika persepsi soal nuklir kembali digali dan dibangun ulang dari cetak biru yang berbeda? Bagaimana jika tragedi dipotret bukan hanya dari sudut pandang korban?
Dari trailer Oppenheimer, kita memperoleh kisi-kisi soal kelahiran bom nuklir yang tak pernah diinginkan penemunya. Ia mengajak penonton mengamati bagaimana takdir bisa menyeret manusia ke arah yang berbeda dari yang mereka mau.
Meski dalam dunia seni pada hakikatnya tema sudah habis, Nolan amat piawai mendudukkan dirinya berseberangan dengan anggapan umum soal bagaimana sebuah tema dihadirkan. Dalam Dunkirk, misalnya, Nolan menyangkal bahwa film tentang perang mesti kolosal, heroik, atau megah. Sebaliknya, ia menghadirkan sudut pandang yang amat pribadi dan melankolis.
Hal serupa juga Nolan lakukan dalam sekuel superhero Batman, The Dark Knight Rises. Ia tak mau pasar menuntutnya membuat film pahlawan super yang banal akan adu kekuatan. Sebaliknya, ia menggeser adu otot jadi adu otak melalui permainan yang penuh intrik.
Dalam Oppenheimer, sebagaimana biasanya, Nolan tampaknya punya ambisi untuk menguliti persepsi soal nuklir dari sudut pandang yang berbeda.
Jika menonton film-film Nolan serupa ujian nasional, pertanyaannya ialah “bagaimana kita mesti menyikapi dan memikirkan ulang sebuah takdir yang tak pernah kita mau?”
Jawabannya bisa kita temukan saat Oppenheimer tayang Juli nanti.