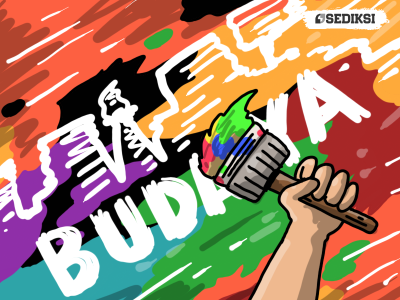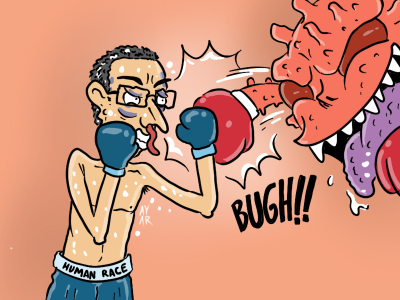“Jika manusia berpikir, Tuhan akan tertawa.”
Begitu sedikit kutipan dari pepatah Yahudi, yang Milan Kundera katakan saat menerima hadiah sastra internasional dari Israel.
Dari kutipan itu, saya bertanya-tanya…. Kenapa Tuhan tertawa ketika kita berpikir?
Meski pemaknaan Tuhan tertawa sulit dijelaskan, namun manusia yang berpikir mempunyai aneka ragam makna.
Mungkin ini juga mengapa jargon “saya berpikir, maka saya ada,” lahir dan kerap dipakai sebagai doktrin monoton di semua institusi ajar formal dan non-formal.
Manusia “kerdil” yang mempunyai kebebasan
Manusia yang berpikir menghadapkan pada situasi manusia yang sebenarnya kerdil, belum banyak tahu. Seperti dalam Catatan Pinggir, Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa diri manusia yang kerdil ini sudah jauh terendus setelah Kopernikus menjelaskan Bumi bukanlah pusat tata surya pada Abad 15.
Istilah manusia yang kerdil juga dikemukakan oleh Nietzsche sejak teori Kopernikus dikenal. Ia pernah mengungkap dalam memoarnya pada tahun 1870-an, bahwa manusia adalah makhluk di sebuah bintang kecil yang nun jauh yang merasa menemukan apa artinya “mengetahui”; ia hidup dalam satu menit yang takabur yang disebut “sejarah dunia“–tapi hanya satu menit.
Manusia yang kerdil dan belum banyak tahu ini juga menjadi penanda pemahaman humanisme mulai tumbuh. Bahwa manusia mampu dan mempunyai kebebasan untuk menemukan kebenaran. Meski kebenaran itu adalah ketidakpastian.
Baca Juga: Nietzsche Pun Seorang Hipster
“Menyimpang” dari pemikiran umum
Ungkapan manusia modern selalu berada di tengah jembatan, bukan di ujung tujuan–dan karenanya membuat kita selalu gamang, tidak dipusingkan oleh Milan Kundera.
Kegamangan menjadi hal yang wajar bagi Kundera. Dalam situasi yang gamang ini, manusia bisa memilih atau bahkan tidak memilih apapun–keanekaragaman yang tak tepermanai.
Milan Kundera mengungkapnya secara jenaka: “Jangan anggap itu semua dengan serius”. Menganggap yang serius jadi tidak lagi serius sebagai tindakan penolakan atas semua bentuk pengkerdilan diri yang terjadi.
Pada gilirannya, Kundera mengajak kita untuk menyimpang dari pemikiran yang umum, pemikiran isme-isme yang kolot, dan jadilah seseorang yang tak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya.
Apa yang dimaksud kebebasan individu menurut Kundera, dalam pandangan saya, adalah condong ke arah eksperimental. Agar manusia membuat sejarah untuk masa depan yang otentik, tanpa adanya cermin kebohongan yang diperindah, tanpa ada kemajemukan paham.
Salah satu catatan ingatan masa depan dari Kundera adalah persoalan masa lalu yang dituliskan oleh pemenang, konteksnya pada Praha Musim Semi 1968 yang dimenangkan oleh Partai Komunis.
Ungkapan “perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa” perkataan tokoh Mirek di halaman 3 ‘Kitab Lupa dan Gelak Tawa’ terkadang tidak ditafsirkan secara penuh. Hanya sebagai kebutuhan untuk melawan kekuatan besar yang berkembang yakni pelupaan.
Padahal, jika dirunut dalam ceritanya, Mirek sama liciknya dengan Partai Komunis yang ditentangnya. Jika Mirek bisa mengambil surat-surat yang ia kirim ke Zdena di masa lalunya, Mirek ingin menghapus masa lampau, menghapus kenangannya bersama Zdena. Ingin menjadi penguasa masa depan yang dapat menulis ulang sejarah.
Alhasil, berbagai ideologi di masa lalu, atau isme-isme yang saling perang dominasi, menurut Kundera, akan selalu melaksanakan: “Ketidakadilan lama diperbaiki, ketidakadilan baru dilakukan”. Baik dalam masyarakat komunis maupun konsumeris, akan selalu ada ketidakjujuran dan solidaritas palsu kitsch.
Dalam berbagai karya Kundera, ia bolak balik memberi arti kitsch yang banal itu dan apa karya yang esensial tanpa harus diembel-embeli oleh isme-isme. Selurus itu, Kundera juga selalu menggunakan premis dasar: manusia tidak benar-benar bisa memahami satu sama lain; dan hampir semua niat, tujuan, dan rencana yang kita buat selalu salah perhitungan, bahkan secara konsisten bisa menjadi bumerang.
Novel oratoris ‘Kitab Lupa dan Gelak Tawa’ (1979) tersebut ia tulis saat merekam memoar kejahatan yang ia dan sosialis Rusia-Ceko perbuat atas nama komunisme, yang kemudian -isme ini mengkhianatinya atau malah sebaliknya?
Lebih dekat dengan Milan Kundera
Setelah membaca berbagai obituari mengenai Milan Kundera yang meninggal pada 12 Juli 2023 lalu, saya simpulkan Kundera adalah seorang hedonis yang tidak mau dilabeli politik tertentu, serta seorang yang memegang prinsip tentang supremasi seni serta kebebasan individu di atas ideologi apa pun.
Dalam esai ‘Testaments Betrayed’, Milan Kundera menyatakan: “Saya akhirnya melakukan beberapa percakapan aneh,” lanjutnya. ‘Apakah Anda seorang Komunis, Tuan Kundera?’ “Tidak, saya seorang novelis.” ‘Apakah Anda seorang pembangkang?’ “Tidak, saya seorang novelis.” ‘Apakah Anda di kiri atau kanan?’ ‘Juga tidak. Saya seorang novelis.’”
Hampir semua karya fiksi Milan Kundera selalu bertemakan: seks yang mengobjektifikasi perempuan, kebebasan manusia sebagai individu, dan keanehan komikal yang nyata ada di sekitar kita.
Paling kentara bisa kita baca di cerpen Kundera berjudul ‘Labirin Permainan’ diterjemahkan Muhidin M Dahlan. Yang mana, tokoh perempuan dalam cerita tersebut digambarkan alami dualitas: sebagai perempuan yang baik di mata masyarakat, dan sebagai manusia yang bebas berbicara apa saja, mengenakan pakaian apa saja, dan bisa berekspresi dengan sesuka hati.
Kundera tidak sempurna. Objektifikasi pada perempuan pada tiap karyanya membuatnya dimusuhi oleh para feminis. Dan ia sempat berkilah: pisahkan karya dengan penciptanya.
Meski dari generasi yang berbeda, saya melihat Kundera yang lahir tahun 1929, punya nasib yang hampir sama dengan George Orwell, yang lahir tahun 1903. Keduanya bolak-balik diayun ambing oleh pertarungan isme-isme yang terjadi di era 1940-an.
Dalam tulisan Zen RS di buku saku ‘Orwell dan Tatapan Seekor Anjing’ menjelaskan jika perubahan sikap yang ambigu yang dilakukan oleh Orwell, berasal dari situasi politik di Eropa yang terus menerus mengalami turbulensi, silang sengkarut, yang membuat ideologi-ideologi bisa saling bertentangan di satu waktu namun bisa segendang sepenarian untuk situasi yang lain.
Pembedanya, Orwell terlibat dan menyaksikan bangkitnya sosialisme tanpa melihat keruntuhannya. Namun, Kundera menyaksikan keruntuhan sosialisme totaliter serta menjadi korbannya.
Oleh karenanya, Orwell hingga meninggal tahun 1950 masih memegang keyakinan kepada sosialisme sebagai–mula-mula dan yang terutama–hasrat kepada kebebasan dan keadilan.
Sementara, Kundera meyakini humanisme (yang bahkan ia tak mau menyebut isme ini) adalah pangkal dari kebebasan individu serta mencemooh kebodohan serta dogma sosialisme serta konsumerisme yang beracun.
Yang mana, ketika hak individu sudah diakui penuh, tidak ada seorang pun yang memiliki kebenaran absolut dan setiap orang berhak untuk dipahami.
Namun, apa yang diinginkan Kundera sepertinya masih jauh. Meski, pengetahuan berkembang sejak abad 15, di saat bersamaan pengkerdilan diri manusia terus digalakkan secara masif dan sistemik oleh isme-isme, pemuka agama kafir, politisi korup, guru konservatif, hingga polisi yang dibiakkan oleh negara.
Pada saat manusia masih berusaha berpikir, kini Milan Kundera mungkin sudah tertawa bersama Tuhan. Rest in laugh, Milan Kundera!