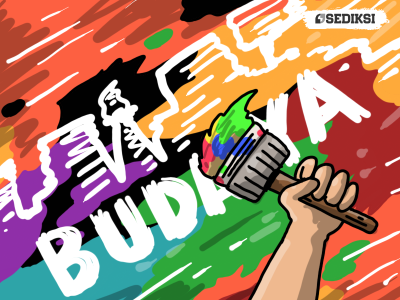Jika hanya melihat posternya, film Fair Play (2023) tampaknya hanya menjanjikan tontonan panas nan melenakan. Dugaan itu tak sepenuhnya salah, sebab fragmen panas memang tersebar di sepanjang film berdurasi 1 jam 51 menit ini.
Tapi begitu kita masuk ke dalam ceritanya, akan disadari bahwa fragmen syur itu hanya pemanis belaka. Fair Play menawarkan hal lain. Ia membawa kritik pedas terhadap realitas masyarakat hari ini yang masih melanggengkan nilai-nilai patriarkis.
Lalu, bagaimana kritik tersebut dilayangkan oleh film garapan sutradara Chloe Domont yang dibintangi oleh Phoebe Dynevor dan Alden Ehrenreich ini?
Gambaran Ketimpangan Gender di Wall Street
Di bagian awal, film memperlihatkan gambaran penuh kebahagiaan sepasang kekasih, yaitu Emily (Phoebe Dynevor) dan Luke (Alden Ehrenreich), di sebuah pesta. Meskipun demikian, sang sutradara nampaknya tak menghendaki penonton untuk terlena terlalu lama dengan hal ini.
Film selanjutnya beralih pada realitas Emily dan Luke sebagai pekerja di salah satu firma terbesar dunia, Wall Street. Topeng pun mesti dikenakan, sebab perusahaan itu secara tegas melarang hubungan percintaan antar pekerjanya.
Tidak ada lagi musik pesta. Yang ada ialah suara langkah kaki yang memijak lantai kantor dengan tergesa-gesa, layar-layar penuh angka, serta pekerja—yang mayoritasnya laki-laki—bertampang serius.
Ruang kerja itu diperlihatkan penuh rasionalitas, keperkasaan, dan kekuatan. Semua itu merupakan atribut yang melekat dalam lingkungan berjubah maskulin yang kental.
Penonton segera tahu, bahwa Emily menjadi salah satu pengecualian, mengingat selain dirinya, pekerja perempuan di ruangan itu bisa dihitung jari.
Laporan Investopedia berjudul What Causes Wall Street’s Gender Pay Gap? memperlihatkan bahwa lingkungan Wall Street masih didominasi oleh pekerja laki-laki, sementara perempuan kurang mendapat representasi dalam hal jenjang dan peningkatan jabatan penting. Tak hanya itu, mereka pun masih menghadapi perbedaan gaji yang nyata.
Data dari ADP menunjukkan bahwa perempuan hanya memperoleh rata-rata penghasilan 83 sen dari 1 dolar yang didapat laki-laki.
Di laporan yang sama, dari gaji rata-rata di bidang keuangan sebesar 33 dolar per jam, perempuan hanya mendapatkan penghasilan 27 dolar per jam, sementara laki-laki memperoleh hingga 40 dolar per jam.
Gambaran-gambaran di atas memperlihatkan kenyataan sebenarnya, bahwa perusahaan sekelas Wall Street pun masih menghadapi permasalahan ketidaksetaraan gender.
Tidak Hanya di Dunia Kerja, Hubungan Percintaan Pun Tak Luput dari Patriarki
Film ini menunjukkan bahwa karakter patriarkis yang mendiskreditkan perempuan tidak hanya terjadi di dunia kerja, namun juga merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan lain seperti hubungan percintaan.
Di suatu pagi, Emily tak sengaja mendengar rumor kalau Manajer Portofolio yang baru saja dipecat bakal digantikan oleh Luke. Setelah memberitahukannya kepada sang kekasih, keduanya merayakan kabar itu dengan segelas anggur dan gambaran pesta tunangan yang meriah.
Tapi kembali, Chloe tak membuat kesenangan berumur panjang. Sebab, rupanya Emily-lah yang dipromosikan sebagai Manajer Portofolio.
Emily terkejut, tak menyangka, tapi dia pun bahagia. Hanya satu hal yang mengganjal di benaknya: ia khawatir membuat Luke kecewa. Bagaimana respons Luke?
Kita tentu bisa menduga respons laki-laki yang mencintai Emily itu. Dengan seulas senyum, Luke berujar bahwa dia bangga dengan pencapaian Emily. Bahwa Emily pantas mendapat posisi itu. Tapi, apa benar Luke juga tak kalah bahagianya mendengar kabar itu?
Pada bagian ini, penonton sudah mulai merasakan bibit konflik utama di dalam film. Penonton dipancing untuk berpikir bahwa apa yang dikatakan tidak sepenuhnya menggambarkan kebenaran sesungguhnya.
Pada titik ini juga, parade letupan menjengkelkan nan menggemaskan khas film-film psychological thriller, mulai menunjukkan belangnya. Selanjutnya, penonton tak diberi kesempatan untuk menghela napas.
Dari sini, konflik di antara Emily dan Luke semakin memanas. Selain itu, sebaran diskriminasi gender dalam lingkungan patriarkis dan gambaran kerapuhan maskulinitas terlihat semakin nyata.
Luke digambarkan sebagai replika laki-laki dengan nilai patriarkis yang kental sekalipun tertutupi topeng. Di awal, dia memang mengapresiasi pencapaian Emily dengan ujaran “Aku bangga padamu” dan “Karenanya aku mencitaimu” yang dikatakan berulang-ulang.
Namun, ada bagian dari dirinya yang terlucuti dan hal itu semakin sulit ditutupi. Jauh di lubuk hatinya, Luke menyimpan rasa kemarahan dan ketidakterimaan.
Ia memang tak secara gamblang menunjukkan itu di depan Emily. Namun, kerapuhan maskulinnya terejewantahkan dalam tatapan saat Emily asyik mengobrol bersama bos mereka.
Ia juga mulai rajin menyimak buku self-development demi menggambalikan kediriannya yang terlucuti. Ia bahkan sampai enggan berhubungan intim bersama Emily sekalipun perempuan itu pasangannya.
Di mata Luke, Emily tak pantas mendapatkan promosi itu sebab dirinyalah yang layak. Kepercayaan diri itu menebal lantaran dia laki-laki, sementara Emily perempuan dan sudah selayaknya ada di bawah tingkatannya.
Luke bahkan menilai Emily mendapatkan jabatan itu bukan karena kemampuan dan kelayakannya, melainkan perilaku ganjen ditopang penampilan manis yang melekat dalam tubuh kekasihnya itu.
Tuduhan ini tentu saja merupakan penilaian sepihak Luke yang ditopang ego maskulinnya dan fakta dirinya yang tak bisa menerima kenyataan kalau Emily lebih layak sekalipun dia perempuan.
Di sini, Luke seolah menjelma filsuf Yunani, Pythagoras, yang mengatakan (dalam Beauvoir, 2003) bahwa laki-laki berhubungan dengan prinsip kebaikan, sementara perempuan kebalikannya, mereka berhubungan dengan prinsip keburukan.
Sosok Emily sebagai Representasi Pekerja Perempuan dalam Budaya Patriarki
Kedirian Emily menjelma sebagai perangkat kritik Chloe atas lingkungan maskulin dan tangan-tangan pelanggeng nilai patriarkis yang diwakilkan oleh Luke.
Posisi Emily memang sulit. Kendati jabatannya sudah setingkat lebih tinggi di atas Luke dan rekan kerjanya, kediriannya sebagai perempuan dalam lingkungan patrarkis tak serta-merta menjadi lebih baik.
Ia mesti menghadapi pendiskreditan atas keperempuanannya yang dinilai selalu mengedepankan perasaan dalam menyikapi suatu hal. Misalnya, pada suatu rapat perusahaan, mereka membahas prediksi hasil pembelian saham klien mereka.
Emily mengutarakan pandangannya, tapi rekan kerjanya, Gary (Sebastian de Souza), menganggap pandangan tersebut semata diperkuat oleh intuisi Emily saja. Padahal, pendapat itu ditopang dengan analisis mendalam yang telah terlebih dahulu dilakukan Emily.
Tak hanya itu, demi membaur bersama rekan setingkat lainnya, Emily mesti menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tak dikehendakinya.
Ia harus mengevaluasi pakaian yang dikenakannya dan membuatnya menjadi lebih tertutup. Emily bahkan mesti ikut menghadiri pesta di strip-bar penuh laki-laki yang melontarkan candaan seksis.
Di sini, Chloe menunjukkan kenyataan pekerja-perempuan dalam lingkungan patriarkis lewat berbagai persoalan yang harus dihadapi Emily.
Dalam konteks pekerja di Indonesia, apa yang dialami Emily sejalan dengan laporan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, yang menyebut perempuan masih mengalami gender shaming di lingkungan kerja.
Mereka dianggap penghambat pekerjaan, menjadi sasaran seksisme dan stereotip buruk terkait kinerja dan kedirian mereka.
Baca Juga: Kultur Rekrutmen Kerja yang Makin Jancuk
Mematahkan Stigma Patriarkis Lewat Hubungan Emily dan Luke
Apakah Emily, yang dilekatkan dengan perasaan dan intuisi, tak bisa menunjukkan sisi rasionalitas yang nyata?
Pertanyaan itu segera terjawab. Luke, sebagai salah satu representasi penuh “rasionalitas” dalam film, justru tak selamanya memegang kendali atas hal itu.
Dari menit ke menit, penonton semakin ditunjukkan betapa rapuhnya ego maskulin yang melekat dalam dirinya. Ketika ketidakterimaan itu menebal, Luke beraksi dengan menunjukkan tindakan-tindakan tanpa pertimbangan rasional.
Karakter Luke mencentang seluruh ciri-ciri figur yang patut dibenci: mulai dari egois, arogan, manipulatif, playing victim, sampai pengecut.
Di sisi lain, Emily, yang dianggap selalu mengandalkan perasaan dan intuisi, tampil mendobrak label tersebut. Memang, ia masih mencintai kekasihnya, sehingga dalam beberapa kesempatan dirinyalah yang membersihkan sisa kekacauan yang ditimbulkan Luke.
Namun, demi menghadapi Luke yang semakin di luar kontrol dan nalar, Emily sejelas-jelasnya figur paling rasional dalam konflik ini.
Penampilannya mematahkan stigma bahwa perempuan tak bisa berpikir rasional dan melulu mengedepankan perasaannya. Saat tiba di akhir film, Chloe pun semakin menegaskan penampilan Emily yang meruntuhkan sekat terpinggirkan dan pelabelan lemah tersebut.
Kendati begitu, kemenangan Emily tidak serta-merta membuat kritik yang ditampilkan Chloe selesai. Dalam Fair Play, Chloe juga mengekspos kebanggaan maskulin yang justru dipenuhi kerapuhan dan perlu ada yang diubah di sana.
Namun, akhir film yang ditutup dengan akhir terbuka mengindikasi hal lain: bahwa kritik itu belum selesai dan masih ada yang perlu disoroti. Luke memang terlucuti. Tapi, ia hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem besar yang masih bergeliat bebas.
Realitas patrarki masih perlu disoroti serta direkonstruksi ulang. Sebab, keberadaannya yang mendiskeditkan perempuan merupakan permasalahan zaman yang belum berakhir.
Di situlah Fair Play berdiri dengan gagah. Sebagai debut pensutradaraan film panjang pertama Chloe, kedudukan Fair Play patut diperhatikan.
Sebagai sebuah kritik atas realitas masa kini, Fair Play tampil tanpa mengumbar khotbah panjang tentang ketidakadilan, melainkan tampil dengan adegan dan dialog yang subtansial. Sehingga, kritiknya menyusup secara wajar tanpa kehilangan ketegasannya.
Sementara itu, sebagai film psychological thriller, Fair Play layak menjadi pertimbangan bagi siapa pun yang menginginkan tontonan menguras emosi nan menggemaskan.