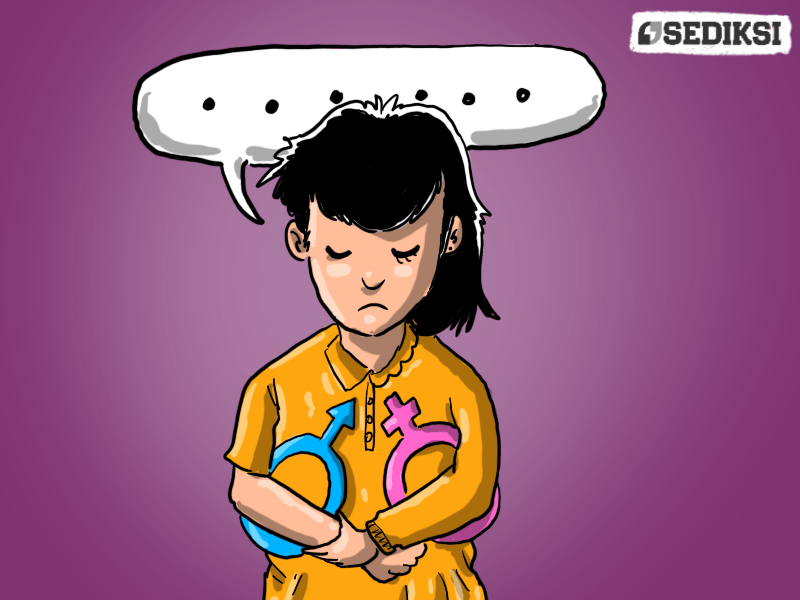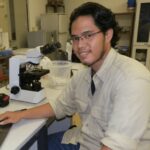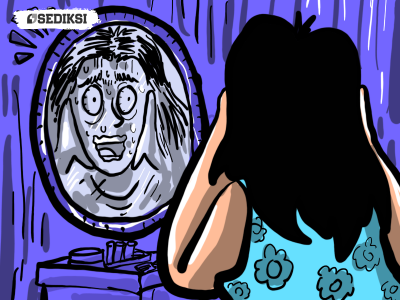Ada sebuah video social experiment di media sosial untuk mengetahui bagaimana orang-orang mendefinisikan sex dan gender mereka. Social experiment tersebut dilakukan oleh orang kulit putih atau “orang barat” dengan menanyakan pronoun atau ‘kata ganti orang’ kepada beberapa orang yang mereka temui.
Pronoun atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan ‘kata ganti’ mengacu pada pemahaman tentang jenis kelamin dan gender. Seperti she atau he. Dengan kata lain, bagaimana jenis kelamin atau gender seseorang ingin diidentifikasi oleh orang lain. Entah sebagai perempuan, laki-laki, atau tidak keduanya.
Menariknya, dalam social experiment itu terdapat jawaban yang memilih untuk tidak mengelompokkan jenis kelamin atau gendernya ke dalam kelompok mana pun.
Contoh dialognya kurang lebih begini:
“what’s your pronoun?”
Kemudian dijawab:
“I am non binary,” atau “my pronoun is we.”
Pertanyaan soal kata ganti ini muncul di tengah riuhnya gagasan soal anti-gender movement. Bagi para penganut gender non-biner, sistem pengelompokan jenis kelamin di dalam Bahasa Inggris yang membagi manusia sebagai laki-laki dan perempuan (biner) tidaklah cukup representatif untuk mengekspresikan gender yang menurut mereka, begitu banyak.
Pertanyaan tentang pronoun membuat saya mengernyitkan dahi dan misuh dalam hati. Masa kayak gini aja ditanyain.
Dalam Bahasa Indonesia sendiri, untuk menyebut individu tunggal maupun jamak digunakanlah kata ganti yang lebih menunjukkan jumlah alih-alih jenis kelamin.
Misalnya saat kita membicarakan seseorang bernama Siskaeee dengan tiga huruf e di belakang namanya, kita akan menggunakan kata ganti ia atau dia. Demikian juga saat kita membicarakan seseorang bernama Joni, kita pun akan menggunakan kata ganti ia atau dia.
Kata ganti ia atau dia untuk Siskaeee dan Joni sama-sama digunakan tanpa spesifik menjelaskan jenis kelamin keduanya. Hal ini karena di dalam Bahasa Indonesia tidak mengenal kata ganti yang langsung merujuk pada jenis kelamin.
Namun penyebutan kata ganti dalam Bahasa Inggris secara gramatikal mensyaratkan spesifikasi jenis kelamin pada manusia atau benda. Dengan begini, artinya pronoun untuk Siskaeee adalah she dan Joni adalah he. Tidak bisa dibolak-balik.
Mengganti Pronoun Menjadi Non-Biner, Mungkinkah?
Saya merasa bahwa adanya gagasan mengubah pronoun menjadi they, we, ataupun non-binary merupakan bukti ketidakmampuan negara barat mendidik putra-putrinya memahami konsep gender berdasarkan jenis kelamin. Sebuah pemahaman yang selama ini dipakai bahkan dilestarikan dalam aturan gramatikal.
Bayangkan jika gagasan mengubah pronoun ini diadopsi menjadi kebiasaan dan akhirnya dibakukan menjadi aturan gramatikal Bahasa Inggris. Bukankah itu artinya akan terjadi revisi sejarah yang masif?
Berapa banyak cetak ulang yang dilakukan terhadap literatur dan diktat berbahasa Inggris yang di dalamnya menceritakan tokoh-tokoh penting baik fiksi maupun non fiksi? Sulit membayangkan bagaimana tokoh-tokoh dalam dongeng karya H.C. Andersen, misal Ariel si little mermaid, diganti dengan pronoun we.
Atau narasi pada cerita Si Pangeran Katak diganti dengan “seorang individu non-binary yang dicium oleh cinta sejatinya yaitu they, lalu berubah menjadi manusia tampan dan hidup bahagia selamanya.”
Eh tapi, bukankah kata sifat “tampan” biasanya diasosiasikan dengan kata ganti he? Memang puncak komedi.
Bagi saya, gagasan mengganti pronoun ini tidak masuk akal. Kalaupun ada negara yang meresmikan, akan sangat ribet untuk dunia literasi.
Gender Dysphoria dan Kebingungan Mengidentifikasi Diri
Melihat perilaku orang-orang penganut non-binary gender ini, saya berasumsi bahwa mereka mengalami kebingungan mengidentifikasi gender.
Dalam ilmu psikologi, kebingungan semacam ini dirangkum dalam sebuah fenomena psikis yang diistilahkan sebagai gender dysphoria. Namun, seseorang yang menjawab pertanyaan gender dengan pronoun jamak tidaklah serta-merta disimpulkan mengidap gender dysphoria.
Gender dysphoria lebih menekankan pada ekspresi gender dan situasi psikologis yang akhirnya membawa pada pertanyaan “sebenarnya jiwaku perempuan meski fisikku laki-laki” atau “sebenarnya aku laki-laki atau perempuan sih?”
Fenomena ini terjadi dalam kondisi tekanan psikologis akibat ketidaksesuaian jenis kelamin dengan ekspresi gender. Hal ini haruslah diputuskan secara medis atau telaah psikiatris dan tidak sekedar ikut-ikutan tren gagasan gender non-biner.
Seringnya gender dysphoria sudah dimulai sejak anak-anak. Namun ekspresinya baru terlihat saat seorang individu mengalami pubertas dan menginjak dewasa. Contohnya kelompok transgender yang merasa tidak cocok dengan identitas gender awal mereka.
Seorang profesor psikiatri klinis Columbia University Jack Drescher mengatakan, individu transgender diketahui mengejar validasi sosial tertentu. Transgender mengubah nama mereka dengan pronoun tertentu dan bahkan sampai mengubah identitas gender mereka pada dokumen resmi.
Kenyataannya, tidak semua orang dengan gender dysphoria punya pilihan berobat. Prosedur operasi penggantian kelamin perlu biaya mahal. Banyak pengidapnya memilih terapi hormon.
Pengidap gender dysphoria lantas berkompromi dengan lingkungan dan berpakaian sesuai jenis kelaminnya yang dipilihnya saat ini. Individu dengan kondisi ini juga mencari dukungan dan validasi melalui komunitas transgender di media sosial.
Beberapa pengidap memilih mengekspresikan identitas gendernya pada tempat yang lebih tertutup untuk menghindari penghakiman sosial. Mereka yang punya kondisi ini cenderung menarik diri dari pergaulan.
Meskipun tidak semua transgender atau individu dengan gender dysphoria mengejar validasi sosial dan menganggap gender adalah privasi, namun fenomena ini melahirkan gesekan antara penganut konservartif dan golongan anti-gender.
Soal Sex dan Gender, Mari Kembali Pada Realita
Dengan menarik asumsi sex dan gender adalah sama, maka jika seseorang menawarkan gagasan di luar itu artinya ia sedang menantang konsep konservatif dan siap diuji kesahihannya.
Hanya ada dua jenis manusia di dunia ini, yaitu pria dan wanita. Satu yang berpenis, satu lagi yang punya vagina. Kita tidak usah membicarakan konstruksi sosial budaya dahulu.
Kita boleh berdebat sepanjang hari apakah jenis kelamin dan gender itu sama atau berbeda. Kita juga bisa berdebat soal apakah kita perlu mulai menerima bahwa gender tidak hanya dua. Lebih ekstrim lagi, mempertanyakan apakah kita boleh dengan mudahnya menganggap orang yang menolak konsep non binary gender sebagai orang yang close minded.
Sheikh Assim Al Hakim, seorang ulama yang tinggal di Jeddah, Arab Saudi dalam sebuah kesempatan ketika ditanya tentang gender, beliau menjawab I am a bird.
Ulama yang terkenal jenaka ini paham munculnya fenomena pengaburan identitas gender oleh pihak tertentu. Gagasan agenda ini menjadikan manusia mengenali tidak lagi dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.
Agenda pengaburan identitas menggunakan kata kunci “ekspresi gender” menitikberatkan pada gagasan bahwa manusia yang punya titid tidak selalu harus disebut sebagai laki-laki. Oleh sebab itu sheikh Assim Al Hakim memilih mendefinisikan dirinya sebagai seekor burung.
Jangan-jangan jawaban satir itu merupakan pesan sublim untuk menunjukkan bahwa “sudah jelas-jelas lho saya ini laki-laki, pake nanya, cok!”