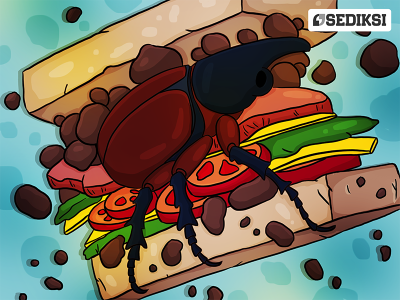Sejauh pengetahuan saya orang perlu makan nasi, bukan makan cerita, apalagi kalau harus paham metodenya dulu. Seperti kata Jason Ranti, lewat gubahan saya: perut kosong mana mempan dikasih historiografi.
Begitu kira-kira yang muncul di benak saya ketika membaca opini balasan Alfian atas opini balasan saya atas opini Alfian (biar kayak Marx, kritik atas kritik atas kritik). Tapi, jangan keburu naik pitam, saya tak bermaksud menghina.
Pertama-tama, saya paham dengan cara berpikir Alfian. Publik mungkin memang tak paham metode sejarah, perangkat penelitiannya, cara interpretasinya, dan seterusnya.
Maka, yang dipikirkan Alfian adalah bagaimana cara agar supaya publik paling tidak bisa sedikit memahami, atau dalam bahasa Alfian, “supaya tak “terbawa arus” dan “menelan mentah-mentah.”
Di sini, saya justru memuji Alfian karena cukup merasa punya tanggung jawab publik dalam soal ini. Tak banyak sejarawan yang punya keresahan mulia seperti itu. Tapi masalahnya, saya pikir kekhawatiran Alfian salah sasaran.
Pada titik inilah sebenarnya letak kecongkakan akademik yang saya katakan sebelumnya. Bukan sekadar pada diksi yang dipilih dan digunakan Alfian, melainkan pada bagaimana ia memosisikan subjek-subjek dalam esainya. Dan itu, bagi saya, fatal.
Perangkat Kecongkakan
Supaya tak terlalu teoretis, saya coba kutipkan saja opini terakhir Alfian:
“Bukan bermaksud menghina, tapi tidak sedikit masyarakat kita yang memang masih belum bisa menelaah sebuah informasi dengan baik dan masih memiliki kecenderungan untuk melakukan interpretasi tanpa berbekal fakta yang mendasar.”
Jika logika kalimat ini saya balik lewat pertanyaan: jadi, kalau sebagian besar masyarakat kita tidak bisa, lantas siapa yang bisa menelaah informasi dengan baik dan punya interpretasi yang sah menyoal sejarah?
Untungnya saya tak perlu repot-repot menjawab karena Alfian menjawabnya sendiri dalam dua paragraf berikutnya:
“… peran sejarawan ataupun akademisi sejarah yang seharusnya menjadi gatekeeper dan insinyur masyarakat pun beberapa kali masih tak dihiraukan oleh masyarakat itu sendiri.”
Di situ, Alfian punya subject positioning yang jelas dalam logika esainya. Publik luas, atau “tidak sedikit masyarakat kita” dalam bahasa Alfian secara leterlek, diandaikan tak punya perangkat pengetahuan yang mumpuni untuk melakukan interpretasi historis. Sementara sejarawan memilikinya lewat penggunaan diksi “gatekeeper” dan “insinyur masyarakat”.
Artinya, sejak awal Alfian tidak memosisikan subjeknya dengan setara. Ada yang lebih berpengetahuan di satu sisi dan tidak berpengetahuan di sisi lain.
Makanya kalimat “… masih tak dihiraukan oleh masyarakat itu sendiri” kemudian muncul, seolah yang berpengetahuan ini harus di-taklid oleh mereka yang tidak.
Alfian juga menggunakan diksi seperti “… hanya akan tersampaikan kepada kelompok yang sudah paham dengan sejarah saja.” Artinya, Alfian mengandaikan ada yang “liyan” dalam soal pengetahuan sejarah.
Baca Juga: Apakah Kita Harus Percaya Pada Pakar?
Makanya saya berani mengatakan tulisan Alfian menunjukkan kecongkakan akademik karena menganggap sejarawan punya surplus perangkat pengetahuan dibandingkan dengan publik, dan oleh karena itu harusdidengar.
Lalu, apa iya demikian? Jawabannya, ya, kagak lah!
Buktinya Alfian sendiri bercerita bahwa ia mendengar, dengan telaten dan seksama, kisah bapaknya, atau mbahnya. Tapi. yang luput dipikirkan Alfian ialah kisah-kisah itu juga sudah diceritakan sebagai sebentuk interpretasi, bukan sekadar sumber primer.
Saya yakin Alfian sudah paham betul bahwa dalam kajian historiografis tidak ada sumber se-primer apapun yang bersih dari motif dan perspektif, baik tertulis, lisan, visual, dan seterusnya.
Sumber itu sendiri sudah sebentuk interpretasi dan jelas bisa diproduksi siapa saja tanpa perlu melulu melalui kerangka metodik yang ketat.
Hipokrisi yang gamblang semacam ini merupakan bentuk paripurna dari kecongkakan akademik. Sadar bahwa siapa saja bisa menginterpretasi sejarah, tapi justru membuat batasan ini dan itu.
Dalam kasus Alfian, ia memberikan batasannya pada kepemilikan perangkat pengetahuan berupa metode sejarah supaya seseorang bisa menginterpretasi sejarah dengan kaffah. Masak iya begitu?
Saya tahu, secara sadar, Alfian tak bermaksud menghina atau menunjukkan kecongkakan. Masalahnya secara tak sadar, tulisan Alfian jelas memperlihatkan sebaliknya.
Tapi, yah,mungkin ia hanya sedang khilaf.
Metode Sejarah, Metode Apalah: Menyoal Politik Interpretasi Historis
Karena positioning yang demikian, Alfian lantas membahas metode sejarah dalam kedua esainya. Di sinilah letak perbedaan saya dengan Alfian.
Saya menolak bentuk pemosisian demikian sejak awal dan jelas menolak menghina publik dengan meletakkan pengetahuannya berada “di bawah” sejarawan. Karena kenyataannya memang tidak demikian.
Sebagai subjek, publik juga punya nalar epistemik serta metode sendiri. Sehingga, “pertarungan” interpretatif antara sejarawan dan publik tidak terjadi dalam ranah edukasi atau metodik, tapi dalam aras pewacanaan. Hal inilah yang luput disadari Alfian dan membuat kritiknya kepada publik, bagi saya, salah sasaran.
Dari pada ruwet, saya kasih contoh kasus saja. Belakangan ini banyak makam-makam “orang suci” bermunculan di banyak tempat. Dasar dari penetapan mistifikasi makam ini bukan atas riset sejarah melainkan karena terdapat pemuka agama yang menyampaikan wacana bahwa ada “orang suci” yang dimakamkan di sana.
Jika ditinjau dari sudut pandang historiografis, hal ini jelas problematik karena tak ada pembuktian yang mumpuni. Tapi, justru di sini poin pentingnya. Publik punya nalar dan metode sendiri.
Wacara mistifikasi dari pemuka agama itu menurut saya dipercayai publik bukan sekadar karena dia benar atau salah, tapi juga karena ada faktor-faktor lain.
Baca Juga: Masalah Kita dengan Hantu Masa Lalu
Misalnya, di luar masalah kepercayaan, mistifikasi makam itu mendatangkan keuntungan ekonomi pada warga desa di sekitarnya.
Jika kemudian ada sejarawan datang dan melakukan riset lalu kemudian membantah perkataan si pemuka agama, apakah warga kemudian “harus” percaya pada wacana yang dibawa sejarawan itu?
Lalu, bagaimana dengan keuntungan kapital yang sudah diperoleh publik sebelumnya?
Mau makan pake apa, dong, pak sejarawan? Mata pencaharianku mbok usik, jaluk diantemi po piye?
Maksud saya begini. Ketika berhadapan dengan publik, soal-soal historis itu tidak lagi sekadar menyoal kebenaran ilmiah.
Terdapat pula faktor lain yang perlu masuk dalam pertimbangan. Maka, fokus Alfian pada penyemaian metode sejarah kepada publik, sekalipun niatnya baik, jelas salah sasaran.
Dalam persoalan yang menjadi muara perdebatan saya dengan Alfian pun juga begitu. Publik yang percaya pada wacana simplifikasi dan pseudo-histori Neo Historia punya nalar serta metode sendiri yang jangan-jangan tidak kita pertimbangkan.
Bisa jadi untuk melepaskan kejemuan mereka dari pelajaran sejarah monoton di sekolah, atau untuk gaya hidup supaya terlihat edgy, atau karenafaktor-faktor lain yang tidak melulu berkaitan dengan kebenaran ilmiah.
Di sini, politik interpretasi historis berlaku karena ada kontestasi di ruang publik atas interpretasi sejarah. Dan dalam konteks kontestasi itu kebenaran ilmiah bukan satu-satunya faktor
Di saat yang sama, publik tidak bisa diandaikan sebagai subjek “liyan”, melainkan amat sangat dinamis dan cerdas dengan caranya sendiri.
Jika kita memahami konteks kontestasi interpretasi di ruang publik ini, tawaran saya yang dikatakan Alfian sebagai “idealis” itu justru jadi jalan keluar yang paling masuk akal: menghadirkan wacana untuk berkontestasi dalam ruang interpretasi publik secara terus-menerus.
Perkara publiknya mau percaya atau malah mau menginterpretasi wacana itu dengan cara story, history, atau mystery, atau dengan beragam macam jenis model interpretasi lainnya, itu sudah bukan domainsejarawan. Biarkan publik menjadi subjek otonom yang bisa mengolah wacananya sendiri.
Sukur-sukur apabila publik mau percaya pada wacana yang berdasarkan metode ilmiah. Lebih sukur lagi kalau mau belajar lebih jauh tentang metode sejarah.
Tapi, kalau tidak, sejarawan tak bisa memaksa selain terus berupaya menghadirkan pewacanaan dalam kontestasi ruang publik tadi.
Dalam soal ini, kritik tidak hanya saya ajukan pada Alfian. Menurut saya, kebiasaan kaum terdidik kita untuk menyalahkan publik atas “ketidakpahaman” merupakan sebentuk kemalasan serta banalitas berpikir.
Karena publiknya “tak paham” plus si terdidik ini “malas” berkontestasi secara pewacanaan, maka dicap bodoh saja. Tanggung jawab intelektual kemudian dianggap selesai dan publik seolah menjelma jadi gerombolan tak bernalar.
Saya tahu tak banyak yang berani mengatakannya segamblang itu. Tapi masalahnya, mentalitas intelektual kita sejauh ini seolah mau mengatakan begitu melulu.
Jadi, mbok ya tulung, jangan dibiasakan.