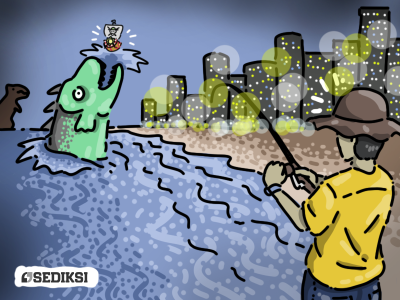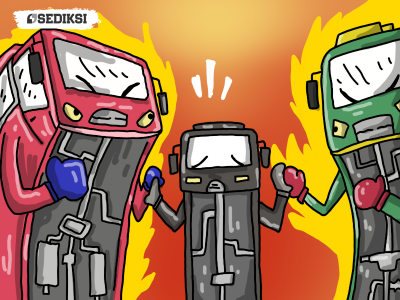Baru-baru ini ramai berita soal Husein Ali Rafsanjani, seorang guru yang mengundurkan diri dari ASN karena dimintai pungli oleh BKPSDM Pangandaran. Ia akhirnya memutuskan untuk melapor dan naga-naganya mendapat perlakuan intimidatif dari lembaga terkait.
Merespon kejadian ini, reaksi masyarakat rata-rata senada. Meski mayoritas suara di media sosial mengecam lembaga pemerintah, namun ada saja tanggapan bodoh yang nyempil.
Sebagaimana biasanya, ada tanggapan yang bernada permisif pada perilaku korup, dan seakan merendahkan upaya si pelapor dalam membela haknya. Saat saya mengintip bio-nya, beberapa akunnya berasal dari generasi yang lebih senior.
Diberitakan Kompas, kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani diberhentikan dari jabatannya. Sementara Husein sendiri baru-baru ini dikabarkan bakal dipindahtugaskan ke Bandung.
Win-win solution? Ya jelas tidak!
Menjadi pemuda di Indonesia kadang serba salah. Menjadi guru seperti Oemar Bakri jelas lebih susah.
Melihat hal ini, saya percaya pada pergerakan warganet yang kadang-kadang bisa beringas. Suara mereka sering lebih efektif ketimbang lembaga pemerintah yang kerap lelet, dan sering bikin runyam.
Guru Juga Punya Hak Melawan
Simpati saya pada Bung Husein hadir karena pemahaman saya soal tidak enaknya jadi seorang guru yang memang berniat mengabdi untuk dunia pendidikan. Tanpa jabatan dan tanpa bisnis sampingan pula.
Almarhum ayah saya seorang guru matematika. Ia rutin berangkat mengajar tiap pagi, kemudian pulang pada sore hari. Malam harinya masih menggarap silabus, RPP, atau tugas tambahan lain. Di sela rutinitasnya, ia juga mengerjakan tugas lain yang seabreg. Mengoreksi tugas siswanya, misalnya.
Ayah saya percaya bahwa proses mengajar adalah dialog kemanusiaan. Ia mengajak siswanya belajar di luar kelas sebagai selingan dari ruang kelas. Ia juga merogoh kantong pribadi untuk membikin alat peraga.
Mungkin di suatu masa, ayah saya pernah membaca Paulo Freire, Horace Mann, atau pengagum Ki Hajar Dewantara. Sehingga, hidupnya diabdikan untuk mengajar semenjak bujang.
Dari ceritanya, ia kerap berdebat soal sistem pendidikan kita punya banyak celah. Di lain waktu, ia mempertanyakan pengajar yang asal-asalan, maupun ‘titipan’ orang dalam. Ia juga pernah berdebat dengan kepala sekolah soal penentuan kebijakan yang tak taat administrasi.
Mungkin ia pernah betul-betul membaca buku-buku begawan pendidikan seperti mereka. Ia membayangkan bahwa pendidikan adalah alat untuk memerdekakan pikiran. Ia tak ragu mengajarkan bahwa tiap orang menyuarakan pendapatnya, termasuk pada anaknya.
Seiring dewasa, hal-hal yang harusnya biasa itu menjadi tak biasa ketika saya berkuliah dan bekerja.
Dalam dunia kampus, tunduk serupa ternak pada rektorat yang bermasalah adalah hal yang biasa bagi mahasiswa. Di dunia pekerjaan, menjilat atasan adalah hal normal untuk naik jabatan. Dalam dunia bisnis atau pergerakan, bermental pragmatis sampai semua hal dijadikan usaha adalah hal lumrah.
Bagi jiwa anak-anak saya yang masih tersisa, semua hal itu menjadi aneh. Sesuatu yang normal dan ideal malah dibayangkan sebagai hal aneh. Kita punya pendapat, juga hak menggugat hal-hal yang tak sesuai, seperti yang dilakukan oleh Bung Husein.
Coba bayangkan, bagaimana jika Ki Hajar Dewantara yang bertekad untuk memperluas akses pendidikan untuk masyarakat non-ningrat itu malah dikatai, “kamu itu terlalu idealis” lantas memilih menyerah dan melupakan keresahannya?
Bayangkan pula Hasyim Asy’ari memilih rebahan ketimbang menyerukan gagasan soal dakwah, cinta, dan kebangsaan?
Mungkin sampai saat ini kita semua masih menjadi inlander pandir yang terburai seperti remahan ayam krispi.
Pemakluman yang Tak Seharusnya Dimaklumi
Pemakluman terhadap kesalahan-kesalahan yang disengaja oleh penguasa tampaknya sudah mengakar erat di masyarakat kita. Dibela dengan alasan tak masuk akal pula. Kebanyakan kasus diakhiri dengan ucapan maaf dan mengaku khilaf.
Khilaf itu nggak sengaja. Masa iya saat korupsi, melakukan pungli, maupun mendiskriminasi itu semuanya dilakukan tanpa sadar?
Sekalipun anak-anak muda pengalamannya belum seberapa, mereka juga nggak segoblok itu buat diakali terus-terusan.
Di lain sisi, perilaku menyalahkan anak muda atas sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kian diminati. Generasi muda dicap melempem, mengada-ada maupun idealis. Lagu lama itu, bos. Basi!
Sikap patuh dan ngentengin macam itu berpeluang membuat kita permisif pada “yang di atas”. Misalnya, menjadi begitu pemaaf pada pelaku pungkli, predator seskual, maupun orang-orang korup.
Sebaliknya, pada generasi muda, sikap nyinyir selalu dikedepankan. Tak peduli apa upayanya, generasi muda selalu dibayangkan melakukan hal-hal sepele.
Pola ini tampak menunjukkan adanya bias penilaian. Bentuknya berupa sikap permisif pada orang yang lebih berkuasa, maupun hal lain yang sifatnya ke atas. Sementara pada saat yang sama mengerdilkan upaya generasi muda.
Hal-hal semacam ini tak bisa dimaklumi. “Beginilah realita. Hidup itu kejam dan semua ini adalah proses seleksi alam,” itu omong kosong dan tak sesuai dengan konteks kehidupan sosial manusia.
Jika seandainya proses seleksi ini adalah filter untuk menentukan siapa yang akan berkuasa, maka bisa dibayangkan orang-orang seperti apa yang akan duduk menjadi penguasa nantinya. Orang-orang menjilat jika berada di bawah, dan akan menindas jika berada di atas. Yang menjadi pemimpin di masyarakat maling adalah maling paling bejat.
Baca Juga: Meminta Maaf Itu Murah, Maka Berhenti Saja!
Menormalisasi Hal-Hal yang Harusnya Biasa
Terkait kelakuan orang-orang tua ngehek tadi, sudah saatnya kita menormalisasi sikap rajin untuk datang tepat waktu, merampungkan pekerjaan sesuai target, dan membiasakan menegur atasan yang keliru. Bukankah sejak TK kita diajarkan untuk bersikap berani karena benar dan takut jika salah?
Saya paling sebal jika ada omogan “Ah, kamu kan masih muda. Belum tahu rasanya kehidupan.”
Kata-kata “anaknya masih idealis” sering kali menjadi ungkapan yang disematkan kepada seseorang sebagai pengganti ungkapan kenaifan, utopisme, atau sikap-sikap lain yang dipandang tidak realistis.
Saya justru ingin menanyakan balik. bagaimana bisa seseorang menua tanpa idealisme di dalam dirinya? Tidak ada tujuan, tidak ada impian, dan tidak ada sesuatu untuk diperjuangkan. Rasanya pastilah mengerikan. Seperti hidup tapi seakan sudah mati.
Anak muda boleh saja dibilang naif, idealis, atau apa pun itu. Dunia memang perlu membiasakan hal-hal yang memang sudah seharusnya. Apa yang keliru dari melawan yang bejat dan memperjuangkan yang ideal?
Saya nggak muluk-muluk punya impian Indonesia harus maju. Menjaga untuk tidak berkelakuan minus saja sudah bagus.
Banyak kok orang-orang yang berada di fase sulit dan tetap menjaga idealismenya. Guru Husein, misalnya. Juga ayah saya, dan orang-orang yang berjuang membuka ruang-ruang belajar untuk lebih banyak orang.
Mereka semua orang biasa, yang menjalani hidup dengan biasa pula, punya mimpi, punya idealisme, bersuara saat melihat ketidakadilan, dan menolak tunduk pada penindasan.